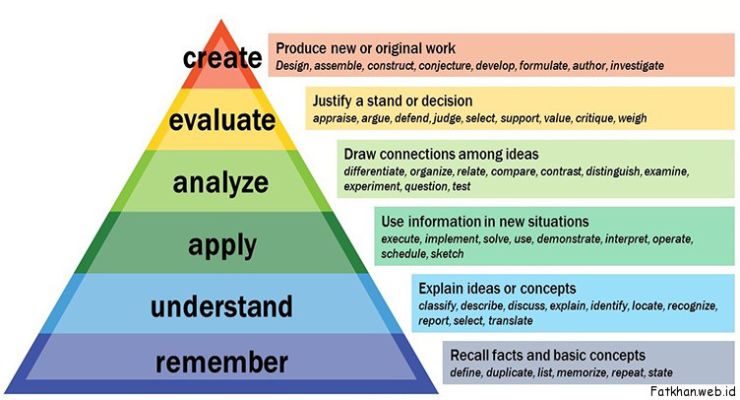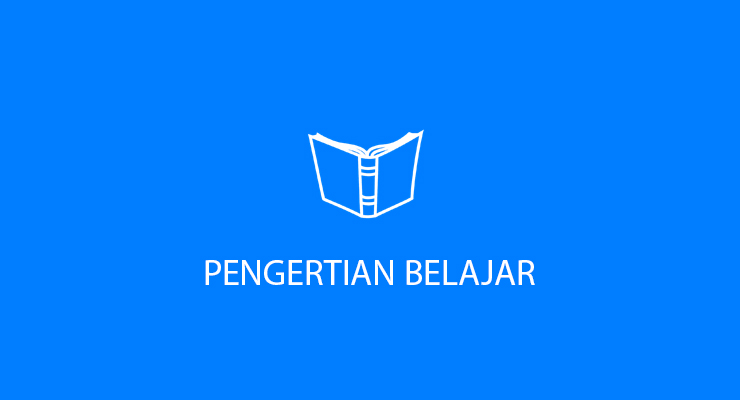Berikut ini adalah contoh Laporan PKL SMK Administrasi Perkantoran. Laporan ini dibuat oleh Siswa asal SMKN 2 Purwerejo. Laporan ini disusun dalam 4 bab.
Daftar isi
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Didasari dalam rangka meningkatkan wawasan pengalaman belajar dan Penguasaan Keterampilan atau Keahlian Profesi tertentu pada siswa – siswi, antara lain diperlukannya adanya penciptaan berbagai aktivitas belajar dilingkungan Sekolah. Kondisi demikian telah lama menjadi pusat perhatian Dunia pendidikan, lebih-lebih untuk sekolah Kejuruan, bahwa penguasaan keahlian Profesi sebagai salah satu tujuan Esensial yang menggambarkan eksistensi sekolah kejuruan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya kesempatan melalui pengenalan pada Dunia Kerja yang sebenarnya.
Praktek Kerja Industri dan Instansi (Prakerin) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian, professional yang memadukan secara sistematika dan sinkron program pendidikan disekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dengan tertata dan terprogram untuk mencapai tingkat keahlian professional tertentu.
Salah satu upayah mewujudkan hal tersebut, yaitu menyelenggarkan Program Kegiatan Praktek Kerja Industri dalam rangka Pendidikan Sistem Ganda di dunia kerja terkait dengan kondisi obyektif sekolah yang bersangkutan. Sehubungan dengan dasar pemikiran sebagaimana diutarakan diatas, SMK Negeri 2 Purworejo menerjunkan semua siswa kelas II (dua) untuk melaksanakan Pendidikan Program Sistem Ganda (PSG) yang di tetapkan oleh sekolah.
Prakerin menambah wawasan dan pengalaman kepada siswa/siswi guna kemanfaatan studi sehingga pada gilirannya lulus memuaskan yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya masing-masing, sejalan dengan tuntutan pembangunan bangsa.
B. Pengertian
Praktek Kerja industri adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian propesi yang memadukan secara sistematis dan singkron antara pendidikan disekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung didunia kerja dengan terarah dan terprogram untuk mencapai tingkat keahlian yang propesional tertentu. Prakerin adalah bagian dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada SMK.
Prakerin merupakan bagian dari program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di Dunia Usaha/Dunia Industri. Program yang dilaksanakn di industri/perusahaan, meliputi Praktek dasar kejuruan, dapat dilaksanakan sebagian di sekolah dan sebagian lainnya di industri. Praktek dasar kejuruan dapat dilaksanakan di industri apabila industri pasangan memiliki fasilitas pelatihan di industrinya. Ababila industri memilliki sepenuhnya dilaksanakn di sekolah.
Praktek keahlian produktif dilaksanakan di industri dalam bentuk “On the Job Training”, berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa (pekerjaan yang sesungguhnya) di industri atau perusahaan. Pengaturan program a, b harus disepakati pada awal program oleh kedua pihak.
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuannya
- Mengembangkan pengetahuan, sikap dan kemampuan serta menambah wawasan siswa-siswi yang berkaitan dengan pelajaran yang telah diterima di sekolah.
- Melatih kerja dan pengamatan teknik-teknik yang diterapkan di tempat Peraktek Kerja Industri (Prakerin) sesuai di bidang keahlian yang dimiliki.
- Untuk mencari pengalaman dalam Prakerin di dunai usaha/industri.
- Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di sekolah.
- Untuk menambah bekal hidup di masa depan.
- Memperkokoh Link and Match kesesuaian, kecocokan antara Program Sekolah dengan tuntutan dunia kerja.
2. Manfaatnya
Dengan adanya Praktek Sistem Ganda (PSG), ilmu yang diperoleh dari sekolah dapat dirasakan manfaatnya dan dikembangkan dilapangan, dan siswa juga mendapatkan wawasan baik disekolahan maupun di instansi/perusahaan.
D. Rumusan Masalah
Mengapa kami memilih Prakerin di UPT DIKPORA Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo ?
Karena di tempat itu menjadi salah satu keputusan dari sekolah dan disesuaikan dengan jurusan yang kami tekuni yaitu Administrasi Perkantoran juga menambah pengalaman kerja dan juga bisa lebih memahami tentang manajemen pendidikan yang ada di lingkungan wilayah Kecamatan Bayan.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode yang penulis gunakan untuk mendapat informasi yaitu :
- Observasi (Pengamatan) – Metode ini penulis gunakan sewaktu melaksanakan Prakerin.
- Interview (Wawancara) – Dengan menanyakan langsung data-data kepada pimpinan.
Bab II. Pembahasan
A. Sejarah Berdiri
Kantor Ranting DIKPORA Kec. Bayan berdiri tahun 1966 sebelum bertempat di Desa Besole kantor tersebut berada di Jalan Raya No. 164 Desa Bandungrejo. Menempati milik Bapak Suyut Hadi Saputra. Kantor tersebut mulai dipindahkan ke Desa Besole pada tahun 1970 dengan mendapat bantuan pemerintah berupa swadaya masyarakat wali murid.
- Poerwo Pandoyo – Tahun 1966 s/d Tahun 1967
- Suyut Hadi Saputra – Tahun 1967 s/d Tahun 1970
- Ngaiso Wardi Sumarto – Tahun 1970 s/d Tahun 1974
- S. Padmo Wiyoto – Tahun 1974 s/d Tahun 1976
- S. Tjipto Rahardjo – Tahun 1976 s/d Tahun 1978
- Sumardi, BA – Tahun 1978 s/d Tahun 1980
- Sengkan, BA – Tahun 1980 s/d Tahun 1982
- Sutarno Kusumo Diharjo – Tahun 1982 s/d Tahun 1984
- Sutedjo – Tahun 1984 s/d Tahun 1988
- Yuwono Trisunu – Tahun 1988 s/d 30-07-1990
- S. Priyanto Hadi, BA : 30-07-1990 s/d 05-01-1991
- Sularno, BA: 05-01-1991 s/d 31-08-1993
- Natular S,BA/G.Triyanti/Supodo, BA: 31-08-1993 s/d 22-05-2001
- Drs. Subarno: 23-05-2001 s/d 05-07-2002
- Ponen, S,B.Pd: 05-07-2002 s/d 31-03-2004
- P. Jaenal Abidin
- Drs. L.E. Harjono: 31-03-2004 s/d 30-06-2010
- Sudarman, S.Pd: 01-07-2005 s/d 30-04-2006
- Amat Tulus, BA: 01-05-2006 s/d 31-01-2010
- Sudarman, S.Pd: 01-02-2010 s/d 31-07-2011
- Drs. Muh Hamidi, M.Pd: 01-08-2011 s/d 29-02-2012
- Ngadino, S.Pd, M.M: 01-03-2012 s/d 17-10-2013
- Drs. Joko Sutanto, M.Pd: 18-10-2013 s/d 12-08-2014
- Drs. Sardi, M.M: 23-01-2015 s/d Sekarang
B. Visi dan Misi UPT Dikpora Kec. Bayan
1. Visi
Profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan.
2. Misi
- Mewujudkan dan Meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga pendidik.
- Mengusahakan terpenuhinya tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
- Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat secara akuintable.
C. Profil UPT DIKPORA Kecamatan Bayan
1. Profil UPT DIKPORA Kecamatan Bayan
UPTD Pendidikan yang ada di Kecamatan memegang peran sangat penting, demi terwujudnya pencapaian program pemerintah wajib belajar 9 tahun. UPTD Pendidikan ini didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku dari Pemerintah Daerah dengan di keluarkannya Lembaran Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 (Pasal 2 ayat 2.b :116) yang berbunyi “UPTD yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah UPTD pada Dinas Pendidikan meliputi UPTD Pendidikan Dasar”.
“UPTD Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD Pendidikan wajib melaksanakan prinsip koordinasi baik di lingkungan kerja sendiri maupun satuan organisasi serta dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
2. Wilayah Kerja
Dasar/landasan penulisan Memori Jabatan ini adalah :
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 9 tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tenis Pendidikan dan Kebudayaan Bayan.
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.2/4026/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan/Penunjukkan dalam jabatan Struktural Eselon II, III, IV, dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Wilayah kerja UPT DIKPORA Kec. Bayan adalah meliputi 25 desa dan 1 kelurahan, yaitu :
- Desa Bayan
- Desa Tanjungrejo
- Desa Besole
- Desa Dewi
- Desa Bandungrejo
- Desa Botorejo
- Desa Bandung kidul
- Desa Botodaleman
- Desa Jatingarang
- Desa Dukuhrejo
- Desa Tangkisan
- Desa Pekutan
- Desa Krandegan
- Desa Pucangagung
- Desa Ketiwijayan
- Desa Sambeng
- Desa Jono
- Desa Jrakah
- Desa Pogung juru tengah
- Desa Bringin
- Desa Pogungrejo
- Desa Grantung
- Desa Pogungkalangan
- Desa Kalimiru
- Desa Banjarejo
- Kelurahan Sucen juru tengah
Adapun luas wilayah Kecamatan Bayan meliputi areal seluas 4.321.160 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Gebang
- Sebelah Timur: Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Banyuurip
- Sebelah Selatan: Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngombol
- Sebelah Barat: Kecamatan Kutoarjo
Wewenang dan tanggung jawab kepala UPT DIKPORA Kecamatan Bayan adalah meliputi :
1. Jumlah Sekolah PAUD, TK, SD, dan MI
- Jumlah PAUD : 20
- Jumlah Taman Kanak: 32
- Jumlah Sekolah Dasar: 28
- Jumlah Madrasah Ibtidaiyah: 2
2. Jumlah Murid PAUD, TK, SD, dan MI
- Jumlah Murid PAUD : 524 anak
- Jumlah Murid TK : 1109 anak
- Jumlah Murid SD : 4133 anak
- Jumlah Murid MI : 221 anak
3. Jumlah Guru PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Guru PAUD: 68 orang
- Guru TK N Pembina: 6 orang
- Guru TK DPK: 26 orang
- Guru Swasta: 82 orang
- Penjaga: 2 orang
- TU: 3 orang
4. Jumlah Kepala SD, Guru SD, dan Penjaga SD
- Kepala SD: 23 orang
- Guru Kelas: 128 orang
- Guru Olahraga : 28 orang
- Guru Agama Islam: 19 orang
- Penjaga SD: 8 orang
- Guru WB: 78 orang
5. Jumlah Kepala MI, Guru MI, dan Penjaga MI
- Kepala MI: 1 orang
- Guru Kelas: 5 orang
- Guru Olahraga: – orang
- Guru Agama Islam: 2 orang
- Tenaga Administrasi: 1 orang
- Penjaga: 1 orang
- Guru WB: 108 orang
6. Organisasi Pemuda di Kecamatan Bayan
Karang Taruna 26 kelompok, berlokasi di setiap desa se-Kecamatan Bayan yang berjumlah 26 desa. Kegiatan Olahraga, meliputi 12 cabang yaitu :
- Sepak Bola
- Gerak Jalan
- Bola Volly
- Kasti
- Bulutangkis
- SKJ
- Tenis Meja
- Atletik
- Sepak Takraw
- Pencak Silat
- Catur
- Tarik Tambang
7. Jumlah Gugus Depan di Kecamatan Bayan
- Siaga: 30 pa + 30 pi
- Penggalang: 6 pa + 6 pi
- Gudep Teritorial: Gudep
- Penegak: 1 pa +1 pi
8. Peninggalan Benda Purbakala
- Prasasti
- Joni
- Beji (sumur)
- Masjid
- Batu Bata
- Guci
- Besi Aji
- Uang Logam
- Kayu Bekas Titian
- Krowong
9. Organisasi Kesenian Yang Ada di Kecamatan Bayan
- Tari Klasik
- Karawitan
- Paduan Suara
- Shalawatan
- Orkes Melayu
- Orkes Keroncong
- Kemprengan
- Samroh
- Dolalak
- Wayang Kulit
- Campursari
- Kuda Kepang
10. Kepercayaann Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada dua :
- SBP 1945
11. Kantor UPT DIKPORA
Kec. Bayan menempati gedung milik sendiri di atas tanah millik Desa Besole dengan cara menyewa dan dibangun secara gotong-royong pada tahun 1970 (pada tahun 1966 berada di Desa Bandungrejo rumah Bapak Suyud Hadi Saputra). Jumlah karyawan Kantor UPT DIKPORA Kec. Bayan ada 11 terdiri dari :
- Kepala UPT: – orang
- Pengawas TK/SD: 4 orang
- Penilik PAUD: 1 orang
- Ka. Subag. TU: 1 orang
- Staf: 4 orang
- WB: 1 orang
Sesuai Dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 821.2/4026/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan/Penunjukkan dalam jabatan Struktural Eselon II, III, IV, dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka Kepala UPT DIPORA Kec. Bayan mempunyai wewenang untuk memonitoring, menilai, dan mengendalikan bidang TK/SD, keolahragaan, Pendidikan Generasi Muda, Pendidikan Masyarakat, Kebudayaan dan Pengembangannya.
Dalam melaksanakan tugas, kami selalu bekerja sama dengan Nivo Kecamatan, terutama dengan Muspika dan dibantu oleh seluruh staf UPT DIPORA Kec. Bayan dan seluruh masyarakat.
D. Gambaran Lokasi UPT DIKPORA Kecamatan Bayan
Lokasi UPT DIKPORA Kecamatan Bayan yang beralamat di Jl. Gajah Mada Km. 07 Purworejo, Desa Besole, Kec. Bayan, Kab Purworejo,. Kode POS 54223.
E. Korelasi UPT DIKPORA dengan SMK Negeri 2 Purworejo
Korelasi dalam dunia pendidikan antara UPT DIKPORA dan SMK Negeri 2 Purworejo yaitu sama-sama untuk saling memajukan pendidikan agar anak didiknya mendapatkan pelajaran atau ilmu yang bermanfaat bagi dirinya serta nusa dan bangsa.
Bab III. Hasil Prakerin
A. Persiapan
Berkaitan dengan adanya program Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Purworejo, yang bertujuan untuk memenuhi kurikulum di sekolah, maka sekolah kami mengajukan izin Praktek Kerja Lapangan di UPT DIKPORA Kecamatan Bayan pada Tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 17 Maret 2017, adapun persiapannya sebagai berikut :
- Surat Tugas
- Buku Prakerin
- Daftar Hadir Prakerin
- Kartu Identitas Peserta Prakerin
Prakerin SMK Negeri 2 Purworejo tersebut yang berlandaskan pada :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan
- Kepmendikbud No. 080/U/1993, tentang Kurikulum SMK
- Kepmendikbud No. 323/U/1993, tentang Penyelenggaraan PSG pada SMK
B. Pelaksanaan dan hasil Kegiatan
Pelaksanaan Prakerin di mulai tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 17 Maret 2017, di Kantor UPT DIKPORA Kecamatan Bayan.
1. Pelaksanaan
- Pembelajaran di dunia kerja adalah bagian intergral dari program diklat secara menyeluruh, karena itu materi yang dipelajari dan kompetensi yang dilatihkan harus jelas kaitannya dengan profil kompetensi tamatan yang ditetapkan.
- Mengingat iklim kerja yang ada di SMK berbeda dengan yang terjadi di dunia kerja maka sekolah menyiapkan peserta sesuai dengan karakteristik dan tuntutan dunia kerja tempat berlatih.
- Sebelum peserta diterjunkan untuk belajar di dunia kerja, sekolah bersama Institusi Pasangan mengadakan pembekalan bagi peserta yang menyangkut :
- Pemahaman tentang program pelatihan yang akan diikuti
- Pemahaman peraturan ketenagakerjaan secara umum dan tata tertib (disiplin) pekerja di tempat mereka akan bekerja
- Orientasi tempat kerja
- Peserta ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan program yang telah disepakati
- Sejauh berkaitan dengan misi program peserta dapat diperlakukan sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya
- Peserta dapat diberi pekerjaan lain, sejauh tidak mengganggu program yang telah ditetapkan
- Segala sesuatu yang menyangkut peraturan dan tata tertib, disiplin pekerja di institusi pasangan dunia kerja dapat dilakukan terhadap peserta sejauh berkaitan dengan misi program
- Kegiatan pelatihan di institusi pasangan diprogramkan sesuai dengan program bersama yang telah disepakati
- Peserta pelatihan adalah tingkat dua semester kedua selama satu bulan dan tingkat tiga semester kedua selama dua bulan.
2. Hasil Kegiatan
Pada pelaksanaan prakerin di Kantor UPT DIKPORA Kec. Bayan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:
| NO | Kegiatan |
| 1. | Melaksanakan Pelayanan Prima |
| 2. | Mengetik dan mengolah dokumen/data secara manual/computer |
| 3. | Mengerjakan administrasi secara manual/computer |
| 4. | Menangani tamu |
| 5. | Menangani telepon/facsimile |
| 6. | Mengelola pertemuan/rapat |
| 7. | Mengelola arsip/dokumen kantor |
| 8. | Menangani alat tulis/perlengkapa kantor |
| 9. | Menangani jadwal kegiatan/perjalanan dinas pimpinan |
a. Umum meliputi pengelolaan surat menyurat serta kearsipan :
- Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- Penerimaan dan pelayanan tamu
- Mengurus/ mengatur rumah tangga kantor
- Mengesahkan salinan ijasah/STTB dan mengganti yang hilang/rusak
- Lain-lain yang bersifat umum.
b. Kepegawaian meliputi :
- Pengelolaan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya dari pendidikan prasekolah.
- Mengerjakan buku induk pegawai dan data file
- Menyelesaikan DP3
- Membuat pengawasan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiunan
- Pelaksana usulan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Tata Usaha, Penjaga dari Persekolahan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah
- Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai UPT Dikpora Kec. Bayan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga UPT Dikpora Kec. Bayan
- Pelaksana Tata Usaha perbekalan/material.
c Perlengkapan meliputi :
- Memelihara dan menyimpan barang-barang inventaris kantor
- Menerima dan mendistribusikan barang-barang droping
- Mendata barang-barang inventaris kantor
- Membuat laporan
- Lain-lain yang berhubungan dengan perlengkapan
d. Keuangan yang meliputi :
- Mengambil dan membagi gaji Guru SD
- Membukukan dan mempertanggungjawabkan penerimaan ATK (belanja rutin)
- Meng-SPJkan penerimaan alat tulis
- Pengurusan belanja Ma tersebut Sub 1 meliputi :
- Belanja alat rumah tangga kantor
- Biaya dokumentasi
- Biaya pemeliharaan gedung
- Biaya pemeliharaan peralatan kantor
e. Data dan statistik meliputi :
- Mengumpulkan dan mengelola data laporan TK/SD
- Menyusun/menyajikan data
- Membuat laporan mengenai perkembangan pendidikan TK/SD
- Lain-lain yang berhubungan dengan data statistik.
Demikian hasil kegiatan yang penulis peroleh selama melaksanakan praktek Prakerin di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut selama lebih kurang dua bulan tersebut.
Bab IV. Penutup
A. Kesimpulan
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi, dan dapat mengenal lebih jauh bagaimana cara bekerja dilapangan sesuai keahlian masing-masing siswa. Sehingga siswa dapat melihat gambaran mengenai kagiatan bidang usaha dimasa yang akan datang, serta siswa-siswi mengetahui standar kompetensi yang akan dijadikan peluang kerja dan kesempatan kerja.
Dalam dunia usaha dibutuhkan kedisiplinan yang cukup baik, instansi-instansi biasanya memerlukan karyawan yang disiplin, terampil, rajin dan cerdas. Pada praktek kerja lapangan ini diperlukan keahlian yang cukup. Selama penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Mekarmukti, penulis merasa bangga bisa mendapatkan Ilmu yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya serta memperoleh banyak pengalaman.
Tujuan lain PKL (Praktek Kerja Lapangan) adalah menambah wawasan yang luas bagi siswa dan siswi, terutama dalam bidang yang di tempatinya. Adapula tempat yang disukai yakni diruangan pendataan, penulis bisa belajar dan dapat mengetahui yang belum penulis dapatkan selama ini, terutama pengetahuan tentang berbagai aplikasi kependidikan yang tersedia.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) telah terlaksana dengan baik, dengan program keahlian masing-masing tanpa halangan apapun dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPTD Pendidikan beserta semua rekan kerjanya yang telah bersedia menerima penulis apa adanya untuk melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan bersedia mendampingi penulis selama PKL berlangsung.
B. Saran
Dengan segenap kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis menyarankan bagi semua pembaca khususnya siswa-siswi SMK Mekarmukti terutama adik kelas agar lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang diadakan disekolah dan bagi semua teman seperjuangan agar tetap bersemangat dan berjuang dalam mengembangkan potensi diri dan menjaga nama baik sekolah.
Sebuah karya pasti mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, penulis merasa bahwa karya yang telah dibuat ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun semangat kami agar dapat membuat yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk saran dan kritiknya dapat menghubungi sekolah atau pihak yang bersangkutan.
Sebagai kata penutup dalam penulisan tugas ahir ini, penulis panjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan jerih payah penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga apa yang telah kami paparkan dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi diri kami khususnya dan pembaca pada umumnya.
Hanya kepada Allah lah segalanya penulis kembalikan, sebab di tangan-Nyalah sumber segala kebenaran. Bila ada sedikit kebenaran dalam tugas ahir ini semata-mata datangnya dari Allah SWT dan bila terdapat banyak kesalahan itu karena kedho’ifan penulisan.
Demikianlah penulisan laporan ini dibuat, semoga bermanfaat Amin ya Mujibassa’ilin.