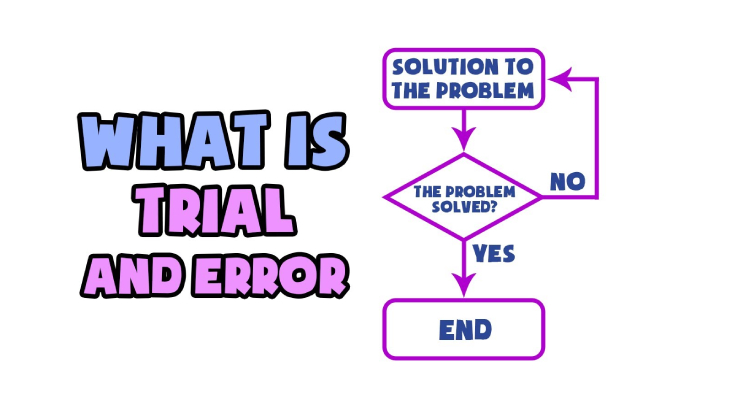Berikut ini Contoh Makalah Perkembangan Peserta Didik dalam perspektif Pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk me
Perkembangan Peserta Didik
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dsb. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangan lebih banyak alternatif lainnya.
Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya “kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama masa kanak-kanak.
Kemampuan berpikir dalam dimensi moral (moral reasoning) pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap “pemberontakan” remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik.pada masa remaja ia akan mempertanyakan mengapa dunia sekelilingnya membiarkan korupsi itu tumbuh subur bahkan sangat mungkin korupsi itu dinilai baik dalam suatu kondisi tertentu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah besar, jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja untuk tidak lagi mempercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua atau pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika orangtua atau pendidik tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, apalagi jika lingkungan sekitarnya tidak mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.
Peranan orangtua atau pendidik sangat besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orangtua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Orangtua yang tidak mampu memberikan penjelasan dengan bijak dan bersikap kaku akan membuat sang remaja tambah bingung. Remaja tersebut akan mencari jawaban di luar lingkaran orangtua dan nilai yang dianutnya. Ini bisa menjadi berbahaya jika “lingkungan baru” memberi jawaban yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orangtua. Konflik dengan orangtua mungkin akan mulai menajam.
Bab II. Tinjauan Pustaka
Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti to grow atau to grow maturity (Golinko, 1984 dalam Rice, 1990). Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, seperti DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan remaja sebagai periode. Papalia dan Olds (2001) tidak memberikan pengertian remaja (adolescent) secara eksplisit melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja (adolescence).
Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.
Menurut Adams & Gullota (dalam Aaro, 1997), masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.
Papalia & Olds (2001) berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan Anna Freud (dalam Hurlock, 1990) berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.
Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai (Hurlock, 1990). Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi badan masih terus bertambah. Sedangkan bagian dari masa dewasa antara lain proses kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak (Hurlock, 1990; Papalia & Olds, 2001).
Remaja: pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa
Yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan (Papalia & Olds, 2001). Perubahan itu dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya pertambahan tinggi atau berat tubuh; dan kualitatif, misalnya perubahan cara berpikir secara konkret menjadi abstrak (Papalia dan Olds, 2001). Perkembangan dalam kehidupan manusia terjadi pada aspek-aspek yang berbeda. Ada tiga aspek perkembangan yang dikemukakan Papalia dan Olds (2001), yaitu:
- perkembangan fisik,
- perkembangan kognitif, dan
- perkembangan kepribadian dan sosial.
Aspek-aspek perkembangan pada masa remaja
A. Perkembangan fisik
Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik (Papalia & Olds, 2001). Perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif (Piaget dalam Papalia dan Olds, 2001).
B. Perkembangan Kognitif
Menurut Piaget (dalam Santrock, 2001), seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru.
Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget (dalam Papalia & Olds, 2001) mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal (dalam Papalia & Olds, 2001).
Tahap formal operations adalah suatu tahap dimana seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan mencapai tahap operasi formal remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Berbeda dengan seorang anak yang baru mencapai tahap operasi konkret yang hanya mampu memikirkan satu penjelasan untuk suatu hal. Hal ini memungkinkan remaja berpikir secara hipotetis. Remaja sudah mampu memikirkan suatu situasi yang masih berupa rencana atau suatu bayangan (Santrock, 2001). Remaja dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan pada saat ini dapat memiliki efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat membahayakan dirinya.
Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, dimana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, dimana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan (Santrock, 2001).
Salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir egosentrisme (Piaget dalam Papalia & Olds, 2001). Yang dimaksud dengan egosentrisme di sini adalah “ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain” (Papalia dan Olds, 2001). Elkind (dalam Beyth-Marom et al., 1993; dalam Papalia & Olds, 2001) mengungkapkan salah satu bentuk cara berpikir egosentrisme yang dikenal dengan istilah personal fabel.
Personal fabel adalah “suatu cerita yang kita katakan pada diri kita sendiri mengenai diri kita sendiri, tetapi [cerita] itu tidaklah benar” . Kata fabel berarti cerita rekaan yang tidak berdasarkan fakta, biasanya dengan tokoh-tokoh hewan. Personal fabel biasanya berisi keyakinan bahwa diri seseorang adalah unik dan memiliki karakteristik khusus yang hebat, yang diyakini benar adanya tanpa menyadari sudut pandang orang lain dan fakta sebenarnya. Papalia dan Olds (2001) dengan mengutip Elkind menjelaskan “personal fable” sebagai berikut :
“Personal fable adalah keyakinan remaja bahwa diri mereka unik dan tidak terpengaruh oleh hukum alam. Belief egosentrik ini mendorong perilaku merusak diri [self-destructive] oleh remaja yang berpikir bahwa diri mereka secara magis terlindung dari bahaya. Misalnya seorang remaja putri berpikir bahwa dirinya tidak mungkin hamil [karena perilaku seksual yang dilakukannya], atau seorang remaja pria berpikir bahwa ia tidak akan sampai meninggal dunia di jalan raya [saat mengendarai mobil], atau remaja yang mencoba-coba obat terlarang [drugs] berpikir bahwa ia tidak akan mengalami kecanduan. Remaja biasanya menganggap bahwa hal-hal itu hanya terjadi pada orang lain, bukan pada dirinya”.
Pendapat Elkind bahwa remaja memiliki semacam perasaan invulnerability yaitu keyakinan bahwa diri mereka tidak mungkin mengalami kejadian yang membahayakan diri, merupakan kutipan yang populer dalam penjelasan berkaitan perilaku berisiko yang dilakukan remaja (Beyth-Marom, dkk., 1993). Umumnya dikemukakan bahwa remaja biasanya dipandang memiliki keyakinan yang tidak realistis yaitu bahwa mereka dapat melakukan perilaku yang dipandang berbahaya tanpa kemungkinan mengalami bahaya itu.
Beyth-Marom, dkk (1993) kemudian membuktikan bahwa ternyata baik remaja maupun orang dewasa memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang berisiko merusak diri (self-destructive). Mereka juga mengemukakan adanya derajat yang sama antara remaja dan orang dewasa dalam mempersepsi self-invulnerability. Dengan demikian, kecenderungan melakukan perilaku berisiko dan kecenderungan mempersepsi diri invulnerable menurut Beyth-Marom, dkk., pada remaja dan orang dewasa adalah sama.
C. Perkembangan kepribadian dan sosial
Yang dimaksud dengan perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik; sedangkan perkembangan sosial berarti perubahan dalam berhubungan dengan orang lain (Papalia & Olds, 2001). Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri. Yang dimaksud dengan pencarian identitas diri adalah proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup (Erikson dalam Papalia & Olds, 2001).
Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding orang tua (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Dibanding pada masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain dengan teman (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Dengan demikian, pada masa remaja peran kelompok teman sebaya adalah besar.
Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang memadai untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentuan diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok teman sebaya (Conger, 1991).
Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang remaja tentang perilakunya (Beyth-Marom, et al., 1993; Conger, 1991; Deaux, et al, 1993; Papalia & Olds, 2001). Conger (1991) dan Papalia & Olds (2001) mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya merupakan sumber referensi utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. Bagi remaja, teman-teman menjadi sumber informasi misalnya mengenai bagaimana cara berpakaian yang menarik, musik atau film apa yang bagus, dan sebagainya (Conger, 1991).
1. Ciri-ciri Masa Remaja
Masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja.
- Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan sebagai masa storm & stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja, misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan nampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah.
- Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
- Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa.
- Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa.
- Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut.
2. Tugas perkembangan remaja
Tugas perkembangan remaja menurut Havighurst dalam Gunarsa (1991) antara lain :
- memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan kawan sebaya, baik laki-laki maupun perempuan
- memperoleh peranan sosial
- menerima kebutuhannya dan menggunakannya dengan efektif
- memperoleh kebebasan emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya
- mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri
- memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan
- mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga
- membentuk sistem nilai, moralitas dan falsafah hidup
Erikson (1968, dalam Papalia, Olds & Feldman, 2001) mengatakan bahwa tugas utama remaja adalah menghadapi identity versus identity confusion, yang merupakan krisis ke-5 dalam tahap perkembangan psikososial yang diutarakannya. Tugas perkembangan ini bertujuan untuk mencari identitas diri agar nantinya remaja dapat menjadi orang dewasa yang unik dengan sense of self yang koheren dan peran yang bernilai di masyarakat (Papalia, Olds & Feldman, 2001).
Untuk menyelesaikan krisis ini remaja harus berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, apakah nantinya ia akan berhasil atau gagal yang pada akhirnya menuntut seorang remaja untuk melakukan penyesuaian mental, dan menentukan peran, sikap, nilai, serta minat yang dimilikinya.
D. Perkembangan Moral Pada Masa Remaja
Istilah moral berasal dari kata Latin “mos” (moris) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.
Nilai-nilai moral itu, seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain, serta larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras dan berjudi.
Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya.
3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orangtuanya. Dia belajar untuk mengenal nlai-nilai dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan nilai moral anak, peranan orangtua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orangtua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak , diantaranya sebagai berikut :
a. Konsisten dalam mendidik anak
Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orangtua pada suatu waktu, harus juga dilarang apabila dilakukan pada waktu lain.
b. Sikap orangtua dalam keluarga
Secara tidak langsung, sikap orangtua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orangtua yang keras (otoriter) cenderung melahirkan sikap disiplin semu oada anak, sedangkan sikap yang acuh tak acuh atau sikap masa bodoh, cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggungjawab dan kurang mempedulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orangtua adalah sikap kasih saying, keterbukaan, musyawarah (dialogis).
Interaksi dalam keluarga turut mempengaruhi perkembangan moral anak
c. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut
Orangtua merupakan panutan (teladan) bagi anak, termasuk disini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orangtua yang menciptakan iklim yang religious (agamis), dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik.
d. Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma
Orangtua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari prilaku berbohong atau tidak jujur. Apabila orangtua mengajarkan kepada anak, agar berprilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggungjawab atau taat beragama, tetapi orangtua sendiri menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya, dan akan menggunakan ketidakkonsistenan orangtua itu sebagai alas an untuk tidak melakukan apa yang diinginkan orangtuanya, bahkan mungkin dia akan berprilaku seperti orangtuanya.
3.3 Karakteristik Perkembangan
Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berfikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masala-masalah yang bersifat hipotetis maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka (Gunarsa,1988).
Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada karena dianggap sebagai suatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggung jawabkannya secara pribadi (Monks, 1988). Perkembangan moral remaja yang demikian, jika meminjam teori perkembangan moral dari Kohlberg berarti sudah mencapai tahap konvensioanl. Pada akhir masa remaja seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut tahap pascakonvensional ketika orisinilitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas. Pemikiran moral remaja berkembang sebagai pendirian pribadi yang tidak tergantung lagi pada pendapat atau pranata yang bersifat konvensional.
Melalui pengalaman atau berinteraksi social dengan orang tua, guru, teman sebaya atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas, seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan.
Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berprilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologis (rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya).
Dikaitkan dengan perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, menurut Kusdwirarti Setiono (Fuad Noshori, Suara Pembaharuan, 7 Maret 1997) pada umunya remaja berada dalam tingkatan konvensional, atau berada dalam tahap ketiga (berprilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok), dan keempat (loyalitas terhadap norma atau peratutan yang berlaku dan diyakininya).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusmara (Mahasiswa PPB FIP IKIP Bandung) terhadap siswa kelas II SMA Negeri 22 Bandung pada tahun 1995 ditemukan bahwa tingkatan moral mereka itu bersifat menyebar, yaitu pada tingkat pra-konvensional (14%), konvensional (38%), dan pasca-konvensional (48%). Jumlah para siswa yang menjadi responden penelitiannya sebanyak 120 orang.
Dengan masih adanya siswa SMU (remaja) pada tingkat pra-konvensional atau konvensional, maka tidaklah heran apabila diantara remaja masih banyak yang melakukan dekadensi moral atau pelecehan nilai-nilai seperti tawuran, tindak criminal, meminum minuman keras, dan hubungan seks di luar nikah.
Remaja berprestasi dan tawuran adalah dua hal berbeda yang merupakan cerminan moral yang dianut remaja.
Keragaman tingkat moral remaja disebabkan oleh factor penentunya yang beragam juga. Salah satu factor penentu atau yang mempengaruhi perkembangan moral remaja itu adalah orangtua. Manurut Adamm dan Gullotta (183: 172-173) terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orangtua mempengaruhi nilai remaja, yaitu sebagai berikut :
- Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat moral remaja dengan tingkat moral orangtua (Haan, Langer & Kohlberg, 1976).
- Ibu-ibu remaja yang tidak nakal mempunyai skor yang lebih tinggi dalam tahapan nalar moralnya daripada ibu-ibu yang anaknya nakal, dan remaja yang tidak nakal mempunyai skor lebih tinggi dalam kemampuan nalar moralnya daripada remaja yang nakal (Hudgins & Prentice, 1973).
- Terdapat dua factor yang dapat meningkatkan perkembangan moral anak atau remaja, yaitu :
- Orangtua yang mendorong anak untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu, dan
- Orangtua yang menerapkan disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir induktif (Parikh, 1980).
3.4 Upaya-upaya Sekolah Dalam Rangka Mengembangkannya
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun social.
Upaya sekolah dalam memfasilitasi tugas-tugas perkembangan siswa akan berjalan baik apabila di sekolah tersebut telah tercipta iklim atau atmosfir yang sehat atau efektif, baik menyangkut aspek menejemennya maupun profesionalisme para personelnya.
Masa remaja akhir sudah mampu memahami dan mengarahkan diri untuk mengemnbangkan dan memelihara identitas dirinya. Dalam proses perkembangan independensi sebagai antisipasi mendekati masa dewasa yang matang, remaja :
- Berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berprilaku, memahami kemampuan dan kelemahan dirinya.
- Meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusia seperti apa yang dia inginkan.
- Memperhatikan etika masyarakat, keinginan orangtua dan sikap teman-temannya.
- Mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkannya.
BAB IV
PERKEMBANGAN NILAI
PADA MASA REMAJA
4.1 Pengertian
Menurut Sutikna (1988:5), nilai adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan-santun. Menurut Spranger , dikutip oleh Sunaryo Kartadinata (1988), nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternative keputusan dalam situassi social tertentu.
Jadi, nilai itu merupakan :
1. Sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya.
2. Produk social yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya.
3. Sebagai standar konseptual yang relative stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya.
Spranger menggolongkan nilai ke dalam enam jenis nilai, yaitu :
1. Nilai teori atau nilai keilmuan
Adalah nilai yang mendasari perbuatan seseorang berdasarkan pertimbangan rasional.
2. Nilai ekonomi
Adalah nilai yang mendasari perbuatan atas dasar pertimbangan untung rugi atau financial.
3. Nilai social atau solidaritas
Tidak memperhitungkan laba atau rugi terhadap dirinya yang penting dia dapat melakukannya untuk kepentingan orang lain dan menimbulkan rasa puas pada dirinya.
4. Nilai agama
Atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu benar menurut agama dan merasa berdosa jika tidak berbuat sesuai yang disyariatkan agama.
5. Nilai seni
Atas dasar pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni yang terlepas dari berbagai pertimbangan material.
6. Nilai Politik
Atas dasar pertimbangan baik-buruknya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.
Remaja sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat memiliki nilai-nilai yang dianutnya. Nilai yang dianut remaja tersebt dapat dipengaruhi oleh posisi kehidupan mereka, apakah kehidupan secara modern atau secara tradisional. Nilai yang dianutnya akan berpengaruh terhadap prilaku remaja tersebut.
Nilai-nilai kehidupan yang perlu diinformasikan dan selanjutnya dihayati oleh para remaja tidak terbatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja, namun juga seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila misalnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, nilai-nilai estetik, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk sesuai dengan perkembangan remaja.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila contohnya :
· Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban.
· Mengembangkan sikap tenggang rasa
· Tidak semena-mena terhadap orang lain.
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Nilai adalah suatu ukuran atau parameter terhadap suatu obyek tertentu Nilai dapat diartikan sebagai ukuran baik atau buruknya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai harga (value) dari sesuatu. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun (sutikna, 1988:5).
Beberapa factor yang mempengaruhi perkembangan nilai ada masa remaja adalah sebagai berikut :
1. Diri Sendiri
Setiap orang memiliki ukuran baik atau buruk sesuatu dengan sudut pandang orang tersebut terhadap sesuatu, sehingga jika si A menganggap bersendawa setelah makan itu adalah baik, belum tentu si B menganggap hal tersebut juga prilaku yang baik. Jadi, setiap orang memiliki penilaian tersendiri terhadap sesuatu yang akan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Hal ini termasuk dalam sikap normative, yaitu nilai merupakan suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku. Misalnya : nilai kesopanan dan kesedrhanaan, orang yang selalu bersikap sopan akan selalu berusaha menjaga tutr kata dan sikapnya sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam masa remaja, mereka menganggap diri mereka adalah benar dan apa yang mereka yakini pun adalah benar.
2. Teman/Orang Terdekat
Pengaruh dari orang lain juga berperan dalam terwujudnya suatu nilai. Teman atau orang terdekat biasanya memiliki suatu paham dan sifat yang hamper sama satu sama lainnya. Dalam pertemanan biasanya mudah untuk saling memahami dan memberikan penanaman suatu paham ke teman lainnya dan orang tersebut akan menganggap suatu paham yang ditanam padanya adalah benar. Ini dikarenakan dalam pertemanan mereka akan saling mempercayai satu sama lainnya. Misalnya : si A berjalan didepan orang yang lebih tua yang sedang duduk tanpa member hormat (membungkuk sedikit), lalu teman terdekatnya yang melihat itu mengatakan bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan dan merupakan hal yang tidak sopan. Seharusnya kita melewati orang yang lebih tua, sebaiknya membungkuk sedikit (member hormat kepada yang lebih tua). Sehingga setelah diberikan pemahaman, si A mengerti dam melakukan apa yang dikatakan temannya tersebut. Pada masa remaja, seseorang akan lebih percaya atau memiliki hubungan yang lebih dekat dengan temannya dibandingkan hubungan dengan keluarganya. Mereka lebih sering bersosialisai dengan temannya sehingga penanaman nilai akan mudah terserap dan ditanam pada diri remaja tersebut.
3. Pergaulan
Pergaulan yang memberikan pengaruh yang baikakan mewujudkan suatu nilai yang baik poula dan sebaliknya. Didalam pergaulan terdapat interaksi nilai yang dianut seseorang. Bisa saja nilai yang dulu dianggap baik dapat berubah menjadi nilai yang buruk setelah interaksi atau penglihatan yang dialaminya dalam pergaulan. Tetapi itu tergantung dari remaja tersebut, apakah ia bertahan terhadap nilai yang telah dianutnya atau akan merubahnya. Di dalam perkembangan, hal ini mungkin saja terjadi. Misalnya menceritakan hal-hal yang buruk/kejelelkan orang lain. Yang dulunya dianggap biasa saja, setelah pergaulan yang membawa nilai positif melalui pembelajaran nilai tersebut berubah menjadi buruk.
Pergaulan pada masa remaja turut menentukan nilai yang dianutnya.
Pergaulan menjadi hal yang penting pada masa remaja. Pada saat itu pergaulan menentukan sikap/tingkah laku dari nilai yang dan seseorang. Pergaulan yang baik akan menciptakan nilai yang baik dan sebaliknya. Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak yang sangat rawan dalam penentuan nilai. Ditekankan sekali lagi bahwa pada masa remaja, seseorang lebih sering berinteraksi dengan temannya dalam bentuk pergaulan disbanding dengan keluarganya.
4. Teknologi
Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di era sekarang, remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh : internet memiliki fasilitas yang menwarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung.
Remaja dan internet
Nilai positifnya, ketika remaja atau siswa mencari bahan pelajaran yang mereka butuhkan mereka dapat mengaksesnya dari internet. Namun internet juga memiliki nilai negative seperti tersedianya situs porno yang dapat merusak moral remaja. Apalagi pada masa remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan sangat rentan terhadap informs sperti itu. Mereka belum bisa mengolah pikiran secara matang yang akhirnya akan menimbulkan berbagai tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan hamil di luar nikah/hamil usia dini.
5. Lingkungan / Masyarakat
Kenyamanan dalam bertempat tinggal memiliki peran yang besar dalam pembentuukan nilai individu. Remaja yang memiliki potensi tersosialisasi baik akan pandai berteman dan memiliki tenggang rasa yang kuat. Hal ini didukung oleh lingkungan yang mendukung pula. Maka akan terwujud nilai kesejaheraan yang baik. Bagi remaja hal ini akan berguna untuk mewujudkan rasa percaya diri dan bersosialisasi yang baik kepada masyarakat.
· Identifikasi dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai model. Maksudnya mengikuti sikap dan prilaku yang dianggapnya sebagai idola.
· Hubungan anak dengan orangtuanya.
· Adanya control dari masyarakat yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri buat pelanggar-pelanggarnya.
· Unsur Lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.
· Aktivitas-aktivitas anak remaja yang diperankannya.
4.3 Karakteristik Perkembangan
Karena masa remaja merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka masa remaja menjadi suatu periode yang sangat penting dalam pembentukan nilai (Horrocks, 1976; Adi, 1986; Monks, 1989). Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang (Sarwono, 1989). Pembentukan nilai-nilai baru dilakukan dengan cara identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau model tertentu atau bisa saja berusaha mengembangkannya sendiri.
4.4 Upaya-upaya Sekolah Dalam Rangka Mengembangkannya
Nilai adalah suatu ukuran atau parameter terhadap suatu obyek tertentu. Nilai dapat diartikan sebagai ukuran baik atau buruknya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai harga (value) dari sesuatu. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun (Sutikna, 1988:5).
Dapat dikatakan bahwa lingkungan adalah faktor yang paling penting bagi perkembangan nilai, remaja yang seiring dengan pematangan kepribadian remaja tersebut. Nilai bersifat abstrak, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Meskipun abstrak, nilai merupakan suatu realitas, sesuatu yang ada dan dibutuhkan manusia. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku, misalnya nilai kesopanan dan kesederhanaan. Misalnya, seseorang yang selalu bersikap sopan santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata dan sikap sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut.
Kondisi psikologis remaja mengalami ketidakstabilan. Dalam keadaan seperti itu, mereka perlu dibimbing untuk mengenal nilai-nilai dalam kehidupan 3 yang tidak terbatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja, tetapi juga nilai-nilai keagamaan, keadilan, estetik dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk sesuai dengan perkembangan remaja.
Ketika anak berada dalam masa perkembangan, pembentukan moralnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Dimulai dari lingkungan keluarga, dimana orang tua mengenalkan nilai-nilai sederhana seperti kesopanan terhadap ayah dan ibu. Saat pergaulan anak tersebut makin luas pada usia remaja, dia akan mengenal lebih banyak nilai-nilai kehidupan melalui kejadian-kejadian di sekitarnya. Remaja terdorong untuk mengidentifikasi peristiwa yang dialaminya sehingga dapat membedakan sikap mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan
Upaya membantu remaja menemukan identitas diri:
a. Berilah informasi tentang pilihan-pilihan karier dan peran-peran orang dewasa
b. Membantu siswa menemukan sumber-sumber untuk memecahkan masalah pribadinya (melalui guru konseling)
c. Bersikap toleran terhadap tingkah laku remaja yang dipandang aneh. Caranya: mendiskusikan tentang tatakrama dlm berpakaian
d. Memberi umpan balik yg realistik tentang dirinya. Caranya: berdiskusi dg siswa, member contoh orang lain yg sukses dalam hidup.
Menurut Kohlberg ;
1. Anak menganggap baik dan buruk atas dasar akibat yang ditimbulkannya berupa kepatuhan dan hukuman atas kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya, jika anak tidak mau belajar maka dia tidak akan diijinkan untuk bermain dengan temannya.
2. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung kepada aturan yang ada di luar dirinya atau ditentukan oleh orang lain, tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadian dapat dipandang dari berbagai sisi yaitu sisi manfaat dan kerugiannya.
3. Anak mulai memasuki umur belasan tahun, dimana anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain.
4. Anak merasakan bahwa perbuatan baik yang diperlihatkan bukan hanya agar dapat diterima lingkungan, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan atau norma sosial, contohnya seorang remaja yang mulai belajar menghormati orang yang lebih tua dengan bersikap ramah dan santun
5. Remaja menyadari adanya hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial melalui kata hati yang dirasakannya. Maksudnya, jika dia menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat maka lingkungan aka memberikan perlindungan dan rasa nyaman padanya.
6, (Prinsip Universal), remaja mengadakan penginternalisasian moral yaitu remaja melakukan tingkah laku moral yang dikemudikan oleh tanggung jawab batin sendiri, menjadikan penilaian moral sebagai nilai-nilaipribadi yang tercermin pada tingkah lakunya.
Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Hurlock (1986: 322) mengemukakan bahwa sekolah merupakan factor penentu bagi perkembangan kepribadian anak (siswa), baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berprilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orangtua. Ada beberapa alassan, mengapa sekolah memainkan peranan penting yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu ;
a) Siswa harus hadir disekolah
b) Sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan ‘konsep dirinya”.
c) Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah
d) Sekolah member kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses
e) Sekolah member kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistic.
BAB V
PERKEMBANGAN AGAMA
PADA MASA REMAJA
5.1 Pengertian
Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan emosi yang begitu cepat dalam diri remaja,,seperti ketidakstabilan perasaan remaja kepada Tuhan/Agama.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adams dan Gullotta (1983), agama memberikan sebuah kerangka moral, sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya, agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini, agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya.
Fitrah beragama ini merupakan disposisi (kemampuan dasar) yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama remaja sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang direfleksikan kedalam peribadatan kepada-Nya.
Kebutuhan remaja akan Allah kadang-kadang tidak terasa ketika remaja dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Sebaliknya Allah sangat dibutuhkan apabila remaja dalam keadaan gelisah, ketika ada ancaman, takut akan kegelapan, ketika merasa berdosa.
Jadi,,kesimpulannya,,perasaan remaja pada agama adalah ambivalensi. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya pada Tuhan, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh dan menentang (Zakiyah Darajat, 2003:96-96 dan Sururin, 2002:70).
5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Tidak sedikit remaja yang bimbang dan ragu dengan agama yang diterimanya,,W. Sturbuck meneliti mahasiswa Middle Burg College. Dari 142 remaja yang berusia 11-26 tahun, terdapat 53% yang mengalami keraguan tentang:
a) Ajaran agama yang mereka terima.
b) Cara penerapan ajaran agama.
c) Keadaan lembaga-lembaga keagamaan.
d) Para pemuka agama
Menurut analisis yang dilakukan W.Starbuck, keraguan itu disebabkan oleh factor:
1. Kepribadian
Tipe kepribadian dan jenis kelamin, bisa menyebabkan remaja melakukan salah tafsir terhadap ajaran agama.
Ø Bagi individu yang memiliki kepribadian yang introvert, ketika mereka mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhan.
Misalnya: Ketika berdoa’a tidak terkabul,,maka mereka akan menjadi ragu akan kebenaran sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang Tuhan tersebut. Kondisi ini akan sangat membekas pada remaja yang introvert walau sebelumnya dia taat beragama.
Ø Untuk jenis kelamin
Wanita yang cepat matang akan lebih menunjukkan keraguan pada ajaran agama dibandingkan pada laki-laki cepat matang.
2. Kesalahan Organisasi Keagamaan dan Pemuka Agama
Kesalahan ini dipicu oleh “dalam kenyataannya,,terdapat banyak organisasi dan aliran-aliran keagamaan”. Dalam pandangan remaja hal itu mengesankan adanya pertentangan dalam ajaran agama. Selain itu remaja juga melihat kenyataan “Tidak tanduk keagamaan para pemuka agama yang tidak sepenuhnya menuruti tuntutan agama”.
3. Pernyataan Kebutuhan Agama
Pada dasarnya manusia memiliki sifat konservatif (senang dengan yang sudah ada),, namun disisi lain,,manusia juga memiliki dorongan curiosity (dorongan ingin tahu).
Kedua sifat bawaan ini merupakan kenyataan dari kebutuhan manusia yag normal. Apa yang menyebabkan pernyataan kebutuhan manusia itu berkaitan dengan munculnya keraguan pada ajaran agama?
Dengan dorongan Curiosity, maka remaja akan terdorong untuk mempelajari/mengkaji ajaran agamanya. Jika dalam pengkajian itu terdapat perbedaan-perbedaan atau terdapat ketidaksejalanan dengan apa yang telah dimilikinya (konservatif) maka akan menimbulkan keraguan.
4. Kebiasaan
Remaja yang sudah terbiasa dengan suatu tradisi keagamaan yang dianutnya akan ragu untuk menerima kebenaran ajaran lain yang baru diterimanya/dilihatnya.
Kebiasaan mengaji untuk menanamkan nilai-nilai agama
5. Pendidikan
Kondisi ini terjadi pada remaja yang terpelajar. Remaja yang terpelajar akan lebih kritis terhadap ajaran agamanya. Terutama yang banyak mengandung ajaran yang bersifat dogmatis. Apalagi jika mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan ajaran agama yang dianutnya secara lebih rasional.
6. Percampuran Antara Agama dengan Mistik
Dalam kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat,,kadang-kadang tanpa disadari ada tindak keagamaan yang mereka lakukan ditopangi oleh mistik dan praktek kebatinan. Penyatuan unsur ini menyebabkan remaja menjadi ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik.
Penyebab keraguan remaja dalam bidang agama yang dikemukakan oleh Starbuck diatas,,adalah penyebab keraguan yang bersifat umum bukan yang bersifat individual. Keraguan remaja pada agama bisa juga terjadi secara individual. Keraguan yang bersifat individual ini disebabkan oleh:
a. Kepercayaan
Yaitu: Keraguan yang menyangkut masalah ke-Tuhanan dan implikasinya. Keraguan seperti ini berpeluang pada remaja agama Kristen,,yaitu: tentang ke-Tuhanan yang Trinitas.
b. Tempat Suci
Yaitu: keraguan yang menyangkut masalah pemuliaan dan pengaguman tempat-tempat suci.
c. Alat Perlengkapan Agama
Misalnya: Fungsi salib pada ajaran agama kristen
d. Fungsi dan Tugas dalam Lembaga Keagamaan
Misalnya: Fungsi pendeta sebagai penghapus dosa
e. Pemuka agama, biarawan dan biarawati
f. Perbedaan aliran dalam keagamaan
Keraguan yang dialami remaja dalam bidang agama dapat memicu konflik dalam diri remaja. Bentuk dari konflik itu “Remaja akan dihadapkan kepada pemilihan antara mana yang baik dan yang buruk serta antara yang benar dan salah”.
Jenis konflik yang memungkinkan dialami remaja:
a) Konflik yang terjadi antara percaya dan ragu.
b) Konflik yang terjadi antara pemilihan satu diantara dua macam agama atau antara dua ide keagamaan atau antara dua lembaga keagamaan.
c) Konflik yang terjadi oleh pemilihan antara ketaatan beragama atau sekuler.
d) Konflik yang terjadi antara melepaskan kebiasaan masa lalu dengan kehidupan keagamaan yang didasarkan atas petunjuk Ilahi.
Jadi,
v Tingkat keyakinan dan ketaatan remaja pada agama sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelesaikan keraguan dan konflik batin yang terjadi dalam dirinya.
v Dalam upaya mengatasi konflik batin, para remaja cenderung untuk bergabung dalam peer groups-nya dalam rangka berbagi rasa dan pengalaman. Kondisi inipun akan mempengaruhi keyakinan dan ketaatan remaja pada agama (Jalaluddin, 2002:78-81)
Faktor lain yang mempengaruhi adalah,,adanya motivasi dari dalam diri remaja itu sendiri. Menurut Yahya Jaya,,motivasi beragama adalah: Usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindak keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama.
Menurut Nico Syukur, Manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan dalam 4 hal:
1. Didorng oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik:
v Frustasi karena kesukaran alam
v Frustasi karena social
v Frustasi karena moral
v Frustasi karena kematian
2. Didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat
3. Didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia.
4. Didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan.
5.3 Karakteristik Perkembangan
Apakah remaja memikirkan Tuhan sama dengan cara berpikir anak ? Apakah perkembangan intelektual mempengaruhi perkembangan terhadap Tuhan atau agama? Karena pandangan terhadap Tuhan atau agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan berpikir, maka pemikiran remaja tentang Tuhan berbeda dengan pemikiran anak.
Kemampuan berpikir abstrak remaja memungkinkannya untuk dapat mentransformasikan keyakinan beragamanya. Dia dapat mengapresiasi kualitas keabstrakan Tuhan sebagai Yang Maha Adil, Maha Kasih Sayang. Berkembangnya kesadaran atau keyakinan beragama, seiring dengan mulainya remaja menanyakan atau mempermasalahkan sumber-sumber otoritas dalam kehidupan, seperti pertanyaan “Apakah Tuhan Maha Kuasa, mengapa masih terjadi penderitaan dan kejahatan di dunia ini?”
Untuk memperoleh kesadaran beragama remaja ini, dapat disimak dalam uraian berikut :
1. Masa Remaja Awal (sekitar usia 13-16 tahun)
Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan, kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya, mungkin pula mengalami kegoncangan . Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, kan tetapi kadang-kadang menjadi berkurang yang terlihat pada cara beribadah yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan rohaninya cenderung skeptic (was-was) sehingga muncul keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual (misalnya ibadah sholat) yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan.
Kegoncangan alam keagamaan ini mungkin muncul, dikarenakan oleh factor internal maupun eksternal. Faktor internal yang berkaitan dengan matangnya organ seks, yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun disisi lain ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang agama. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja. Faktor internal lainnya adalah bersifat psikologis, yaitu sikap independen, keinginan untuk bebas, tidak mau terikat oleh norma-norma keluarga ( orangtua). Apabila orangtua atau guru-guru kurang memahami da mendekatinya secara baik, bahkan bersikap keras, maka sikap itu akan muncul dala bentuk tingkah laku negative (negativisme), seperti membandel, oposisi, menentang atau menyendiri, dan acuh tak acuh.
Apabila remaja kurang mendapat bimbingan keagamaan dalam keluarga, kondisi keluarga yang kuarang harmonis, orangtua yang kurang memberikan kasih saying dan berteman dengan kelomopok sebaya yang kurang menghargai nilai-nilai agama, maka kondisi diatas akan menjadi pemicu berkembangnya sikap dan perilaku remaja yang kurang baik atau asusila, seperti pergaulan bebas (free sex), minum-minuman keras, mengisap ganja dan menjadi troublemaker (pengganggu ketertiban/pembuat keonaran) dalam masyarakat.
2. Masa Remaja akhir ( 17-21 tahun)
Secara psikologis, masa ini merupakan permulaan masa dewasa, emosinya mulai stabil dan pemikirannya mulai matang (kritis). Dalam kehidupan beragama, remaja sudah mulai melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Remaja sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya diantaranya ada yang shalih dan ada yang tidak shalih. Pengertian ini memungkinkan dia untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama, namun tidak melaksanakan ajaran agama atau perilakunya bertentangan dengan nilai agama.
Salah satu tugas perkembangan yang diukur adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ;
1. Mengembangkan pemahaman agama
2. Meyakini agama sebagai pedoman hidup
3. Meyakini bahwa setiap perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan
4. Meyakini kehidupan akhirat
5. Meyakini bahwa Tuhan Maha Penyayang dan Maha Pengampun
6. Melaksanakan ibadah
7. Mempelajari kitab suci
8. Berdoa kepada Tuhan
9. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama
10. Menghormati kedua orangtua dan orang lain
11. Bersabar dan bersyukur
5.4 Upaya-upaya Sekolah Dalam Rangka Mengembangkannya
5.4.1 Pendidikan Agama di Sekolah dan Pembinaan Mental Remaja
Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul, kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru Agama di sekolah apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidak sukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurang senangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens, yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton teve, jalan-jalan ke mall, “ngeceng”, pacaran dan hal-hal lain meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktifitas positif seperti remaja mesjid, berwiraswasta atau ikut organisasi eskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan.
Cara seorang guru mengajar turut mempengaruhi pemahaman yang diterima anak/remaja.
Jawaban dari permasalahan diatas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama (having religion) melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive, yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton teve, jalan-jalan, hura-hura dan lain sebagainya.
Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru Agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja, seorang guru Agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah (kurikulum) atau kepentingan guru Agama melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru Agama di sekolah. Seorang guru Agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agamapun harus terkesan akrab dan kemunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog (satu arah), indoktriner, terkesan sangar (karena hanya membicarakan halal haram) harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan (dalam rangka penghayatan makna ibadah) atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut (sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial). Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah.
Namun diatas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah disamping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal (intrinsik) di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar usur-unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda (remaja) yang berkualitas.
5.4.2 Upaya-upaya Sekolah Dalam Rangka Mengembangkannya
Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut (pola ibadah).
Menurut Havighurs (1961:5), sekolah memunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah seyogyanya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa ( yang berusia remaja) untuk mencapai perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam berinteraksi social, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tugas perkembangan agama pada masa remaja ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan, yang mempunyai tugas suci untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah ini misinya adalah untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan atau kenyamanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan keimanan dan ketakwaan ini merupakan tugas perkembangan yang penanamannya dimulai sejak usia dini. Pada usia remaja, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian tugas perkembangang ini, pada setiap remaja tampaknya bersifat heterogen. Heterogenitas perkembangan ini dipengaruhi oleh factor pengalaman keagamaan masing-masing, terutama dilingkungan keluarganya.
Dalam rangka membantu remaja (siswa) dalam mengokohkan atau memantapkan keimanan dan ketakwaannya, maka sekolah seyogyanya melakukan upaya-upaya berikut :
1. Pimpinan (kepala sekolah dan para wakilnya), guru-guru, dan personel sekolah lainnya harus sama-sama mempunyai terhadap program pendidikan agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah, baik melalui :
a) Proses belajar-mengajar di kelas
b) Bimbingan (pemaknaan hikma hidup beragama/beribadah, pemberian dorongan, contoh/tauladn baik dalam bertutur kata, berprilaku, berpakaian, maupun melaksankan ibadah)
c) Pembisaan dalam mengamalkan nilai-nilai agama.
2. Guru agama seyoganya memiliki kepribadian yang mantap (ahlakul karimah), pemahaman dan ketrampilan professional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran, sehingga mata pelajaran agama menjadi menarik dan bermakana bagi remaja.
3. Guru-guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya , sehingga siswa memiliki apresiasi yang positif terhadap nilai-nilai agama.
4. Sekolah menyediakan sarana ibadah (mesjid) sebagai laboratorium rohaniah yang cukup memadai, serta memfungsinkannya secara maksimal.
5. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian, pesantren kilat, ceramah-ceramah keagamaan, atau diskusi keagamaan secara rutin.
6. Bekerja sama dengan orangtua siswa dalam membimbing keimanan dan ketakwaan siswa.
Ekstrakurikuler kerohanian adalah salah satu upaya sekolah dalam mengembangkan nilai agama
Mengenai peranan guru dalam pendidikan akhlak, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa penyembuhan badan memerlukan seorang dokter yang tahu tentang tabiat badan serta macam-macam penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Demikian pula halnya dengan penyembuhan jiwa dan akhlak. Keduanya membutuhkan guru (pendidik) yang tahu tentang tabiat dan kekurangan jiwa manusia serta tentang cara memperbaiki dan mendidiknya. Kebodohan dokter akan merusak kesehatan orang sakit. Begitupun kebodohan guru akan merusak akhlak muridnya.
Sekolah mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik karena sebagian besar waktu mereka habis untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah. peran Sekolah Dalam Mengembangkan Tugas Perkembangan adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya
2. Mencapai perkembangan kemandirian pribadi
3. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME
Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah beragama anak, atau siswa, sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan ini terkait mengembangkan pemahaman, pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia, serta sikap apresiatif terhadap ajaran atau hukum-hukum agama. Upaya-upaya itu adalah sebagai berikut:
1. Dalam mengajar, guru hendaknya menggunakan pendekatan (metode) yang bervariasi (seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demontrasi, dan berkisah), sehingga anak tidak merasa jenuh mengikutinya.
2. Dalam menjelaskan materi pelajaran, guru agama hendaknya tidak terpaku kepada teks atau materi itu saja (bersifat tekstual), tetapi materi itu sebaiknya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat (kontekstual).
3. Guru hendaknya memberikan penjelasan kepada siswa, bahwa semua ibadah ritual (mahdloh) akan memberikan makna yang lebih tinggi di hadapan Allah, apabila nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ibadah tersebut direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Guru hendaknya memiliki kepribadian yang baik (akhlak mulia).
5. Guru hendaknya menguasai bidang studi yang diajarkannya secara memadai, minimal materi-materi yang terkandung dalam kurikulum.
6. Guru hendaknya memahami ilmu-ilmu lain yang relevan atau yang menunjang kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar, seperti psikologi pendidikan, bimbingan konseling, metodologi pengajaran, administrasi pendidikanm teknik evaluasi, dan psikologi belajar agama.
7. Pimpinan sekolah, guru-guru dan pihak sekolah lainnya hendaknya memberikan contoh, tauladan yang baik dalam mengamalkan ajaran agama, seperti dalam melaksanakan ibadah shalat, menjalin tali persaudaraan, memelihara kebersihan, mengucapkan dan menjawab salam, semangat dalam menuntut ilmu, dan berpakaian muslim/muslimat (menutup aurat).
8. Guru-guru yang mengajar bukan pendidikan agama hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam materi-materi pelajaran yang diajarkannya.
9. Sekolah hendaknya menyediakan saran ibadah (mesjid) yang memadai dan memfungsikannya secara optimal.
10. Sekolah hendaknya menyelenggarakan kegiatan ektrakulikuler kerohanian bagi para siswa dan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan secara rutin.
Hal Ini Berdasarkan Teori Perkembangan Peserta Didik Pada Tugas Perkembangan Masa Remaja Menurut Havigrus :
– Mencapai hubungan lebih matang dengan teman sebaya
– Mencapai peran sosial wanita atau pria
– Menerima keadaan fisik dan menggunkan secara efektif
– Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya
– Mencapai jaminan kemandirian ekonomi
– Memilih dan mempersiapkan karir
– Mempersipakan pernikahan dan hidup keluarga
– Mengembangkan ketrampilan intelektual
– Mencapai tingkah laku yang bertangung jawab secara sosial
– Memperoleh seperangkat nilai dan norma dalam bertingkah laku
– Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Zakiyah Darajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, Cet. VII, 1983.
Drs. H. Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cet. II, 1991.
Drs. Jalaluddin Rahmat Msc, Islam Alternatif, Penerbit Mizan, Bandung, Cet. I, 1986.
Makalah-makalah Ibu Dra. Susilaningsih MA (dosen Mata Kuliah Psikologi Agama di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Syamsu Yusuf. (2002). Psikologi Belajar Agama. Bandung: Maestro.
Singgih Gunarsa. (2004). Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. Jakarta: Gunung Mulia
Tim Pustaka Familia. (2006). Konsep Diri Positif, Menentukan Prestasi Anak. Yogyakarta: Kanisius.
Singgih Gunarsa. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
http://ardika.blog.uns.ac.id/files/2010/05/makalah-perkembangan-nilai-moral-dan-sikap/
Ali, Muhammad.2004.Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik.Jakarta : PT. Bumi Aksara.