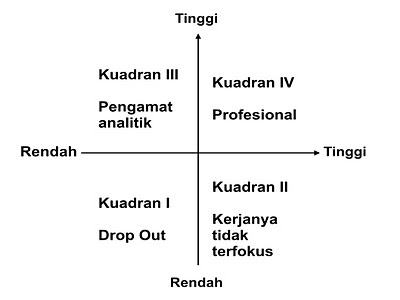Mata Kuliah Kewirausahaan mengkaji tentang prinsip dan konsep kegiatan ekonomi pada industri rumah tangga, kecil dan menengah. Mata kuliah adalah mata kuliah wajib nasional yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran dengan kegiatan produktif pribadi maupun bagi orang lain.
Daftar isi
Kewirausahaan
Mata kuliah ini membahas kewirausahaan yang berbasis prinsip ekonomi, mengingat perkembangan serta paradigma pelayanan kesehatan kewirausahaan orientasinya tidak saja pada pelajaran yang berkualitas tetapi juga berorientasi ekonomi yang dilakukan oleh industri jasa, sebelum membahas tentang kewirausahaan lebih dalam ada baiknya kita kupas dalam tentang Ilmu Ekonomi.
A. Kegiatan Ekonomi
- Menurut Wonnacott Ilmu Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan.
- Menurut Albert L Meyers Ilmu Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan kepuasan kepuasan akan kebutuhan tersebut.
Kaitannya dengan kewirausahaan (entrepreneurship) bagaimana seorang pengusaha atau manager dengan memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.
B. Pembagian Ilmu Ekonomi
- Macro Economy Theory (Teori Ekonomi Makro)
- Micro Economy Theory (Teori Ekonomi Mikro)
Teori Ekonomi Makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan kegiatan ekonomi pada lebih Nasional dan Global baik dalam bentuk unit usaha, pendapatan, produksi, investasi dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, Ekonomi Makro tidak mempelajari tentang kegiatan ekonomi Individu dan perusahaan.
Pendapatan Nasional adalah Jumlah/seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu (dalam 1 Tahun). Perkembangan Pendapatan Nasional ditinjau dari sudut jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dari penjualan barang dan jasa-jasa menurut harga jasa yang berlaku disebut NASIONAL INCOME AT MARKET PRICE dan setelah dikurangi pajak tidak langsung disebut NATIONAL INCOME AT FACTOR COST.
Contoh :
Pabrik Rokok GG menjual rokoknya selama 1 Tahun sebesar Rp. 10 Milyar, dari penjualan tersebut menghabiskan bahan baku dan sebagainya sebanyak Rp 7 Miliar jadi penghasilan Nasional Incom Of Market Price Nya sebesar Rp. 3 Milyar sebagai pengusaha berkewajiban membayar pajak kepada Pemerintah sebesar Rp. 1 Milyar maka National Income At Factor Cost Nya sebesar Rp. 2 Milyar.
Yang dimaksud dengan Teori Ekonomi Mikro adalah Pengetahuan ekonomi yang mempelajari unsur-unsur ekonomi secara individu atau perusahaan sebagai pemecahan dari variable-variabel ekonomi makro biasanya membahas harga-harga barang dan jasa secara individual.
Mereka yang menghasilkan produk disebut produsen dan yang menggunakan disebut konsumen. Interaksi antara produsen dan konsumen timbul demand and supply theoridisebut Alternative Productive Possibilities.
Seandainya pilihan pada A maka semua resources kita gunakan untuk menghasilkan barang sandang (15) bahan pangan (0). Bila pilihan selanjutnya pada F maka semua resources digunakan untuk menghasilkan bahan pangan (5) sandang (0). Pilihan A dan F adalah pilihan ekstrim dan pilihan BCDE adalah kombinasi antara (A↔f).
C. Sistem Perekonomian Indonesia
Perekonomian Nasional dan kesejahtraan sosial di Indonesia berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila dimana secara Demokrasi Ekonomi produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua dibawah pimpinan atas pemilihan anggota-anggota masyarakat.
1. Ciri Positif
a. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
b. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara diperuntukan kemakmuaran rakyat.
c. Bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
d. Hak milik perorangan diakui.
e. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Ciri Negatif
a. System etatisme = Negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan yang bisa mematikan daya kreasi.
b. Sistem Free Fight Liberalism = menumbuhkan eksloitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
c. Monopoli = Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok.
D. Pengertian/Definisi Wirausaha
Pengertian dan Penggunaan istilah wirausaha sama dengan wiraswasta. Wirausaha dalam bahasa asing disebut Entrepreneur, kewirausahaan disebut Entrepreneurship. Pengertian wirausaha = wiraswasta = Saudagar, wiraswasta berasal dari kata Wira yang berarti manusia unggul, pahlawan, teladan, berbudi luhur, berani, pahlawan, berjiwabesar. Swa artinya sendiri dan Sta artinya berdiri sedangkan saudagar berasal dari kata Sau yang berarti seribu ; dagar artinya akal. Jadi pengertian wirausaha = wiraswasta :
1. Menurut Wasty Soemanto wiraswasta adalah keberanian, keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.
2. Menurut Daued Yoesoef menyatakan bahwa wiraswasta adalah ;
1. Memimpin usaha baik secara teknis atau ekonomis dengan berbagai aspek fungsional ;
a. Memiliki dipadang dari sudut permodalan (owner)
b. Memanage (manager)
c. Menanggung resiko.
d. Pelopor usaha artinya menciptakan sesuatu yang new and different
e. Innovative, imitator
2. Membawa keuntungan uang maksimal
3. Membawa usaha kearah kemajuan perluasan, pengembangan melalui jalan kepemimpinan ekonomi.
Kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah satu proses dari menjalankan kegiatan baru kreatif, inovatif dalam memproses sesuatu untuk dirinya dengan member nilai tambah bagi masyarakat. Jadi tidak hanya bertumpu pada faktor ekonomi saja tetapi pertimbangan sosiologis dan politis.
E. Ada 5 Tipe Pokok Wiraswasta yaitu :
1. Wiraswasta sebagai orang Vak (Captain of industry) dibidang tertentu ia membangkitkan dirinya untuk berprestasi mempertahankan dan mengembangkan kewirausahaan.
2. Wiraswasta adalah orang bisnis baik untuk dirinya keluarga maupun untuk lingkungannya.
3. Wiraswasta adalah sosial engineer artinya owner mengingatkan pegawainya meminimalisir kerugian perusahaan
4. Wirausaha adalah manager untuk memajukan usahanya dengan managemen modern
5. Wirausaha adalah sebagai orang uang.
Peranan Wirausaha :
1. Harus mampu memecahkan persoalan bangsa dari belenggu kemiskinan dan pengangguran.
2. Sebagai Generator pembangunan lingkungan dibidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahtraan.
3. Memberi contoh pada masyarakat demi sebagai pribadi unggul yang patut di contoh dan diteladani karena RAJUBER.
4. Menghormati hukum dan perundang-undangan
5. Membangun dirinya dan membantu masyarakat
6. Mendidik karyawan menjadi mandiri disiplin dan jujur
7. Memberi contoh bagaimana bekerja keras tetapi tidak melupakan perintah agama.
8. Hidup efisien tidak boros.
Manfaat Wirausaha :
Ada dua darmabakti wirausaha dalam pembangunan bangsa yaitu :
1. Sebagai pengusaha memberikan darmabakti melaksanakan proses produksi, distribusi dan konsumsi dalam berusaha mengingatkan pendapatan masyarakat.
2. Sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi mengingatkan ketahanan Nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing.
Dari uraian tersebut diatas, kemudian mengapa masyarakat kurang berminat terhadap profesi wirausaha ? banyak faktor dari jawaban ialah ;
1. Menjadi wirausaha memiliki sifat agresif
2. Ekspansif
3. Bersaing
4. Egois
5. Tidak jujur
6. Kikir
7. Sumber penghasilan tidak setabil
8. Pekerjaan rendah
9. Tidak terhormat
Pandangan semacam ini dianut oleh sebagaian penduduk, sehingga mereka tidak tertarik, mereka tidak menginginkan anaknya terjun ke dunia wirausaha bahkan cita-citanya diarahkan untuk menjadi Pegawai Negeri bukan Pedagang.
Landasan filosofis ini yang menyebabkan Putra-putri (Anak bangsa) ini tidak termotifasi terjun kedunia bisnis.
Rakyat Indonesia sebagaian besar beragama Islam seharusnya meniru/mencontoh Rosullullah SAW yang bergerak dibidang bisnis.
“Pekerjaan apa yang paling baik ya Rosullullah? Rosullullah menjawab seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. Yang bersih berarti sebagaian dari kegiatan profesi bisnis.
Gambaran ideal manusia wiraswasta adalah orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya, tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapinya, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan instansi sosial. Dan dalam keadaan yang bisa (tidak darurat) manusia-manusia wiraswasta bahkan akan mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir batin.
DR. Suparman mengatakan ciri manusia wiraswasta sebagai berikut:
1. Tahu apa maunya, dengan merumuskannya, merencanakan upaya, dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya.
2. Berpikir teliti dan berpandang kreatif dengan imajinasi konstruktif.
3. Siap mental untuk menyerap dan menciptakan kesempatan serta siap mental dan kopetensi untuk memenuhi persyaratan kemahiran mengerjakan sesuatu yang positif.
4. Membiasakan diri bersikap mental positif maju dan selalu bergairah dalam setiap pekerjaan.
5. Mempunyai daya penggerak dari yang selalu menimbulkan inisiatif.
6. Tahu menyesuaikan dirinya, waktu dan mensyukuri lingkungannya.
7. Bersedia membayar harga kemajuan, yaitu kesediaan berjerih payah.
8. Memajukan lingkungan dengan menolong orang lain, agar orang lain dapat menolong dirinya sendiri.
9. Membiasakan membangun disiplin diri, bersedia menabung dan membuat anggaran waktu dan uang.
10. Selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, kesalahan dan pengalaman pahit, selalu berprihatin selalu.
11. Menuasai salesmanship (kemampuan jual), memiliki kepemimpinan, dan kemampuan memperhitungkan resiko.
12. Mereka berwatak maju dan cerdik, serta percaya pada diri sendiri.
13. Mampu memusatkan perhatian terhadap setiap tujuannya.
14. Berkepribadian menarik, memahami seni berbicara dan seni bergaul.
15. Jujur, bertanggung jawab, ulet, tekun dan terarah.
16. Memperhatikan kesehatan diri.
17. Menjauhkan diri dari sifat iri dengki, rakus, dendam atau takut tersaingi.
18. Bersyukur kepada Tuhan YME.
Keuntungan dan Kelebihan menjadi Wirausaha :
a. Keuntungan menjadi wirausaha.
1. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri,
2. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh,
3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal,
4. Terbuka seseorang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha kongkrit,
5. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos.
b. Kelemahan :
1. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, dan memikul berbagai resiko, jika resiko ini diantisipasi secara baik, maka berarti wirausaha telah menggeser resiko tersebut.
2. Bekerja keras dan waktu / jam kerjanya panjang
3. Kualitas kehidupannya masih rendah, sampai usahanya berhasil, sebagai dia harus berhemat.
4. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya.
1. Beberapa Faktor Kritis Untuk memulai usaha baru
Ada beberapa faktor kritis yang berperan dalam membuka usaha baru yaitu:
1. Personal, menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang.
2. Sociological, menyangkut masalah hubungan dengan family dsb.
3. Environmental, mengangkut hubungan dengan lingkungan (Bygrave,1994:3).
Apabila seseorang mempunyai ide untuk membuka suatu usaha baru maka dia mencari faktor-faktor lain yang dapat mendorongnya. Dorongan-dorongan ini tergantung pada beberapa faktor antara lain faktor famili, teman, pengalaman , keadaaan ekonomi, keadaaan lapangan kerja dan sumber daya yang tersedia.
Faktor sosial lainnya yang berpengaruh terhadap minat memualai bisnis ini ialah masalah tangung jawab terhadap keluarga. Orang yang berumur 25 tahun akan lebih mudah membuka bisnis dibandingkan dengan seseorang yang berumur 45 tahun, yang sudah punya istri, beberapa anak, banyak beban, cicilan rumah, biaya rumah tangga dan sebagainya. Di samping ini ada faktor sosial lainnya yang berpengaruh.
Faktor lain yang berpengaruh dalam membuka bisnis ialah pertimbangan antara pengalaman dengan spirit, energi dan rasa optimis. Biasanya orang-orang muda lebih optimis energk, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berumur. Oleh sebab itu pembukaan usaha sebaiknya dilakukan pada saat seseorang memiliki rasa optimis dan sudah dipertimbangkan secara matang.
2. Model Proses Kewirausahaan
Model proses perintisar dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Bygrave menjadi urutan langkah-langkah berikut ini.
| Innovation (Inovasi) |
| Triggering Event (Pemicu) |
| Implementation (Pelaksanaan) |
| Growth (Pertumbuhan) |
1. Proses inovasi
Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Adanya inofasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia menjadi pemicu kearah memulai usaha.
Sedangkan faktor-faktor enfiroment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman dan kreatifitas tidak diragukan lagi pengalaman adalah sebagai guru yang berharga yang memicu perintisan usaha apalagi ditunjang oleh adanya peluang dan kreatifitas
2. Proses pemicu
Beberapa faktor personal yang mendorong Trigger Event artinya memicu atau memaksa seseorang untuk terjun kedunia bisnis adalah:
– Adanya ketidak puasan terhadap pekerjaan yang sekarang,
– Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak ada pekerjaan lain,
– Dorongan karena faktor usia,
– Keberanian menanggung resiko,
– Dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis,
Faktor-faktor Environment yang mendorong pemicu bisnis adalah:
– Adanya persaingan dalam dunia kehidupan
– Adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya memiliki tabungan, modal, warisan, memiliki bangunan yang lokasi strategis dan sebagainya
– Mengikuti latihan-latihan atau incubator bisnis sekarang banyak kursus-kursus bisnis dan lembaga manajemen fakultas ekonomi melaksanakan pelatihan dan incubator bisnis
– Kebijaksanaan pemerintah misalnya adanya kemudahan-kemudahan dalam lokasi berusaha ataupun fasilitas kredit, dan bimbingan usaha yang dilakukan oleh depnaker.
Sedangkan faktor-faktor sociological yang menjadi pemicu serta pelaksanaan bisnis adalah:
– Adanya hubungan-hubungan atau relasi-relasi dengan orang lain
– Adanya tim yang dapat kerjasama dalam berusaha.
– Adanya dorongan dari orang tua untuk membuak usaha
– Adanya bantuan family dalam berbagai kemudahan.
– Adanya pengalaman-pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya.
3. Proses pelaksanaan
Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut:
– Adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total.
– Adanya menejer pelaksana sebagai tangan kanan, pembantu utama
– Adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis
– Dan adanya visi, pandangan yang jauh kedepan guna mencapai keberhasilan
4. Proses pertumbuhan
Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain:
– Adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan oprasional berjalan produktif.
– Adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak.
– Adanya struktur dan organisasi yang sudah membudidaya. Budaya perusahaan jika sudah terbentuk dan diikuti dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh karyawan maka pertumbuhan perusahaan akan berkembang pesat.
– Adanya produk yang dibanggakan, atau keistimewaan yang dimiliki misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen, personalia dan sebagainya.
Sedangkan faktor environment yang mendorong implementasi dan pertumbuhan bisnis adalah sebagai berikut:
– Adanya unsure persaingan yang cukup menguntugkan dunia persaingan saat ini sangat tajam, ada berbagai bentuk persaingan yang ada di pasar muali dari pengusaha pasar yang sangat dominan, yang mempunyai kekuatan yang sedang dan yang lemah. Dalam istilah pemasaran mereka ini terdiri atas market, leader, market challenger, market folowwer dan market nicher. dipasar ditemukan pemimpin pasar, pada setiap produk, atau merek yang dijual dipasar ada merek yang melekat dihati konsumen. Mereka ini market share nya paling banyak/luas ini disebut market leader. Kemudian menyusul penantang pasar (market challenger), yang berusaha menunggu kesempatan mengatasi leader.
Setelah itu ada market follower yang ikut-ikutan saja karena modal terbatas, merek belum terkenal dan terakhir market nicher yang menjual produknya pada relung-relung celah pasal yang belum terisi oleh merek lain.
– Adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinyu.
– Adanya bantuan dari investor Bank yang memberikan fasilitas keuangan.
– Adanya sumber-sumber yang tersedia yang masih bisa dimanfaatkan.
– Adanya kebijaksanaan Pemerintah yang menunjang berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan.
3. Berbagai Macam Tipe Wirausaha
Dari pengamatan prilaku wirausaha maka dapat dikemukakan tiga tipe wirausaha, yaitu:
1. Wirausaha yang memiliki inisiatif.
2. Wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu.
3. Yang menerima resiko atau kegagalan.
Bila ahli ekonomi seorang entrepreneur adalah orang yang mengkombinasikan resources, tenaga kerja, material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenankan perubahan-perubahan, inovasi dan perbaikan produksi lainnya. Dengan kata lain wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal dan skill untuk tujuan berproduksi.
Bagi seorang psychologist seorang wirausaha adalah seorang yang mempunyai dorongan kekuatan dari alam untuk memperoleh sesuatu tujuan, sukamengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan orang lain.
Bagi seorang businessman atau wirausaha adalah merupakan ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang partner, pemasok, konsumen atau seseorang yang bisa diajak kerjasama.
Bagi seorang pemodal melihat wirausaha adalah seorang yang menciptakan kesejahtraan buat orang lain, yang menemukan cara-cara untuk menggunakan, resources, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat.
Sedangkan kewirausahaan adalah proses dinamika untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skill dan resourcs yang ada. Dalam pengertian wirausaha di atas tersimpul konsep-konsep sepeti situasi baru, mengorganisir, menciptakan, kemakmuran, dan menanggung resiko, wirausaha ini dijumpai pada semua profesi seperti pendidikan, kesehatan, peneliti, hukum, arsitektur, engineering, pekerjaan social dan distribusi.
Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang ain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi.
Raymond Kao & Russel Knight (1987:13), memberikan definisi tentang wirausaha dengan menekankan pada aspek keberhasilan berusaha yang dinyatakannya sbb: An entrepreneur is an independent growth oriented owner-operator.
Manager sebuah divisi pada suatu perusahaan bebas melakukan kegiatan dalam melakukan devinisinya akan tetapi dia harus tunduk kepada aturan-aturan umum perusahaan. Sebagai kesimpulan Raymond Kao menyatakan bahwa adalah sulit untuk menggambarkan secara pasti pengertian wirausaha untuk tujuan akademis.
Selanjutnya diungkapkan pula 3 tipe utama dari wirausaha yaitu:
1. Wirausaha Ahli (Craftman).
2. The Promoter.
3. General Manager
– Wirausaha Ahli atau seorang penemu memiliki suatu ide yang ingin mengembangkan proses produksi system produksi, dan sebagainya. Dia cendrung bergerak dalam bidang penelitian membuat model percobaan laboratorium dan sebagainya. Dia juga menjual lisensi idenya untuk dijadikan produk komersial. Pengetahuannya lebih banyak pada bidang teknis produksi dibandingkan pengetahuan di bidang pengawasan, finance dan sebagainya. Misalnya seorang tukang mendirikan sebuah perusahaan kontruksi seorang sopir truk membuka perusahaan pengangkutan, seorang dokter membuka sebuah perusahaan klinik kesehatan. Sebagian besar wirausaha berasal dari tipe-tipe individu seperti ini.
– The Promoter adalah seorang individu yang tadinya mempunyai latar belakang pekerjaan sebagain seles atau bidang marketing yang kemudian mengembangkan perusahaan sendiri. Keterampialan yang sudah ia miliki biasanya merupakan faktor pendorong untuk mengembangkan perusahaan yang baru ia rintis.
– General Manager adalah seorang individu yang ideal yang secara sukses bekerja pada sebuah perusahaan dia banyak menguasai keahlian bidang produksi, permasalahan, permodalan dan pengawasan).
Berdasarkan uraian diatas istilah entrepreneur mempunyai arti yang berbeda pada setiap orang karena mereka melihat konsep ini dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada beberapa aspek umum yang terkandung dalam pengertian entrepreneur yaitu adanya unsur resiko, kreatifitas, efisiensi, kebebasan dan imbalan.
Pertumbuhan wirausaha dimasa yang akan datang di Negara kita sangat cerah, kita menghadapi masa depan yaitu masa pengembangan kegiatan wirausaha yang ditunjang oleh lembaga pendidikan yang mengembangkan pengetahuan kewirausahaan didorong pula oleh kebijaksanaan pemerintah dan berbagai bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta.
Jalan Menuju wirausaha Sukses.
| COPRENEURS |
| FAMILY OWNEDEntrepreneur |
| HOMEBASEDEntrepreneur |
| PART TIMEEntrepreneur |
| IMMIGRANTEntrepreneur |
| MINORITYEntreprener |
| WOMENEntrepreneur |
| BERBAGAI MACAM PROFIL WIRAUSAHA |
Macam Profil Wirausaha
1. Womon Entrepreneur
Banyak wanita yang terjun kedalam bidang bisnis. Alasannya mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh faktor-faktor antara lain ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya, membantu ekonomi rumah tangga, frustasi terhadap pekerjaan sebelumnya dan sebagainya.
2. Minority Enterpreneur
Kaum minoritas terutama di negeri kita Indonesia kurang memiliki kesempatan kerja dilapangan pemerintah sebagaimana layaknya warga negara pada umumnya. Oleh sebab itu, mereka berusaha menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula para perantau dari daerah tertentu yang menjadi minoritas pada suatu daerah, mereka juga bergiat mengembangkan bisnis. Kegiatan bisnis mereka ini makin lama makin maju, dan mereka membentuk organisasi minoritas di kota-kota tertentu.
3. Immigrant Entrepreneurs
Kaum pendatang yang memasuki suatu daerah biasanya sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh sebab itu, mereka lebih leluasa terjun dalam pekerjaan yang bersifat non formal yang dimulai dari berdagang kecil-kecilan sampai berkembang menjadi perdagangan tingkat menengah.
4. Pare Time Entrepreneurs
Memulai bisnis dalam mengisi waktu lowong atau part time merupakan pintu gerbang untuk berkembang menjadi usaha besar. Bekerja part time tidak mengorbankan pekerjaan dibidang lain misalnya seorang pegawai pada sebuah kantor mencoba mengembangkan hobi yang menarik. Hobi ini akhirnya mendatangkan keuntungan yang lumayan. Ada kalanya orang ini beralih propesi, dan beralih menjadi pegawai, beralih ke bisnis yang merupakan hobinya.
5. Home-Based Entrepreneurs
Apa bila ibu-ibu rumah tangga yang memualai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga misalnya ibu-ibu yang pandai membuat kue dan aneka masakan, mengirim kue-kue ke toko eceran disekitar tempatnya. Akhirnya usaha makin lama makin maju. Usaha catering banyak dimulai dari rumah tangga yang bisa masak. Kemudian usaha catering ini berkembang melayani pesanan untuk pesta.
6. Family-Owned Business
Sebuah keluarga dapat membuka berbagai jenis dan cabang usaha. Mungkin saja usaha keluarga ini dimulai lebih dulu oleh bapak setelah usaha bapak maju dibuka cabang baru dan dikelola oleh ibu. Kedua perusahan ini maju dan membuka beberapa cabang lain mungkin jenis usahanya berbeda atau lokasinya berbeda. Masing-masing usahanya ini bisa dikembangkan atau dipimpin oleh anak mereka. Dalam keadaan sulitnya lapangan kerja pada saat ini maka kegiatan semacam ini perlu dikebangkan.
7. Copreneurs
Copreneurs antrepreneurial comples who work together as co-owners their businesses. (zimmerer & Scarborough, 1996:9)
Cppreneursini berbeda dengan usaha famili yang disebut sebagai usaha Mom & Pop (“Pop as “boss” and Mom as “subordinate”)
Coprenears disebut dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang disadasarkan atas keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli dibidang ini diangkat menjadi penanggung jawab divisi-divisi tertentu dari bisnis yang sudah ada.
Konsep 10 D dari Bygrave
Selanjutnya dapat digambarkan beberapa karakteristik dari wirausahaan yang berhasil memiliki sifat-sifat yang dikenal dengan istilah 10 D (Bygrave, 1994:5)
| 1. Dream |
Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya tersebut.
| 2. Decisiveness |
Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara tepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan dia mengambil keputusan adalah mempunyai faktor kunci (key factor) dalam kesuksesan bisnisnya.
| 3. Doers |
Begitu seorang wirausaha membuat keputusan maka dia langsung menindak lanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatan secepat mungkin yang dia sanggup artinya seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan.
| 4. Determination |
Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian. Rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dia dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin diatasi.
| 5. Dedication |
Dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi, kadang-kadang dia mengorbankan hubungan kekeluargaan, melupakan hubungan dengan keluarganya untuk sementara. Mereka bekerja tidak mengenal lelah, 12 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya.
| 6. Devotion |
Devation berarti kegemaran atau kegila-gilaan. Demikian seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya dia mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang mendorong dia mencapai keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produk yang ditawarkannya.
| 7. Details |
Seorang wirausaha sangat mperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya.
| 8. Destiny |
Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain.
| 9. Dollars |
Wirausaha tidak sama mengutamakan mencapai kekayaan. Motifasinya bukan memperoleh uang. Akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Mereka berasumsi jika mereka sukses berbisnis maka mereka pantas mendapat laba/bonus/hadiah.
| 10. Dollars |
Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Orang-orang kepercayaan ini adalah orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnisnya.
Beberapa Kelemahan Wirausaha Indonesia
Heidjrachman Ranu Pandojo (1982:16) menulis bahwa sifat-sifat kelemahan orang kita bersumber pada kehidupan penuh raga, dan kehidupan tanpa pedoman, dan tampa orientasi yang tegas.
Lebih rinci kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sifat mentalitet yang meremehkan mutu.
2. Sifat mentalitet yang suka menerabas.
3. Sikap tak percaya kepada diri sendiri.
4. Sikap tak disiplin.
5. Mengabaikan rajuber.
Ciri Wirausaha Sukses :
Pada awalnya tidak semua wirausaha sukses mempunyai ciri-ciri kewirausahan. Mungkin hanya beberapa saja, tetapi ciri tersebut dapat menjadi kenyataan atau dikebangkan apabila seorang mempunyai energi dan motifasi untuk berkembang. Paling tidak ada 12 yang mencirikan suksesnya kewirausahaan seseorang yaitu:
1. Adaptability, Adalah kecakapan dalam menyesuaikan diri dari lingkungan yang baru dan menciptakan pemecahan yang kreatif pada masalah yang timbul.
2. Competitveness, yaitu kemauan untuk bersaing, mempersiapkan diri untuk persaingan dan mencari keuntungan bersaing.
3. Confidence, mempunyai keyakinan bahwa apa yang sudah direncanakan akan berhasil dilaksanakan.
4. Discipline, kemampuan untuk fokus pada masalah dan tepat pada schedule dan deadline yang telah digariskan sebagai tolak ukur kerjanya.
5. Drive, Kemampuan untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah dibuat.
6. Honesty, mempunyai komitmen untuk berbuat atau bertindak jujur dan berhubungan bisnis dengan cara fair.
7. Organization, dengan merumuskan tugas-tugas yang dijalankan dengan cara benar dan teratur, pandai mendapatkan dan menggunakan informasi serta memfile kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan baik.
8. Perseverance, pantang menyerah, tujuan menjadi bagian terdalam dalam hidupnya untuk dicapai, dan tidak mudah patah semangat dalam menghadapi hambatan-hambatan.
9. Persuasiveness, pandai meyakinkan kepada orang lain perihal ide dan rencananya. Pandai mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan idenya kepada orang lain.
10. Risk taking, siap bila tidak berhasil dan pandai mengkalkulasi risiko sehingga dapat menghindari hambatan-hambatan
11. Understanding, kemampuan mendengarkan, pendapat orang dan mempunyai jiwa teposeliro kepada orang lain atau selalu mengapresiasi keberhasilan orang lain dan mau share (berbagi rasa) dalam kesukaran orang lain.
12. Vision, mempunyai pandangan kedepan dan mempunyai ramalan hari depan yang baik dalam mencapai goalnya.
Proses kewirausahaan yang dapat dipakai sebagai pedoman seseorang untuk mempraktekan jiwa kewirausahaan disebut “The Ten Commandments of Entrepreneurship”.
Sepuluh Progran Kewirausahaan
Kesepuluh program tersebut adalah :
1. Dibuat tujuan usaha dan diupayakan untuk dicapai (Set your goal and for it).
2. Kerja keras (tidak loyo) dan tidak pernah semangat (Be tireless and persevere).
3. Fokus pada ceruk pasar (Focus on niche markets).
4. Jangan berlarut-larut, dan laksanakan keputusan segera (Be decisive and implement decision quickly).
5. Organisasi yang responsif terhadap stakeholders.
6. Mengelola CF (Cash Flow) dengan baik.
7. Creative dan innovative
8. Minimisasi lapisan manajemen (delayerisasi)
9. Maksimisasi profit melalui pembiayaan minimal dan tingginya produktivitas.
10. Percaya pada diri sendiri
Murphy and peck, menggambarkan delapan anak tangga untuk mencapai puncak karir. Delapan anak tangga ini dapat pula digunakan oleh seorang wirausaha dalam mengembangkan propesinya.
1. Mau kerja keras (Capacity for hard work).
Kerja keras murupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Rosullullah sangat marah melihat orang pemalas dan suka berpangku tangan bahkan beliau secara simbolik member hadiah kampak dan tali kepada seseorang lelaki agar mau bekerjakeras mencari kayu dan menjualnya kepasar. Demikian pula jika mau berusaha, mulailah berusaha sejak subuh, jangan tidur sesudah subuh, cepatlah bangun dan mulailah kegiatan untuk hari itu akhirnya laki-laki itu sukses dalam hidupnya.
Demikianlah setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat ia harus bekerja keras membanting tulang dalam merintis perusahaannya. Seorang pengusaha taksi mungkin tadinya ia hanya seorang supir angkutan umum seorang mengusaha tekstil mungkin tadinya seorang pedagang kredit tekstil atau tukang jait, dan banyak lagi contoh yang dapat kita jumpai dalam riwayat hidup pengusaha yang sukses.
Sikap kerja keras harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dalam hal ini, unsur disipin memainkan peranan penting sebab, bagaimana orang mau bekerja keras jika disiplin tidak ada. Dia harus mengatur waktu, sesuai irama kehidupan, bangun pagi, siap-siap untuk bekerja, mulai bekerja, istirahat (tidak terlalu lama), dan seharusnya sampai malam tiba malam hari ia tidur (tidak begadang sampai larut malam). Ada satu lagi elemen penting dalam keberhasilan kerja keras, yaitu berserah diri kepada Allah SWT, dengan selain berdoa kepadan-Nya Ya Allah perbaikilah nasibku,……dst. Insya Allah kerja keras yang diiringi dengan doa akan memperoleh sukses. Seorang mahasiswa yang belajar keras tiap malam, plus doa setelah salatnya. Insya Allah soal-soal ujian akan muncul dari materi yang sudah ia pelajari dan nialai A gampang diraih.
2. Bekerja sama dengan orang lain (Getting Things Done With and Through people).
Perbanyaklah teman dengan orang-orang dibawah ataupun dengan orang-orang diatas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan dan patuh serta disiplin menghadapi atasan dan hindarkan permusuhan. Dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan mudah tercapai. Inilah yang disebut ”manajemen” yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Seorang wirausahawan mudah bergaul, disenangi oleh masyarakat. dia tidak suka fitnah, sok hebat, arogan, tidak suka menyikut, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, dan sebagainya. Dia harus berprilaku yang menyenangkan bagi setiap orang, sehingga memudahkannya berkerjasama dalam mencapai keberhasilan.
3. Penampilan yang baik (Good Appearance).
Ini bukan berarti penampilan bodiface / muka yang elok atau paras yang cantik akan tetapi lebih ditekankan pada penampilan prilaku jujur, disiplin, banyak orang tertipu dengan rupa nan elok tetapi ternyata orangnya penipu ulung. Ingatlah, pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang dimana-mana dan akan sukses berkerjasama dengan siapa saja.
Seorang lulusan sekolah menengah atau alumni sebuah perguruan tinggi melamar dan diterima bekerja di sebuah perusahaan. Dia berpenampilan baik seperti diceritakan diatas, maka dengan cepat ia naik pangkat menduduki posisi kunci dalam perusahaan tersebut. Berkat naluri wirausahanya ia bisa menabung dari income-nya tiap bulan, kemudian mencari peluang-peluang usaha lain. Setelah modal tabungan dirasa cukup, maka ia dapat menjelma menjadi wirausahawan sukses. Peluang usahanya wirausahanya bisa dalam bentuk mensuplai komoditi yang diperlukan oleh bekas perusahaan tempat ia semuala bekerja atau merintis wirausaha dalam jenis komoditi yang sama dikota yang sama atau ia pindah ke kota lain.
4. Yakin (Self Confidence).
Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan sesuatu usaha, jangan ragu dan bimbang niatlah berjalan baik, kemudian berserah diri, tawakal kepada Allah Swt.
Self confidence ini diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari, melangkah pasti, tekun, sabar, tidak ragu-ragu. Setiap hari otaknya selalu berputar membuat rencana dan perhitungan-perhitungan alternatif. Dia bisa saja menguji buah pikiranya dengan teman-teman lain, baik yang pro maupun yang kontra dengan rencananya.
5. Pandai membuat keputusan (Making Sovnd Decision).
Jika anda dihadakan pada alternatif, harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain, setelah itu ambil keputusan, jangan ragu-ragu.
Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikirannya ia akan dapat mengambil keputusan terbaik.
6. Mau Menambah Ilmu Pengetahuan (College Education).
Zaman sekarang pendidikan adalah nomor satu. Tenaga tak terdidik harganya murah sekali. Sebaliknya orang terdidik, memiliki ilmu dan keterampilan akan dibayar mahal. Benarlah Rosulullah yang mewajibkan semua muslim menuntut ilmu dari ayunan sampai keliang kubur. Pendidikan ini bukan berarti harus masuk keperguruan tinggi, melainkan pendidikan dalam bentuk kursus-kursus, penataran dikantor, membaca buku, dan sebagainya.
Pendidikan college dalam bentuk diploma akan sangat membantu seseorang menemukan dan mengembangkan jiwa serta oprasional wirausaha. Akan tetapi hal yang penting disini adanya tambahan pengetahuan.
7. Amisi untuk maju (Ambition Drice)
Kita jangan loyo, pasrah menyerah tak mau berjuang. Kita harus punya semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigi dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan, biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, propesi apapun yang dihadapi, kita harus mampu melihat kedepan dan berjuang untuk menggapai apa yang diidam-idamkan.
8. Pandai berkomunikasi (Ability to Communicate).
Pandai berkomunikasi berarti pandai berorganisasi buah pikiran kedalam bentuk ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perintah orang lain. Komunikasi baik, diikuti dengan prilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Akhirnya dengan keterampilan berkomunikasi itu seseorang dapat mencapai puncak karir meraih kursi empuk yang menjadi idaman setiap orang.
9. Karakteristik wirausaha yang sukses dari zimmerer.
1. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya. Boleh dikata setiap saat pikiran tidak lepas dari perusahaannya.
2. Mau bertanggung jawab. Apa saja tindakan yang ia lakukan, selalu diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab ia tidak takut rugi.
3. Keinginan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan mempertahankan internal locus of contor yaitu minat kewirausahaan dalam dirinya.
4. Peluang untuk mencapai obsesi. Seorang wirausaha mempunyai obsesi mencapai prestasi tinggi dan ini bisa diciptakannya.
5. Toleransi menghadapi resiko kebimbangan dan ketidak pastian.
6. Yakin pada dirinya.
7. Kreatif dan fleksibel.
8. Ingin memperoleh balikan segera. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman guna memperbaiki penampilannya.
9. Enerjik tinggi seorang wirausaha lebih enerjik dibandingkan rata-rata orang lain.
10. Motifasi untuk lebih unggul seorang wirausaha mempunyai motifasi untuk bekerja lebih baik dan lebih unggul dari apa yang sudah dia kerjakan.
11. Berorientasi kemasa depan.
12. Mau belajar dari kegagalan. Seorang wirausaha tidak takut gagal, dia memusatkan perhatiannya pada kesuksesan dimasa depan dan menggunakan kegagalan ini sebagai guru yang berharga.
13. Kemampuan memimpin. Seorang wirausah harus mampu menjadi pemimpin yang baik dia memimpin sumberdaya manusia yang berbagai macam karakternya. Dan juga dia memimpin sumberdaya non manusia yang harus dikelola sebaik-baiknya.
TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN
I. Permintaan dan Kurve Permintaan
Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pengertaian permintaan dan kurve permintaan yang memuat pendapat beberapa akhli sebagai berikut;
a. Permintaan
| 1. Albert L. Meyers2. George L. Bach | :: | Jumlah barang dimana para pembeli bersedia membelinya dengan harga yang mungkin pada suatu ketikaJumlah barang dimana para pembeli bersedia membelinya pada berbagai kemungkinan harga |
b. Kurve Permintaan
| 1. Samuelson Paul A2. P. Wonnocott | :: | Hubungan antara harga dan jumlah barang dibeli/dimintaSuatu garis/sekala yang menggambarkan berbagai kemungkinan suatu barang atau jasa dimana pembeli bersedia membelinya pada berbagai kemungkinan tingkat harga |
Pada pengertian diatas maka jelas bahwa yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang dimana pembeli bersedia membelinya pada suatu tingkat harga tertentu.
Hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan tingkat harga disebut “DEMAND FUNCTION”
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
1. Selera Konsumen
2. Harga barang cendrung naik, turun
3. Tingkat pendapatan masyarakat
4. Adanya barang lain (Substitusi)
5. Jumlah Penduduk yang mengkonsumsi barang tesebut
6. Intensitas kebutuhan
II. Penawaran dan Kurve Penawaran
a. Penawaran ialah sejumlah suatu barang dan jasa dimana penjualan besedia menjual pada suatu atau berbagai tingkat harga.
b. Kurve penawaran ialah suatu garis yang menunjukan suatu titik antara berbagai kemungkinan tingkat harga dengan jumlah yang ditawarkan.
Hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang ditawarkan tersebut adalah “SUPPLY FUNCTION”.
Faktor yang mempengaruhi :
1. Harga Barang
2. Harga barang lain yang erat hubungannya
3. Teknologi
4. Biaya produksi
5. Tujuan perusahaan
6. Jumlah produksi lain
MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA
Pengertian Produktifitas
Didalam beberapa ensiklopedia, produktifitas didefinisikan sebagai berikut :
2. Productivity in economics is the ratio of what is produced to what is require to produce it
Inti dari pengertian produktifitas yang diungkap tadi adalah menyangkut perbandingan hasil yang diperoleh dengan sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Ada yang mengatakan produktifitas itu adalah kuantitas atau volume dari produksi atau jasa yang dihasilkan, akan tetapi produktifitas bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas produk yang dihasilakan yang juga dipakai sebagai pertimbangan mengukur tingkat produktifitas. Jadi dalam menentukan produktifitas tidak hanya dilihat dari faktor kuantitas saja tetapi juga kualitas jika seseorang menghasilkan produksi 100 unit per bulan dari bulan berikutnya menghasilkan 150 unit maka tingkat produktifitas naik 50%, akan tetapi jika menghasilkan sama seperti bulan lalu 100 unit tetapi kualitasnya bagus maka itupun disebut produktifitas.
Ada 3 ukuran produktifitas yang harus di pertimbangkan dalam mengelola organisasi yaitu :
1. Untuk tujuan strategi, apakah organisasi sudah benar sesuai dengan yeng telah digariskan.
2. Efektifitas, sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai baik kuantitas maupun kuantitas.
3. Efisiensi, bagaimana perbandingan output dibagi input dimana pengukuran output semurah diadakannya kualitas dan kuantitas
Atas uraian diatas maka produktifitas dapat diukur menurur tingkatan-tingkatan yaitu :
→ Individu
→ Kelompok
→ Organisasi
Keuangan Negara APBN/APBD
Dalam rangka menciptakan tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD’45 dibentuk perumusan negara yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam berbagai bidang pembentukan fungsi pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yan perlu dikelola dalam system pengelolaan uang Negara.
APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara)
Adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi penyelenggaraan jangka waktu tertentu (1 Tahun).
Setiap Tahun Presiden mengajukan RAPBN untuk membahas bersama DPR sesuai dengan Undang-undang 1945 (Pasal 23).
1. Prinsip Penyusunan APBN
a. Tabungan selalu meningkat
b. Azas berimbang dan dinamis
c. Peningkatan pendapatan
d. Peningkatan pendapatan pajak
e. Prioritas Pengelolaan rutin yang penting
f. Pemanfaatan SDM dan SDA
2. Fungsi APBN
a. Fungsi distribusi menunjukan pembagian dana pada berbagai sektor
b. Fungsi stabilisasi menjaga kestabilan arus uang dan arus barang
c. Fungsi alokasi menunjukan sasaran dan prioritas pembangunan sehingga kebutuhan umum dapat terpenuhi.
d. Fungsi pertumbuhan ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi
e. Fungsi pengendali informasi.
Sumber-sumber Penerimaan
1. Penerimaan Dalam Negeri
a. Penerimaan Pajak
1. Pajak dalam Negeri
2. Pajak perdagangan internasional
3. Penerimaan SDM, Minyak, Gas, Batubara
4. Bagian Laba BUMN
5. Hibah
b. Penerimaan Luar Negeri
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Pinjaman Proyek
2. Pengeluaran Pemerintah
1. Belanja
a. Pengeluaran rutin
1. Beanja Barang
2. Belanja Pegawai
3. Belanja Modal
4. Belanja Hibah
5. Belanja Modal
6. Pengeluaran Pembangunan
7. Pembiayaan Prodak
Dana Perimbangan
Dana bagi hasil
DAU
DAK
Dana Otonomi Khusus.
SOAL-SOAL LATIHAN KEWIRAUSAHAAN
1. Jelaskan pengertian tersebut dibawah ini;
a. Wirausaha ?
b. Wiraswasta ?
c. Saudagar ?
d. Kewirausahaan ?
2. Melihat banyaknya manfaat wirausaha tersebut maka ada 2 darmabakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, apa saja itu ?
3. Mengapa sebagai masyarakat indonesia secara pisikologis tidak tertarik atau kurang berminat terhadap propesi wirausaha ? Jelaskan !
4. Perkembangan pendapatan Nasional ditinjau dari sudut jumlah penghasilan yang diterima masyarakat dari penjualan barang dan jasa menurut masyarakat harga yang berlaku disebut Notional income at market price dan Nasional in come at factor cost. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut dan beri dengan contoh !?
5. Menurut Joseph Schumpeter entrepreneur atau wirausaha adalah orang orang yang mendobrak system ekonomi dengan memperkenalkan barang dan jasa yang New and different. Jelaskan dan berikan contohnya !?
6. Apa saja yang menjadi keuntungan dan kelemahan wirausaha itu ? sebutkan satupersatu ?
7. Menurut Murphy and Peck ada 8 anak tangga untuk mencapai puncak karier diantaranya adalah :
a. Capacity for hard work
b. Getting things done with and through people.
c. Making sound decision
Jelaskan satu persatu ?
8. Bagaimana menurut Zimmerer tentang karakteristik wirausaha yang sukses itu ? Sebutkan satupersatu ?
9. Benarkah wirausaha yang sukses selalu belajar dari kegagalan ?