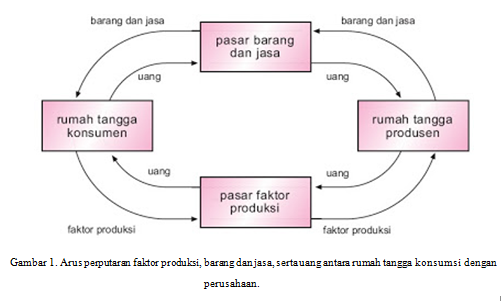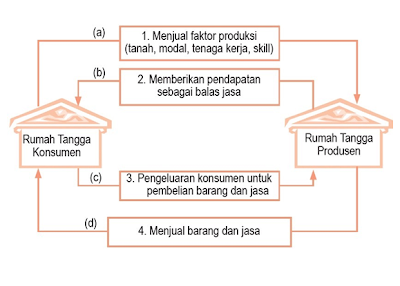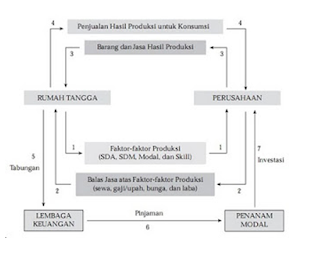Daftar isi
Teori Humanistik
Teori pendidikan adalah suatu pandangan pendidikan yang diidealkan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem konsep dan dalil. Ada juga yang mengatakan teori pendidikan adalah serangkaian konsep, definisi, asumsi dan proposisi tentang cara merubah sikap dan tingkah laku seseorang dalam rangka mewujudkan manusia yang adil dan beradab.
Teori Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia.Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka.Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berfikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka.Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka.
Menurut para tokoh aliran ini penyusunan dan pemilihan materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa.Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia secara utuh dan membantu mengembangkan potensi dan keterampilan mereka.
Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar yaitu proses memperoleh informasi baru dan internalisasi informasi ini pada individu. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti pula.
Selain teori belajar behavioristik dan toeri kognitif, teori belajar humanistik juga penting untik dipahami.Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri.Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan si yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada penertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya.
Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna atau “Meaningful learning” yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini, mengatakan bahwa belajar merupakanasmilasi bermakna.Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam strujtur konitif yang telah dimilikinya. Teori humanstik berpendapat bahwa belajar apapu dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal.
Pemahamanan terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia.Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat elektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu, akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini elektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Teori humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun, asal tujuannya tercapai, yatu memanusiakan manusia.
Manusia adalah makhluk yang kompleks.Banyak ahli di dalam menyusun teorinya hanya terpaku pada aspek tertentu yang sedang menjadi pusat perhatiannya.Dengan pertimbangan-pertimbangantertentu setiap ahli melakukan penelitiannya dari sudut pandangnya masing-masing dan menganggap bahwa keterangannya tentang bagaimana manusia itu belajar adalah sebagai keterangan yang paling memadai. Maka akan terdapat berbagai teori tentang belajar sesuai dengan pandangan masong-masing.
Dari penalaran di atas ternyata bahwa perbedaan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain sering kali hanya timbul karena perbedaan sudut pandangan semata, atau kadang-kadang hanya perbedaan aksentuasi. Jadi keterangan atau pandangan yang berbeda-beda itu hanyalah keterangan mengenai hal yang satu dan sama dipandang dari sudut yang berlainan. Dengan demikian teori humanistik dengan pandangannyadengan pandangannya elektik yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi justru harus dilakukan.
Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya adalah Kolb yang terkenal dengan “Belajar Empat Tahap”nya, honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam siswa, Hubemas dengan “Tiga macam tipe belajar”nya, serta Bloom dan Krathwohl yang terkenal dengan “Taksonomi Bloom”nya.
Tokoh-tokoh Teori Humanistik
Ø Historis Teori Humanistik
Aliran Humanistik muncul sekitar tahun 1960-1972.Kemudian muncul bebrapa perubahan dan inovasi baru sampai dekade terakhir. Adapun tokoh – tokoh yang mempelopori psikologi humanistik yang digunakan sebagai teori belajar humanisme sebagai berikut :
Abraham Maslow
Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang paling di kenal adalah teori tentang Hierarchy of Needs ( Hirarki kebutuhan ). Dia mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. Pada diri orang memiliki rasa takut yang dapat membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya, tetapi di sisi lain memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan. Manusia juga bermotivasi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya.Kebutuhan – kebutuhan tersebut memiliki tingkatan mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.
Carl Rogers, adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu mengatasi masalah–masalah kehidupannya. Menurutnya hal yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran yaitu : Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar.Siswa tidak harus belajar tentang hal – hal yang tidak ada artinya. Siswa akan mempelajari hal – hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi siswa. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.
Dari bukunya Freedom to learn, ia menunjukan sejumlah prinsip – prinsip yang terpenting adalah :
Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud – maksud tersendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri di anggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.Belajar yang bermakna di peroleh siswa dengan melakukanya. Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Bagaimana proses belajar dapat terjadi menurut teori belajar humanisme? Orang balajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil.
Ø Bloom dan Krathwohl
Dalam hal ini, Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai (dipelajari) oleh siswa, yang tercakup dalam tiga kawasan berikut.
Kognitif, terdiri dari enam tingkatan, yaitu:
1. Pengetahuan (mengingat, menghafal);
2. Pemahaman (menginterpretasikan);
3. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah);
4. Analisis (menjabarkan suatu konsep);
5. Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh);
6. Evaluasi (membandingkan ide, nilai, metode, dsb).
Psikomotor, terdiri dari lima tingkatan, yaitu:
1. Peniruan (menirukan gerak);
2. Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak);
3. Ketepatan (melakukan gerak dengan benar);
4. Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar);
5. Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar).
Afektif, terdiri dari lima tingkatan, yaitu:
1. Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu);
2. Merespon (aktif berpartisipasi);
3. Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu);
4. Pengorganisasian (menghubung – hubungkan nilai-nilai yang dipercayai);
5. Pengalaman (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup).
Sementara itu, Kolb membagi tahapan belajar menjadi empat tahap, yaitu:
a. Pengalaman konkret; Pada tahap ini seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian.Dia belum mempunyai kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut.Dia pun belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu.
b. Pengalaman aktif dan reflektif; Siswa lambat laun mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya.
c. Konseptualisasi; Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau “teori” tentang sesuatu hal yang pernah diamatinya. Pada tahap ini siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum ( generalisasi ) dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama.
d. Eksperimentasi aktif Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Dalam dunia matematika misalnya, siswa tidak hanya memahami “ asal-usul” sebuah rumus, tetapi ia juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya.
Ø Pandangan Honey Dan Mumford Terhadap Belajar
Tokoh teori humanistik lainnya adalah Honey dan Mumford.Pandangannya tentang belajar diilhami oleh pandangan kolb mengenai tahap-tahap di atas. Honey dan Mumford menggolong-golongkan orang yang belajar ke dalam empat macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis dan golongan pragmatis. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Karakteristik tang dimaksud adalah :
a. Kelompok aktivis
Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok aktivis adalah mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Orang-orang tipe ini mudah diajak berdialog, memiliki pikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain.
Namun dalam melakukan suatu tindakan sering kali kurang pertimbangan secara matang, dan lebih banyak didorong oleh kesenangannya untukmelibatkan diri. Dalam kegiatan belajar, orang-orang demikian senang pada hal-hal yang sfatnya penemuan-penemuanbaru, seperti pemikiran baru, pengalaman barru dan sebagainya, sehingga metode yang cocok adalah problem solving, barinstorming. Namun mereka akan cepat bosan dengan kegiatan-kegiatan yang implementasinya memakan waktu lama.
b. Kelompok reflector
Mereka yang termasuk dalam kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis.Dalam dalam melakukan suatu tindakan, orang-orang tipe rflektor sangant berhati-hati dan penuh pertimbangan.Pertimbangan-pertimbangan baik-buruk dan untung-rugi, selalu memperhitungkan dengan cermat dalam memutuskan sesuatu.Orang orang demikian tidak mudah dipengaruhi, sehingga mereka cenderung bersifat konservatif.
c. Kelompok teoritis
Lain halnya dengan orang-orang tipe teoritis, merreka memiliki kecenderugan yang sangat keritis, suka menganalisis, selalu berfikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Segala sesuatu sering dikembalikan kepada teori dan konsep-konsep atau hukum-hukum.Mereka tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif.Dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, kelompok teoritis penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis da tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. Mereka tampak lebih tegas dan mempunyai pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.
d. Kelompok pragmatis
Berbeda dengan orang-orang tipe prangmatis, mereka memiliki sifat-sifat praktis, tda suka berpanjang lebardengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya.Bagi mereka yang penting adalah aspek-aspek praktis, sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan.Sesuatu hanya bermanfaat jika dapat dipraktekkan.Teori, konsep, dalil, memang penting, tetapi jika itu semua tidak dapat dipraktekkan maka teori, konsep, dalil, dan lain-lain itu tidak ada gunanya.Bagi mereka, sesuatu lebih baik dan berguna jika dapat dipraktekkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3. Ciri-ciri dan Prinsip dalam Teori Humanistik
Berdasarkan teori Kolb ini, Honey dan Mumford menggolongkan siswa menjadi empat tipe, yakni:
1. Aktivis; Ciri dari siswa ini adalah suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru dan cenderung berpikiran terbuka serta mudah diajak berdialog. Namun, siswa seperti ini biasanya kurang skeptis terhadap sesuatu. Dalam belajar mereka menyukai metode yang mampu mendorong seseorang menemukan hal-hal baru, seperti brainstorming atau problem solving .Akan tetapi mereka cepat merasa bosan dengan hal-hal yang perlu waktu lama dalam implementasi.
2. Reflektor; Siswa tipe ini cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah sehingga dalam mengambil keputusan mereka lebih suka menimbang-nimbang secara cermat baik buruknya.
3. Teoris; Siswa tipe ini biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif.Berpikir rasional adalah sangat penting.Dan mereka cenderung sangat skeptis dan tidak suka hal-hal yang spekulatif.
4. Pragmatis; Siswa pada tipe ini menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Bagi mereka teori memang penting, tapi tidak akan berguna jika tidak dipraktikkan.
4. Aplikasi Teori Humanistik Terhadap Pembelajaran Siswa
Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan daam konteks yang lebih praktis.Teori ini diangagap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi dari pada bidang pendidikan, sehingga sukar menterjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih kongkret dan praktis.Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.
Semua komponen pendidikan temasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri.Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri.Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai.
Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ni amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi-taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakekat kejiwaan manusia. Hal ini akan dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi pembelajaran, serta pengembangan alat evaluasi, ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut.
Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagai mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur, kondisi belajar yang dapat diatur dan ditentukan, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa, mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak berarti bagi siswa (Rogers dalam Snelbecker, 1974). Hal tersebut tidak sejalan dengan teori humanistik.Menurut teori ini, agr belajar bermakna bagi siswa, diperlukan insiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri. Maka siswa akan mengalami belajar eksperiensial (experiential learning).
Dalam prakteknya teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berfikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walaupun secara ekspilsit belum ada pedman baku tantang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik, namun paling tidak langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik, namun paling tidak langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan (2001) dapat digumakan sebagi acuan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagi berikut :
- Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran.
- Menentukan materi pembelajaran.
- Mengidentifikasi kemampuan awal (entri behvior) siswa.
- Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar.
- Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran.
- Membimbing siswa belajar secara aktif.
- Membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya.
- Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya.
- Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi nyata.
- Mengevaluasi proses dan hasil belajar.
Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran.
Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri , mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif.Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah :
1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur dan positif.
2. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri.
3. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri.
4. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukkan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dariperilaku yang ditunjukkan.
5. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggungjawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya.
6. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya.
7. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa.
Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial.Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku.
Ø Ciri-ciri guru yang baik dan kurang baik menurut Humanistik
Guru yang baik menurut teori ini adalah : Guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan siswa dengan mudah dan wajar. Ruang kelas lebih terbuka dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan siswa dengan komentar yang menyakitkan, bertindak agak otoriter, dan kurang peka terhadap perubahan yang ada.
Ø Teori kurikulum humanistic
Konsep dasar
Kurikulum humanistik dikembangkan oleh ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu oleh jhon dewey dan J.J Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa.Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan.Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep gesalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif.
Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa.Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, akrab.Berkat situasi tersebut anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa (mendorong siswa), dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu.Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Aliran yang termasuk dalm pendidikan humanistik yaitu pendidikan: konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern.
Pendidikan konfluen menekankan keutuhan pribadi, individu harus merespon secara utuh terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Pendidikan kritikisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme rousseau. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Pendidikan mistikisme modern adalah aliran yang menekankan latihan dan pengebangkan kepekaan perasaan, kehalusan budi peerti, melalui sensitivity training, yoga, meditasi, dan sebagainya.
Ø Karakteristik kurikulum humanisik
Kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik, berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid.
Karekteristik humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Guru selain harus menciptakan hubungan yang hangat dengan urid, juga mampu menjadi sumber. Ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Sesuai prinsip yang dianut humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan prilaku, bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan.