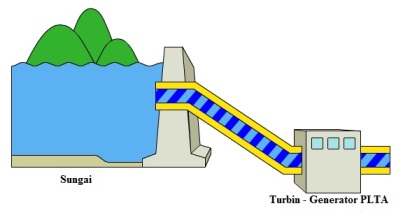Berikut ini contoh makalah Strategi Andragogi. Malah ini berisi tentang konsep strategi belajar yang diterpakan pada pembelajaran orang dewasa.
Strategi Andragogi
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Orang dewasa terus berusaha meningkatkan pengalaman hidupnya agar lebih matang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Orang dewasa bukan lagi menjadi obyek sosialisasi yang dibentuk dan dipengaruhi orang lain untuk menyesuaikan dirinya dengan keinginan para pemegang otoritas di atas dirinya sendiri, akan tetapi dalam perspektif pendidikan, orang dewasa lebih mengarahkan dirinya kepada pencapaian pemantapan identitas dan jati dirinya untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan demikian keikut sertaan orang dewasa dalam belajar memberikan dampak positif dalam melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Pendidikan orang dewasa tidak cukup hanya dengan memberi tambahan pengetahuan saja, namun harus dibekali dengan rasa percaya yang kuat dalam dirinya sehingga apa yang akan dilakukan dapat dijalankan dengan baik.
Orang dewasa belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus akan tetapi orang dewasa belajar untuk meningkatkan kehidupannya. Dengan belajar orang dewasa akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi, sehingga belajar orang dewasa lebih fokus pada peningkatan pengalaman hidup tidak hanya pada pencarian ijasah saja. Sifat belajar orang dewasa yaitu subyektif dan unik, hal itulah yang membuat orang dewasa untuk semakin berupaya semaksimal mungkin dalam belajar, sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai. Orang dewasa tidak lagi bergantun pada orang lain, sehingga memiliki kemampuan dan pengalaman secara mandiri dalam pengambilan keputusan. Salah satu prinsip belajar orang dewasa adalah belajar karena adanya suatu kebutuhan. Dengan mengetahui kebutuhan orang dewasa sebagai peserta didik, maka akan dapat dengan mudah dan dapat ditentukan kondisi belajar yang harus diciptakan, isi materi apa yang harus diberikan, strategi, teknik serta metode apa yang cocok digunakan. Yang terpenting dalam pendidikan orang dewasa adalah apa yang dipelajari peserta didik, bukan apa yang diajarkan pengajar. Artinya, hasil akhirnya adalah apa yang diperoleh orang dewasa dari suatu pembelajaran, bukan apa yang dilakukan pengajar dalam pembelajaran itu.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, kami dapat menarik beberapa masalah yang telah kami rumuskan, yaitu sebagai berikut :
- Apakah arti dan pengertian dari strategi ?
- Apakah arti dan pengertian dari andragogi ?
- Bagaimana strategi pembelajaran pada orang dewasa ?
- Apa hubungan konsep Khit-pan dalam andragogi ?
- Apa implikasi dari konsep andragogi dalam pembelajaran?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini, antara lain :
- Untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Andragogi.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan arti dan pengertian strategi.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan arti dan pengertian andragogi.
- Untuk menyebutkan dan menjelaskan strategi pembelajaran pada orang dewasa.
- Mengetahui dan menjelaskan konsep Khit-pan dalam Andragogi.
- Mengetahui implikasi konsep dari andragogi dalam pembelajaran.
Bab II. Pembahasan
A. Pengertian Strategi
Istilah strategi berasal dari bahasa Yunanistrategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan.
Seiring dengan perkembangan disiplin ilmu, pengertian strategi menjadi bermacam-macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus, pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang sifatnya umum tersebut, ada juga pengertian strategi yang lebih khusus, seperti yang diungkapkan oleh dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad.
Menurut Hamel dan Prahalad pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan komptensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.
Sedangkan menurut Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) seperti yang dikutip oleh Rangkuti (2005:4) : “Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi”.
Salah satu definisi strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:12) yang mengatakan : “strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.
Dari pengertian strategi yang telah banyak disimpulkan oleh para ahli, yang intinya menyatakan bahwa strategi adalah suatu alat yang digunakan untu mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa nsehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.
B. Pengertian Andragogi
Andragogi berasal dari kata andros atau aner yang berarti orang dewasa. Kemudian agogos berarti memimpin. Andragogi berarti memimpin orang dewasa, sedangkan pedagogi berasal dari kata paes, yang berarti anak, dan agogos berarti memimpin. Pedagogi berarti memimpin anak – anak.
Dari segi definisi, andragogi adalah seni dan ilmu mengajar orang dewasa (Knowles, 1980). Sebagai ilmu, tidak ubahnya seperti ilmu yang lain, tentunya andragogi dapat dipelajari oleh siapa saja karena ia mengikuti hukum – hukum keilmuan pada umumnya yang bersifat objektif. Sebagai seni atau kiat, andragogi adalah krativitas yang merupakan kecakapan kreatif dan keahlian seseorang yang terkait dengan rasa estetika, terikat dengan kepribadian, karakter atau watak di pendidik. Ada pendidik yang sangat piawai dalam memengaruhi dan memperlakukan anak-anak didiknya yang berdampak pada rasa senang dan simpati kepada si pendidik. Dengan kesabarannya, ketelatenannya dan rasa humornya, seorang pendidik lebih memikat hari anak lebih dari yang lain. Begitu sebaliknya, ada pendidik yang kurang dapat melakukan hal-hal seperti dimaksudkan tadi walaupun mungkin dia sangat menguasai dan pandai secara keilmuan. Tampaknya ilmu mendidik saja belum cukup dan harus dipadukan dengan seni. Demikianlah, sebenarnya mendidik merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam membantu orang lain, baik anak ataupun orang dewasa, dalam belajar.
Ada juga yang mendefinisikan andragogi sebagai ilmu tentang orang dewasa belajar atau the science of learning (Laird, 1981), yang dalam hal ini lebih merupakan psikologi belajar. Di samping itu, ada juga yang menitikberatkan pada pemberian bantuan, yang mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu tentang bagaimana membantu orang dewasa belajar (Brundage, 1981). Di indonesia, Direktorat Pendidikan Masyarakat telah mulai mengadopsi ide ini sejak tahun 1970-an dengan menggunakan istilah membelajarkan dan juga pembelajaran orang dewasa.
Jadi ringkasnya, andragogi adalah seni dan ilmu tentang bagaimana membantu orang dewasa belajar. Dalam hal ini, pendidik harus berusaha bagaimana membantu mempermudah atau memfasilitasi orang dewasa belajar. Dalam hubungan ini, diyakini bahwa wujud bantuannya pasti berbeda dengan anak karena karakteristik yang berbeda antara keduanya.
C. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa
Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dituntut memiliki kemampuan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemampuan tersebut sebagai sarana serta usaha dalam memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran untuk menyajikan materi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan prgoram pembelajaran. Untuk menentukan atau memilih pendekatan pembelajaran, hendaknya berangkat dari perumusan tujuan yang jelas. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, kemudian memilih pendekatan pembelajaran yang dipandang efisien dan efektif. Pemilihan pendekatan pembelajaran ini hendaknya memenuhi kriteria efisien dan efektif. Suatu pendekatan pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila strategi tersebut dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dari pendekatan yang lainnya. Kriteria lain yang perlu diperhatikan dalam memilih pendekatan pembelajaran adalah tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih pendidik dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Srategi pembelajran terdiri atas dua kata, strategi dan pembelajaran. Istialah strategi (strategy) berasal dari kata kerja dalam bahsa Yunani, “stratego” yang berarti merencanakan (to plan). Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajran. Pembelajaran adalah upaya sistematis dalam membantu warga belajar dalam mengembangkan potensinya secara optimal melalui kegiatan belajar.
Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, peserta didik, untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik dengan lingkungannya. Tujuan strategi pembelajaran adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivutas dan produktifitas kegiatan pembelajaran. Isi kegiatan pembelajaran adalah bahan/materi pembelajaran yang bersumber dari kurikulum yang telah disusun dalam program pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui oleh pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sumber pendukung kegiatan pembelajaran mencakup fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran (Sudjana, 2005).
Menurut Dick dan Carey (1990 : 1) strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan dalam mengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat mencapai isi pelajaran atau mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Lebih lanjut Dick dan Carey (1990) :
Menyebutkan lima komponen umum dari strategi instruksional sebagai berikut:
- Kegiatan pra instruksional.
- Penyajian informasi.
- Partisipasi peserta didik .
- Tes.
- Tindak.
Gagne dan Briggs dalam Atwi Suparman (1996: 156) mengemukakan sembilan urutan kegiatan instruksional, yaitu:
- Memberikan motivasi atau menarik perhatian.
- Menjelaskan tujuan instruksional kepada peserta didik .
- Mengingatkan kompetensi prasyarat .
- Memberi stimulus (masalah, topik, dan konsep).
- Memberikan petunjuk belajar.
- Menentukkan penampilan peserta didik .
- Memberi umpan balik .
- Menilai penampilan.
- Menyimpulkan.
Strategi pembelajaran orang dewasa pada pendidikan keaksaraan fungsional terdiri dari lima langkah kegiatan, yaitu menulis, membaca, berhitung, diskusi dan aksi/penerapan. Langkah-langkah tersebut, bukan berarti langkah yang baku/kaku atau harus berurutan. Tetapi bisa saja dilakukan secara acak, misalnya dimulai dari diskusi, kemudian belajar membaca, menulis dan seterusnya. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi serta kesepakatan di dalam kelompok belajar. Namun demikian, kebiasaan yang ditemui adalah melalui diskusi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa juga dimulai dari masalah yang ditemui (aksi) peserta didik, kemudian didiskusikan di kelompok belajar, menulis, membaca dan seterusnya.
Keefektifan kegiatan belajar, sangat bergantung pada kemampuan tutor dalam mengarahkan, dan membimbing peserta didik di dalam kegiatan belajarnya. Pengalaman juga menunjukkan bahwa, kegiatan menulis perlu didahulukan dan pada kegiatan membaca. Karena melalui kegiatan belajar menulis, peserta didik sedikit demi sedikit langsung belajar membaca. Sebaliknya apabila peserta didik didahulukan belajar membaca, maka cenderung kurang terampil dalam hal menulis.
Kegiatan pembelajaran partisipatif sebagai upaya pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sudjana (2005:155) keikutsertaan peserta didik diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu: perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Partisipasi dalam perencanaan merupakan bentuk keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan dan menentukan prioritas masalah, sumber-sumber atau potensi yang tersedia. Hasil dari identifikasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran.dan penetapan program kegiatan pembelajaran.
Partisipasi dalam pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Iklim belajar yang kondusif ditandai dengan :
- Kedisiplinan peserta didik.
- Terjadi hubungan antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik yang akrab, terbuka, terarah, saling menghargai, saling membantu dan saling belajar.
- Interaksi pembelajar yang sejajar. Kegiatan pembelajaran lebih ditekankan pada peran peserta didik (student centered). Peserta didik diberikan kesempatan secara luas dalam kegiatan pembelajaran, peran pendidik membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menciptakan iklim pembelajaran kondusif, misalnya: pendekatan tematik, descoveri-inkuiri, kontektual, cooperative learning, konstruktrukvistik, meaningfull learning, dsb. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan, misalnya; metode diskusi, tanya jawab, problem solving, discovery-inkuiri, simulasi, brainstorming, role playing,games, siklus belajar berbasis pengalaman, demonstrasi, kooperatif, dan sebagainya.
Partisipasi dalam evaluasi pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam menghimpun informasi mengenai pengelolaan pembelajaran dan perubahan yang dirasakan selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam partisipasi evaluasi pembelajaran ini, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada seluruh komponen pembelajaran (refeksi pembelajaran) dan suasana diri (moood meter) dalam mengikuti pembelajaran.
Langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran partisipatif adalah:
- Melakukan assesment kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran.
- Memilih tema/pokok bahasan dan/atau tugas yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan menentukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran.
- Mengenai dan mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran.
- Mengidentifikasi isi/materi atau bahan pelajaran/rincian tugas pembelajaran.
- Merumuskan tujuan pembelajaran.
- Merancang kegiatan pembelajaran, dengan memilih metode, media pembelajaran yang digunakan secara tepat dan pengelolaan waktu.
- Memilih fasilitas pembelajaran dan sumber bahan yang mendukung proses pembelajaran.
- Mempersiapkan sistem evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran.
- Mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Menurut Tom Nesbit, Linda Leach & Griff Foley (2004) bahwa ada enam prinsip dalam praktek pembelajaran orang dewasa agar dapat diterapkan secara efektif, yaitu:
- Adanya partisipasi secara sukarela.
- Adanya perasaan respek secara timbal balik.
- Adanya semangat berkolaborasi dan kooperasi.
- Adanya aksi dan refleksi.
- Tersedianya kesempatan refleksi kritis dan
- Adanya iklim pembelajaran yang kondusif untuk belajar secara mandiri.
Prinsip tersebut sangat berkaitan dengan karakteristik orang dewasa yang telah memiliki konsep diri dan pengalaman yang cukup banyak. Konsep diri orang dewasa telah mandiri dan bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam menentukan pilihan atau keputusan pemecahan masalah. Pengalaman merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi orang dewasa. Setiap peserta memiliki pengalaman yang bervariasi, tingkat pendidikan, kematangan dan lingkungan yang berbeda pula. Untuk itu pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Peserta sebagai sumber belajar, oleh karena itu teknik pembelajaran yang diterapkan diorientasikan pada upaya penyerapan pengalaman mereka melalui; diskusi kelompok, curah pendapat, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, focus group discussion.
- Penekanan pada aplikasi praktis, pengetahuan baru, konsep-konsep, dan
- Pengalaman baru dapat dijelaskan melalui pengalaman praktis yang pernah dialami peserta didik. Hasil dari pembelajaran dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupannya.
- Materi pembelajaran dirancang berdasarkan pengalaman dan kondisi peserta didik.
D. Konsep Khit-pan dalam Andragogi
Konsep Khit-pan ini dilakukan dalam program pendidikan luar sekolah di Thailand, dan konsep Khit-pan ini dapat pula diterapkan pada pendidikan orang dewasa di Indonesia. Khit-pan ini berarti dapat berfikir secara rasional dan kritis, pada akhirnya menuju pemecahan masalah. Seseorang yang mengalami Khit-pan akan mampu mendekati masalah sehari-hari secara sistematis. Ia akan mampu menelaah penyebab masalahnya, ia akan mampu menelaah penyebab masalahnya, ia akan mampu mengumpulkan informasi untuk pengambilan tindakan yang harus diambil, dalam rangka pemecahan masalah.
Konsep Khit-pan didasari filsafat bhuda. Pertama; hidup adalah penderitaan, kedua; penderitaan dapat diatasi, ketiga; untuk mengatasi, maka sumber penderitaan harus diidentifikasikan dan kemudian baru mencari cara pemecahan yang baik.Sehubungan dengan konsep Khit-pan, maka pengembangan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 4 strategi, yaitu:
- Strategi pertama sebelum merancang kegiatan pembelajaran dilakukan lebih dahulu identifikasi kebutuhan warga belajar dalam mencari kebutuhan belajar digunakan baseline survey. Hasilnya dipecah menjadi 73 konsep.
- Strategi kedua, merencanakan satuan pelajaran dan proses diskusi, sehingga setiap pertemuan memberikan kesempatan untuk berlatih dalam pemecahan masalah. Melalui pertemuan-pertemuan peserta didik mengembangkan kemampuan kritis tentang keadaan dalam kehidupannya sehari-hari, dimana mereka telah mempunyai pengalaman yang dapat mereka sumbangkan dalam diskusi tersebut.
- Strategi ketiga, banyak menggunakan gambar atau perangsang diskusi, dan berfungsi sebagai alat untuk mempraktekkan teknik atau keterampilan memecahkan masalah. Tugasnya adalah menciptakan bahan-bahan belajar yang merangsang untuk mengembangkan pola pikir yang rasional dan kritis.
- Strategi keempat, kurikulum disusun secara luwes untuk mengakomodasi keanekaragaman peserta didik. Hal ini memungkinkan kepada tutor untuk menerapkan dan menyesuaikan program belajarnya dengan keadaan lingkungan setempat dan menyesuaikan dengan minat peserta didik serta dimasukkannya masalah-masalah baru yang diidentifikasikan oleh peserta didik selama proses belajar berlangsung, suasana belajar diatur secara luwes. Peraturan-peraturan di dalam kelas untuk orang dewasa lebih longgar dari pada peraturan-peraturan yang berlaku pada sekolah-sekolah formal biasa. Tempat belajar tidak harus di dalam ruangan dan juga di rumah penduduk, dibalai desa, dan sebagainya. Cara duduk peserta didik tidak diatur seperti di dalam kelas, sehingga pendidik dapat saling tatap muka
E. Implikasi Konsep Andragogi Dalam Pembelajaran
Konsep Andragogi didasarkan pada sedikitnya 4 asumsi tentang karakteristik warga belajar yang berbeda dari asumsi yang mendasari pedagogi tradisional,yaitu:
- Konsep diri mereka bergerak dari seseorang dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain kearah seseorang yang mampu mengarahkan diri sendiri.
- Mereka telah mengumpulkan segudang pengalaman yang selau bertambah yang menjadi sumber belajar yang semakin kaya.
- Kesiapan belajar mereka menjadi semakin berorientasi kepada tugas-tugas perkembangan dari peranan sosial mereka.
- Perspektif waktu mereka berubah dari penerapan yang tidak seketika dari pengetahuan yang mereka peroleh kepada penerapan yang segera, dan sesuai dengan itu orientasi mereka kearah belajar bergeser dari yang berpusat kepada mata pelajaran kepada yang berpusat kepada penampilan.
Usaha-usaha ke arah penerapan teori andragogi dalam kegiatan pendidikan orang dewasa telah dicobakan oleh beberapa ahli, berdasarkan empat asumsi dasar orang dewasa yang di atas yaitu: konsep diri, akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar.
Asumsi dasar tersebut dijabarkan dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyiapkan Iklim Belajar yang Kondusif
Faktor lingkungan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran model Andragogi langkah pertama yang harus dikerjakan adalah menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Ada tiga hal yang perlu disiapkan agar tercipta iklim belajar yang kondusif itu. Pertama, penataan fisik seperti ruangan yang nyaman, udara yang segar, cahaya yang cukup, dan sebagainya. Termasuk di sini adalah kemudahan memperoleh sumber-sumber belajar baik yang bersifat materi seperti buku maupun yang bukan bersifat materi seperti bertemu dengan fasilitator. Kedua, penataan iklim yang bersifat hubungan manusia dan psikologis seperti terciptanya suasana atau rasa aman, saling menghargai, dan saling bekerjasama. Ketiga, penataan iklim organisasional yang dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan SDM, penerapan filosofi manajemen, penataan struktur organisasi, kebijakan finansial, dan pemberian insentif.
2. Menciptakan Mekanisme Perencanaan Bersama
Perencanaan pembelajaran dalam model Andragogi dilakukan bersama antara fasilitator dan peserta didik. Dasarnya ialah bahwa peserta didik akan merasa lebih terikat terhadap keputusan dan kegiatan bersama apabila peserta didik terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Menetapkan Kebutuhan Belajar
Dalam proses pembelajaran orang dewasa perlu diketahui lebih dahulu kebutuhan belajarnya. Ada dua cara untuk mengetahui kebutuhan belajar ini adalah dengan model kompetensi dan model diskrepensi. Model kompetensi dapat dilakukan dengan mengunakan berbagai cara seperti penyusunan model peran yang dibuat oleh para ahli. Pada tingkat organisasi dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis sistem, analisis performan, dan analisis berbagai dokumen seperti deskripsi tugas, laporan pekerjaan, penilaian pekerjaan, analisis biaya, dan lain-lain. Pada tingkat masyarakat dapat digunakan berbagai informasi yang berasal dari penelitian para ahli, laporan statistik, jurnal, bahkan buku, dan monografi. Model dikrepensi, adalah mencari kesenjangan. Kesenjangan antara kompetensi yang dimodelkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh peseta didk. Peseta didik perlu melakukan self assesment.
4. Merumuskan Tujuan Khusus (Objectives) Program
Tujuan pembelajaran ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan. Banyak terjadi kontroversi dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini karena perbedaan teori atau dasar psikologi yang melandasinya. Pada model Andragogi lebih dipentingkan terjadinya proses self-diagnosed needs.
5. Merancang Pola Pengalaman Belajar
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu disusun pola pengalaman belajarnya atau rancangan programnya. Dalam konsep Andragogi, rancangan program meliputi pemilihan problem areas yang telah diidentifikasi oleh peserta didik melalui self-diagnostic, pemilihan format belajar (individual, kelompok, atau massa) yang sesuai, merancang unit-unit pengalaman belajar dengan metoda-metoda dan materi-materi, serta mengurutkannya dalam urutan yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik dan prinsip estetika. Rancangan program dengan menggunakan model pembelajaran Andargogi pada dasarnya harus dilandasi oleh konsep self-directed learning dan oleh karena itu rancangan program tidak lain adalah preparat tentang learning-how-to-learn activity.
6. Melaksanakan Program (Melaksanakan Kegiatan Belajar)
Catatan penting pertama untuk melaksanakan program kegiatan belajar adalah apakah cukup tersedia sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membelajarkan dengan menggunakan model Andragogi. Proses pembelajaran Andragogi adalah proses pengembangan sumberdaya manusia. Peranan yang harus dikembangkan dalam pengembangan sumberdaya manusia adalah peranan sebagai administrator program, sebagai pengembang personel yang mengembangkan sumberdaya manusia. Dalam konteksi pelaksanaan program kegiatan belajar perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan berbagai teknik untuk membantu orang dewasa belajar dan yang berkaitan dengan berbagai bahan-bahan dan alat-alat pembelajaran.
7. Mengevaluasi Hasil Belajar dan Menetapkan Ulang Kebutuhan Belajar
Proses pembelajaran model Andragogi diakhiri dengan langkah mengevaluasi program. Pekerjaan mengevaluasi merupakan pekerjaan yang harus terjadi dan dilaksanakan dalam setiap proses pembelajaran. Tidak ada proses pembelajaran tanpa evaluasi. Proses evaluasi dalam model pembelajaran Andragogi bermakna pula sebagai proses untuk merediagnosis kebutuhan belajar. Untuk membantu peserta didik mengenali ulang model-model kompetensi yang diharapkannya dan mengasses kembali diskrepensi antara model dan tingkat kompetensi yang baru dikembangkannya. Pengulangan langkah diagnosis menjadi bagian integral dari langkah evaluasi. Dalam khasanah proses evaluasi terdapat empat langkah yang diperlukan untuk mengefektifkan assessment program yaitu evaluasi reaksi yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana peserta didik merespon suatu program belajar; evaluasi belajar dilaksanakan untuk mengetahui prinsip-prinsip, fakta, dan teknik-teknik yang telah diperoleh oleh peserta didik; evaluasi perilaku dilaksanakan untuk memperoleh informasi perubahan perilaku peserta didik setelah memperoleh latihan; dan evaluasi hasil dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.
Aplikasi yang diutarakan di atas sebenarnya lebih bersifat prinsip-prinsip atau rambu-rambu sebagai kendali tindakan membelajarkan orang dewasa. Oleh karena itu, keberhasilannya akan lebih benyak tergantung pada setiap pelaksanaan dan tentunya juga tergantung kondisi yang dihadapi. Jadi, implikasi pengembangan teknologi atau pendekatan andragogi dapat dikaitkan terhadap penyusunan kurikulum atau cara mengajar terhadap warga belajar. Namun, karena keterikatan pada sistem lembaga yang biasanya berlangsung, maka penyusunan program atau kurikulum dengan menggunakan andragogi akan banyak lebih dikembangkan dengan menggunakan pendekatan ini.
Sebagai orang dewasa merasakan bahwa konsep-diri seseorang dapat berubah. Mereka mulai melihat peranan sosial mereka dalan hidup tidak lagi sebagai warga belajar “full time”. Mereka melihat diri mereka semakin sebagai penghasil atau pelaku. Sumber utama kepuasan-diri mereka sekarang adalah penampilan mereka sebagai pekerja, suami/isteri, orang tua, dan warga negara. Orang dewasa memperoleh status baru, di mata mereka dan orang-orang lain, dari tanggung jawab yang non-pendidikan ini. Konsep-diri mereka menjadi sebagai pribadi yang mengarahkan dirinya sendiri. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai mampu membuat keputusan-keputusan mereka sendiri dan menghadapi akibat-akibatnya, mengelola hidup mereka sendiri. Dalam hal itu mereka juga mengembangkan satu kebutuhan psikologis yang dalam untuk dilihat orang lain sebagai orang yang mampu mengarahkan diri sendiri.
Orang dewasa menemukan bahwa mereka dapat bertanggung jawab bagi pembelajaranmereka sendiri, sebagaimana mereka lakukan bagi segi-segi lain kehidupan mereka, mereka mengalami perasaan lega dan gembira. Kemudian mereka akan memasuki kegiatan belajar dengan keterlibatan-diri yang mendalam, dengan hasil yang seringkali mengejutkan bagi mereka sendiri dan para fasilitator mereka.
Bab III. Penutup
A. Simpulan
Strategi pembelajaran dapat ditinjau dari ilmu, seni dan keterampilan yang digunakan pendidik dalam membantu baik itu memotivasi, membimbing, membelajarkan dan memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Di samping itu strategi pembelajar dapat dimaknai sebagai prosedur pembelajaran dalam mengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran dari beberapa komponen pembelajaran yang berupa materi pembelajaran, peserta didik, waktu, alat, bahan, metode pembelajaran, sistem evaluasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Strategi pembelajaran orang dewasa (andragogi) merupakan prosedur yang dilakukan dalam membantu orang dewasa dalam belajar. Dalam belajar, orang dewasa telah memiliki konsep diri yang harus dihargai, memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sumber belajar, orientasi belajar diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan peran dan status sosial dalam masyarakat.
B. Saran
Sebagai seseorang yang akan menjadi pendidik nantinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaiman karakteristik dan kebutuhan apa saja yang diperlukan serta perlu dipenuhi. Sedangkan dalam kasus orang dewasa, yang notabene baik itu dalam hal pemikiran maupun tingkah laku yang sudah berbeda dengan anak-anak, penddikan orang dewasa memiliki harga diri dan jati dirinya yang membutuhkan engakuan, karena itu akan sangat berpengaruh pada proses belajarnya. Dan dengan mengetahui kebutuhannya, maka dapat dengan mudah dan dapat ditentukan kondisi belajar yang harus diciptakan, apa isi yang harus diberikan dan bagaimana strategi serta teknik yang cocok digunakan.