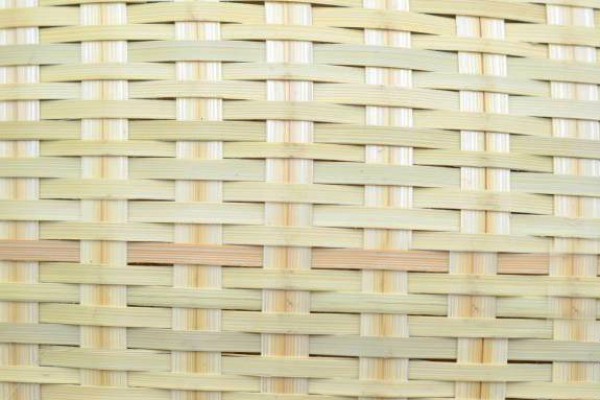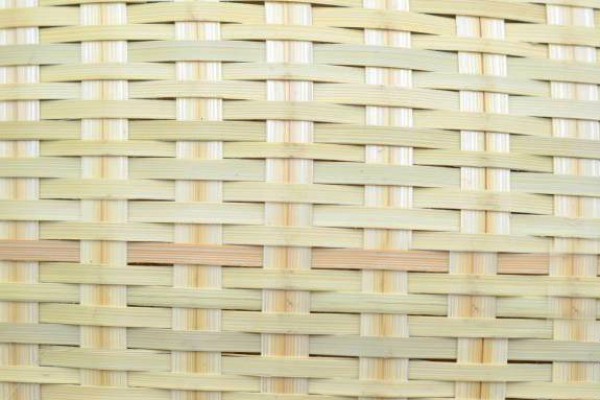Berikut contoh makalah dengan judul Andragogi dalam praktek. Makalah ini berisi penjelasan terkait dengan pembelajaran pada orang dewasa.
Daftar isi
Andragogi dalam Praktek
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Andragogi adalah proses belajar dalam suatu pendidikan yang ditujukan untuk orang dewasa. Orang dewasa adalah manusia individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Orang dewasa menyadari bahwa belajar merupakan proses menjadi dirinya sendiri bukan proses untuk dibentuk menurut kehendak orang lain dan kegiatan belajarnya harus melibatkan individu atau client dalam proses pemikiran: apa yang mereka inginkan, apa yang dilakukan, menentukan dan merencanakan serta melakukan tindakan apa saja yang perlu untuk memenuhi keinginan tersebut.
Pada dasarnya “orang dewasa” memiliki banyak pengalaman baik dalam bidang pekerjaannya maupun pengalaman lain dalam kehidupannya. Untuk menghadapi peserta didik yang pada umumnya “orang dewasa” dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang berbeda dengan “pendidikan dan pelatihan” ala bangku sekolah, atau pendidikan konvensional yang sering disebut dengan pendekatan pedagogis. Dalam praktek “pendekatan pedagogis” yang diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa seringkali tidak cocok. Untuk itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih cocok dengan “kematangan”, “konsep diri peserta” dan “pengalaman peserta”. Didalam dunia pendidikan, stategi dan pendekatan ini dikenal dengan “Pendidikan Orang Dewasa” (Adult Education).
Demi terlaksananya pendidikan untuk orang dewasa ini perlu adanya program-program ataupun kegiatan, baik yang dicanangkan oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh instansi pemerintahan. Kegiatan-kegiatan ini berupa kegiatan pendidikan diluar sekolah (PLS), pembelajarannya pun berbeda dengan pembelajaran di sekolah pada umumnya.
Permasalahan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah adalah hasil belajar, output dan outcomenya. Ketidakmampuan peserta memahami dengan baik materi dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan indikasi kurang berhasilnya kegiatan pendidikan luar sekolah. Rendahnya hasil belajar sebagai indikator dari ketidakberhasilan pembelajaran, dimana peserta maupun tidak mampu menerima dengan baik bahan belajar yang diajarkan oleh tutor. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pembelajaran pendidikan luar sekolah adalah metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaannya dan andragogi belum diterapkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran.
Untuk itu pada makalah ini kami akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan atau praktek andragogi dalam kegiatan mendidik orang dewasa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, makalah ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :
- Bagaimana penerapan andragogi dalam kegiatan pembelajaran?
- Bagaimana pendidikan orang dewasa (andragogi) yang tumbuh dan berkembang dalam masyrakat?
- Kegiatan apa saja yang diprogramkan demi terlangsungnya pendidikan orang dewasa dilingkungan masyarakat?
- Bagaimana pendidikan orang dewasa (andragogi) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan?
C. Tujuan Penulisan
Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- Mengetahui penerapan andragogi dalam kegiatan pembelajaran.
- Mengetahui pendidikan orang dewasa (andragogi) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Mengetahui kegiatan-kegiatan yang diprogramkan demi terlangsungnya pendidikan orang dewasa dilingkungan masyarakat.
- Mengetahui pendidikan orang dewasa (andragogi) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan.
D. Sistematika Penulisan
Pada Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan dari isi makalah kami.
Pada Bab II Pembahasan, menguraikan mengenai bagaimana penerapan andragogi dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana perkembangan pendidikan orang dewasa dilingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintahan, dan kegiatan apa saja yang dicanangkan oleh masyarakat dan pemerintah demi terlaksananya pendidikan bagi orang dewasa.
Pada Bab III Penutup, menguraikan menngenai kesimpulan dan saran untuk melengkapi makalah kami.
Bab II. Pembahasan
A. Penerapan Andragogi dalam Kegiatan Pembelajaran
Secara jelas Knowles (1979) menyatakan apabila peserta didik (warga belajar) telah berumur 17 tahun, penerapan prinsip andragogi dalam kegiatan pembelajarannya telah menjadi suatu kelayakan. Usia warga belajar pada kelompok belajar program PLS rata-rata di atas 17 tahun, sehingga dengan sendirinya penerapan prinsip andragogi pada kegiatan pembelajarannya semestinya diterapkan.
Perlunya penerapan prinsip andragogi dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa dikarenakan upaya membelajarkan orang dewasa berbeda dengan upaya membelajarkan anak. Membelajarkan anak (pedagogi) lebih banyak merupakan upaya mentransmisikan sejumlah pengalaman dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Apa yang ditransmisikan didasarkan pada pertimbangan warga belajar sendiri, apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi warga belajar di masa datang. Sebaliknya, pembelajaran orang dewasa (andragogi) lebih menekankan pada membimbing dan membantu orang dewasa untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka memecahkan, masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Ketepatan pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pembelajaran tentu akan mempengaruhi hasil belajar warga belajar. (Budiningsih, 2005).
Perbedaan antara membelajarkan anak-anak dengan membelajarkan orang dewasa terlihat dari upaya pembelajaran orang dewasa. membelajarkan orang dewasa berpusat pada warga belajar itu sendiri (learned centered). Tutor harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Prinsip tersebut dijadikan pegangan atau panduan dalam praktek membimbing kegiatan belajar orang dewasa. Pendekatan-pendekatan pembelajaran orang dewasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajarnya dapat dipandang sebagai ilmu dan seni (art and science) membantu atau menolong orang dewasa belajar.
1. Orang Dewasa Sebagai Warga Belajar
Cara belajar orang dewasa jauh berbeda dengancara belajar anak-anak. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan belajar bagi orang dewasa harus didekati dengan cara yang berbeda pula. Menyamakan pendekatan pendidikan anak dengan pendekatan pendidikan orang dewasa dapat mengakibatkan kegiatan pendidikan tersebut menjadi suatu hal yang menyakitkan bagi orang dewasa. Kondisi yang menyakitkan tersebut tentu akan sulit untuk mengharapkan hasil belajar yang maksimal.
Menurut Knowles (1979), perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam belajar didasarkan pada empat asumsi tentang orang dewasa. Asumsi-asumsi tersebut ialah: (1) orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda dengan anak-anak, (2) orang dewasa mempunyai konsep diri, (3) orang dewasa mempunyai orientasi belajar yang berbeda dengan anak-anak, dan (4) orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar.
Orang dewasa dalam belajar jauh berbeda dengan anak-anak, Seharusnya menggunakan pendekatan yang berbeda pula dalam membelajarkan anak. Pendekatan yang layak adalah pendekatan andragogi. Bila dihubungkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang terorganisir di kelompok belajar, maka pendekatan andragogi akan semakin terasa pentingnya. Sebab setiap kegiatan yang terorganisir sudah tentu mempunyai atau didasarkan pada pedoman-pedoman tertentu. Pedoman inilah yang menjadi prinsip-prinsip kerja agar kegiatan berjalan pada prosedur yang benar dan sesuai dengan tujuan. (Mappa. 1994)
2. Penerapan Andragogi dalam Performansi Tutor
Tutor sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran orang dewasa. Tutor memasuki kelas dengan bekal sejumlah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini seharusnya melebihi dari yang dimiliki oleh peserta. Seorang tutor dengan pengetahuan dan pengalamannya itu tidaklah cukup untuk membuat peserta untuk berperilaku belajar dalam kelas melainkan sikap tutor sangatlah penting. Seorang tutor bukan merupakan “pemaksa” untuk terjadinya pengaruh terhadap peserta, namun pengaruh itu timbul karena adanya keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar. Untuk mengusahakan adanya perubahan, tutor hendaknya bersikap positif terhadap warga belajar.
Sikap seorang tutor mempunyai arti dan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Umumnya tutor yang memiliki daya tarik akan lebih efektif dari pada tutor yang tidak menarik. Sikap menyenangkan yang ditampilkan oleh tutor akan ditanggapi positif oleh peserta, pada gilirannya berpengaruh terhadap intensitas perilaku belajarnya. Sebaliknya, fasilitator yang menampilkan sikap tidak menyenangkan akan dinilai negatif oleh peserta, sehingga mengakibatkan kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan.
Ada beberapa hal yang dianggap penting dimiliki oleh para tutor dalam proses interaksi belajar yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya warga belajar, yaitu (1) bersikap manusiawi dan tidak bereaksi secara mekanis atau memahami masalah peserta didik hanya secara intelektual; ikut merasakan apa arti manusia dan benda bagi mereka; berada dan bersatu dengan peserta didik; membiarkan diri sendiri mengalami atau menyatu dalam pengalaman para peserta didik; merenungkan makna pengalaman itu sambil menekan penilaian diri sendiri, (2) Bersikap kewajaran: jujur, apa adanya, konsisten, terbuka; membuka diri; merespon secara tulus ikhlas, (3) Bersikap respek: mempunyai pandangan positif terhadap peserta; mengkomunikasikan kehangatan, perhatian, pengertian, menerima orang lain dengan penghargaan penuh; menghargai perasaan dan pengalaman mereka, dan (4) Membuka diri: menerima keterbukaan orang lain tanpa menilai dengan ukuran, konsep dan pengalaman diri sendiri; secara aktif mengungkapkan diri kepada orang lain dan mau mengambil resiko jika melakukan kekeliruan. (Malik, 2011).
3. Penerapan Andragodi dalam Pengorganisasian Bahan Belajar
Pengorganisasian bahan belajar sedemikian rupa, memudahkan warga belajar dalam mempelajarinya. Pengorganisasian bahan belajar dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Setiap bahan belajar yang ingin disampaikan, harus dilihat dari ketertarikan warga belajar terhadap materi yang disampaikan, kesesuaian materi dengan kebutuhan warga belajar, dan kesamaan tingkat dan lingkup pengalaman antara tutor dan warga belajar.
Bahan belajar yang berisi pengetahuan, keterampilan dan atau nilai-nilai akan disampaikan oleh tutor kepada warga belajar. Bahan belajar itu pula yang akan dipelajari oleh warga dalam mencapai tujuan belajar. Materi harus dipilih atas pertimbangan sejauh mana peranannya dalam menciptakan situasi untuk penyesuaian perilaku warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Materi itu pun akan mempengaruhi pertimbangan tutor dalam memilih dan menetapkan teknik pembelajaran. (Iryanto, 2011).
Seorang tutor hendaknya mengetahui faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam memilih bahan belajar untuk diajarkan. Ketertarikan warga belajar dalam memilih dan mempelajari bahan belajar adalah merupakan manifestasi dari perilaku belajar warga belajar. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam memilih bahan belajar adalah tingkat kemampuan peserta, keterkaitannya dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta, tingkat daya tarik bahan belajar, dan tingkat kebaharuan dan aktualisasi bahan.
4. Penerapan Andragogi dalam Metode Pembelajaran
Penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa berimplikasi pada penggunaan teknik pembelajaran yang dipandang cocok digunakan di dalam menumbuhkan perilaku warga belajar. Knowles mengklasifikasi teknik pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar berdasarkan tipe kegiatan belajar, yakni; sikap, pengetahuan dan keterampilan. (Sudjana. 2005).
Kegiatan belajar pada pendidikan orang dewasa masih merupakan kegiatan belajar yang paling efisien dan paling dapat diterima serta merupakan alat yang dinamis dan fleksibel dalam membantu orang dewasa belajar. Oleh karena, kegiatan belajar merupakan alat yang dinamis dan fleksibel dalam membantu orang dewasa, maka penggunaan metode belajar diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Metode belajar orang dewasa adalah cara mengorganisir peserta agar mereka melakukan kegiatan belajar, baik dalam bentuk kegiatan teori maupun praktek. (Mappa. 1994).
Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar, harus (1) berpusat pada masalah, (2) menuntut dan mendorong peserta untuk aktif, (3) mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya, (4) menumbuhkan kerja sama, baik antara sesama peserta, dan antara peserta dengan tutor, dan (5) lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan merupakan transformasi atau penyerapan materi.
B. Pendidikan Orang Dewasa yang Tumbuh dan Berkembang dalam Masyarakat
Sebagaimana yang dikemukakan Knowles (1970), andragogi sekurang-kurangnya didasarkan pada empat asumsi, yakni:
- Konsep dirinya bergerak dari pribadi yang tergantung kearah pribadi yang mandiri,
- Manusia mengakumulasikan banyak pengalaman yang diperolehnya, sehingga menjadi suatu sumber belajar yang berkembang,
- Kesiapan belajar manusia secara meningkat diorientasikan pada tugas perkembangan peranan sosial yang dibawa, dan
- Perspektif waktunya berubah dari suatu pengetahuan yang tertunda penerapannya menjadi penerapan yang segera secara seiring orientasinya terhadap belajar beralih dari suatu orientasi terpusat pada mata pelajaran kepada orientasi terpusat pada mata pelajaran kepada orientasi terpusat pada masalah.
Jenis-jenis pendidikan dilaksanakan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). PKBM merupakan pusat (centra) dan atau wadah seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi atau bakatnya yang dikelola/diselenggarakan oleh diri dan untuk masyarakat. PKBM diharapkan sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk lebih aktif dalam memilih kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal peningkatan masyarakatnya. PKBM juga merupakan salah satu upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat sekaligus menyongsong diberlakukannya otonomi daerah secara lebih luas. Kegiatan-kegiatan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang dilaksanakan PKBM adalah:
1. Life Skill
Pendidikan kecakapan hidup merupakan satu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup dan kehidupannya secara tepat guna dan berdaya guna. Kecakapan hidup adalah sebagai pengetahuan yang luas dan interaksi kecakapan yang diperkirakan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia dewasa untuk dapat hidup secara mandiri di masyarakat. Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skill) merupakan bagian dalam pengembangan kurikulum terpadu, karena pengembangan kecakapan hidup seharusnya tidak berdiri sendiri melainkan terintegritas dengan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang lain. Supaya tidak menjadi dangkal, maka substansi pengembangan kecakapan hidup harus terpadu dengan beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum di suatu lembaga pendidikan, jadi bukan sekedar pendidikan keterampilan atau vokasional dasar yang terpisah-pisah.
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dituntut untuk memiliki sekaligus 4 jenis kecakapan (Life Skill), yaitu:
a. Kecakapan Pribadi
Kecakapan pribadi mencakup kecakapan untuk mengenal diri sendiri, kecakapan berfikir secara rasional dan kecakapan untuk tampil dengan percaya diri yang mantap. Sebagai contoh bentuk kecakapan pribadi adalah sebagai berikut :
- Kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk lingkungan.
- Kesadaran akan potensi diri dan terdorong untuk mengembangkannya.
- Kecakapan untuk menggali informasi.
- Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan.
- Kecakapan memecahkan masalah secara arif dan kreatif.
b. Kecakapan Sosial
Kecakapan sosial mencakup kecakapan untuk berkomunikasi, melakukan kerja sama, bertenggang rasa, dan memiliki kepedulian serta tanggungjawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Adapun contoh bentuk kecakapan sosial adalah sebagai berikut :
- Kecakapan mendengarkan
- Kecakapan membaca
- Kecakapan berbicara
- Kecakapan menulis
- Kecakapan menulis gagasan atau pendapat
- Kecakapan sebagai teman kerja yang menyenangkan
- Kecakapan sebagai pimpinan yang berempati
c. Kecakapan Akademik
Kecakapan akademik adalah kecakapan untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Demikian yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, eksplorasi, inovasi dan kreasi melalui pendekatan ilmu, selain itu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil teknologi untuk mendukung kegiatannya. Contoh kecakapan akademik yaitu sebagai berikut :
1) Kecakapan mengidentifikasi variable dan hubungan
2) Kecakapan merumuskan hipotesis
3) Kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian
d. Kecakapan Vocational
Kecakapan vocational mencakup kecakapan yang berkaitan dengan bidang keterampilan-keterampilan professional tertentu dalam dunia usaha dan industri, baik untuk dipergunakan bekerja sebagai karyawan/karyawati maupun usaha mandiri.
Adapun tujuan diberikannya kecakapan hidup kepada peserta didik yaitu diantaranya agar ia memiliki:
- Keterampilan, pengetahuan dan setiap yang dibutuhkan dalam memenuhi dunia kerja, baik bekerja mandiri (wirausaha) dan bekerja pada perusahaan produk jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
- Motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat penghasilan, yang unggul dan mampu bersaing di pasar global.
- Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri, maupun untuk anggota keluarga.
d. Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan disetiap lapisan masyarakat.
Ada beberapa tahapan dalam mengelola kecakapan hidup bagi peserta didik, diantaranya:
a. Perencanaan
Kegiatan life skill ini direncanakan oleh PKBM, sebelum PKBM merencanakan, kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan bekerja masyarakat. Kegiatan yang diawali dengan kebutuhan belajar masyarakat akan lebih efektif dalam pelaksanaannya.
b. Pelaksanaan
Kegiatan life skill ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan narasumber yang terkait dengan program/kegiatan yang telah direncanakan. Sarana/prasarana yang telah tersedia haruslah relevan dengan program yang telah direncanakan. Pada pelaksanaan kegiatan ini harus mengacu/berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dirjen PLS Depdiknas.
c. Evaluasi
Kegiatan life skill ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai. Untuk menilai program ini dilakukan dengan melihat sesuai penerapan kegiatan didalam masyarakat. Semakin banyak anggota life skill menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, semakin berhasil kegiatan ini. Selanjutnya program ini berhasil dapat dilihat dari tingginya etos kerja warga belajar dan dapat menghasilkan karya yang unggul dan maupun bersaing dengan pasar global.
2. Majelis Taklim
Majelis taklim adalah sekelompok masyarakat, atau sekumpulan orang-orang yang ingin mendalami ajaran agama Islam, biasanya majelis taklim ini ada di kelurahan atau di kenagarian ataupun jorong. Pada kegiatan majelis taklim ini, materi yang dipelajari meliputi: ibadah, syari’at, dan muamalat. Kehadiran majelis taklim ini, sudah jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan hubungan sesama manusia, meningkatkan keimanan dan mendalami syariat Islam.
Tujuan diadakannya majelis taklim ini diantaranya yaitu :
- Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- Meningkatkan kualitas pemahaman agama,
- Memperkokoh dakwah Islamiyah,
- Beramal sesuai dengan ilmu dan agama yang dipelajari,
- Meningkatkan syariat agama Islam,
- Memberikan pelajaran dan pembinaan terhadap masyarakat, dan
- Menyemarakkan dan memakmurkan masjid-masjid.
Adapun cara mengelola kegiatan majelis taklim ini yaitu :
a. Perencanaan
Kegiatan majelis taklim ini direncanakan oleh pengurus serta anggota. Perencanaan disusun atas dasar kebutuhan belajar anggota-anggota. Pada umumnya kegiatan-kegiatan direncanakan dalam bentuk jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek direncanakan untuk memenuhi kebutuhan mendalam ajaran agama biasanya 5 kali seminggu.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pada kelompok majelis taklim ini sangat ditentukan dari tersedianya waktu anggota dan disepakati secara bersama.
c. Evaluasi
Kegiatan evaluasi pada majelis taklim ini tidak ada evaluasi yang berprogram, sesuai dengan ciri pendidikan luar sekolah, evaluasi banyak diarahkan kepada self evaluation (evaluasi diri).
C. Pendidikan Orang Dewasa yang Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
Pendidikan orang dewasa yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain :
1. Pelatihan dan Pengembangan Program KB (Keluarga Berencana) Nasional
Kewenangan Balatbang BKKBN mendukung kewenangan pemerintah dalam program KB Nasional, terutama untuk peningkatan SDM, tenaga pengelola dan pelaksana program. Adapun tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan program pelatihan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelola dan pelaksana program KB Nasional melalui :
- Penyelenggaraan kegiatan penjajakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan (need assessment),
- Penyusunan desain pelatihan dan pengembangan,
- Penyusunan bahan diklat, kurikulum materi, metoda, media, strategi dan instrument evaluasi,
- Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan,
- Evaluasi program pelatihan dan pengembangan evaluasi pasca pelatihan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan.
- Meningkatkan kualitas program pelatihan.
- Mengembangkan koordinasi dan kemitraan pihak terkait. Pokok-pokok pengelolaan diantaranya sebagai berikut :
- Upaya peningkatan kualitas institusi Balatbang
- Upaya peningkatan kualitas program pelatihan, dan
- Pengembangan jejaring kerja dan koordinasi.
Adapun upaya peningkatan kualitas instansi diklat adalah sebagai berikut :
- Peningkatan kualitas SDM Balatbang meningkatkan kompetensi SDM diklat (struktural) fungsional dan staf menjadi SDM yang dapat merubah pola pikir peserta didik sesuai dengan perubahan lingkungan strategi dan kompetensi dalam menjalankan kegiatannya.
- Meningkatkan motivasi belajar dengan menerapkan learning organization.
- Merubah pola pikir, pola interaksi yang bersifat statis menjadi dinamis, dan kreatif sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Mengembangkan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan, dengan memanfaatkan waktu luang yang ada.
- Meningkatkan kemampuan dan membina hubungan dengan pihak luar.
- Membangun jaringan pengembangan prestasi secara mandiri dengan pihak luar.
- Peningkatan sarana dan prasarana diklat. Penyediaan sarana PBM standar (alat bahan yang kondusif untuk PBM).
Bab III. Penutup
A. Simpulan
Pendidikan orang dewasa atau yang sering disebut dengan andragogi adalah suatu proses dimana orang-orang yang sudah memiliki peran sosial sebagai orang dewasa melakukan aktivitas belajar yang sistematik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk membuat perubahan dalam pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan.
Perbedaan antara membelajarkan anak-anak dengan membelajarkan orang dewasa terlihat dari upaya pembelajaran orang dewasa. membelajarkan orang dewasa berpusat pada warga belajar itu sendiri (learned centered).
Cara belajar orang dewasa jauh berbeda dengan cara belajar anak-anak. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan belajar bagi orang dewasa harus didekati dengan cara yang berbeda pula. Menyamakan pendekatan pendidikan anak dengan pendekatan pendidikan orang dewasa dapat mengakibatkan kegiatan pendidikan tersebut menjadi suatu hal yang menyakitkan bagi orang dewasa. Kondisi yang menyakitkan tersebut tentu akan sulit untuk mengharapkan hasil belajar yang maksimal.
B. Saran
Kita sebagai seorang mahasiswa yang berperan langsung dalam proses pendidikan khususnya pendidikan orang dewasa senantiasa memperluas pemahaman dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dan mengaplikasikan pembelajaran secara aktif mengenai belajar orang dewasa dalam kegiatan belajar dan pembelajaran.