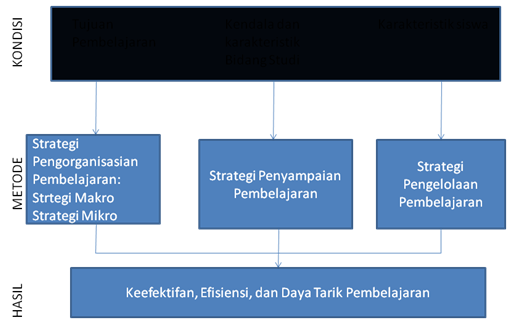Abad Pertengahan & Zaman Renaisans
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sejarah Eropa memiliki bentangan waktu yang panjang dimulai dari zaman paleolithikum ribuan tahun yang lalu. Secara garis besar, sejarah Eropa dibagi menjadi 3 periode, yaitu: Eropa klasik, Eropa pertengahan, dan Eropa modern. Di sini kita akan membahas tentang Eropa abad pertengahan pada masa abad kegelapan dan juga masa pencerahan (Renaisans).
Abad pertengahan adalah periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarkhi-monakhi nasional. Dimulainya penjelajahan samudera, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimulainya renaissance pada tahun 1517.Abad pertengahan sering diwarnai dengan kesan-kesan yang tidak baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kalangan yang memberikan stereotipe kepada abad pertengahan sebagai periode buram sejarah Eropa mengingat dominasi kekuatan agama yang begitu besar sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip moralitas yang agung membuat kekuasaan agama menjadi begitu luas dan besar di segala bidang.
Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan.Eropa dilanda Zaman Kegelapan sebelum tiba Zaman Pembaharuan. Yang dimaksud Zaman Kelam atau Zaman Kegelapan ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan.Menurut Ensikopedia Amerika, zaman ini berlangsung selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi.
Gelap juga dianggap sebagai tidak adanya prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh.Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan.Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera masalah, malah ada yang dibunuh.
Segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekasiaran Roma. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat-keputusan adalah para ahli agama.Bahkan segala sesuatu yang bertentangan dengan penafsiran dewan gereja merupakan pelanggaran hukum berat.
Akibatnya setiap inovasi yang berasal dari kaum ilmuan selalu digagalkan oleh dewan gereja. Ya itu tadi pokoknya bila dewan gereja tidak paham dan tidak memiliki dasar argumen yang kuat di dalam injil maka inovasi tersebut merupakan perkara pelanggaran agama berat. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Nicholas Coppernicus yang berakhir tragis akibat teorinya yang mengatakan.
Akibat terlalu banyak intervensi dewan Gereja pada sendi-sendi kehidupan, termasuk juga pelarangan terhadap temuan maupun inovasi baru yang tidak ada pada injil maka akhirnya terjadi stagnasi secara multi dimensi yang lambat laun berimbas pada timbulnya krisis multi dimensi.Dan sebagai lawannya maka muncullah zaman Renaisans yang sering di sebut sebut sebagai zaman kelahiran kembali.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalahnya, yaitu :
- Apa yang dimaksud abad pertengahan ?
Apa yang dimaksud zaman renaisan ?
- Bagaimana awal mula abad pertengahan dan renasisans ?
- Apa saja faktor faktor penyebabnya ?
- Bagaimana karakteristiknya ?
- Bagaimana perkembangan agama pada masa itu ?
- Apa saja penyakit yang melanda saat itu ?
- Bagaimana perkembangan ilmu,filsafat dan seni ?
- Bagaimana penjelajahan samudra pada saat itu ?
- Bagaimana hukum yang berlaku ?
- Siapa saja tokoh yang berperan didalamnya?
- Apa saja dampak umumnya ?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuannya, yaitu :
- Untuk memperoleh data tentang abad pertengahan dan zaman Renaisans.
- Untuk memenuhi tugas dari pembimbing kami.
Bab II. Kajian Pustaka
A. Abad Pertengahan
Abad Pertengahan adalah periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah prakarsa raja Charlemagne pada abad 5 hingga munculnya monarkhi-monarkhi nasional, dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta Reformasi Protestan dengan dimulainya renaisans pada tahun 1517.Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan.
Eropa dilanda Zaman Kelam (Dark Ages) sebelum tiba Zaman Pembaharuan. Maksud “Zaman Kelam” ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelek dan ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Amerika, tempo zaman ini selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roma dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi. “Gelap” juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud tindakan dan cengkraman kuat pihak berkuasa agama; Gereja Kristen yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik.
Mereka berpendapat hanya gereja saja yang layak untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains asa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka ditolak. siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera malah ada yang dibunuh.
Pikiran ini, terimplementasi melalui teori yang dikeluarkan oleh Thomas Aquinas (1274) seorang ahli falfasah yakni “ negara wajib tunduk kepada kehendak gereja ”. St Augustine (1430) sebelumnya juga berpendirian demikian. Manakala Dante Alighieri (1265-1321) berpendapat kedua-dua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri, dan mestilah bekerjasama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch, 1992, 172-174).
Dalam paradigma abad pertengahan, dua wilayah agama dan dunia terpisah total satu dengan yang lain sehingga tidak ada peluang bagi ekspansi satu terhadap yang lain atau pembauran antar keduanya. Seorang manusia kalau tidak ‘melangit’ haruslah ‘membumi’, atau kalau tidak meyakini kekuasaan alam gaib terhadap segala urusan hidupnya, maka dia harus memutuskan hubungan secara total dengan Tuhan dan roh-roh kudus, dan jika dia menghargai jasmani dan urusan materinya maka dia bukan lagi seorang rohaniwan dan berarti telah memutuskan hubungan dengan Tuhan.
Kata Augustine “Siapapun yang mahir dalam kesenian, perang, dan filsafat adalah orang yang bejat dan sesat, karena dia berasal dari kota setan dimana kebahagiaannya tak lebih dari sekadar topeng yang menipu, dan keindahannya hanya merupakan wajah alam kubur”. Kota inilah yang tidak diterima oleh Tuhan dan fitrah manusia. Karena orang yang sombong dan angkuh adalah merupakan kepekatan hari dan orang yang memiliki pengetahuan tentang segala yang harus diketahui oleh orang-orang terpuji. Dan ketika melihat kota setan ini tenggelam ke dalam kesesatan dan kesombongannya, maka semua sudut kegelapannya akan terlihat.
Konsep diatas, dipertegas oleh Fritjof Capra (2004) yakni : “Para ilmuwan pada Abat Pertengahan, yang mencari-cari tujuan dasar yang mendasari berbagai fenomena, menganggap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Tuhan, roh manusia, dan etika, sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki signifikansi tinggi, jadi ilmu didasarkan atas penalaran keimanan”.
Dengan demikian, kerangka berpikir yang dominan pada abad pertengahan dan tekanan kuat para elit gereja yang menganggap dirinya pengawas tatanan yang menguasai dunia dan telah menginterogasi ideologi para ilmuan dan menyeret mereka ke pengadilan serta menganggap kegiatan ilmiah sebagai campurtangan setan, kemudian faktor-faktor lain yang berada di luar pembahasan ini telah menjadi latar belakang munculnya Renaisans yang telah melahirkan teriakan protes terhadap kondisi yang dominan pada abad pertengaha.
Abad Pertengahan berakhir pada abad ke-15 dan kemudian disusul dengan zaman Renaissance. Zaman Renaissance berlangsung pada akhir abad ke-15 dan 16. Kesenian, sastra musik berkembang dengan pesat. Ada suatu kegairahan baru, suatu pencerahan. Ilmu pengetahuan mulai dikembangkan oleh Leonardo da Vinci (1452-1519), Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1643), dll.
B. Zaman Renaisans
Zaman Renaisans (bahasa Inggris: Renaissance) adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada Abad Pertengahan Akhir dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Meskipun pemakaian kertas dan penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide-idenya dari abad ke-15 dan seterusnya, perubahan Renaissance tidak terjadi secara bersama maupun dapat dirasakan di seluruh Eropa.Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani,orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani-Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik.Kebudayaan klasik ini dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia.
Dalam dunia politik, budaya Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi, dan dalam ilmu peningkatan ketergantungan pada sebuah observasi. Sejarawan sering berargumen bahwa transformasi intelektual ini adalah jembatan antara Abad Pertengahan dan sejarah modern. Meskipun Renaissance dipenuhi revolusi terjadi di banyak kegiatan intelektual, serta pergolakan sosial dan politik, Renasaince mungkin paling dikenal karena perkembangan artistik dan kontribusi dari polimatik seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo, yang terinspirasi dengan istilah “Manusia Renaissance”.
Ada konsensus bahwa Renaissance dimulai di Florence, Italia, pada abad ke-14. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usulnya dan karakteristik, berfokus pada berbagai faktor termasuk kekhasan sosial dan kemasyarakatan dari Florence pada beberapa waktu, struktur politik,perlindungan keluarga dominan, Wangsa Medici dan migrasi sarjana Yunani dan terjemahan teks ke bahasa Italia setelah Kejatuhan Konstantinopel di tangan Turki Utsmani.
Kata Renaissance, yang terjemahan literal dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggris adalah “Rebirth” (atau dalam bahasa Indonesia “Kelahiran kembali”), pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Perancis Jules Michelet pada tahun 1855 dalam karyanya, Histoire de France. Kata Renaissance juga telah diperluas untuk gerakan sejarah dan budaya lainnya, seperti Carolingian Renaissance dan Renaissance dari abad ke-12.
Bab III. Pembahasan
A. Awal Mula
Di sini kita akan membahas tentang Eropa abad pertengahan pada masa abad kegelapan.Abad pertengahan adalah periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarkhi-monakhi nasional. Dimulainya penjelajahan samudera, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimulainya renaissance pada tahun 1517.
Abad pertengahan sering diwarnai dengan kesan-kesan yang tidak baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kalangan yang memberikan stereotipe kepada abad pertengahan sebagai periode buram sejarah Eropa mengingat dominasi kekuatan agama yang begitu besar sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip moralitas yang agung membuat kekuasaan agama menjadi begitu luas dan besar di segala bidang.Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan.
Eropa dilanda Zaman Kegelapan sebelum tiba Zaman Pembaharuan. Yang dimaksud Zaman Kelam atau Zaman Kegelapan ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan Menurut Ensikopedia Amerikana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi.
Gelap juga dianggap sebagai tidak adanya prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera, malah ada yang dibunuh. segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekasiaran Roma. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat-keputusan adalah para ahli agama. Bahkan segala sesuatu yang bertentangan dengan penafsiran dewan gereja merupakan pelanggaran hukum berat.
Akibatnya setiap inovasi yang berasal dari kaum ilmuan selalu digagalkan oleh dewan gereja. Ya itu tadi pokoknya bila dewan gereja tidak paham dan tidak memiliki dasar argumen yang kuat di dalam injil maka inovasi tersebut merupakan perkara pelanggaran agama berat. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Nicholas Coppernicus yang berakhir tragis akibat teorinya yang mengatakan.Akibat terlalu banyak intervensi dewan Gereja pada sendi-sendi kehidupan, termasuk juga pelarangan terhadap temuan maupun inovasi baru yang tidak ada pada injil maka akhirnya terjadi stagnasi secara multi dimensi yang lambat laun berimbas pada timbulnya krisis multi dimensi.
Zaman Kegelapan (Dark Ages)
Abad kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaisannce atau munculnya kembali peradaban lama. Dari masa sebelum masehi yang kental dengan Filsafat Relativisme (Kebenaran) Sofisme Yunani Kuno, berlanjut ke apa yang kemudian dinamakan Jaman Abad Pertengahan yang berlangsung lama, kurang lebih selama lima belas Abad, dari sekitar Abad I sampai Abad XV M.Masa ini disebut juga sebagai Era atau masa Medieval atau juga Abad Kegelapan atau Dark Ages) dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam ‘alaihis salam menapakkan kaki di muka Bumi dan berdakwah.
Beliau dikenal juga sebagai Isa bin (anak) Maryam, yang dengan sejumlah perkecualian dan catatan perbedaan mendasar adalah hampir dapat dikenal sama juga sebagai Yesus Kristus atau Yesus dari Nazareth dalam khazanah Kristen.Kegemparan akan datangnya ’Yesus dari Nazareth’ yang tak memiliki ayah dan nasabnya ditahbiskan kepada Maryam (Maria), ibunya, dan dalam hidup singkatnya menampilkan berbagai mukjizat luar-biasa itu, mengguncang peradaban manusia di sekitarnya saat itu, dan banyak orang yang kemudian berspekulasi akan kenyataan ini.Di masa ini, lahir pula agama Kristen, dan ide-idenya mendominasi relung kehidupan masyarakat Eropa dan pengikutnya, termasuk para Pemikirnya. Dan wajah peradaban Barat pada Abad Pertengahan ini, karenanya, didominasi oleh Filsafat Kristen.
Filsafat Kristen atau Abad Pertengahan ini, antara lain bertokohkan Filsuf Plotinus, (Santo atau Saint) Augustinus atau Augustine, (Saint) Anselmus, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Albert Agung, Thomas Aquinas, dsb. Yang kesemuanya sepakat mengedepankan iman dogmatis (tak boleh dibantahi) Kristiani, dan telaahnya pun bersifat religius-dogmatis.Akibat pengaruh hebat dan dominan Agama Kristen yang didominasi oknum kaum Gerejawan dan Monarki Baratnya dengan segala ragam tafsir dogmatisnya.
Dan tak pelak pemanfaatan Platonisme ala Yunani Kuno (dicetuskan Plato) yang mengajarkan bahwa kebenaran itu sudah ada dengan sendirinya dan berpusat kepada Tuhan namun berjenis dan berbungkus baru, yang disebut sebagai Neo-Platonisme, menjadi gencar dan ditahbiskan sepenuhnya tanpa telaah kristis kepada iman Kristiani. Ini, mau tak mau mendukung pula klaim dogmatis akan kebenaran Kristen.Para ahli Filsuf dan Agamawan mereka di saat itu karenanya teguh bermottokan ”Credo et intelligam” atau ”Keyakinan (keimanan agama) berkedudukan di atas pemikiran (logika), keyakinan mengungguli pemikiran” atau lebih mudahnya, ”Yakini dulu sesuatu, baru carikan alasan untuk menjelaskannya”.
Maka, dengan sendirinya, Akal (di Barat) benar-benar kalah pada masa ini (terutama terlihat pada isi Filsafat dari Plotinus, Augustinus, Anselmus). Bahkan potensi pemanfaatan akal diganti mutlak oleh Augustinus dengan Iman dogmatis, sebelum penghargaan terhadap potensi Akal sempat muncul kembali kemudian pada masa Thomas Aquinas di akhir masa Abad Pertengahan itu.Dan karenanya pula, Aquinas kemudian ditentangi hebat dan dibenci sebagian besar masyarakat gereja yang terlanjur menjadi pendukung jalur hati iman Kristiani yang dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan di atas adalah iman mutlak dogmatis kristiani yang tidak mengindahkan telaah kritis akal.
Ini juga tak pelak menyebabkan masyarakat Barat di masa itu secara luas menjadi percaya dan beriman dogmatis akan ‘rasa hati’ (atau yang adalah agama, Kristen, lebih tepatnya Kristen Katolik, bagi mereka), karena menurut mereka agama adalah rasa hati dan Filsafat adalah pemikiran. Filsafat dan Agama itu sendiri, satu hal yang di masa sesudahnya terutama masa Thomas Aquinas, dicoba untuk disatu-padukan namun menemui sejumlah kendala sampai masa Modern merebak.Keyakinan Kristiani yang mendominasi di masa Abad Pertengahan ini, menjadikannya tidak boleh atau tidak mudah untuk dapat dikritiki, sekaligus membuat kedudukan mereka yang berada dalam struktur otoritas agamanya menjadi tinggi dan tak dapat disalahkan. Dan karenanya ini juga membuat mereka makmur secara ekonomi juga sebagai pemegang mandat negara dengan mandat Otokrasi dan Teokrasi Kristiani.
Dan kenyataan ini bagi sebagian orang lain, misalnya rakyatnya yang mereka pimpin, artinya juga adalah kesemena-menaan yang diorganisasikan. Kekuasaan absolut negara dan pusat-pusat kesejahteraan masyarakat saat itu dipegang mutlak oleh Gereja dan Kerajaan, dengan pajak sistem Feodalisme berdasarkan tafsir mereka terhadap iman Kristiani dan bahwa Gereja adalah wakil Tuhan di Bumi dan bahwa sistem pemerintahan yang terbenar adalah Kerajaan Kristiani penyokongnya. Golongan Ksatria, dan Raja adalah pelindung rakyat dan rakyat harus membayar pajak kepada mereka yang penafsirannya seringkali dianggap semena-mena oleh rakyat.
Tak pelak juga, maka, perkembangan ilmu-pengetahuan yang biasanya berdasarkan kepada gelitikan pemikiran, rasa penasaran, kebertanya-tanyaan pemikiran pun menjadi lambat pula. Pendeknya, potensi telaah akal pada masa ini dihambati.
Di saat Zaman Kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama. Gagasan tentang Dark Age berasal dari Petrarch (seorang humanis,cendekiawan dan penyair Italia) pada tahun 1330-an.
Dia menulis tentang orang-orang yang hidup sebelum dia, ia berkata: “Di tengah kesalahan bersinar seorang genius, mata mereka melihat dengan tajam meskipun mereka dikelilingi oleh kegelapan yang sangat pekat “. Para penulis yang beragama Kristen, termasuk Petrarch sendiri telah lama menggunakan kiasan ” terang melawan gelap “untuk menggambarkan” kebaikan melawan kejahatan “. Petrarch adalah orang pertama yang menggunakan kiasan dan memberikan makna sekuler dengan membalikkan penerapannya. Zaman klasik telah lama dianggap sebagai zaman “gelap” karena kurangnya kekristenan yang dilihat oleh Petrarch sebagai zaman “cahaya” karena prestasi dan pencapaian kultural, sedangkan pada zaman Petrarch, diduga kurang prestasi budaya sehingga Petrarch memandangnya sebagai zaman kegelapan (dark age).
Abad pertengahan merupakan zaman dimana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru malah gereja lah yang mengatur pemerintahan. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereka akan mendapat balasan yang sangat kejam. Contohnya, pembunuhan Copernicus mengenai teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, tetapi hal ini bertolak belakang dari gereja sehingga Copernicus dibunuhnya.
Pemikiran manusia pada Abad Pertengahan ini mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir (ekstologi). Kehidupan manusia pada hakekatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada theology. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat scholastik yaitu suatu pemikiran filsafat yang dilandasi pada agama dan untuk alat pembenaran agama. Oleh karena itu disebut Dark Age atau Zaman Kegelapan.Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan.
Eropa dilanda Zaman Kegelapan sebelum tiba Zaman Pembaharuan. Yang dimaksud Zaman Kelam atau Zaman Kegelapan ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan Menurut Ensikopedia Amerikana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi.
Gelap juga dianggap sebagai tidak adanya prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera, malah ada yang dibunuh. segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekasiaran Roma. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat-keputusan adalah para ahli agama. (lihat perilaku kaum Salafy yang kini justru meniru mereka) Bahkan segala sesuatu yang bertentangan dengan penafsiran dewan gereja merupakan pelanggaran hukum berat.
Akibatnya setiap inovasi yang berasal dari kaum ilmuan selalu digagalkan oleh dewan gereja. Ya itu tadi pokoknya bila dewan gereja tidak paham dan tidak memiliki dasar argumen yang kuat di dalam injil maka inovasi tersebut merupakan perkara pelanggaran agama berat. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Nicholas Coppernicus yang berakhir tragis akibat teorinya yang mengatakan akibat terlalu banyak intervensi dewan Gereja pada sendi-sendi kehidupan, termasuk juga pelarangan terhadap temuan maupun inovasi baru yang tidak ada pada injil maka akhirnya terjadi stagnasi secara multi dimensi yang lambat laun berimbas pada timbulnya krisis multi dimensi.
Renaisans di Italia
Florencia Kota Pelopor
Florencia menjadi pelopor renaissance di Italia, bukan justru kota Roma, Milano atau Venesia. Menurut John Hele dan Plum Florensia menjadi kota pelopor Renaissance di Italia karena berbagai faktor antara lain adalah :
- Kota Florencia pada zaman Romawi bernama Florentia itu secara geografis merupakan kota pedalaman Italia Utara yang sangar strategis, subur karena dibelah oleh Sungai Arno dan menjadi kota pertemuan dari berbagai kota di Italia Utara antara lain Genoa, Lucca dan Pisa di sebelah barat, Siena dan Arezzo di sebelah selatan, Urbino, San Marino dan Romagna di sebelah timur serta Bologna, Modena di bagian Utara. Maka tidak mengherankan jika Florencia menjadi kota pertemuan dagang yang kaya raya dan besar pada abad ke-XIII.
Florencia sebagai kota industry khususnya wol (terbaik di Italia) dan tekstil pada umumnya. Menurut John Hele pada abad ke XIV sudah ada 21 gilda utama yang dimiliki oleh para hakim, notaries, importir dan pengusaha dan 44 gilda kecil sebagai pendukungnya yang dimiliki oleh pengrajin, pedagang.
- Florencia sebagai pusat keuangan Italia masa itu. Kota ini mempunyai penduduk yang besemboyan “per non dormire (agar jangan tidur, maksudnya tidur tidak mendatangkan rezeki)” dan “Florentinis ingentis nihil arduit est (tidak ada yang dapat dikerjakan oleh orang Florencia)”.
- Florencia merupakan ibukota Republik Florentia yang pada prinsipnya menganut system pemerintahan demokrasi dan memperhatikan kepentingan rakyat. Maka kreativitas seni dan inteletual dapat bebas berkembang. Didirikannya pendidikan formal di Accademia Plato yang didirikan oleh keluarga Medici sehingga melahirkan seniman-seniman besar, para ilmuan terkenal, sastrawan jenius dan arsitek besar. Maka tidak mengherankan apabila dapat mempertahankan kemasyuran dan berperan penting dalam modernisasi Italia selama dua abad. Florencia telah menjadi awal pembaharuan berbagai bidang kehidupan manusia dari sumber-sumber daya manusia, keuangan, perdangangan, sosial dan budaya, Benih-benih humanism yang melahirkan liberalism, individualism serta rasionalisme mendapat tempat subur untuk berkembang ke seluruh penjuru Eropa.
Keluarga Medici
Keluarga Medici merupakan salah satu keluarga yang terkenal di Italia pada zaman renaissance. Keluarga ini mulai mempunyai nama terhormat dalam masyarat pada abad ke XIV ketika Averardo de Medici yang terkenal dengan nama Bicci berhasil dalam usahawan swasta ulat sutera, kain lenen dan akhirnya menjadi bankir. Usaha ini dilanjutkan anaknya yang bernama Giovanni di Bicci meluas ke luar Italia. Keluaga Medici mulai terlibat dalam berbagai bidang terutama politik, ketika Giovani terpilih menjadi hakim agung di Florancia pada 1421.
Giovani mempunyai dua anak yang bernama Casimo dan Lorenzo. Casimo berhasil menjadikan keluarga Medici mencapai puncak kejayaan pada bidang politik, ekonomi bahkan agama. Ia juga tokoh utama yang menjadi pelopor dan pelindung bidang budaya, kesenian dan ilmu pengetahuan. Casimo adalah pewaris etos kerja orang Florencia yaitu per non dormire sehingga ia memadukan usaha bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dengan semboyan tersebut. Jasanya antara lain menjadi pendukung utama untuk mendirikan Accademia Plato di Florencia pada tahun 1642 sehingga ia ikut serta dalam menentukan arah perkembangan dunia akedemisi. Kemudian mendorong mendirikan Akademia Seni pada 1460 yang dipimpin oleh Michelangelo. Ia juga mendorong seniman untuk bersemboyan I’art pour I’art bukan I’art pour d’argent (seni untuk uang).
Lorenzo merupakan penerus Casimo, ia tampil sebagai diplomat ulung, seniman dan akhirnya menjadi penguasa di Florencea. Keturuan lain keluarga Medici ada yang menjadi pemimpin gereja yang tertinggi seperti Paus Leo X (1513-1521), Paus Clemens VII (1523-1534), Paus Pius IV (1559-1565), Paus Leo IX tahun 1605. Sejak Paus Leo X tampil banyak pula paus yang menjadi peminat dan pelindung karya seni serta mengangkat keturunan Keluarga Medici menjadi Duke of Urban. Sementara itu pada masa Paus Clemens VII, keturunan Medici yang bernama Alessandro diangkat menjadi pendiri dinasti Tuscani yang berkuasa hingga abad XVIII.
3.2 Faktor Faktor
· Abad Pertengahan
Periode Abad Pertengahan awal antara tahun 500-1000 merupakan masa transisi dalam sejarah Eropa yg kacau sehingga disebut sebagai ‘abad kegelapan’. Periode ini ditandai dengan :
® Invasi suku-suku barbar, mula-mula orang-orang Jerman (Goth, Frank, Anglo-Saxon, dll), kemudian disusul bangsa Skandinavia (Viking) antara tahun 800-1000.
® Terbentuknya kerajaan-kerajaan Jerman dan terjadinya perang-perang perebutan wilayah kekuasaan antara kerajaan-kerajaan tersebut.
® Kehancuran Romawi Barat menyebabkan ekonomi bergeser dari kota-kota ke pedesaan. Pergeseran ini mendorong kemunculan sistem feodal di Eropa.
Disintegrasi Kekaisaran Romawi Barat setelah sekitar 800 tahun dengan serangkaiaan penaklukan ,ekspansi dan konsolidasi politik serta aktifitas kultural, kemudia digantikan perannya oleh Gereja.Jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, secara politis membawa pengaruh terjadinya berbagai kerajaan barbar di Eropa.Setiap kerajaan barbar harus berupaya menata pemerintahan sendiri,karena telah lepas dari pengaturan dan pengawasan Kekaisaran Romawi.Adapun berbagai negara Jerman yang penting,yang didirikan di atas reruntuhan Kerajaan Romawi Barat adalah:
® Kerajaan Goth Timur,wilayahnya meliputi Italia,Slav,dan Burgundia (Swiss)
® Kerajaan Goth Barat,meliputi Spanyol,Kerajaan Vandal di Afrika Utara,Kerajaan Franka di Perancis,Belgia,Belanda,dan Jerman Barat.Sementara itu,sumbangan bangsa Aglo-Saxons yang terhalau dari Jerman menyerbu ke tanah Inggris,kemudian mendesak bangsa-bangsa Kelt yang datang lebih dulu ke kepulauan itu.
Akibat runtuhnya Romawi Barat,telah menyebabkan wajah Eropa menjadi masyarakat Agraris dengan rumah tangga desa tertutup.Disitu tidak terdapat lalu lintas uang.Semua wujud kemasyarakatan didasarkan atas kepemilikan tanah.Hanya pemilik tanah yang memungkinkan adanya administrasi dan sistem militer negara,keadaan ini menciptakan kebutuhan akan tanah-tanah luas.
Telah terjadi anarkhi selama tiga abad (abad VI,VII,VIII) pada masa Keruntuhan Romawi,tercipta ketidakstabilan politik,terjadi anarkhi,tidak ada keamanan perorangan dan hak milik,di situ terjadi pertentangan semua melawan semua.Kekerasan terjadi dimana-mana ,para petani mencari perlindungan di sekitar benteng yang diperkuat terhadap ancaman penyerbuan gerombolan bersenjata.Maka,orang-prang merdeka makin lama makin tergantung pada tuan tanah,bahkan ada yang membayar dengan kemerdekaanya,tuan tanah bertindak sebagai pelindung kaum tani dan harta kekayaannya digunakan untuk biaya perang dan untuk memberi bantuan dalam bahaya kelaparan.Sebaliknya,balas jasa mengerjakan tanah untuk kepentingan tuan tanahnya.Dengan adanya kenyataan tersebut terjadilah hubungan foedal,para petani bersumpah setia dalam ikatan foedal untuk memenuhi kebutuhan hidup para tuan tanah yang memberi bantuan dan perlindungan,keselamatan hidup demi tuan tanah.
· Renaisans
Latar belakang timbulnya Renaissance jika dilihat dari beberapa aspek adalah kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi Abad Pertengahan.
· Kondisi sosial
Saat itu kehidupan masyarakat Eropa sangat terikat pada doktrin gereja. Segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya, dan kehilangan harga dirinya. Kehidupan manusia tidak tenteram karena senantiasa diintip oleh intelijen gereja, sehingga menimbulkan sikap saling mencurigai dalam masyarakat.
· Kondisi budaya
Terjadi pembatasan kebebasan seni dalam arti bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni ditujukan kepada kehidupan akhirat sehingga budaya tidak berkembang. Demikian pula dalam bidang ilmu pengetahuan karena segala kebenaran hanya kebenaran gereja.
· Kondisi politik
Raja yang secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara, kenyataannya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melancarkan ambisinya. Adakalanya kekuatan militer kaum bangsawan dan kaum gereja lebih kuat dari kekuatan militer milik raja.
· Kondisi ekonomi
Berlaku sistem ekonomi tertutup, yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa.Kondisi-kondisi di atas menyebabkan masyarakat Eropa terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu timbullah upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut.Perubahan-perubahan yang terjadi akibat upaya untuk keluar dari kondisi Abad Pertengahan menjadi latar belakang langsung munculnya Renaissance, sebagai berikut :
® Kehidupan sosial masyarakat Eropa yang tidak lagi mau terbelenggu oleh ikatan gereja. Mereka memalingkan diri dari kehidupan akhirat kepada keduniaan sehingga pengaruh gereja merosot. Kehidupan materialistis semakin berkembang mendesak kehidupan keagamaan.
® Masyarakat berlomba-lomba memasuki kawasan kota dagang dan kota industri, menjadi buruh dengan tujuan berusaha merubah kehidupan ekonomi ke arah yang lebih baik. Petani-petani yang pada Abad Pertengahan setia mengerjakan tanah para bangswan feodal, kini hilang berganti dengan golongan masyarakat baru yang disebut buruh pabrik.
® Seiring dengan laju urbanisasi, berubah pula fungsi kota dari fungsi politis menjadi juga pusat perdagangan dan industri.
® Munculnya kaum borjuis sebagai kelompok baru yang kaya dan mampu menyaingi kaum bangsawan. Kelompok borjuis yang menguasai perdagangan tidak suka pada kelompok bangsawan dan gereja, sehingga hanya mau membayar pajak kepada raja. Akhirnya raja kembali memegang kekuasaan politik tertinggi yang ditaati perintahnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
® Naskah-naskah ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi Kuno dijumpai kembali oleh masyarakat Barat, dibawa oleh ilmuwan yang lari dari Konstantinopel ke Italia setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki.
® Timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis (zaman Abad Pertengahan) menjadi optimistis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi sosial masyarakat agraris yang feodalistik. Maka kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas. Termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama sehingga menemukan dirinya sendiri dan menjadi fokus pada kemajuan diri sendiri. Antroposentrisme menjadi pandangan hidup dengan humanisme menjadi pegangan sehari-hari. Selain itu adanya dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat Renaissance sehingga menyebar ke seluruh Italia dan Eropa.
3.3 Karakteristik
v CIRI-CIRI ABAD PERTENGAHAN
1. Feodalisme
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, feodalisme adalah system sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, system social yang menagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja, sistemsosial di Eropa pada abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar ditangan tuan tanah.
Dalam id.wikipedia.org, feodalisme adalah sebuah system pemerintahan dimana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vasal. Para vassal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vassal pada giliran ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti.
Sejak itu muncul orang-orang kuat sebagai tuan tanah yang mengatur pemakaian tanah diwilayah kekuasaannya. Tempat tingga mereka yang disebut kastil atau puri. Kekuasaan mereka ditopang oleh bawahannya. System ini kemudian berkembang luas. Bangsawan menjadi kelompok yang sangat istimewa dan melakukan regenerasi berdasarkan keturunan.
Sesuai dengan penelusuran ensiklopedia feudal atau feudal, merupakan satu istilah yang digunakan pada awal era modern yakni abad ke-17 merujuk pada pengalaman system politik diEropa abad pertengahan. System politik yang terbangun pada masa itu ditentukan oleh perpaduan antar para militer legal maupun tidak atau warlord, tuan tanah, bangsawan raja, yang lantas tersusun hirarki dalam masyarakat yang khas : ada raja, ada bangsawan, tetapi juga ada pelayan dan budak (vassal). Kata kuncinya tetap hirarki.
Menurut fokusnya, kekuasaan politik bersifa local dan personal yang menghasilkan sesuatu “dunia social dari klaim-klaim dan kekuasaan-kekuasaan tumpang tindih” (Anderson, hlm.,1974a, hlm. 149) beberapa diantara klaim-klaim dan kekuasaan ini mengalami konflik; dan tidak ada pemerintah atau Negara yang berdaulat dalam arti yang paling tinggi di atas wilayah dan penduduk yang ada (Bull, 1977, hlm.254). dalam system kekuasaan ini banyak dipenuhi ketegangan, dang sering terjadi perang.
Didunia abad pertngahan, ekonomi didominasi oleh pertanian, dan kelebihan apa pun yang dihasilkan menjadi sasaran klaim-klaim yang bersaing. Klaim yang berhasil menjadi dasar untuk menciptakan dan mempertahankan kekuasaan politik. Tetapi jaringan kerajaan-kerajaan, para pangeran, istri-istri para bangsawan dan pusat-pusat kekuasaan lainnya yang bergantung pada susunan ini diperumit oleh munculnya kekuasaan-kekuasaan alternative di kota-kota kecil dan kota-kota besar. Kota-kota dan federasi kota bergantung pada perdagangan dan manufaktur serta akumulasi modal yang relative tinggi. Mereka mengembangkan struktur-struktur social dan politik yang berbeda dan sering menikmati system-sistem pemerintahan independent yang ditentukan oleh para warganegara.
2. Skolastik
Upaya skolastik abad pertengahan Dalam gambaran historis singkat ini, metode untuk menghubungkan iman dan rasio yang pertama dibahas adalah filsafat Thomistik Gereja Roma Katolikl. Selain persetujuan (assent) pribadi orang percaya, dalam sistem ini iman artinya informasi yang diwahyukan yang ada dalam Alkitab, tradisi, dan suara hidup dari gereja Roma. Akal budi artinya informasi yang dapat diperoleh melalui pengamatan inderawi terhadap alam dan dinterprestasi intelek. Rasionalis abad ke-17 membedakan akal budi (reason) dengan sensasi (inderawi), Thomas membedakan akal budi (reason) dan wahyu. kebenaran akal budi adalah kebenaran yang dapat diperoleh melalui kemampuan indera dan intelek alamiah manusia tanpa bantuan anugrah supranatural.
Kerajaan Roma hidup dari abad ke-18 sampai awal abad ke-19. pada puncaknya, ia mencerminkan suatu usaha, dibawah perlindungan gereja Katolik, untuk menyatukan dan mensentralisir pusat-pusat kekuasaan dunia kristen barat yang terpisah-pisah menjadi suatu kerajaan menjadi suatu kerajaan kristen yang disatukan secara khusus kekuasaan sekular yang aktual dari kerajaan dibatasi oleh struktur-struktur kekuasaan yang kompleks dari eropa feodal disatu pihak dan gereja katolik dipihak lain.
Sepanjang abad pertengahan gereja secara konsisten berusaha menempatkan otoritas spiritual diatas otoritas sekuler dan berusaha mengubah sumber otoritas dan kebijaksanaan yang diakui dari wakil-wakil duniawi ini kepada wakil-wakil duniawi lainnya. Pandangan duniawi (world view) kristen menstransformasikan pertimbangan-pertimbangan tindakan politk dari suatu kerangka duniawi kepada kerangka teologis “ia menegaskan bahwa kebaikan terletak pada ketundukannya terhadap kehendak Tuhan”.
v Ciri Ciri Renaisans
Ciri utama renaisens adalah individualisme, humanisme, lepas dari agama. Manusia sudah mengandalkan akal (rasio) dan pengalaman (empiris) dalam merumuskan pengetahuan. Yang berkembang pada waktu itu sains, dan penemuan-penemuan dari hasil pengembangan sains yang kemudian berimplikasi pada semakin ditinggalkannya agama karena semangat humanisme. Fenomena tersebut cukup tampak pada abad modern.
Kebudayaan Yunani-Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Filsafat Yunani, misalnya menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus memahami lingkungan alamnya dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup.
· INDIVIDUALISME DAN HUMANISME
Secara umum, individualisme dapat diartikan sebagai satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri.
Tidak mudah menentukan batas yang jelas mengenai akhir zaman pertengahan dan awal yang pasti dari zaman modern. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan para ahli sejarah tentang peralihan zaman pertengahan ke zaman modern. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa zaman pertengahan berakhir ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Usmani pada tahun 1453 M. Peristiwa tersebut dianggap sebagai akhir zaman pertengahan dan titik awal zaman modern.
Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi, demikian pula filsafat tidak berkembang, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Dalam perenungan mencari alternatif itulah orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju, pemikiran tidak dikungkung, sehingga sains berkembang, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali.
Pada abad pertengahan orang telah mempelajari karya-karya para filosof Yunani dan Latin, namun apa yang telah dilakukan oleh orang pada masa itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh kaum humanis. Para humanis bermaksud meningkatkan perkembangan yang harmonis dari kecakapan serta berbagai keahlian dan sifat-sifat alamiah manusia dengan mengupayakan adanya kepustakaan yang baik dan mengikuti kultur klasik Yunani.
Para humanis pada umumnya berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah pada diri manusia adalah modal yang cukup untuk meraih pengetahuan dan menciptakan peradaban manusia. Tanpa wahyu, manusia dapat menghasilkan karya budaya yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa humanisme telah memberi sumbangannya kepada renaisans untuk menjadikan kebudayaan bersifat alamiah.
Zaman renaisans banyak memberikan perhatian pada aspek realitas. Perhatian yang sebenarnya difokuskan pada hal-hal yang bersifat kongkret dalam lingkup alam semesta, manusia, kehidupan masyarakat dan sejarah. Pada masa itu pula terdapat upaya manusia untuk memberi tempat kepada akal yang mandiri. Hal ini dibuktikan dengan perang terbuka terhadap kepercayaan terhadap orang-orang yang enggan menggunakan akalnya. Asumsi yang digunakan adalah, semakin besar kekuasaan akal, maka akan lahir dunia baru yang dihuni oleh manusia-manusia yang dapat merasakan kepuasan atas dasar kepemimpinan akal yang sehat.
Zaman ini juga sering disebut sebagai Zaman Humanisme. Maksud ungkapan tersebut adalah manusia diangkat dari Abad pertengahan. Pada abad tersebut manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Karena semangat humanisme tersebut , akhirnya agama Kristen semakin ditinggalkan, sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat terpisah dari agama dan nilai-nilai spiritual.
Menurut Mahmud Hamdi Zaqzuq, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kelahiran Renaisans, yaitu:
® Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. Gerakan tersebut lahir sebagai hasil dari penerjemahan ilmu-ilmu Islam ke dalam bahasa latin selama dua abad, yaitu abad ke-13 dan 14. Bahkan sebelumnya telah terjadi penerjemahan kitab-kitab Arab di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal itu dilakukan setelah Barat sadar bahwa Arab memiliki kunci-kunci khazanah turas klasik Yunani.
® Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Usmani, terjadi migrasi para pendeta dan sarjana ke Italia dan negara-negara Eropa lainnya. Para sarjana tersebut menjadi pionir-pionir bagi pengembangan ilmu di Eropa. Mereka secara bahu-membahu menghidupkan turas klasik Yunani di Florensia, dengan membawa teks-teks dan manuskrip-manuskrip yang belum dikenal sebelumnya.
® Pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan beragam ilmu.
Selain itu, ada beberapa faktor yang dikemukakan Slamet Santoso seperti yang dikutip Rizal Mustansyir, yaitu :
® Hubungan antara kerajaan Islam di Semenanjung Iberia dengan Prancis membuat para pendeta mendapat kesempatan belajar di Spanyol kemudian mereka kembali ke Prancis untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh di lembaga-lembaga pendidikan di Prancis.
® Perang Salib (1100-1300 M) yang terulang enam kali, tidak hanya menjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadikan para tentara atau serdadu Eropa yang berasal dari berbagai negara itu menyadari kemajuan negara-negara Islam, sehingga mereka menyebarkan pengalaman mereka itu sekembalinya di negara-negara masing-masing.
3.4 Agama
Zaman di ini kekuasaan gereja sangat besar bahkan melebihi kekuasaan raja atau pemimpin Negara pada saat itu, pada essensinya sejak masa dulu gereja memang tidak pernah ditempatkan dalam sebuah struktur sosial, dikarenakan karena gereja yaitu bentuk manifestasi dari agama Kristen protestan atau katolik yang menurut mereka tidak bisa dimasukkan pada struktur sosial dalam masyarakat karena fokusnya yaitu dalam ranah hubungan manusia dengan tuhan, tetapi apakah dengan tidak masuk ke dalam struktur sosial mereka ini posisi mereka menjadi tidak penting? justru posisi gereja pada hakekatnya berada tepat dibawah kekuasaan kerajaan karena kebanyakan para pastur merupakan penasehat kerajaan.Tetapi yang terjadi pada zaman ini justru sebaliknya, gereja memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan segala apapun, siapapun, dan kapanpun itu, dengan menggunakan kekuatan tuhan sebagai pelaksana kekuasaan mereka, apapun yang dikeluarkan gereja pada saat itu tidak boleh dilanggar oleh satu orang pun karena itu adalah perintah dari tuhannya, begitu pula dengan filsafat dan pengetahuan, apa yang dikatakan oleh pihak gereja merupaka suatu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh ditentang, posisi pastur pada saat itu tertinggi dalam struktur vertikal lapisan masyarakat.
Pada akhirnya semua warga tunduk sampai pada suatu kasus dimana ada yang menentang kebijakan gereja ini, yaitu penentuan bahwa Bumi yang mengitari matahari atau Matahari yang mengitari bumi, pada saat itu dari pihak gereja mengeluarkan ajaran bahwa Matahari mengitari bumi dengan Surga dan neraka yang berada diatas dan dibawahnya, karena yang menjadi acuan mereka yaitu hanya dengan melihat perputaran matahari dari pagi yang muncul di timur dan tenggelam di barat pada sore harinya.
Tetapi pendapat ini ditentang oleh seorang pemikir besar yang bernama Galileo, menurutnya Bumilah yang mengitari Matahari, toh pada essensinya itu merupakan suatu kebenaran tetapi pihak gereja tidak dapat menerima itu, dia dihukum dibakar hidup-hidup karena telah menentang gereja, hal inilah yang menyebabkan kemandegan dari para pemikir barat pada saat itu karena kekuasaan gereja yang begitu besar, dan bukan lain hal ini disebabkan semata-mata ketika suatu golongan memiliki hak yang istimewa yang tidak di dapatkan orang lain pada umumnya maka dia bisa bertindak apapun yang diingnkannya.
3.5 Wabah Penyakit
Sampar Hitam—Wabah dari Eropa Abad Pertengahan
Kala itu tahun 1347. Wabah ini telah mengamuk di Timur Jauh. Kini ia menyebar ke pinggiran Eropa bagian timur.
Orang Mongol sedang mengepung Genoa yang berbenteng, pusat perdagangan Kaffa, yang sekarang disebut Feodosiya, di Semenanjung Krim. Setelah terjangkit penyakit misterius yang membunuh sebagian besar dari mereka, orang Mongol menghentikan penyerangan. Tetapi sebelum mundur, mereka melancarkan tembakan maut. Dengan katapel raksasa, mereka melontarkan mayat-mayat korban wabah yang masih hangat melewati tembok kota. Sewaktu belakangan beberapa pasukan Genoa naik kapal dayung untuk melarikan diri dari kota yang telah dilanda wabah, mereka menyebarkan penyakit itu ke setiap pelabuhan yang mereka kunjungi.
Dalam sebulan, kematian melanda seluruh Eropa. Dengan cepat penyakit itu menyebar ke Afrika Utara, Italia, Spanyol, Inggris, Prancis, Austria, Hongaria, Swiss, Jerman, Skandinavia, dan kawasan Baltik. Dua tahun kemudian, lebih dari seperempat populasi Eropa, sekitar 25 juta jiwa, telah menjadi korban dari apa yang disebut ”malapetaka demografis paling brutal yang pernah dikenal umat manusia”—Sampar Hitam.
· Membubuh Dasar untuk Malapetaka
Tragedi Sampar Hitam tidak hanya mencakup penyakit itu sendiri. Sejumlah faktor turut memperparah malapetaka ini, salah satunya adalah semangat keagamaan. Sebuah contoh adalah doktrin api penyucian. ”Pada akhir abad ke-13, kepercayaan akan api penyucian tersebar di mana-mana,” kata sejarawan Prancis, Jacques le Goff. Pada awal abad ke-14, Dante menghasilkan karyanya yang berpengaruh, The Divine Comedy, dengan uraiannya yang terperinci tentang neraka dan api penyucian. Berkembanglah iklim keagamaan yang membuat masyarakat cenderung menghadapi wabah dengan sikap apatis dan pasrah, memandang hal itu sebagai hukuman dari Allah sendiri. Sebagaimana akan kita lihat, cara berpikir yang pesimis demikian malah menyulut penyebaran penyakit tersebut. ”Keadaan itu benar-benar ideal bagi penyebaran wabah tersebut,” kata buku The Black Death, oleh Philip Ziegler.
Selain itu, terdapat problem gagal panen yang berulang-ulang di Eropa. Akibatnya, populasi yang sedang bertumbuh pesat di benua tersebut mengalami malnutrisi—tidak kuat melawan penyakit.
· Wabah Itu Menyebar
Menurut Guy de Chauliac, dokter pribadi Paus Clement VI, ada dua wabah yang menyerang Eropa: pneumonia dan bubo. Ia melukiskan gangguan kesehatan ini secara terperinci sebagai berikut, ”Yang pertama berlangsung selama dua bulan, penderitanya terus-menerus demam dan muntah darah, lalu mati dalam waktu tiga hari. Yang kedua berlangsung setelah itu, penderitanya juga terus-menerus demam tetapi disertai abses (bisul bernanah) dan karbunkel (bisul batu) pada bagian luar tubuh, khususnya di ketiak dan pangkal paha. Penderitanya akan mati dalam lima hari.” Para dokter tidak berdaya untuk menghentikan penyebaran wabah itu.
Banyak orang melarikan diri karena panik—meninggalkan ribuan orang yang terinfeksi. Sebenarnya, para bangsawan kaya dan para profesional termasuk yang pertama-tama melarikan diri. Meskipun ada pemimpin agama yang ikut melarikan diri, banyak komunitas keagamaan menyembunyikan diri dalam biara-biara mereka, berharap dapat terhindar dari kontaminasi.
Di tengah-tengah kepanikan ini, paus menyatakan tahun 1350 sebagai Tahun Suci. Para musafir yang mengadakan perjalanan ke Roma dijamin langsung masuk firdaus tanpa melewati api penyucian! Ratusan ribu musafir mengindahkan seruan itu—menyebarkan wabah tersebut seraya mereka mengadakan perjalanan.
· Upaya yang Sia-Sia
Upaya-upaya untuk mengendalikan Sampar Hitam terbukti sia-sia karena tidak seorang pun tahu persis bagaimana penyakit itu ditularkan. Kebanyakan orang menyadari bahwa kontak langsung dengan penderita—atau bahkan dengan pakaiannya—sangat berbahaya. Beberapa orang bahkan takut bertatapan langsung dengan penderitanya! Akan tetapi, penduduk Florence, Italia, menuding kucing dan anjing sebagai penyebabnya. Mereka membantai binatang-binatang ini, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut malah membuka jalan bagi makhluk yang justru berkaitan dalam menyebarkan kontaminasi—tikus.
Seraya angka kematian meningkat, ada yang berpaling kepada Allah memohon pertolongan. Pria dan wanita memberikan semua milik mereka kepada gereja, sambil berharap agar Allah melindungi mereka dari penyakit itu—atau setidaknya mengaruniai mereka kehidupan surgawi jika mereka mati. Hal ini sangat memperkaya gereja. Jimat keberuntungan, patung Kristus, serta kotak-kotak kecil berisi ayat (phylactery) menjadi populer sebagai penangkal. Ada juga yang berpaling kepada takhayul, ilmu gaib, dan obat palsu untuk memperoleh kesembuhan. Minyak wangi, cuka, dan ramuan khusus konon dapat menangkal penyakit itu. Mengeluarkan darah adalah cara pengobatan favorit lainnya. Kalangan medis yang terpelajar dari University of Paris bahkan menghubungkan wabah tersebut dengan kesejajaran posisi planet-planet! Akan tetapi, penjelasan dan ”pengobatan” palsu tidak sanggup menghentikan penyebaran wabah pembunuh ini.
· Dampak yang Belum Sirna
Setelah lima tahun, Sampar Hitam tampaknya hampir berakhir. Tetapi sebelum akhir abad itu, wabah tersebut kambuh paling tidak sebanyak empat kali. Dampak Sampar Hitam sebanding dengan dampak Perang Dunia I. ”Hampir semua sejarawan modern sependapat bahwa pemunculan wabah endemis itu telah menimbulkan dampak yang teramat dalam terhadap ekonomi dan masyarakat setelah tahun 1348,” komentar buku The Black Death in England terbitan tahun 1996.
Wabah tersebut memusnahkan sebagian besar populasi, dan dibutuhkan waktu berabad-abad untuk memulihkan kondisi beberapa daerah. Dengan berkurangnya angkatan kerja, tentu saja upah kerja meningkat. Para tuan tanah yang kaya jatuh miskin, dan feodalisme—yang mencirikan Abad Pertengahan—terpuruk.
Demikian, wabah itu menjadi pemicu perubahan politik, agama, dan sosial. Sebelum wabah itu, Prancis menjadi buah bibir di antara kaum terpelajar di Inggris. Akan tetapi, meninggalnya sejumlah besar guru Prancis turut menjadikan bahasa Inggris lebih menonjol daripada bahasa Prancis di Inggris. Perubahan juga terjadi dalam lingkungan agama. Sebagaimana dikomentari oleh sejarawan Prancis, Jacqueline Brossollet, akibat kurangnya calon imam, ”Gereja sering kali merekrut orang-orang yang kurang berpengetahuan dan apatis”. Brossollet menyatakan bahwa ”kebobrokan [gereja] sebagai pusat dalam pengajaran dan iman merupakan salah satu penyebab terjadinya Reformasi”.
Yang pasti, Sampar Hitam berdampak kuat terhadap kesenian, menjadikan kematian sebagai tema artistik yang umum. Kategori tarian kematian yang terkenal, biasanya menggambarkan tengkorak dan mayat, menjadi simbol populer untuk kuasa maut. Karena bimbang akan masa depan, banyak orang yang selamat dari wabah tersebut meninggalkan semua batasan moral. Tatanan moral pun ambruk hingga kondisi yang luar biasa bejat. Sehubungan dengan gereja, karena kegagalannya mencegah Sampar Hitam, ”orang-orang abad pertengahan merasa telah dikecewakan oleh Gerejanya”. (The Black Death) Beberapa sejarawan juga mengatakan bahwa perubahan sosial akibat Sampar Hitam memupuk individualisme dan bisnis serta meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi—cikal bakal kapitalisme.
Sampar Hitam juga mendorong pemerintah-pemerintah untuk mendirikan sistem pengendalian sanitasi. Setelah wabah itu mereda, Venesia bertindak membersihkan jalan-jalan kota. Raja John II, yang dijuluki si Baik, dari Prancis juga memerintahkan agar jalan-jalan dibersihkan sebagai cara untuk menangkal ancaman epidemi. Raja tersebut mengambil langkah ini setelah mengetahui bahwa seorang dokter Yunani kuno menyelamatkan Athena dari sebuah wabah dengan membersihkan dan mencuci jalanan. Banyak jalanan pada abad pertengahan, yang menjadi selokan terbuka, akhirnya dibersihkan.
· Sudah Berlalu ?
Namun, baru pada tahun 1894, bakteriolog Prancis, Alexandre Yersin, mengidentifikasi basil yang bertanggung jawab atas Sampar Hitam. Basil tersebut dinamakan sesuai namanya, Yersinia pestis. Empat tahun kemudian, seorang Prancis lainnya, Paul-Louis Simond, menyingkapkan bahwa kutu (pada binatang pengerat) berperan memindahkan penyakit tersebut. Sebuah vaksin segera dikembangkan tetapi tidak terlalu sukses.
Apakah wabah itu sudah berlalu? Sama sekali tidak. Pada musim dingin tahun 1910, sebanyak 50.000 orang di Manchuria meninggal karena wabah tersebut. Dan, setiap tahun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendaftarkan ribuan kasus baru—dan jumlahnya terus meningkat. Jenis-jenis baru penyakit ini juga telah ditemukan—jenis yang kebal terhadap obat-obatan. Ya, jika standar-standar dasar higienis tidak dipertahankan, wabah itu senantiasa menjadi ancaman bagi umat manusia. Jadi, buku Pourquoi la peste? Le rat, la puce et le bubon (Mengapa Ada Wabah? Tikus, Kutu, dan Bubo), yang disunting oleh Jacqueline Brossollet dan Henri Mollaret, menyimpulkan bahwa ”wabah itu sama sekali bukan hanya penyakit di Eropa kuno pada Abad Pertengahan, . . . sungguh disesalkan, wabah itu mungkin adalah penyakit masa depan”.
3.6 Perkembangan Ilmu Filsafat & Seni
A. PERKEMBANGAN ILMU PADA ABAD PERTENGAHAN
Akal pada abad Pertengahan ini benar-benar kalah. Hal ini kelihatan dengan jelas pada filsafat Plotinus, Agustinus, Anselmus. Pada Aquinas penghargaan terhadap akal muncul kembali dan karena itu filsafatnya banyak mendapat kritik. Dan abad Pertengahan ini merupakan pembalasan terhadap dominasi akal yang hampir seratus persen pada zaman Yunani sebelumnya, terutama pada zaman Sofis.
Pemasungan akal dengan jelas terlihat pada pemikiran Plotinus. Ia mengatakan bahwa Tuhan (ia mewakili metafisika) bukan untuk dipahami, melainkan untuk dirasakan. Oleh karena itu, tujuan filsafat (dan tujuan hidup secara umum) adalah beratu dengan Tuhan. Jadi, dalam hidup ini, rasa itulah satu-satunya yang dituntut oleh kitab suci, pedoman hidup semua manusia.
Filsafat rasional dan sains tidak begitu penting; mempelajarinya merupakan usaha yang sia-sia, karena Simplicius, salah seorang pengikut Plotinus, telah menutup sama sekali ruang gerak rasional, iman telah menang mutlak. Karena iman harus mutlak, orang-orang yang masih hidup juga menghidupkan filsafat (akal) harus dimusuhi.Agustinus mengganti akal dengan iman; potensi manusia yang diakui pada zaman Yunani diganti dengan kuasa Allah. Ia mengatakan bahwa kita tidak perlu dipimpin oleh pendapat bahwa kebenaran itu relative. Kebenaran itu mutlak yaitu ajaran agama.
Ciri khas dari pada filsafat Abad Pertengahan terletak pada suatu rumusan yang terkenal yang dikemukakan oleh Saint Anselmus, yaitu credo ut intelligam. Rumusan itu berarti iman lebih dahulu, setelah itu mengerti. Imanlah lebih dahulu. Misalnya, bahwa dosa warisan itu ada, setelah itu susunlah argument untuk memahaminya, mungkin juga untuk meneguhkan keimanan itu. Sifat ini berlawanan dengan sifat filsafat raional. Dalam filsafat rasional, pengertian itulah yang didahulukan; setelah dimengerti, baru mungkin diterima dan kalau mau; diimani. Mengikuti jalan pikiran inilah maka saya berkesimpulan bahwa jantung filsafat Abad Pertengahan Kristen terletak pada ungkapan itu. Berdasarkan penalaran itu pula maka menurut hemat saya, tokoh utama peletak kekuatan filsafat Abad Pertengahan adalah St. Anselmus.
Abad Pertengahan melahirkan juga filosof yang terkemuka yaitu Thomas Aquinas. Dia adalah salah satu diantara orang-orang yang berusaha membuat filsafat Aristoteles sesuai dengan agama Kristen.Kita anggap ia menciptakan perpaduan hebat antara iman dan ilmu pengetahuan. Tekanan terhadap pemikiran rasional pada waktu ia hidup telah banyak berkurang. Oleh karena itu ia berhasil mengumumkan filsafar rasionalnya. Yang terkenal adalah beberapa pembuktian tentang adanya Tuhan yang masih dipelajari sampai sekarang.
Zaman ini ditandai dengan tampilnya pada teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuannya hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah ancilla theologia atau abdi agama.
· Definisi/karakteristik Pemikiran Masa Abad Pertengahan
Menurut Herman (2007-27), pada zaman ini dikenal aliran filsafat patristik dan skolastik berdasarkan Theos. Filsuf terkenal pada masa ini adalah Agustinus (354-43 SM) dan Thomas Aquinas (1225-1275) yang memunculkan ajaran Tomisme. Selain itu, dikenal juga filsuf-filsuf muslim pada zaman keemasan abad pertengahan, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusjd, dan Al-Ghazali yang menunjukkan hubungan mata rantai dengan sejarah filsafat Yunani (adanya semboyan mitos-logos-theos). Thomas Aquinas (1225-1227) merupakan murid dari Albertus Agung yang mengembangkan pemikiran Aristoteles. Filsafatnya adlah theologis yang memadukan pemikiran Agustinus dan Neo Platomisme dengan mempergunakan pemikiran Arilstoteles.
Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua zaman atau periode, yakni periode pratistik dan periode skolastik.
1. Patristik (100-700)
Patristik berasal dari kata Latin Patres yang berarti bapa-bapa gereja, adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama kristen.
Didunia barat agama katolik mulai tersebar dengan ajaranya tentang Tuhan, manusia dan etikanya. Untuk mempertahankan dan menyebarkanya maka mereka menggunakan filsafat yunani dan memperkembangkanya lebih lanjut, khususnya menganai soal soal tentang kebebasan manusia, kepribadian, kesusilaan, sifat tuhan. Yang terkenal Tertulianus (160-222), Origenes (185-254), Agustinus (354-430), yang sangat besar pengaruhnya. Zaman ini muncul pada abad ke-2 sampai abad ke-7, dicirikan dengan usaha keras para Bapa Gereja untuk mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen serta membelanya dari serangan kaum kafir dan bid’ah kaum Gnosis.
2. Skolastik 800-1500
Zaman Skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa Patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya.
Para tokoh zaman Skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah-kerajaan dan sekolah-katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung (742-814) dan kelak juga dari lingkungan universitas dan ordo-ordo biarawan. Dengan demikian, kata “skolastik” menunjuk kepada suatu periode di Abad Pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pengajar ulung bermunculan. Namun, dalam arti yang lebih khusus, kata “skolastik” menunjuk kepada suatu metode tertentu, yakni “metode skolastik”. Zaman Skolastik memiliki tiga periode, yaitu :
o Periode Skolstik awal (800-120)
Ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang erat antara agama dan filsafat. Ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada periode ini, diupayakan misalnya, pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan Kitab Suci (Anselmus dan Canterbury). Selanjutnya, logika Aristoteles diterapkan pada semua bidang pengkajian ilmu pengetahuan dan “metode skolastik” dengan pro dan kontra mulai berkembang (Petrus Abaelardus pada abad ke-11 atau ke-12).
o Periode puncak perkembangan skolastik (abad ke-13)
Periode puncak perkembangan skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan yahudi. Filsafat Aristoteles memberikan warna dominan pada alam pemikiran Abad Pertengahan. Aristoteles diakui sebagai Sang Filsuf, gaya pemikiran Yunani semakin diterima, keluasan cakrawala berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yahudi.
Tokoh/filosof Yang Hidup Pada Masa Abad Pertengahan :
1. PLOTINUS ( 204-270 )
Dalam berbagai hal Plotinus memang bersandar pada doktrin-doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas idea. Pada Plato idea itu umum, artinya setiap jenis objek hanya ada satu idenya. Pada Plotinus idea itu partikular, sama dengan dunia partikular. Perbedaan mereka yang pokok ialah pada titik tekan ajaran mereka masing-masing. Sistem metafisika Plotinus di tandai dengan konsep transendens. Menurut pendapatnya dalam pikiran terdapat tiga realitas : The One, The Mind, The Soul.
® The One ( Yang Esa ) adalah Tuhan dalam pandangan philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat di pahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, diluar segala nilai. Yang Esa itu adalah puncak semua yang ada. Ia itu cahaya di atas cahaya. Kita tidak mungkin mengetahui esensinya, kita hanya mengetahui bahwa ia itu pokok atau prinsip yang berada di belakang akal dan jiwa. Ia adalah pencipta semua yang ada. Mereka merasa memiliki pengetahuan keilahian juga tidak akan dapat merumuskan apa Ia itu sebenarnya.
® The Mind ( Nous ) adalah gambaran tentang Yang Esa dan di dalamnya mengandung ide-ide Plato. Ide-ide itu merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan Nouns adalah benar-benar kesatuan. Untuk menghayatinya kita harus melaui perenungan.
® The Soul (psykhe) merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam, soul itu mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam dua aspek, ia adalah energi di belakang dunia, dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai dua aspek, yang pertama intelek yang tunduk pada reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional.
Tentang ilmu Plotinus menganggap sains lebih rendah dari metafisika, metafisika lebih rendah dari pada keimanan. Surga lebih berarti dari pada bumi, sebab syurga itu tempat peristirahatan jiwa yang mulia. Bintang-bintang adalah tempat tinggal dewa-dewa. Ia juga mengakui adanya hantu-hantu yang bertempat diantara bumi dan bintang-bintang. Semua ini memperlihatkan rendahnya mutu sains Plotinus. Plotinus dapat dikatakan sebagai musuh naturalisme. Ia membedakan dengan tegas tubuh dan jiwa, jiwa bagi Plotinus tidak dapat diterjemahkan ke dalam ukuran-ukuran badaniah, fakta alam harus dipahami sesuai dengan spiritualnya. Tujuan filsafat Plotinus ialah terciptanya kebersatuan dengan Tuhan.
Caranya ialah pertama-tama dengan mengenal alam melalui alat indra, dengan ini kita mengenal keagungan Tuhan, kemudian kita menuju jiwa dunia, setelah itu menuju jiwa ilahi. Jadi perenuangan itu dimulai dari perenungan tentang alam menuju jiwa ilahi, objeknya dari yang jamak kemudian kepada Yang Satu. Dalam perenungan terakhir itu terjadi keintiman, tidak terpisah lagi antara yang merenung dengan yang direnungkan.
2. AUGUSTINUS ( 354 – 430 )
Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada dua pool, Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini di ambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Ia yakin benar bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran, karena itu ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu diatas segala jenis (catagories).
Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna dan tidak dapat diubah. Tuhan itu kuno tetapi selalu baru, Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi.
3. BOETHIUS
Boethius memiliki pemikiran yang hampir serupa dengan Augustinus. Sesudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran. Menurunnya kebudayaan latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma kristen.
Asal istilah abad kegelapan adalah penggunaan untuk menunjukan periode pemikiran pada tahun 1000-an, yaitu antara masa jatuhnya imperium Romawi dan Renaissance abad ke-15. Seorang tokoh yang terkenal abad ini adalah St. Anselmus dialah yang mengeluarkan pernyataan credo ut intelligam yang dapat dianggap sebagai ciri utama abad pertengahan. Sekalipun pada umumnya filosof abad pertengahan berpendapat seperti itu (mengenai hubungan akal dan iman), Anselmulah yang diketahui mengeluarkan pernyataan itu.
4. ANSELMUS ( 1033-1109 )
Di dalam filsafat Anselmus kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pernyataannya, credo ut intelligam (believe in order to understand/percayalah agar mengerti). Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Iapun mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berfikir. Kesimpulannya akal hanyalah pembantu wahyu. Anselmus adalah salah seorang “terpelajar”, seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi ia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upayanya membuktikan doktrinnya. Namun selalu imanlah yang mendasari semua itu.
Dalam karyanya Proslogium, yang pada awalnya berjudul Iman Mencari Pengertian (Fides Quaerens Intellectum). Menurut Anselmus, apa yang kita sebut Allah memiliki suatu pengertian yang lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. Apabila kita berbicara tentang Allah, yang kita maksudkan ialah suatu pengertian yang lebih besar dari pada apa saja yang dapat kita pikirkan. Dengan begitu pengertian “Allah” yang ada di dalam rumusan pemikiran kita adalah lebih besar daripada apa saja yang ada di dalam pikiran. Apa yang di dalam pikiran ada sebagai yang tertinggi atau yang lebih besar, tentu juga berada di dalam kenyataan sebagai yang tertinggi dan yang terbesar.
5. THOMAS AQUINAS (1225-1274)
Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan. Aquinas mengatahui banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksestensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikan. Ia mengajukan lima dalil (argumen) untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal, seperti sebagai berikut ini :
· Argumen gerak
· Sebab yang mencukupi
· Kemungkinan dan keharusan
· Memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam
· Keteraturan alam
· Tentang jiwa
Di dalam filsafat gereja, Aquinas mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa pelantara gereja. Sakramen-sakramen gereja itu perlu, sakramen itu mempunyai dua tujuan yaitu : Pertama, menyempurnakan manusia dalam penyembahan kepada Tuhan. Kedua, menjaga manusia dari dosa. Aquinas juga mengatakan bahwa Baptis mengatur permulaan hidup, penyesalan (confirmation) untuk keperluan pertumbuhan manusia dan sakramen maha kudus (eucharist) untuk menguatkan jiwa.
Peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad VII Masehi, dan pada abad VIII Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi. Pada zaman keemasan kebdayaan Islam telah medirikan penerjemahan berbagai karya Yunani, serta menjadi pembuka jalan penggunaan pecahan decimal dan berbagai konsep hitung lainnya. Sekitar abad 600-700 M, kemajuan ilmu pengetahuan berada di peradaban dunia Islam. Sumbangan sarjana Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang :
· Menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskannya sehingga dapat dikenal dunia Barat seperti sekarang ini.
· Memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi dan ilmu tumbuh-tumbuhan.
· Menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar.
Perhubungan antara Timur dan Barat selama Perang Salib sangat penting untuk perkembangan kebudayaan Eropa karena pada waktu ekspansi bangsa Arab telah mengambil alih kebudayaan Byzantium, Persia dan Spanyol sehingga tingkat kebudayaan Islam jauh lebih tinggi daripada kebudayaan Eropa.
· ZAMAN KEEMASAN FILSAFAT
Zaman Keemasan filsafat lazimnya dikenal sebagai zaman renaisans (renaissance). Istilah renaisans berasal dari bahasa Perancis yang terdiri dari kata re yang berarti lagi atau kembali, dan kata neissance yang berarti kelahiran atau kebangkitan. Zaman renaisans adalah zaman kelahiran-kembali kebudayaan Yunani-Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran kristiani. Namun, orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif bagi kebudayaan Yunani-Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik.. Kebudayaan klasik ini juga dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia. Pada zaman ini telah dicapai titik puncak dalam bidang seni, pemikiran, dan sastra.
Pada masa ini banyak filsuf-filsuf islam yang terkenal diantaranya adalah :
A. Filsafat Islam Di Dunia Islam Timur
1. Al-Ghazali / 1050-1111 M (Tahafutut al-Falasifah)
Pokok pemikiran dari al-Ghozali adalah tentang Tahafutu al-falasifah (kerancuan berfilsafat) dimana al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan dengan kerancuan berfikir mereka. Tiga diantaranya, menutur al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang : Qadimnya Alam, Pengetahuan Tuhan, dan Kebangkitan jasmani.
2. Suhrawardi / 1158-1191 M (Isyraqiyah / Illuminatif)
Pokok pemikiran Suhrawardi adalah tentang teori emanasi, ia berpendapat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Nuur An-Nuur (Al-Haq) yaitu Tuhan itu sendiri. Yang kemudian memancar menjadi Nuur al-Awwal, kemudian memancar lagi mejadi Nuur kedua, dan seterusnya hingga yang paling bawah (Nur yang semakin tipis) memancar menjadi Alam (karena semakin gelap suatu benda maka ia semakin padat).
Pendapatnya yang kedua adalah bahwa sumber dari Ilmu dan atau kebenaran adalah Allah, alam dan Wahyu bisa dijadikan sebagai perantara (ilmu) oleh manusia untuk mengetahui keberadaan Allah. Sehingga keduanya, antara Alam dan Wahyu adalah sama-sama sebagai ilmu.
3. Ibnu Khaldun (1332 M-1406 M)
Khaldun membuat karya tentang pola sejarah dalam bukunya yang terkenal: Muqaddimah, yang dilengkapi dengan kitab Al-I’bar yang berisi hasil penelitian mengenai sejarah bangsa Berber di Afrika Utara. Dalam Muqaddimah itulah Ibnu Khaldun membahas tentang filsafat sejarah dan soal-soal prinsip mengenai timbul dan runtuhnya negara dan bangsa-bangsa.
Dalam mempertautkan sejarah dengan filsafat, Ibnu Khaldun tampaknya ingin mengatakan bahwa sejarah memberikan kekuatan intuisi dan inspirasi kepada filsafat, sedangkan filsafat menawarkan kekuatan logika kepada sejarah. Dengan begitu, seorang sejarawan akan mampu memperoleh hasil yang relatif valid dari proses penelitian sejarahnya, dengan dasar logika kritis.Dasar sejarah filsafatnya adalah :
1. Hukum sebab akibat yang menyatakan bawa semua peristiwa, termasuk peristiwa sejarah, berkaitan satu sama lain dalam suatu rangkaian hubungan sebab akibat.
2. Bahwa kebenaran bukti sejarah tidak hanya tergantung kepada kejujuran pembawa cerita saja akan tetapi juga kepada tabiat zaman. Karena hal ini para cendekiawan memberinya gelar dan titel berdasarkan tugas dan karyanya serta keaktifannya di bidang ilmiah.
Karena hal ini para cendekiawan memberinya gelar dan titel berdasarkan tugas dan karyanya serta keaktifannya di bidang ilmiah, yaitu :
· Sarjana dan filosof besar
· Ulama Islam
· Sosiolog
· Pedagang
· Ahli sejarah
· Ahli Hukum
· Politikus
· Sastrawan Arab
· Administrator dan organisator
4. Al-Kindi (806-873 M)
Menurut al-Kindi filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam, oleh karena itu para sejarawan Arab awal menyebutnya “filosof Arab”. Menurutnya batasan filsafat yang ia tuangkan dalam risalahnya tentang filsafat awal adalah “filsafat” adalah pengetahuan tentang hakekat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof dalam berteori ialah mencapai kebenaran dan dalam prakteknya ialah menyesuaikan dengan kebenaran. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : Relevansi agama dan filsafat, fisika dan metafisika (hakekat Tuhan bukti adanya Tuhan dan sifat-sifatNya), Roh (Jiwa), dan Kenabian.
5. Abu Bakar Ar-Razi (865-925 M)
Nama lengkapnya adalah abu bakar muhammad ibn zakaria ibn yahya al-razi. Di barat dikenal dengan Rhazes. Ia lahir di Ray dekat Teheran pada 1 Sya’ban 251 H (865 M. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : Akal dan agama (penolakan terhadap kenabian dan wahyu), prinsip lima yang abadi, dan hubungan jiwa dan materi.
6. Al-Farabi (870-950 M)
Sejarah mencatatnya sebagai pembangun agung sistem filsafat, dimana ia telah membaktikan diri untuk berfikir dan merenung, menjauh dari kegiatan politik, gangguan dan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis baik dalam pemikiran, pernyataan, argumentasi, diskosi, keterangan dan penalarannya. Unsur-unsur penting filsafatnya adalah :
· Logika
· Kesatuan filsafat
· Teori sepuluh kecerdasan
· Teori tentang akal
· Teori tentang kenabian
· Penafsiran atas al-Qur’an.
Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : kesatuan filsafat, metafisika (hakekat Tuhan), teori emanasi, teori edea, Utopia jiwa (akal), dan teori kenabian.
7. Ibnu Maskawih (932-1020 M)
Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya’qub Ibn Miskawih. Ia lahir di kota Ray (Iran) pada 320 H (932 M) dan wafat di Asfahan pada 9 safar 421 H (16 Februari 1030 M). Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : filsafat akhlaq, dan filsafat jiwa.
8. Ibnu Shina (980-1037 M)
Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Ibnu Sina bernama lengkap Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā ( Abu Ali Sina). Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia), dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia (Iran). Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah :
· fisika dan metafisika,
· filsafat emanasi,
· filsafat jiwa (akal), dan
· teori kenabian.
9. Ibnu Bajjah (1082-1138 M)
Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya Ibn Al-Sha’igh Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Samqusti Ibn Bajjah. Ibn bajjah dilahirkan di Saragossa, andalus pada tahun 475 H (1082 M). Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlaq, dan Tadbir al-mutawahhid (mengatur hidup secara sendiri).
10. Ibnu Tufail (1082-1138 M)
Nama lengkapnya adalah abu bakar Muhammad Ibn Abd Al-Malik Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Thufail Al-Kaisyi. Di barat dikenal dengan abu bacer. Ia dilahirkan di guadix, 40 mil timur laut Granada pada 506 H (1110 M) dan meninggal di kota Marraqesh, Marokko pada 581 H (1185 M). Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah : percikan filsafat, dan kisah hay bin yaqadhan.
11. Ibn Rusyd 520 H/1134 M (Teori Kebenaran Ganda)
Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi, Ibnu Rusyid, 1126 – Marrakesh, Maroko, 10 Desember 1198), adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Salah satu Pemikiran Ibn Rusyd adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari seranga al-Ghazali.Untuk itu ia menulis sanggahan berjudul Tahafut al-Tahafut. Dalam buku ini Ibn Rusyd menjelaskan bahwa sebenarnya al-Ghazalilah yang kacau dalam berfikirnya.
12. Nashirudin Thusi
Thusi, nama lengkapnya adalah Abu Ja’far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan Nashir Al-Din Al-Thuai Al-Muhaqqiq. Ia lahir pada 18 Februari 1201 M / 597 H di Thus, sebuah kota di Khurasan. Diantara filsafatnya adalah tentang metafisika, jiwa, moral, politik, dan kenabian.
13. Shuhrawardi al-Maqtul
Nama lengkapnya adalah Syeikh Shihab Al-Din Abu Al-Futuh Yahya Ibn Habasy Ibn Amirak Al-Suhrawardi, ia dilahirkan di suhraward, Iran barat laut, dekat zan-jan pada tahun 548 H atau 1153 M. Diantara filsafatnya adalah tentang metafisika dan cahaya, epistimologi, kosmologi, dan psikologi.
14. Mulla shadra
Nama lengkapnya Muhammad Ibn Ibrahim Yahya Qawami Siyrazi, sering disebut shadr al-din al-sirazi atau akhund mulla shadra. Dikalangan murid-muridnya dikenal dengan shadr al-mutti’allihin. Ia dilahrikan di syiraz pada tahun 979 H/980 H atau 1571 /1572 M dari sebuah keluarga terkenal lagi berpengaruh. Diantara filsafatnya adalah tentang metafisika, epistimologi, dan fisika.
15. Muhammad Iqbal
Dr.Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Wilayah Punjab (pakistan barat) pada tahun 1877. Iqbal berasal dari keluarga Brahma Kashmir, tetapi nenek moyang Muhammad Iqbal telah memeluk islam 200 tahun sebelum Ia dilahirkan. Ayah muhammad Iqbal, Nur Muhammad adalah penganut islam yang taat dan cenderung ke pada ilmu tasawuf. Diantara filsafatnya adalah tentang ego dan khudi, ketuhanan, materi dan kausalitas, moral, dan insan al-Kamil.
v Perkembangan Seni
Sejarah arsitektur gereja abad pertengahan dimulai pada tahun 313 M saat ketika agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang legal.
Setelah Terbebas dari penyiksaan, umat Kristen mulai membangun basilika. Basilika paling bagus dan besar adalah Gereja St. Sophia di Konstantinopel, yang memiliki gaya khas Byzantium. Gaya Byzantium tersebut dalam perkembangan selanjutnya berpengaruh ke daerah-daerah dunia Muslim. Arsitektur Masjid sangat dipengaruhi oleh gaya Byzantium itu. Salah satunya adalah masjid Umar di Yarusalem. Para arsitek di luar Konstantinopel juga mencoba memodifikasikan gaya Byzantium. Salah satu contoh adalah Gereja San Vitale, di Ravena, Italia Utara. Kapel ini semula dimaksudkan untuk mausoleum Karel Agung
· Periode Abad Gelap
Selama abad gelap, di Eropa Barat tidak ada gaya khas yang berkembang. Mundurnya peradaban Romawi berakibat pada melemahnya upaya pengembangan gaya arsitektur orisinal. Kaum barbar, baik Jerman, Slav, maupun Finno-Ugria, paling banter hanya bisa membuat imitasi gaya arsitektur Romawi Barat yang tengah merosot itu.
· Periode Romanesque
Istilah ini mengacu pada seni yang berkembang di Eropa barat dari sekitar tahun 1000 hingga 1200. Gereja-gereja yang dibangun dengan gaya baru di segala penjuru Eropa barat mengingatkan kembali pada basilika-basilika yang dibangun di Roma pada abad IV, V, dan VI. Itulah sebabnya maka gaya baru ini disebut Romansque. Salah satu gereja gaya Romanesque yang terkenal adalah katedral Pisa, yang selesai dibangun pada 1093. Contoh lain dari bangunan gaya Romanesque yang perlu dicatat adalah gereja biara Cluny. Gereja ini diresmikan pada 1131. Gereja Cluny merupakan gereja yanh sangat besar dan megah.
· Arsitektur Gothik
Istilah gothik mengacu pada seni –arsitektur, lukis, dan pahat – tiga abad terakhir zaman pertengahan. Istilah ini berasal dari para penulis akhir Abad Pertengahan yang lebih menaruh perhatian pada kebudayaan Yunani-Romawi daripada kebudayaan abad pertengahan sendiri. Arsitektur gothik adalah kreasi para genius abad pertengahan. Sebagai gaya dalam seni, gaya Gothik ini adalah lebih baik jika diperbandingkan dengan gaya-gaya lainnya. Pengaruh arsitektur Gothik lebih luas daripada gaya Romanesque.
Perbedaan utama antara gaya ini adalah bahwa gaya Gothik serba lancip, sedangkan Romanesque serba bundar. Arsitektur Gothik pertama-tama berkembang di Prancis tengah, terutama di daerah sekitar Paris. Abad XIII merupakan puncak perkembangan arsitektur Gothik . selama masa pemerintahan Raja Louis IX (1226-1270) bermunculanlah karya-karya besar seperti katedral-katedral di Reims, Amiens, Paris, Beauvais, dan yang terbagus adalah katedral Sainte Chapelle, yang berhadapan dengan Notre Dame di Paris. Meskipun arsitektur Gothik pada mulanya muncul di sekitar Paris, ini tidak berarti bahwa gaya ini semata-mata milik Prancis. Arsitektur ini tetap dianggap sebagai hasil dari semangat Kristianitas, karena kristen merupakan agama yang merambah seluruh kawasan Eropa barat.
· Dekorasi Gothik
Ide-ide Gothik bukan hanya tampak pada gaya arsitektur, tetapi juga pada dekorasi seni patung, lukis, hiasan, serta pada setiap bentuk seni kerajinan, termasuk kerajinan yang terbuat dari besi. Motif atau corak dekorasi yang mengandung pesan ajaran kristen. Telah lama gereja menampakkan imaji-imaji tentang Allah Bapa, Kristus, Perawan Maria, para tokoh suci serta malaikat. Penampakan imaji-imaji itu dimaksudkan untuk mendorong semangat keagamaan umat Kristen.
· Seni Pahat: Romanesque dan Gothik
Pahatan menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus serta para santo banyak dijumpai di gereja-gereja. Selama masa Romanesque penggambaran peristiwa-peristiwa tersebut kurang tampak hidup. Hasilnya, seni pahat Romanesque tidak tampak naturalistik. Lain halnya dengan para pemahat Gothik. Sebelum memahat, mereka pahat secara cermat dan naturalistik. Mereka amati kedetilan lekuk-lekuk anatominya. Barulah mereka mulai memahat. Satu hal yang khas dalam seni pahat Gothik adalah penampilannya yang kaku.
· Seni Lukis
Tembok yang rata biasnya dihiasi dengan fresco – gambar yang dilukis dengan air kapur berwarna yang dipakai pada gips yang basah, sesuai dengan sketsa karbon yang telah dirancang. Bentuk lukisan terbaik sebelum tahun 1300 adalah karya para miniaturis. Para miniaturis Irlandia terkenal sebagai ilustator yang piawai, yang membuat hiasan-hiasan yang begitu indah dan kompleks pada buku-buku para biarawan. Karya-karya mereka mencapai puncak perkembangannya selama periode Gothik.
· Seni Lukis Italia
Karena gaya Gothik merupakan produk Eropa utara, pengaruhnya tidak begitu kuat di Italia. Para seniman Italia cenderung tetap mempertahankan metode-metode dan konsepsi-konsepsi lama, yang disebut Greek (Yunani) atau Byzantine (Byzantium). Sama seperti para penganut naturalisme Gothik, para seniman Italia pada mulanya juga lebih senang menciptakan lukisan-lukisan tentang alam, seperti binatang, tumbuhan, bunga, dan sebagainya. Oleh karena itu ketika mereka harus membuat lukisan tentang manusia, hasilnya tampak kaku, dan tidak riil. Dengan kata lain, mereka bersikap tradisional.
Para seniman Italia yang pertama-tama menunjukkan perubahan sikap terhadap komposisi warna, anatomo, pencahayaan, bayangan, dan animasi adalah Cimabue (1302) dan muridnya, Giotto (1336) mereka adalah seniman Florence (Firenze). Karya terbesar Giotto dapat kita lihat di Arena Chapel katedral Padua dan Bardi Chapel Gereja Santa Croce di Florence. Para pelukis sesudah Giotto cenderung sebagai epigon-epigonnya. Mereka hanya bisa mengikuti model-model yang telah dirintis Giotto, tetapi tak mampu menandinginya.
· Seni Pahat Italia
Seni pahat, seperti halnya seni lukis, mengalami serangkaian perubahanyang sangat berarti dalam abad XIV. Sebelum tahun 1300, pahatan-pahatan yang menggambarkan manusi tampak kaku. Karya-karya itu sebagian besar adalah hasil kerja para seniman penganut model Yunani. Ayah dan anaknya yang bernama Niccola dan Giovanni Pisano menghasilkan pahatan-pahatan pada mimbar besar di katedral-katedral di Pisa, Siena, dan Pistoia. Karya-karya ini sudah menunjukkan semangat Gothik. Giotto, selaim pelukis, adalah juga pemahat. Pengaruhnya dalam dunia seni pahat tidak kalah besarnya dengan pengaruhnya dalam dunia seni rupa. Ketenaranya antara lain karena karya-karya pahatannya pada panel-panel rendah, yang ia rancang untuk menghiasi menara lonceng Gereja Santa Maria dan Katedral Florence.
Panel-panel karya Giotto tersebut tampak sederhana. Tetapi justru karena itu, karya-karya tersebut mengundang banyak perhatian. Dan sejak saat itulah para pemahat meninggalkan metode penggambaran yang serba semarak.
· Seni Lukis Flanders
Di Eropa Utara, perintis inovasi dalam dynia seni Lukis adalah para seniman Flanders.Hubert dan Jan van Eyck bersaudara menunjukkan inovasi itu pada karya-karya miniatur mereka yang menjadi ilustrasi pada buku-buku agama. Inovasi lainnya yang dipelopori Van Eyck bersaudara ini adalah penggunaan cat minyak dalam melukis. Kapan tepatnya perintisan inovasi ini dimulai sebenarnya masih kabur. Setelah Van Eyck bersaudara, pelukis lainnya yang perlu dicatat adlah Rogier van der Weyden (1464). Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggambarkan insiden-insiden dramatis, dan mampu membangkitkan emosi yang pedih. Seniman lukis Flanders lainnya lagi yang perlu dicatat adalah Hans Memling (1494. Ia berasal dari Bruges. Ciri khas dari karyanya adlah sentuhan yang halus dan sentimentil.
· Seni Pahat Flanders
Seni pahat Flanders, seperti halnya seni lukisnya, mencapai puncak perkembangannya pada awal abad XV. Ciri khas yang menonjol yang dapat kita amati dalam karya-karya besar yang ada adalah mencuatnya gagasan-gagasan naturalisme, idealisme religius, dan corak penderitaan yang pedih. Seniman pahat Flanders yang terkemuka adalah Claus Sluter, yang berkerja pada istana Duke Philipe di Burgundia. Sluter ditugasi untuk mendekorasi biara Carthuisan di Champmol, dekat Dijon, yang dipersembahkan sebagai mausoleum para pangeran Burgandia.
· Seni Musik Abad Pertengahan
Seperti halnya dengan seni lukis, pahat, dan arsitektur, seni musik abad pertengahan diabadikan untuk gereja. Lagu-lagu dan tari-tarian rakyat sudah barang tentu tetap ada. Namun, karena sebagian besar bukti karya-karya populer itu sudah lenyap, maka kita tidak dapat merekontruksikannya dengan baik. Bahkan musik Yunani dam Romawi telah dilupakan orang. Kreasi seni seorang seniman musik cenderung dilupakan begitu sang seniman tiada. Apalagi seni musik kuno, entah Yahudi, dan Romawi, yidak tertulis, sehingga cepat hilang. Demikian jugalah seni musik populer atau seni musik rakyat abad pertengahan. Meskipun begitu kita tidak boleh berasumsi bahwa abad pertengahan tidak mengenal musik rakyat semacam itu, hanya kaarenaa bukti-bukti historis yang kita dapatkan semata-mata berkaitan dengan musik gereja. Liturgi atau kebangkitan gereja banyak menggunakan musik. Pada mulanya para pemimpin gereja tidak suka menggunakan musik dalam kebangkitan keagamaan. Alasan utamanya adalah karena musik telah menjadi bagian dalam ritus-ritus kaum kafir, pertunjukan-pertunjukan gladiator, maupun hiburan-hiburan tak bermorak dalam masyarakat kafir.
Namun, meski betapa kerasnya sikap para pemimpin gereja, secara perlahan-lahan musik menyelinap masuk ke dalam gereja. Inovasi dalam seni musik banyak bermunculan saat puncak abad pertengahan tiba. Guido d’Arezzo (1050) melengkapi sistem notasi yang telah dikembangkan pada masa itu. Ia menggunakan lima garis paralel yang di atasnya terdapat not-not balok untuk menandai pola titinada. Organ adalah alat musik yang paling penting dalam abad pertengahan. Alat musik ini telah diketemukan jauh sebelumnya. Selain alat musik tiup, alat musik bersenar juga digunakan. Oarang Yunani kuno telah mengenal alat musik bersenar yang disebut cithara. Alat ini dimainkan dengan jari.
Begitu banyak aspek kehidupan akhir abad pertengahan yang menjadi sumber inspirasinya para seniman Gothik. Dan begitu eratnya kaitan antara kreasi-kreasi kesenimanan mereka dengan apa yang menjadi puncak-puncak peradaban Abad pertengahan, sehingga periode ini kemudian lazim disebut Zaman Gothik.
Contoh Karya Terkenal:
Mona Lisa (1497 )
Lukisan tersebut merupakan lukisan yang sangat terkenal hingga kini. Lukisan ini mengandung banyak sekali misteri yang hingga saat ini belum terungkap jelas siapa orang yang dilukis oleh Leonardo, apa motivasinya dan apa sebenarnya tujuan ia melukisnya. Lukisan ini terlihat simple atau biasa saja, tetapi jika lebih diperhatikan lagi, akan terlihat jelas apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari lukisan ini. Ada banyak sekali. Terlebih jika kita memperhatikan tatapan mata dan senyumannya dan latar belakang lukisannya. Tatapan mata dengan paduan senyuman yang terlihat sangat misterius. Butuh waktu bertahun-tahun ia menyelesaikan lukisan ini dan beberapa kali ia memperbaiki sisi lukisan terlebih sisi senyuman objeknya.
Lukisan Mona Lisa menyimpan banyak sekali misteri dan banyak juga ilmuwan yang mengidentifikasikan lukisan ini sebagai lukisan yang menyimpan kode-kode yang dibuat oleh Leonardo. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa ada inisial yang berbeda di kedua mata lukisan Mona Lisa. Ada juga yang bilang latar belakang lukisan tersebut membentuk objek yang berbeda dari apa yang seharusnya. Terkait objek yang dilukis, Mona Lisa diyakini sebagai istri dari saudagar pada masanya yang bernama Lisa Gherardini. Mona diartikan sebagai ‘nyonya’ dengan demikian Mona Lisa berarti Nyonya Lisa. Ada juga yang justru berpendapat bahwa objek dari lukisan tersebut adalah potret diri Leonardo da Vinci sendiri yang dilukis dengan variasi berbeda yang tentu saja menyimpan rahasia tersendiri dari pelukisnya.
The Last Supper (1495)
Lukisan ini dikenal sebagai Perjamuan Terakhir Yesus dengan murid-Nya sebelum ia wafat oleh penyaliban.
Di dalam novel karya Dan Brown dan film yang berjudul The Da Vinci Code, lukisan ini menyimpan makna misterius dan membentuk kode bahwa ada hubungan romantika Yesus dengan salah seorang murid-Nya, Maria Magdalena. Lukisan ini menggambarkan bagaimana perjamuan Yesus di malam terakhir-Nya berkumpul bersama dengan murid-muridNya sebelum ia ditangkap untuk melewati proses penyaliban dan wafat di kayu salib seperti yang dikisahkan Injil. Dalam film dan novel The Da Vinci Code, lukisan ini digambarkan sebagai kode yang dibuat oleh Leonardo untuk menggambarkan bagaimana romantika yang terjadi antara Yesus dengan Maria Magdalena yang bertentangan dengan iman Kristen. Biar bagaimana pun kontroversinya, lukisan ini tetap merupakan maha karya besar dari sosok jenius Leonardo da Vinci yang akan dikenang sepanjang zaman.
Kisah hidup Leonardo da Vinci memang tidak lepas dari fakta-fakta yang memperjelas kejeniusannya sebagai seniman dan ilmuwan. Karya-karya besarnya akan terus diingat, demikian juga pemikirannya yang ia wariskan kepada ilmuwan setelahnya. Sudah terlahir seseorang yang jenius dalam karya maupun pemikirannya dan sebagai contoh orang yang menikmati apa yang ia pelajari tanpa batasan bidan apapun, yang penting dia senang dan menikmati apa yang ia pelajari. Orang itu adalah Leonardo da Vinci, terlahir 500 tahun yang lalu. Leonardo pun meninggal di umurnya yang menginjak 67 tahun di kota Indre-et-Loire, Prancis dan dimakamkan diKapel St.
“St. George Tabernacle” (sekitar 1415–1417) — Museo Nazionale del Bargello, Firenze (Donatello)
3.7 Penjelajahan
Ramainya perdagangan di Laut Tengah, terganggu selama dan setelah berlangsungnya Perang Salib (1096 – 1291). Dengan jatuhnya kota Konstantinopel (Byzantium) pada tahun 1453 ke tangan Turki Usmani, aktivitas perdagangan antara orang Eropa dan Asia terputus. Sultan Mahmud II, penguasa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasannya. Bangsa Barat menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu bangsa Barat berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra,
Ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudra:
Semangat reconguesta, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di mana pun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib.
- Semangat gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani.
Semangat glory, yaitu semangat memperoleh kejayaan atau daerah jajahan.
- Semangat gold, yaitu semangat untuk mencari kekayaan/emas.
- Perkembangan teknologi kemaritiman yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk menyeberangi Samudra Atlantik.
- Adanya sarana pendukung seperti kompas, teropong, mesiu, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan.
- Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo (1271-1292).
- Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat seperti bola, matahari merupakan pusat dari seluruh benda-benda antariksa. Bumi dan bendabenda antariksa lainnya beredar mengelilingi matahari (teori Heliosentris).
v Penjelajahan Samudera Oleh Bangsa Eropa
Negara-negara yang memelopori penjelajahan samudra adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan lainnya. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah Perjanjian Tordesillas. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis demarkasi/khayal yang membentang dari kutub Utara ke kutub Selatan. Daerah sebelah Timur garis khayal adalah jalur/kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah Barat garis khayal adalah jalur Spanyol.
Garis Khayal Tordesillas yang dibuat berdasarkan perjanjian tordesilas
v Pelayaran Orang-orang Portugis
Orang-orang Portugis menjadi pelopor berlayar mencari tempat asal rempah-rempah. Hal ini tidak lepas dari kiat Pangeran Henry Mualim (Henry Navigator) yang memberi hak-hak istimewa kepada keluarga-keluarga saudagar sukses dari Italia, Spanyol, dan Prancis. Tujuannya supaya mereka bersedia tinggal dan berdagang di ibukota Portugis.
Berikut ini penjelajah-penjelajah yang berasal dari Portugis.
1) Bartholomeu Dias
Bartholomeu Dias berangkat dari Lisabon (Portugis) pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung Selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh Dias dan rombongannya, ujung Selatan Benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal Joao II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) karena untuk menghilangkan kesan menakutkan dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia.
2) Vasco da Gama
Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat.
Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk mualim Moor, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Calcuta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Calcuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara- negara Eropa lainnya.
Rute pelayaran pertama Vasco da Gama
3) Alfonso d’ Albuquerque
Setelah beberapa lama menduduki Calcuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu ekspedisi ke Timur dilanjutkan kembali.
Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Calcuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso d’ Albuquerque. Ekspedisi d’ Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511.
v Pelayaran Orang-orang Spanyol
Berikut ini para penjelajah Spanyol yang melakukan pelayaran ke dunia Timur:
1) Christopher Columbus
Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan tiga buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia Timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah.
Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 – 1504, berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi penemu Benua Amerika adalah Christopher Columbus. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortez dan Pizzaro. Cortez menduduki Mexico pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian yaitu Kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Pizzaro, pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan Indian di Peru yaitu suku Inca.
2) Ferdinand Magelhaens (Magellan)
Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magelhaens berlayar ke Barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian del Cano (Sebastian del Cano) dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelhaens-del Cano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhaens di Kepulauan Massava. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol, Philips II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan, Magelhaens gugur (27 April 1521). Akibat peristiwa itu rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian del Cano, menuju Kepulauan Maluku. Magelhaens dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi itu dililitkan pita bertuliskan ‘Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku’.
v Pelayaran orang-orang Inggris
1) Sir Francis Drake
Pada tahun 1577 Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah Barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis.
2) Pilgrim Fathers
Pada tahun 1607 rombongan yang menamakan diri Pilgrim Fathers melakukan pelayaran ke arah Barat. Kapal yang bernama May Flower berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Utara.
3) Sir James Lancester dan George Raymond
Pada pelayaran tahun 1591, Lancester berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang, sampai di Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancester dan maskapai perdagangan Inggris (EIC) berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, dia mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang.
4) Sir Henry Middleton
Pada tahun 1604 pelayaran kedua EIC yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Terjadi persaingan dengan VOC. Selama tahun 1611 – 1617, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana (Kalimantan Barat Daya), Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi.
5) William Dampier
Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah Utara.
6) James Cook
Pada tahun 1770 Cook berhasil mendarat di pantai Timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu Benua Australia.
v Pelayaran Orang-orang Belanda
Biasanya para pedagang Belanda membeli dagangan rempah-rempah dari Portugis di pusat pasar Lisabon. Namun setelah Lisabon dikuasai Spanyol, Belanda mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah. Walaupun Portugis berusaha merahasiakan jalan ke pusat penghasil rempah-rempah, tetapi Belanda berhasil menyusul Portugis dan Spanyol.
Berikut ini beberapa pelaut Belanda yang melakukan penjelajahan ke dunia :
1) Barentz
Pada tahun 1594, Barentz mencari daerah Timur (Asia) melalui jalur lain yaitu ke Utara. Perjalanan Barentz terhambat karena air laut membeku sesampainya di Kutub Utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya, kemudian memutuskan untuk kembali tetapi meninggal dalam perjalanan.
2) Cornelis de Houtman
Pada tahun 1595, de Houtman dengan empat buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam, memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah Timur mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Pada tahun 1596 Cornelis de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di Banten.
3) Abel Tasman
Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah Tenggara Australia. Pada tahun 1642 ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania.
3.8 Hukum
v Inti Ajaran Kristen di Dunia Barat
Doktrin St. Agustiinus bahwa “ Kebenaran hanya ada dalam Gereja, di luar Gereja tidak ada kebenaran”. Artinya ajaran yang bersumber pada rasio adalah tidak benar, kebenaran bersumber pada keyakinan atau iman.iman adalah sumber segala-galanya”.
Oleh karena itu zaman inilah disebut “ the dark ages “ atau masa kekelaman. Disebut dark ages atau masa kekelaman sebab upaya manusia yang telah dirintis dan dikembangkan sejak masa Socrates untuk mencapai kesejahteraan hidup melalui kekuatan akal, justru di masa abad pertengahan ini di hentikan dan sepenuhnya dengan cara mengembangkan ( interpretasi ) terhadap injil ( Evalingelis= Sabda atau Kabar Gembira ). Kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumaber pada akal dihentikan, dan kembali ke mitos dan irrasionalitas. Kata Agustinus “ Kepercayaan adalah jalan pengetahuan “.Teori Agustinus ini menjadi sumber hukum “ Canonika”= Hukum Gereja Katholik yang berada di tangan Kaum Klerus/Pejabat Gereja.
Hukum Kanonik ini adalah hukum anggota-anggota Persekutuan kaum Kristiani, lebih khusus lagi Gereja Katholik Roma ( Emeritus John Gilissen, 2004, hal. 281). Sama halnya dengan tatanan-tatanan keagamaan lainnya adalah kehendak Tuhan, sebagaimana hal ini diwahyukan-Nya kepada manusia, sebagai sumber penting dalam hukum Kanonik. Wahyu tersebut ditemukan dalam Kitab Suci, yang merupakan sumber satu-satunya dari ius divinum ( Hukum Ketuhanan ). Hukum ini di tambah serta dilengkapi dan disesuaikan dengan dekrit-dekrit konsili-konsili dan dekretal-dekretal para Paus maupun oleh kebiasaan. Hukum Romawi juga dipandang sebagai sumber pelengkap hukum kanonik.( ibid, hal.291 )
1. Hukum Itu Tatanan Hidup Penuh Damai ( Agustinus, 354-430 )
Agustinus melihat tatanan hukum sebagai sesuatu yang didominasi oleh tujuan perdamaian. Bahkan res republica dipahami Agustinus sebagai komunitas rasional yang ditentukan dengan nilai-nilai deligere ( yakni di hargai dan dicintai). Sebuah konsep yang berseberangan regnum yang menunjuk pada kerajaa Romawi sebagai segerombolan perampok karena tidak memiliki keadilan. Ditonjolkan pula istilah delicto proximi atau cinta kepada sesama. Semua unsur keadilan itulah yang mesti menjadi dasar hukum.
Tanpa itu maka aturan dalam bentuk apapun tidak layak disebut hukum /lex esse von vedatur, quae justa non fuerit.( Satjipto Rahardjo, 2010, hal.54-55).
Agustinus mengadopsi Zwei Zwarden Theory ( Teori Dua Pedang ) dari Paus Gelasius , yakni Pedang Kerohanian dan Pedang Keduniawian. Pemilahan tersebut ternyata membawa dampak dalam pembentukan hukum yaitu, hukum yang mengatur soal keduniawian ( kenegaraan ) dan hukum yang mengatur soal keagamaan ( kerohanian ). Demikian pula terdapat dua macam kodifikasi hukum yaitu kodifikasi yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifiaksi tersebut dinamakan Corpus Iuris. Kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius, yaitu kodifikasi yang dikeluarkan oleh Gereja. Kodifikasi ini disebut Corpus Iuris Cannonici. Corpus Iuris terdiri atas empat bagian yaitu :
Instituten, ajaran yang mempunyai kekuasaan mengikat seperti undang-undang. Maksudnya, jika ada hal-hal yang kurang jelas pengaturannya, maka dapat di cari dalam instituten.
· Pandecten, penafsiran suatu peraturan oleh para sarjana.
· Codex, yaitu peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh Raja.
· Novollen, yaitu tambahan dari suatu peraturan atas undang-undang.
Sebagai tokoh agama, Agustinus menempatkan hukum Ilahi ( Lex Aeterna) sebagai citra hukum positif. Hukum Ilahi yang abadi menempatkan batas pada semua hukum positif yang tidak boleh dilampaui. Jika hukum positif ( Lex Temporalis ) melanggar aturan Ilahi itu, maka ia telah kehilangan kualitas hukumnya. ( ibid.)
Sumbangan Agustinus pada pengembangan Eksplanasi dibidang hukum antara lain :
· Lewat konsep pengenalan akan Tuhan, sebagai prasyarat keadilan, Agustinus secara implisit, memberi sinyal betapa penting peran sikap etis iman terhadap berseminya keadilan dalam hukum. sikap iman yang tulus menjadi pra-kondisi bagi lahirnya kedamaian dan keadilan.
· Inspirasi teori Agustinus kita dapat melakukan kajian secara empiris tentang banyak hal misalnya, kaitan antara ketaatan hukum dengan penghayatan iman seseorang/ atau suatu komunitas, korelasi,antara religiusitas aparat hukum dengan kepekaan mereka soal keadilan, kaitan antara angka kejahatan dengan afiliasi religious.
· Konsep Agustinus tentang deligere dan delicto proximi yang dapat berfungsi mengkondisikan lahirnya kedamaian dan keadilan, seolah mengingatkan kita tentang pentingnya modal social ( social capital ) dalam kehidupan hukum. disini berkesempatan melakukan kajian tentang interelasi antara suasana penyelenggaraan hukum dengan kondisi modal social yang dimiliki sebuah komunitas. ( ibid, hal.57).
2. Hukum Itu Bagian Tatanan Ilahi ( Thomas Aquinas, 1225-1274 )
Thomas Aqunas merupakan imam Gereja abad pertengahan. Tidak jauh beda dengan Agustinus, Aquinas pun mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama Kristen. Hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Karena jaman ini merupakan era dominasi agama ( yang di awali oleh agama Kristen),maka kehidupan moral dimaksud menujuk pada ukuran agama tersebut. Misalnya mengejar kenbaikan dan menjauhi kejahatan. Hal kebaikan dimaksud antara lain menunjang hak alamiah manusia untuk mempertahankan hidup, cinta dan hidup berkeluarga, kerinduan mengenal Tuhan dan hidup bersahabat. ( ibid, hal.58 )
Imperatif-imperatif moral tersebut berpengaruh pula terhadap hukum. Tata hukum harus di bangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan. Karena itu, sebagaimana tercerminkan dalam doktrin Thomas Aquinas, konfigurasi tata hukum di mulai dari ;
a) Lex Aeterna; Hukum dan kehendak Tuhan
b) Lex Natulais; Prinsip umum ( hukum alam )
c) Lex Divina; Hukum Tuhan yang terdapat dalam Kitab Suci
d) Lex Humane; Hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam.
Jika hukum ( Lex Humane ) menjadi tidak benar karena :
1) Mengabaikan kebaikan masyarakat
2) Mengabdi pada nafsu dan kesombongan pembuatnya
3) Berasal dari keuasaan yang sewenang-wenang
4) Diskriminatif terhadap rakyat, maka hukum itu tidak sah karena bertentangan dengan moral hukum alam dan Tuhan. ( ibid ).
Dalam hukum alam ( Lex Naturalis ) itu terdapat dua prinsip antara lain :
· Prinsipa prima, yang merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak, serta kekal ( berlaku bagi segala bangsa dan masa ).
· Prinsipa secundaria, yang merupakan norma-norma kehiduoan yang fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya, meskipun prinsipa secundaria ini pada dasarnya dapt dikatakan merupakan aktualisasi dari prinsipa prima. ( Ridwan Halim, 2005, hal.185 ).
Hukum pada dasarnya merupakan cerminan tatanan Ilahi. Legislasi hanya memiliki fungsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan tatanan Ilahi itu. Tuga hakim adalah menegakkan keadiloan melalui fungsinya, menerapka hukum dalam kaitan dengan pemberlakuan undang-undang. Pemikiran Aquinas ini hanya bisa di pahami dalam konteks kosmologi dan ontology skolastik. Kosmologi di maksud adalah mengijinkan penalaran rasional selama batas-batas yang ditetapkan oleh wahyu Ilahi tidak di alnggar. Penerapan hukum positif pada kasus riil, harus dibaca sebagai implementasi hukum Ilahi.
Dalam konteks itulah Aquinas membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu, dengan hukum yang di jangkau oleh akal manusia. Hukum yang berasal dari wahyu disebut Ius Divinum Positivum ( hukum Ilahi positif ). Sedangkan hukum yang ditemui lewat kegiatan akal, terdiri dari beberapa jenis, yakni Ius Naturale ( hukum alam ),Ius Gentium ( hukum bangsa-bangsa ), Ius Positivum Humanum ( hukum positif buatan manusia ). ( Satjipto Rahardjo, op.cit, hal, 59 ).
Dalam system Aquinas akal berada diatas kehendak. Bagi Aquinas akal itu mencerahkan, sedangkan kehendak cenderung naluriah. Itulah sebabnya hukum yang berinitikan Iustum ( keadilan ), mutlak merupakan produk akal. Tentang keadilan Aquinas membedakan tiga kategori
· Iustitia Distributiva, ( keadilan distributif ), yang menunjuk kepada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan tidak sama pula. Ini disebut kesederajatan geometris
· Iustitia Comutativa, ( keadilan komutatif atau tukar-menukar ), menunjuk pada keadilan berdasarkan prinsip Aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang sesuai dengan hukum.
· Iustitia Legalis, ( keadilan hukum ), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum.
Bagi Aquinas menaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dalam segala hal ( dan di asumsikan hukum itu berisi kepentingan umum ), maka keadilan hukum di sebut juga sebagai keadilan umum ( Iustitia Generalis ),
Beberapa poin penting teori Aquinas tentang hukum antara lain :
· Hukum dan peundang-undangan harus rasional dan masuk akal, karena ia merupakan aturan dan ukuran tindakan manusia.
· Hukum ditujukan bagi kebaikan umum. Karena hukum merupakan aturan bagi perilaku, dan karena tujuan dari segala perilaku itu adalah kebahagiaan, maka hukum mesti di tujukan bagi kebaikan bersama.
· Karena hukum ditujukan bagi kesejahteraan umum, maka ia hanya dapat di buat oleh nalar dari semua orang lewat badan legislasi.
· Hukum perlu dipublikasikan karena ia mengandung aturan yang memandu hidup manusia, maka aturan itu mesti mereka ketahui agar memiliki nilai kewajiban.
Melalui teorinya tentang keadilan hukum, Aquinas menyisipkan pesan luhur tentang betapa pentingnya mutu dari isi suatu aturan hukum. Aquinas menempatkan keadilan hukum sebagai keadilan umum, justru karena hukum di andaikan berakar pada hukum alam ( yang tidak lain mencerminkan keluhuran Ilahi ).Dan lagi pula hukum itu diasumsikan mengatur kepentingan umum. ( ibid, hal.62 ).Thomas aquinas dengan bukunya yang terkenal antara lain Tsumma Theologiae ( Teologi yang utama ) dan De Regime Principium Ad Regem Cipri ( Tentang Hukum Tata Negara dan Pemerintahan ). Thomas Aquinas adalah pelopor Skolastik, yaitu penganut hukum alam yang melibatkan ajaran Aristoteles kedalam ajaran gereja Katholik, sehingga sering disebut Aristotelisme Kristen. ( Dominikus Rato, op.cit. hal.264 ).
v INTI AJARAN ISLAM DI TIMUR
Pemikir Islam mendasarkan teori hukumnya pada agama Islam, yaitu pada wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi.Dari ahli pikir Islam AI-Syafii-Iah aturan-aturan hukum diolah secara sistematis. Sumber hukum Islam adalah AI-Quran. kemudian Hadis yang merupakan ajaran-ajaran dalam hidup Nabi Muhammad SAW . Peraturan-peraturan yang disetujui oleh umat juga menjadi hukum, hukum mufakat, yang disebut juga ijmak. Sumber hukum yang lainnya adalah qiyas, yaitu analogi atau persamaan. Hukum Islam ini meliputi segala bidang kehidupan manusia. Hukum Islam hidup dalam jiwa orang-orang Islam, dan berdasarkan pada agama. Hukum Islam merupakan hidup ideal bagi penganutnya. Oleh karena Hukum Islam berdasarkan pada Al Quran maka Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan Allah, langsung sebagai wahyu. Aturan hukum harus dibuat berdasarkan wahyu (Muhammad Khalid Masud, 1996: 12-13).
Bab IV. Penutup
A. Kesimpulan
Sejarah Medieval Eropa, atau yang kita kenal sebagai Abad pertengahan Eropa, dikenal sebagai era klasik dimulai dengan munculnya negara-kota Yunani Kuno, Abad Pertengahan Eropa juga merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan memengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan.
Abad Pertengahan adalah periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah prakarsa raja Charlemagne pada abad 5 hingga munculnya monarkhi-monarkhi nasional, dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta Reformasi Protestan dengan dimulainya renaisans pada tahun 1517. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan.
Eropa dilanda Zaman Kelam (Dark Ages) sebelum tiba Zaman Pembaharuan (Renaisans). Masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelek dan ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Amerika, tempo zaman ini selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roma dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi.Gelap juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud tindakan dan cengkraman kuat pihak berkuasa agama.Yaitu Gereja Kristen yang sangat berpengaruh.
Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang layak untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains asa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka ditolak.Siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera masalah , malah ada yang sampai dibunuh.Pikiran ini, terimplementasi melalui teori yang dikeluarkan oleh Thomas Aquinas, seorang ahli falfasah yakni negara wajib tunduk kepada kehendak gereja. St Augustine, sebelumnya juga berpendirian demikian. Manakala Dante Alighieri, berpendapat kedua-dua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri, dan mestilah bekerjasama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch).
Dalam paradigma abad pertengahan, dua wilayah agama dan dunia terpisah total satu dengan yang lain sehingga tidak ada peluang bagi ekspansi satu terhadap yang lain atau pembauran antar keduanya. Seorang manusia kalau tidak melangit haruslah membumi,atau kalau tidak meyakini kekuasaan alam gaib terhadap segala urusan hidupnya.Maka dia harus memutuskan hubungan secara total dengan Tuhan dan roh-roh kudus, dan jika dia menghargai jasmani dan urusan materinya maka dia bukan lagi seorang rohaniwan dan berarti telah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kata Augustine,siapapun yang mahir dalam kesenian, perang, dan filsafat adalah orang yang bejat dan sesat, karena dia berasal dari kota setan dimana kebahagiaannya tak lebih dari sekadar topeng yang menipu, dan keindahannya hanya merupakan wajah alam kubur.
Kota inilah yang tidak diterima oleh Tuhan dan fitrah manusia. Karena orang yang sombong dan angkuh adalah merupakan kepekatan hari dan orang yang memiliki pengetahuan tentang segala yang harus diketahui oleh orang-orang terpuji. Dan ketika melihat kota setan ini tenggelam ke dalam kesesatan dan kesombongannya, maka semua sudut kegelapannya akan terlihat.Konsep diatas, dipertegas oleh Fritjof Capra, yakni Para ilmuwan pada Abat Pertengahan, yang mencari-cari tujuan dasar yang mendasari berbagai fenomena, menganggap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Tuhan, roh manusia, dan etika, sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki signifikansi tinggi, jadi ilmu didasarkan atas penalaran keimanan.
Dengan demikian, kerangka berpikir yang dominan pada abad pertengahan dan tekanan kuat para elit gereja yang menganggap dirinya pengawas tatanan yang menguasai dunia dan telah menginterogasi ideologi para ilmuan dan menyeret mereka ke pengadilan serta menganggap kegiatan ilmiah sebagai campur tangan setan.
Kemudian faktor-faktor lain yang berada di luar pembahasan ini telah menjadi latar belakang munculnya Renaisans yang telah melahirkan teriakan protes terhadap kondisi yang dominan pada abad pertengahan.Abad Pertengahan berakhir pada abad ke-15 dan kemudian disusul dengan zaman Renaissance. Zaman Renaissance berlangsung pada akhir abad ke-15 dan 16. Kesenian, sastra musik berkembang dengan pesat. Ada suatu kegairahan baru, suatu pencerahan. Ilmu pengetahuan mulai dikembangkan oleh Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dll.
Kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal seperti alirn baru Eropah hingga abad ke 18 seperti Humanisme, rsionalisme, nasionalisme dan absolutisme berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini secara langsung melemhkan kekuasaan golongan feudal.Itali telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di Eropah pada abad ke 15. Hal ini terjadi apabila Kota constntinople dikuasai oleh Islam telah jatuh ke tangan orang Barat pada tahun 1453. Keadaan ini telah menyebabkan ramai para ilmuan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Itali. Ini menyebabkan Itali menjadi pusat intelektual terkenal di Eropah pada masa itu.
Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dn kekuasaan golongan feudal yang sentiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropah.Melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo de Vinci yang terkenal sebagi pelukis, pemuzik dan ahli falsafah serta jurutera. Michelangelo merupakan tokoh seni, arkitek, jurutera, penyair dan ahli anotomi.Melahirkan ahli-ahli sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo.Melahirkan ahli matematik seperti Tartaglia dan Cardan yang berusaha menghuraikan persamaan ganda tiga. Tartaglia orang pertama yang menggunakan konsep matematik dalam ketenteraan iaitu mengukur tembakan peluru mariam. Cardan terlibat dalam penghasilan ilmu algebra.Selain itu, Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubatan di Eropah. Antara tokoh perubatan terkenal iaitu William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah.Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat inquiri sehingga membawa kepada aktiviti penjelajahan dan penerokaan.
Ø Dampak Positif :
· Adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalnya ilmu sosial : ilmu bumi, ilmu sejarah dll. Begitu juga dengan ilmu eksak seperti ilmu alam.
· Kebangunan kembali dari peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani-Romawi.
· Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa.
· Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu.
· Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain tokoh perubahan terkenal itu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitis penjelajahan dan kemajuan
· Mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudera.
Ø Dampak negatif :
· Eropa pada priode ini bener-bener mendapat ancaman dari orang-orang arab. Pada khalifah Umamyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang konstantinopel walaupun pada akhirnya pengepungan yang di lakukan Arab gagal total.
· Munculnya suatu isu yang di sebut Kontroversi Ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan,Kristus, dan sang perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak.kontroversi ini mengundang persoalan lama yaitu tentang kebebasan agama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik.
· Pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan (liar). Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma sehingga manusia mengalami krisis aklak seperti mabuk-mabukan dll. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis tetapi juga dikalangan pendeta.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Atang dan Ahmad Saebani, Beni. 2008. Filsafat Umum. Bandung: Pustaka Setia.
Achmadi, Asmoro. Filsafat Umum. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Ahmad Tafsir, op. cit., h. 110-111,112-113,129-131,137-138,173
Anees, Bambang Q- dan Radea Juli A. Hambali. Filsafat Untuk Umum. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Asmoro Achmadi, Filsafat Umum (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 109,110.
Bambang Q-Anees dan Radea Juli A. Hambali, selanjutnya disebut Bambang, Filsafat Untuk Umum (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 334-335
Drs. Atang Abdul Hakim, M.A. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., Filsafat Umum, 2008, Hal. 339,341
Drs. Surajiyo, Filsafat Umum dan Perkembangannya di Indonesia, 2010, Hal. 86.
F. Budi Hardiman, Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche), 2011, Hal. 7,8,10
Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Cet. IX; Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Hardiman, Budi. 2011 Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche). Jakarta : Erlangga.
Harold H. Titus et al., Living Issues in philosophy, diterjemahkan H.M. Rasjidi, Persoalan-Persoalan Filsafat (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), h. 192,258.
Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Cet. IX; Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 11., lihat Jerome R. Ravertz, The Philosophy of Science, diterjemahkan Saut Pasaribu, Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.14-15,29,31-32,36
Ibid., h. 191.
Juhaya S. Praja, op. cit., h.26-27, 96,98-99,109-110.
Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam perspektif (Cet. XVI; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 100-101.
Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education A. D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education, diterjemahkan Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Kontribusi Islam atas dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis abad kemasan Islam (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 271.,276.
Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir. Filsafat Ilmu. Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Nakosteen, Mehdi. History of Islamic Origins of Western Education A. D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education. Diterjemahkan oleh Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah dengan judul Kontribusi Islam atas dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis abad kemasan Islam. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Ravertz, Jerome R. The Philosophy of Science. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu dengan judul Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, selanjutnya disebut Rizal, Filsafat Ilmu (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 58-59.,70,73-74,134.
Surajiyo. 2010. Filsafat Umum dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Suriasumantri, Jujun S. Ilmu dalam perspektif. Cet. XVI; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
Tafsir, Ahmad –Filsafat Umum (Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capr), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
Titus, Harold H., et al. Living Issues in philosophy. Diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi dengan judul Persoalan-Persoalan Filsafat. Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984.
Zaqzuq, op.cit., h. 17-18.