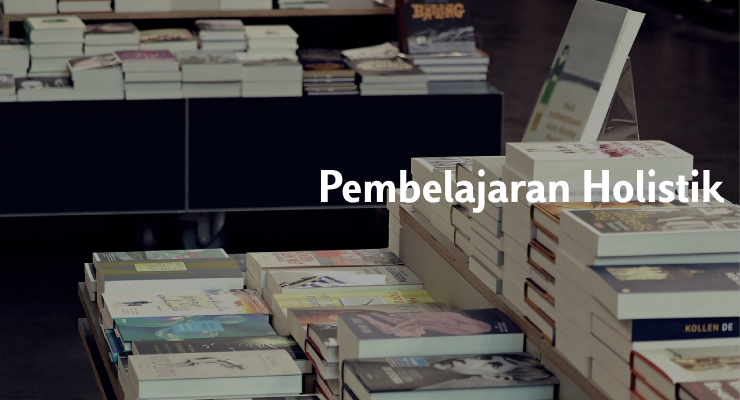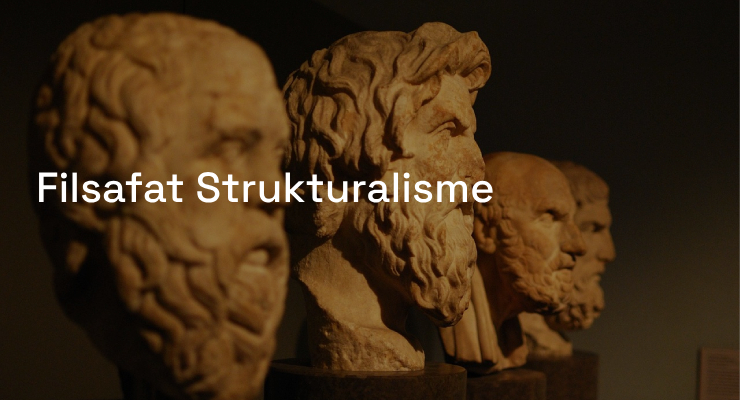Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya dan alam semesta, dan penciptanya. Menurut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang ditetapkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada tahun 1993 dan 1998: Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.Terdapat ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama.
Jika hal ini diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia.Seharusnya, dalam suatu Negara perlu adanya persatuan, sehingga tidak menimbulkan konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya akan terpenuhi. Dengan demikian Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut akan dibahas di sub selanjutnya.
Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara yang biasa disingkat wasantara berasal dari kata wawas (atau dari kata induk mawas)yang mempunyai arti pandang, melihat. Dengan memberikan akhiran -an maka akan mempunyai tambahan arti cara. Wawasan berarti suatu cara pandang/lihat. Kata pandang tidak selamanya dihubungkan dengan panca indera penglihatan tapi dapat diperluas menjadi respon, menyikapi, langkah. Jadi,wawasan adalah suatu cara menyikapi dengan dasar yang tertentu sebagai acuan. Sedangkan nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara.Nusa merupakan isitilah jawa kuno yang mempunyai arti pulau.Antara mengandung makna ada sesuatu yang diapit.Nusantara berarti pulau yang mengapit. Jika diperluas dapat diartikan sebagai kepulauan yang saling terikat satu sama lain. Jadi wawasan nusantara secara arti kata adalah cara pandang suatu bangsa berkepulauan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya dengan kondisi beraneka ragam.
Secara terminologi, menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Adapun landasan wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifiskasinya sebagai berikut:
1. Landasan Idil
Pancasila sebagai faslafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan idiil darpada wawasan nusantara.Karena pada hakikatnya wawasan nusantara merupakan perwujudan dari pancasila.Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung paham keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan.Maka wawasan nusantara mengarah kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
2. Landasan Konstitusional
UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
3. Landasan Visional.
Landasan visional atau tujuan nasional wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :
– Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
– Memajukan kesejahteraan umum
– Mencerdaskan kehidupan bangsa
– Ikut melaksanakan ketertiban dunia
4. Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat mengatasinya, bangsa indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
5. Landasan Operasional
GBHN adalah sebagi landasan wawasan operasional dalam wawasan nusantara, yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973.
Asas Wawasan Nusantara terdiri dari :
1. Kepentingan yang sama
2. Keadilan Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil.
3. Kejujuran Yang berarti keberanian berfikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan relita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau kebenaran itu pahit.
4. SolidaritasYang berarti rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban demi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerja sama Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuann dan kesatuandalam bhinekaan.Merupakan tonggak utama dalam terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.Jika hal ini ambruk maka rusaklah persatuan dan kesatuan kebhinekaan Indonesia.
Wawasan Nusantara meliputi arah pandang kedalam dan keluar
1. Arah pandang ke dalam: Mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor – faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan . Arah pandang kedalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional,baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
2. Arah pandang keluar: Mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera pada pembukaan UUD 1945. Arah pandang kedalam bertujuan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kepada kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerja sama dan sikap saling menghormati. Sumber : Buku Cetak Pengengantar Pendidikan Kewarganegaraan pernerbit PT GramediaPustaka Utama
Kedudukan, Fungsi, dan Wawasan Nusantara
Kedudukan
Kedudukan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :
a. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
b. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
c. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan Visional.
d. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
e. GBHN sebgai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar Nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
Fungsi
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu – rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tujuan
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan – kepentingan individu, kelompok, suku bangsa atau daerah.Kepntingan – kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional . Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir , bersikap , dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara yang dibuat di LEMHANAS 1999: Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sebaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila danUUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila.Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
Hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.
Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan politik , ekonomi , sosial budaya , dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan .
Dengan demikian , Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara , sehingga menggambarkan sikap dan perilaku , paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia .Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
1. Kehidupan Politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hokum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatic ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar danpulau kosong.
2. Kehidupan ekonomi
Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas,hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, danperindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah.Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilanekonomi.Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
3. Kehidupan social
Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segibudaya,status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan
pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
4. Kehidupan pertahanan dan keamanan
Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangunsolidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Kesimpulan
Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.Diperlukan kesadaran sebagai implementasi WNI untuk mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar hal-hal yang diinginkan dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.