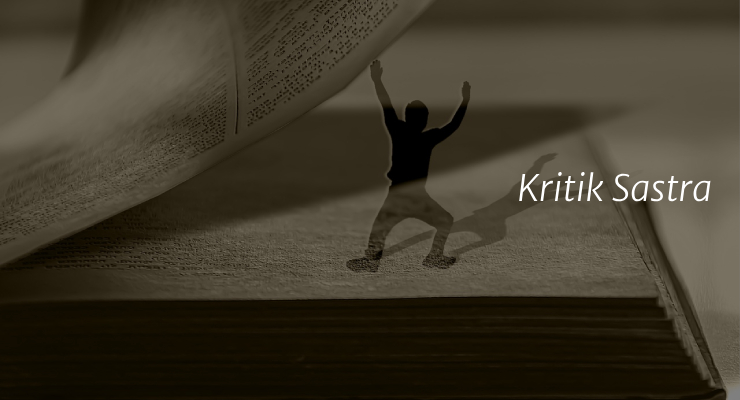Daftar isi
Pengertian dan Fungsi Kebijakan
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Kebijakan adalah kata yang mungkin sering kita dengar, kita ucapkan atau bahkan kita lakukan. Namun dalam konteksnya seringkali kita belum memahami sepenuhnya apa sesungguhnya makna atau arti dari kata kebijakan tersebut, maka dari itu kita harus lihat apa sesungguhnya makna dari kebijakan. Ada bermacam-macam pendapat yang mengemukakan tentang konsep kebijakan, oleh karena itu kita memerlukan kesepakatan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan kebijakan itu sendiri.
Dalam pemahaman yang lebih definitive bahwa kebijakan (policy) menurut hough (1994) merupakan istilah yang sulit di pahami dan menuntut penjelasan yang lebih jauh karena istilah itu sering di gunakan dalam cara yang berbeda, dan untuk menunjukan fenomena yang beragam. Proses kebijakan di dasarkan pada asumsi bahwa kebijakan publik lebih terkait dengan transformasi konflik kelompok dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kebijakan tidak lahir begitu saja melainkan di lahirkan dalam konteks seperangkat nilai yang khusus, tekanan, dan dalam susunan struktur yang khusus, termasuk di dalamya kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.
Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal pikiran manusia. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun demikian ,akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dalam pambahasan makalah kali ini kita akan mengkaji lebih lanjut mengenai makna serta fungsi dari kebijakan itu sendiri.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut :
1. Apa pengertian kebijakan ?
2. Apa fungsi kebijakan ?
C. TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Regulasi Pendidikan, selain itu juga memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan kebijakan yaitu :
1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan.
2. Untuk mengetahui fungsi kebijakan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN
a. Arti dan Makna Kebijakan
Kebijakan adalah terjemahan dari kata “wisdom” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada seeorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian (Imron, 1996:17). Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja pengecualian aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualian tetapi tidak melanggar aturan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian , kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.
Berikut Pengertian kebijakan menurut bebepara ahli
Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
Koontz dan O’Donnell (1987) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan.
Sedangkan Anderson (1979) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.
Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan (mann, 1975). Implikasi kebijakan menurut Mann (1975) mempersyarat dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika di lihat dari sudut pembangunan pendidikan maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan kebijakan selalu di temukan problem. Adapun karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat publik, sangat konsekuensial, sangat kompleks, di dominasi ketidakpastian, dan mencermiinkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya.
Rich (1974) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem.
Menurut poerwadarminta (1984) kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.
Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seorang yang bijak adalah yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya.
Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.[5]
Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan (wisdom) adalah kepandaian, kemahiran kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.[6]
Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.
Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan mengandung arti :
1. Hasil produk keputusan yang di ambil bersama.
2. Adanya formulasi.
3. Pelaksanaanya adalah orang-orang dalam organisasi.
4. Adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan.
Kebijakan penggunaannya sering di sama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar. Sedangkan menurut perserikatan bangsa-bangsa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global. Dengan demikian pengertian kebijakan dapat di artikan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan di ikuti dan di laksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu dengan memproyeksikan program-program.
b. Model-Model Kebijakan Pendidikan
Beberapa masalah kebijakan tidak dapat di pahami hanya dengan menggunakan metodologi kuantitatif, karena sifatnya khusus dan unik seperti kegiatan pembelajaran, peningakatan kualitas mengajar guru, penataan ruang kelas, supervisi pengajaran, perencanaan pengajaran dan kegiatan lainnya di sekolah. Metodologi kualitatif di bidang pendidikan dapat di lakukan dengan mempelajari permasalahan kebijakan secara khusus dan secara rinci dan secara kasus per kasus di telusuri dengan pendekatan kualitatif seperti manajemen sekolah, manajemen kelas, peningkatan kualitas pengajaran, penggunaan fasillitas dan perlengkapan pembelajaran dan sebagainya. Pendekatan analisis kebijakan pada dasarnya menurut Suryadi dan Tilaar (1993:46) meliputi dua bagian besar yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif dan kenyataan kedua metodologi tersebut di laksanakan dalam kegiatan analisis kebijakan. Istilah tipe-tipe model kebijakan menurut Dunn (1981:116) terdiri dari enam model di antaranya model deskriptif dan normatif. Walaupun istilahnya berbeda-beda dalam ilmu pengetahuan pendekatannya selalu berkisar diantara kedua jenis tersebut. Untuk menganalisisinya menurut Dunn (1981:111) dapat di gunakan berbagai model kebijakan yaitu medel deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural, model sebagai pengganti dan perspektif.
1. Model deskriptif
Model deskriptif menurut Suryadi dan Tilaar (1993:46) adalah suatu prosedur atau cara yang di pergunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Cohn (1981) model deskriptif merupakan pendekatan positif yang di wujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan suatu “state of the art”atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang di teliti dan perlu di ketahui para pemakai. Tujuan model deskriptif oleh Dunn memprediksikan atau menjelaskan sebab-sebab dan konsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini di gunakan untuk memantau hasil-hasil dan aksi-aksi kebijakan seperti indikator angka partisipasi murni dan angka drop out yang di publikasikan.
Sedangakan pada tingkat satuan pendidikan setiap kepala sekolah bersama guru dan komitme sekolah mempersiapkan strategi perolehan mutu yang rasional berdasarkan dukungan sumber daya yang ada di sekolah dengan menyajikan keadaan apa adanya. Dengan model deskriptif adalah pendekatan positif yang di wujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan manyajikan suatu “state of the art” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang di teliti dan perlu di ketahui oleh para pemakai. Untuk mendeskripsikan suatu kebijakan menggunakan prosedur atau cara untuk penelitian baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat.
2. Model Normatif
Di antara beberapa model jenis normatif yang sering di gunakan analisis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (model antri), pengaturan volume dan waktu yang optimun (model inventaris), dan keuntungan yang optimum pada investasi publik (model biaya manfaat). Karena masalah-masalah keputusan normatif adalah mencari nilai-nilai variable terkontrol (kebijakan) akan menghasilkan manfaat terbesar (nilai), sebagaaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak di ubah oleh para pembuat kebijakan. Pendekatan normatif menurut Suryadi dan Tilaar (1993:47)[12] di sebut juga pendekatan prespektif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat di gunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan model normatif buakan hanya menjelaskan atau memprediksi tetapi juga memberi dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Juga membantu memudahkan para pemakai hasil penelitian, menentukan atau memilih salah satu cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah.
Model normatif ini tidak hanya memungkinkan analisis atau pengambil kebijakan memperkirakan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan di maksudkan untuk membantu para pengambil keputusan (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Sekolah) memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Pendekatan normatif di tekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang (aksi) yang dapat menyelesaikan masalah-masalh pendidikan yang di butuhkan oleh masyarakat pada semua jenjamg dan jenis pendidikan.
c. Model verbal
Model verbal dalam kebijakan di dekspressikan dalam bahasa sehari-hari, bukan hanya bahasa logika, simbolis dan matematika sebagai masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analisis berstandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi atau penawaran rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah di komunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya yang murah[13]. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang di pakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi,sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan, karena tidak di dukung informasi atau fakta yang mendasarinya.
d. Model Simbolis
Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang di percaya menciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan di peroleh dari model-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode matematika, statistika dan logika. Memang model ini sulit di komunikasikan di antara orang awam, termasuk oleh para pembuat kebijakan, dan bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalah pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model tersebut. Kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya tidak mudah diinterprestasikan, bahkan diantara para spesialis, karena asumsu-asumsinya tidak di nyatakan secara memadai.
Model-model simbolis dapat memperbaiki keputusan kebijakan, tetapi hanya jika premis-premis sebagai pijakan penysun model di buat eksplisit dan jelas. Terlalu sering isi yang pokok menjadi model yang berdasarkan teori dan bukti tidak lebih dari rekonsepsi dan prasangka ilmuwan yang terselubung dalam kekuatan ilmiah dan di hiasi dengan simulasi komputer yang ekstensif.tanpa verivikasi empiris hanya ada sedikit jaminan bahwa hasil praktek semacam itu dapat diandalkan untuk tujuan kebijakan normatif.[14] Karena itu untuk penentuan kebijakan atas dasar angka-angka kuantitatif tidak cukup memadai untuk melakukan prediksi, masih perlu data kualitatif atau fakta-fakta yang real sebagai pertimbangan prediksi dan juga penentuan kebijakan.
e. Model Prosedural
Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal di peroleh dengan cara mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin, sebagai contoh: pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, angkatan kerja terdidik, penuntasan wajib belajar 9tahun, alokasi anggaran pemerintah untuk pembelajaran, dan suplay makanan dalam tahun-tahun mendatang yang tidak dapat diterangkan sercara baik, karena data-data dan informasiyang di perlukan tidak tersedia. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya (meskipun tidak harus) diperoleh dengan bantuan komputer, yang diprogram untuk menghasilkan prdiksi-prediksi alternatif di bawah serangkaian konsumsi yang berbeda-beda.[15]
Model prosedural dicatat dengan memanfaatkan model ekspresi yanng simbolis dalam penentuan kebijakan. Perbedaanya, simbolis menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antara variabel-variabel kebijakan dan hasil, sedangkan model prosediran adalam mensimulasikan hubungan antara variabel tersebut. Model prosedural dapat ditulis dalam bahasa nonteknis yang terpahami, sehingga memperlancar komunikasi antara orang-orang awam. Kelebihannya memungkinkan simulasi dan penelitian yang kreatif, kelemahannya sering mengalami kesulitan mencari data atau argumen yang dapat memperkuat asumsi-asumsinya, dan biaya model prosedural ini relatif tinggi di banding model verbal dan simbolis.
Pada pemerintah desentralisasi sesuai UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah penggunaan model prosedural ini dalam pengambilan kebijakan ada tiga tatanan yakni untuk memenuhi standar nasional dilakukan oleh Depertemen Pendidikan Nasional, untuk membantu kebutuhan satuan pendidikan pada tingkat regional oleh pemerintah provinsi, dan untuk memenuhi anggaran, sarana dan prasarana, fasilitas dan perlengkapan, dan ketenagaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiga tataran ini mempunyai hubungan dengan jumlah variabel kebijakan pendidikan, sedangkan muara dari kebijakan pendidikan adalah satuan pendidikan. Untuk hal-hal tersebut diatas menunjukan bahwa satuan pendidikan bukanlah intitusi penentu kebijakan, tetapi sebagai sarana kebijakan.[16]
f. Model Sebagai Pengganti dan Perspektif
Pendekatan perspektif menurut Suryadi dan Tilaar (1993:47)[17] merupakan upaya ilmu pengetahuanmenawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan. Preskipsi atau rekomendasi diidentikan dengan advokasi kebijakan, yang acapkali dipandang sebagai cara pembuat keputusan idiologis atau untuk menghasilkan informasi kebijakan yang relevan dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai solusi-solusi yang memungkinkan bagi masalah publik. Jadi pengambilan kebijakan bukan atas kemauan atau kehendak para penentu kebijakan, tetapi memiliki alasan-alasan yang kuat dan kebijakan tersebut memang menjadi kebutuhan publik. Bentuk ekspresi dari model kebijakan lepas dari tujuan, menurut Dunn (1981:115) dapat di pandang sebagai pengganti (surrogates) atau sebagai perspektif (perspektives).
Model pengganti (surrogates model) di asumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang subtantif. Model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak sepenuhnya mewakili secara sah masalah subtantif, sebaliknya model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lainyang dapat digunakan untuk merumuskan masalah subtantif. Pebedaan antara model pengganti dan perspektif adalah pentinga dalam analisis kebijakan publik. Kebanyakan masalah penting cenderung sulit di rumuskan. (ill structured).
Karena kebanyakan struktur masalah kebijakan masalah publik adalah kompleks sehingga penggunaan model pengganti secara signifikan meningkatkan probabilitas kesalahan yaitu memecahkan formulasi yang salah dari suatu maslah ketika harus memecahkan masalah yang tepat.[18] Model formal tidak dapat dengan sendirinya memberitahu apakah memecahkan formulasi masalah kebijakan organisasi yang salah ketika harus memecahkan masalah yang tepat. Untuk memutuskan kibijakan pendidikan baik itu pada tatana nasional, regional, dan satuan pendidikan tentu mengacu pada suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memcahkan suatu masalah pendidikan. Hal ini penting, karena pemecahan masalah pendidikan ini harus di lakukan dengan tepat, jika tentu akan mendpatkan kerugian baik waktu, material dan juga pemyimpangan dari tujuan yang telah di tentukan.[19]
B. FUNGSI KEBIJAKAN
Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan atau melaksanakan program dan kegiatan, adapun fungsi dari kebijakan itu sendiri yaitu :
1. Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana srategi akan di laksanakan.
3. Memberikan arahan kepada pelaksana.
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi misi sasaran dan tujuan.
5. Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.[20]
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah kita membaca tentang pengertian dari kebijakan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan (wisdom) adalah kepandaian, kemahiran kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di dasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.
Kebijakan penggunaannya sering di sama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar. kemudian istilah tipe-tipe model kebijakan menurut Dunn (1981:116) terdiri dari enam model di antaranya model deskriptif dan normatif. Walaupun istilahnya berbeda-beda dalam ilmu pengetahuan pendekatannya selalu berkisar diantara kedua jenis tersebut. Untuk menganalisisinya menurut Dunn (1981:111) dapat di gunakan berbagai model kebijakan yaitu medel deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural, model sebagai pengganti dan perspektif.
Adapun dari fungsi kebijakan yaitu :
1. Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana srategi akan di laksanakan.
3. Memberikan arahan kepada pelaksana.
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi misi sasaran dan tujuan.
5. Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.
B. SARAN
Demikian makalah yang dapat penulis sampaikan, tentunya dalam penyusunan makalah ini masih banyak kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas ataupun dalam penyajiannya yang kurang lengkap, pastinya makalah ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangatlah penulis harapkan untuk menjadikan pelajaran pada masa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Dr. H. Ahmad Rusdiana,M.M. 2015. Kebijakan Pendidikan “ dari Filosofi ke Implementasi, BANDUNG : Pustaka Setia
Ir. Agustinus Hermino, S.P., M.Pd. 2014. Kepemimpinan Pendidikan di Era Globallisasi, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
Sagala,Syaiful.2009.Administrasi Pendidikan Kontemporer. Cetakan ke 5. Bandung: Alfabeta
https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kebijakan di akses pada kamis 24 September 2015 pukul 09.48 WIB
https://oktaseiji.wordpress.com/2011/04/24/kebijakan-pendidikan-di-indonesia/? di akses pada 24 september 2015 pukul 10.03 WIB
+-+Copy.jpg)
.jpg)