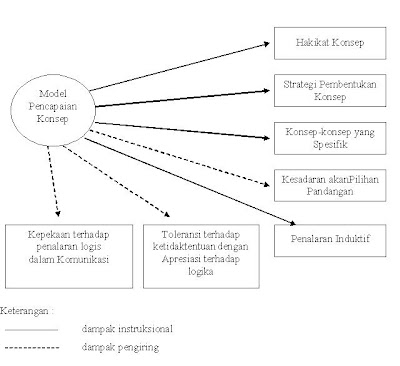Daftar isi
Dampak Judi Pada Remaja
Bab I. Pendahulan
A. Latar Belakang
Berbagai cara yang dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. Perjudian membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, karena sangat mengganggu perekonomian keluarga yang sering berakhir dengan kriminalitas.
Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita.
Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga, yang terjadi perjudian dikalangan remaja semakin meninggkat, dari meja bilyar, lapangan olah raga, hingga judi justru lebih marak digunakan remaja untuk berjudi, hal ini yang melatar belakangi penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul: “Dampak judi pada remaja”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu :
- Mengapa terjadi perjudian pada remaja ?
- Bagaimana dampak judi pada remaja ?
- Bagaimanakah mengatasi judi pada remaja dan cara pencegahannya ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya perjudian dikalangan remaja.
2. Memberi penjelasan tetang perjudian yang dibahas dari sisi kriminologi.
3. Memberi penjelasan tengtang langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi dan mencegah perjudian pada remaja.
1.4 Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian penulis mempergunakan metode kepustakaan. Yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari media buku, Koran, artikel dan situs atau web internet.
Bab II. Kajian Teori
A. Pengertian Judi
2.1.1 Pengertian Judi Menurut Undang-Undang
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU No. 7 Tahun 1974) tidak ada dijelaskan secara rinci defenisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segaa pertaruhan lainnya.”
Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin :
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
2.1.2 Pengertian Judi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pergertian judi adalah permainan dng memakai uang atau barang berharga sbg taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
2.2 Definisi Remaja
2.2.1 Definisi Remaja Menurut Wikipedia
Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.
2.2.2 Definisi Remaja Menurut Hurlock
Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.
2.2.3 Definisi Remaja Menurut Zakiah Derajat
Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.
2.4 Definisi Remaja Menurut Penulis
Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang ditandai dengan perkembangan bebagai aspek seperti fisik, psikologi, dan mentalitas. Biasanya terjadi pada usia 12-24 tahun
2.3 Sejarah Perkembangan Perjudian
Menurut Cohan (1964), perjudian sudah ada sejak jaman prasejarah. Perjudian seringkali dianggap seusia dengan peradaban manusia. Dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang.
Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan. Alice Hewing (dalam Stanford & Susan, 1996) dalam bukunya Something for Nothing: A History of Gambling mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Orang Yunani Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu.
Pada jaman Romawi kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib.
Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi ditempat yang disebut Hazard (mungkin diambil dari nama tempat dimana dadu tersebut diketemukan kembali). Sampai abad ke 18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi.
Pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang dibuat di Eropa dibuat di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.
Sedangkan untuk saat ini yang sering dipakai sebagai bahan taruha adalah hasil akhir dari sebuah pertandingan olahraga. Olahraga yang sering dijadikan taruahan dan menjadi lumrah hukumnya bagi para pecinta olahraga adalah sepakbola. Bahkan sepakbola saat ini sudah dijadikan industri terutama dalam hal perjudian, sponsor dan penjualan pemain sepakbola. Seiring dengan perkembangan teknologi terutama internet, perjudian sepakbola dilakukan setiap hari didunia maya.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pembahasan Secara Umum
Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah :
1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.
Pada awalnya perjudian hanya dilakukan dalam beberapa jenis misalnya perjudian yang sama sering dinamakan undian, lotre, lotto (atau lottery), adu dadu, kartu, dan permainan lainnya. Namun saat ini perjudian sudah menjadi penyakit menular dimana setiap permainan bisa diajdikan sebagai bahan untuk melakukan perjudian. Bahkan olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas saat ini sudah dilegalkan menjadi bahan untuk melakukan pertaruhan.
Salah satu cabang olahraga yang menjadi bahan taruhan perjudian adalah sepakbola. Olahraga yang merupakan olahraga terpopuler saat ini didunia ini dijadikan sebagai bahan terpopuler. Bahkan diinternet saat ini banyak situs atau website yang menyediakan layanan untuk melakukan taruhan sepakbola. Di Eropa hal ini telah dilegalkan menjadi industri dalam dunia sepakbola. Dua website atau situs yang saat ini populer di Indonesia adalahwww.livescore.com dan www.asianbookie.com.
Banyak masalah yang bisa terjadi dalam melakukan perjudian ini. Beberapa masalah dalam perjudian antara lain :
§ Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.
§ Kadang-kadang judi tidaklah adil, jika menang atau kalah, harus membayar sejumlah uang dan menanggung sendiri akibatnya pihak yang menang tidak akan peduli dengan yang kalah.
Meskipun demikian perjudian tetap saja sulit untuk diberantas, jangankan diberantas dikurangi saja sulit, perjudian tetap eksis dimasyarakat. Memberantas perjudian layaknya mengosongkan air laut. Meski pidananya sudah jelas dan perjudian memang salah serta sudah dikonstruksikan sebagai tindak pidana oleh KUHP. Ada wacana yang menyebutkan agar perjudian dilegalkan sekalian dengan membuat pengawas yang ketat atas perjudian. Jika dikaji lebih mendalam perjudian pada dasarnya bagian dari perikatan dan masuk pada ranah perdata.
3.2 Faktor-faktor Penyebab Perjudian Pada Remaja
3.2.1 Faktor Sosial & Ekonomi
Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berfikir, Dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Pandangan yang relative sama juga ada diantara remaja, mereka berusaha memiliki uang lebih dengan cara instan dengan berjudi, apalagi bagi remaja yang memang tumbuh dilingkungan masyarakat yang memang suka berjudi.
3.2.3 Faktor Situasional
Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat remaja penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja. padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.
3.2.3 Faktor Rasa Ingin Tahu
Rasa ingin tahu pada remaja sangatlah besar maka sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.
3.2.4 Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung
memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.
3.2.5 Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan
Remaja yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Umumnya remaja selalu ingin mengunggulkan diri sehingga bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.
3.2.6 Faktor Waktu dan Kesempatan
Umumnya para remaja yang suka berjudi bermula ketika mereka punya banyak waktu luang, yang dimanfaatkan untuk sekedar bermain-main. Merasa permainan mereka kurang menarik maka dibumbui sedikit taruhan. Dengan kondisi tanpa kendali dan pengawasan maka kesempatan untuk terus berjudi akan terus ada. Ketika niatan mereka lebih untuk bertaruh lebih penting dari pada bermain disinilah judi muncul.
3.3 Dampak Judi Terhadap Remaja
3.3.1 Merusak Hubungan Sosial
Ketika remaja sudah mulai diketahui menyukai perjudian tentu akan mendapat sentiment dari masyarakat, karena bagaimanapun perjudian adalah menyimpang dari norma masyarkat yang berlaku. Terlebih orang tua akan memberi respon keras pada anak remaja yang diketahui gemar berjudi, kadang respon keras ini justru memperkeruh suasana yang sering mendorong remaja untuk lebih liar dari sebelumnya.
3.3.2 Menggangu Prestasi Belajar dan Masa Depan
Bagi remaja yang terlibat dalam perjudian, di dalam pikirnyanya hanyalah bagaimana untuk mendapat kemenangan dan kembali bisa berjudi. Hal selain itu bukalan prioritas terlebih, belajar, mada depan adalah urusan nanti. Kadang mereka sering membolos dan meninggalkan sekolah hanya untuk berjudi.
3.3.3 Menjadi Gebang Masuknya Miras dan Narkoba
Satu keburukan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan judi, berkumpul ,bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi denga minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabuk alcohol tentu saja merek mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.
3.3.4 Membawa Permasalahan Keuangan
Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang tepa musnah, ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita ketika menang ini adalah saat tepat untuk berpesta. Sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para penjudi muda ini.
3.3.5 Merupakan Tindak Pidana dan Memicu krimalitas
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang tindakan hukum pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam sebuah perjudian, penangkapan dan kurungan selalu mengancam. Selain itu banyak tindakan criminal lain yang bisa saja muncul akibat judi, krisis keuangan bisa saja memunculkan membuat para penjudi melakukan, pencurian, pemalakan, dan berbagai tidakan kriminal lain secara berantai.
3.4 Upaya Untuk Mengatasi dan Pencegahan Judi Pada Remaja
3.4.1 Pembinaan Penanaman nilai moral dan agama
Bagaimanapun keadaan sikap mental dan moralitas yang baik adalah modal untuk menangkis dari pengaruh-pengaruh buruk terutama nilai-nilai religious senantiasa memberi penajaran yang mendalam untuk berlaku hidup benar dimuka bumi ini. Oleh karena itu pembinaan dan penanaman nilai-nilai moral yang baik dan nilai religius mestinya dilakukan sejak dini dan terus dikembangkan sesuai perkembangan anak.
3.4.2 Membangun komunikasi efektif dan keluarga harmonis
Keluarga sangat berperan penting dalam berbagai masalah perkembangan anak. Dukungan orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh negatif dari luar, bisa dilakukan dengan membangun komunikasi efektif antara orang tua dan anak serta terbentuknya keluarag harmonis akan mencegah remaja untuk mengarah pada perilaku negatif. Tidak jarang anak-anak yang bermasalah disebabkan karena keluarga yang berantakan dan orangtua yang diktator.
3.4.3 Mengarahkan dan Mendukung Anak untuk Melakukan Kegiatan Positif Yang Mereka Sukai.
Begitu banyak waktu kosong pada remaja menjadi alasan untuk melakukan banyak hal negatif, tentu orangtulah yang harus jeli dalam menyikapi hal ini. Mengajak mereka melakukan kegiatan positif saja belum cukup atau kadang malah membebani anak karena merka tidak suka melakukannya. Cobalah untuk mengggalai hal positif apa yang di cintai dan disukai anak sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah prestasi, arahkan dan dukung mereka untuk mencapai cita-cita mereka melalui kegiatan positif yang mereka cintai sendiri, tanpa perlu menjadi seperti orang lain.
3.4.4 Kerja sama Masyarakat dan Aparat dalam Menjaring Perjudian
Aparat penegak hukum tentu akan berupaya melakukan berbagai tindakan untuk segala bentuk praktek perjudian tetapi, kesadaran masyarakat sendiri untuk melaporkan setiap praktek perjudian adalah yang lebih penting. Sepintas judi hanyalah permainan biasa tapi ketika anak-anak melihat maka ini akan sama dengan menanam benih baru. Jadi kesadaran masyarakat untuk meninggalkan segala bentuk permainan judi jauh lebih penting dari laporan dan tindakkan aparat.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelum maka penulis dapat emberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek judi yang terjadi pada remaja disebabkan rasa ingin tahu, lingkungan, situasi, waktu dan kesempatan, serta kekeliruan dalam mempresepsikan kemenangan dan keterampilan.
2. Judi pada remaja memberikan dampak buruk, terhadap pelakunnya berupa rusaknya hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat, menggangu prestasi belajar, menimbulakan masalah keuangan dan menjerumuskan remaja kedalam narkoba dan kriminalitas.
3. Berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah dan mengatasi perjudian pada remaja diantaranya: penanaman niali moral dan agama, membagun keluarga komunikatif dan harmonis, serta mengarahkan remaja untuk melakukan kegiatan positif yang mereka sukai.
4.2 Saran
Perjudian sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dari hasil kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan beberapa saran berikut:
1. Orang tua, masyarakat dan Pemerintah semestinya memenuhi, mengarahkan dan mendukung rasa ingin tahu generasi muda dengan berbagai kegiatan positif.
2. Kesadaran masyarakat bahwa judi adalah perilaku tercela harus kembali digiatkan karena memberi dampak yang sangat buruk terutama pada generasi muda dan remaja.
3. Membangun keluarga harmonis dan lingkungan masyarakat yang baink untuk tumbuh kembang anak-anak dan remaja adalah tanggung jawab setiap keluarga.
DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Ayu Dewi. Tinjauan Kriminologis Terhadap Fzenomena Maraknya Perjudian Togel di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2009.
http://bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/ diakses Jumat tanggal 01 Juli 2011 pukul 12:55
http://blog.re.or.id/perjudian-dan-lokalisasi.htm diakses Jumat tanggal 01 Juli 2011 pukul 12:58
Solahudin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, KUHPdt), Visimedia, Jakarta, 2008.
UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian