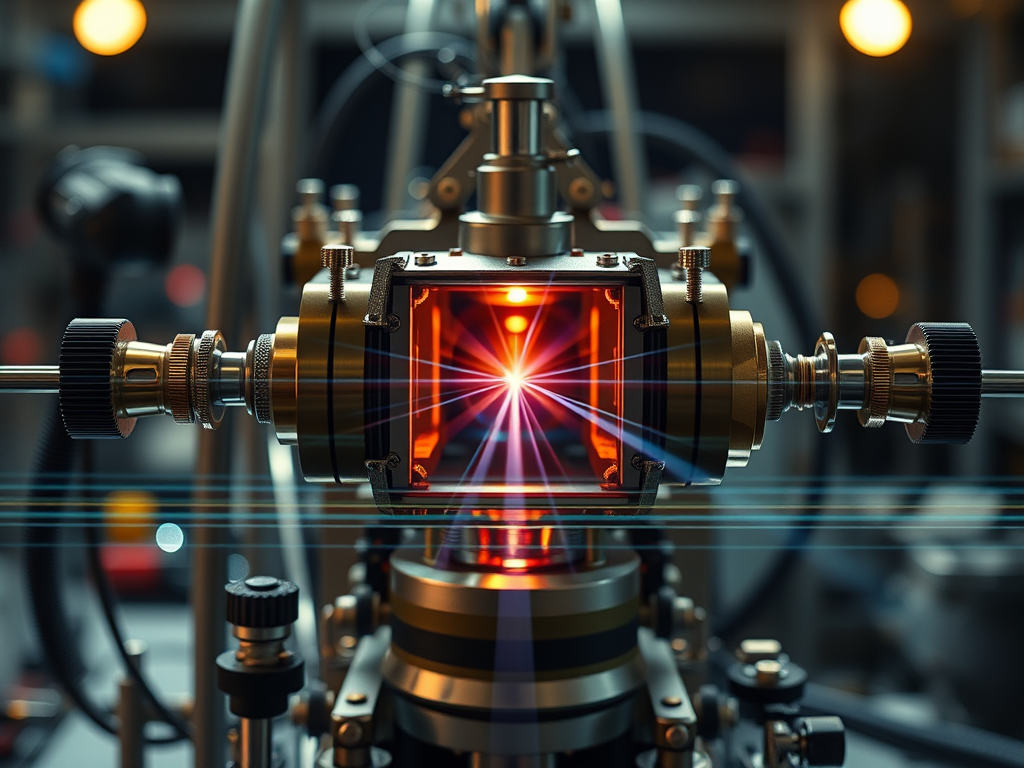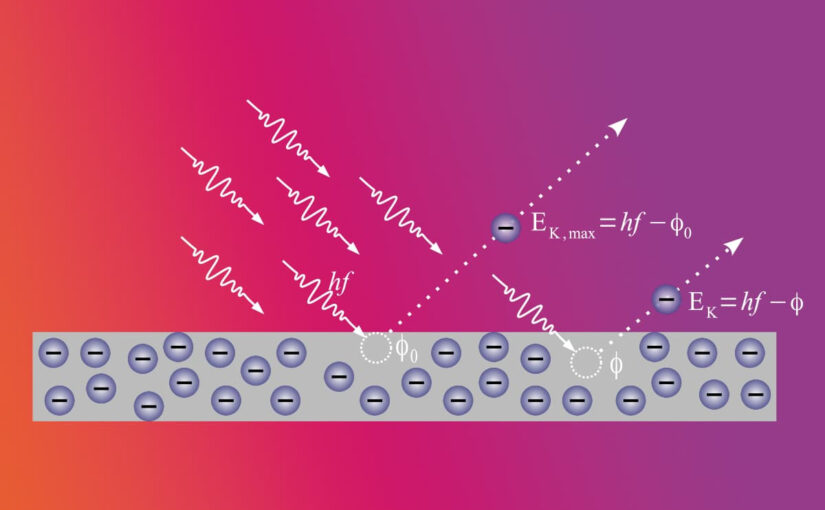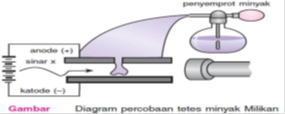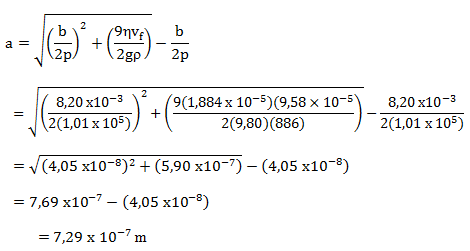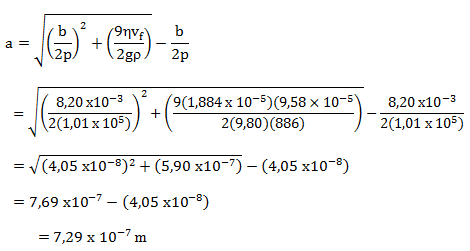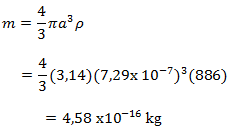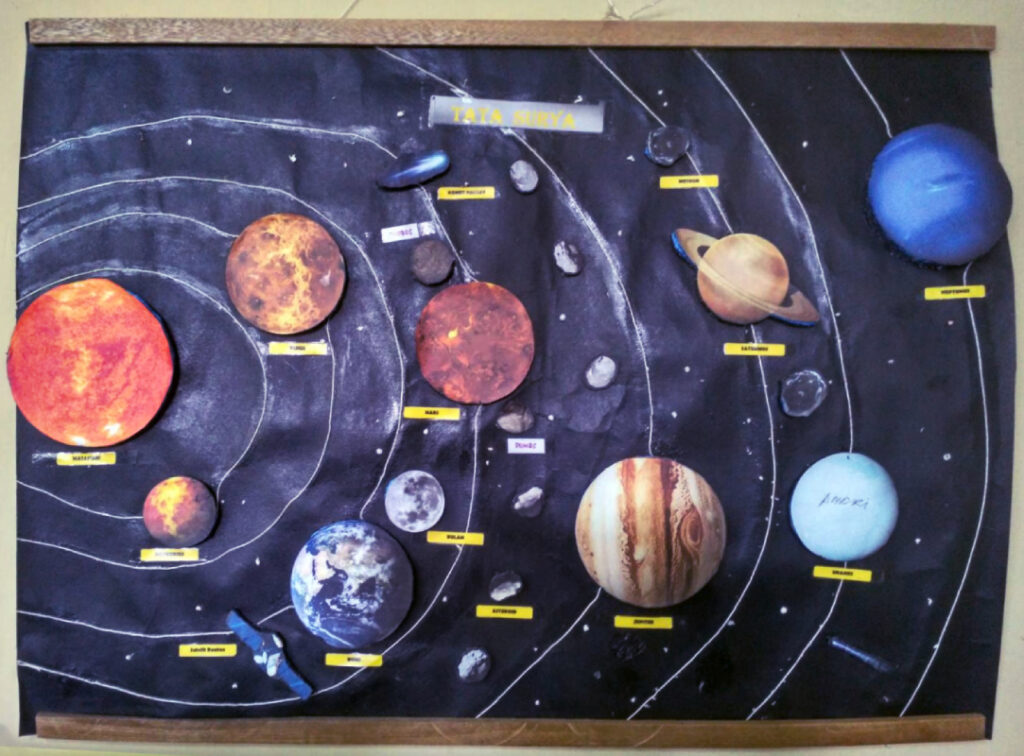Mekanika fluida merupakan kajian fisika yang memiliki banyak bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan kehidupan dimuka bumi dipenuhi oleh fluida baik itu dalam bentuk zat cair maupun gas.
Daftar isi
Aplikasi Mekanika Fluida Dalam Kehidupan Sehari-hari
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Fisika merupakan bidang kajian yang mengkaji fenomena alam kemudian disajikan dalam bentuk hukum, konsep, prinsip dan teori-teori fisika. Hal ini termasuk juga pada benda-benda alir (fluida) seperti zat cair maupuan gas. Aplikasi mekanika fluida tersebar di banyak cabang dan dimanfaatkan oleh manusia. Mulai dari pembuatan perahu, pesawat terbang, parasut, perancangan pipa air dan masih banyak lagi.
Parasut yang biasanya kita dengar atau kita tonton di televisi terkadang menyebabkan kecelakaan bagi penggunanya. Hal tersebut sangat membuat kita merasa penasarn mengapa kecelakaan tersebut bisa terjadi. Apakah orang tersebut belum pandai menggunakan parasut ataukah adakesalahan dalam pembuatan parasutnya. Dan mengapa kita manusia tidak menggunakan prinsip kerja parasut tersebut untuk membuat parasut yang lebih canggih.
Makalah ini diharapkan dapat mengembangkan cara berpikir mahaiswa untuk lebih mengembangkan konsep/prinsip kerja parasut, menghindari terjadinya kecelakaan pada saat terjun paying, dan Serta memahami aplikasi mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari.
B. Tujuan
Melalui makalah ini diharapkan mahasiswa dapat:
- Mengetahui aplikasi mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari (parasut)
- Mengetahui prinsip kerja dan cara pembuatan parasut
Bab II. Kajian Teori

Gambar 1 Gambar Parasut
Di televisi tentu kita sering menyaksikan orang-orang atau tentara melakukan terjun payung dari pesawat udara. Nah bagaimana cara kerja parasut sehingga membuat orang melayang-layang di udara
1. Terjun Payung
Sejarah Terjun Payung
Pada abad ke-15, Leonardo Da Vinci, pembuat lukisan Mona Lisa yang legendaris itu, pernah membuat sketsa yang menggambarkan perlengkapan untuk melakukan terjun payung. Tapi seperti banyak konsep yang pernah dibuatnya, rancangan konsep peralatan terjun payung itu pun belum pernah direalisasikannya menjadi kenyataan. Diduga parasut ini dirancang sebagai alat keselamatan saat terjadi musibah, misalnya kebakaran, pada bangunan tinggi. Karena sketsa itulah Leonardo Da Vinci bisa dianggap sebagai salah satu pionir dalam rancangan konsep parasut untuk terjun payung. Parasut yang dirancangnya itu berbentuk segitiga seperti yang tampak pada gambar. Ternyata akhirnya ada juga yang mencoba merealisasikan parasut yang dulu pernah dirancang oleh seniman yang sekaligus ilmuwan genius itu. Meskipun tentu saja parasut seperti itu tidak akan digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan para SkyDiver jaman sekarang.
Satu abad setelah Leonardo Da Vinci merancang konsep parasut, seorang berkebangsaan Italia, Fausto Veranzio, telah merancang parasut yang berbeda dari konsep yang dibuat oleh Leonardo. Meskipun idenya masih bermula dari impian seniman besar tersebut. Konsep Fausto itu dituangkannya dalam buku tentang mekanika yang berjudul Machinae Nova. Buku yang diterbitkan pada tahun 1595 di Venesia ini memuat 40 sketsa beberapa rancangan mesin dan peralatan. Beberapa dari sketsa itu ada yang menggambarkan aksi manusia melakukan terjun payung dengan menggunakan parasut berbentuk segi empat. Dan pada tahun 1617, Fausto Veranzio berhasil mewujudkan parasut rancangannya itu dengan melakukan uji coba terjun payung dari sebuah menara di kota Venesia. Tapi beberapa literatur mengatakan bahwa sebenarnya Fausto tidak pernah mewujudkan konsep parasutnya itu menjadi sebuah kenyataan.

Gambar 2 Uji Coba Parasut
Usaha-usaha yang dilakukan oleh Leonardo Davinci dan Fausto Veranzio untuk mengembangkan pembuatan parasut telah dilanjutkan orang lain. Berikutnya dilakukan oleh Andre Jacques Garnerin dari Perancis. Pria yang lahir pada tanggal 31 Januari 1769 ini banyak mempelajari bidang fisika sebelum bergabung dalam dinas milter Perancis. Selama beberapa tahun kemudian Garnerin tertarik pada balon berudara panas yang dikembangkan untuk tujuan militer. Selama menjadi tawanan perang di Hungaria, Garnerin mulai melakukan beberapa percobaan untuk mengembangkan parasut. Dia berhasil menyelesaikan rancangannya itu pada tahun 1797. Sebuah parasut berbentuk bundar dengan diameter 23 kaki.
Seperti konsep dari Leonardo dan Fausto, parasut buatan Garnerin ini juga masih dilengkapi dengan kerangka sehingga bentuknya masih mirip payung yang kita gunakan untuk melindungi diri dari terik matahari atau guyuran air hujan. Lalu pada tanggal 22 Oktober 1797 Garnerin menguji coba parasut buatannya itu dengan melompat dari sebuah balon udara yang melayang pada ketinggian 975 meter diatas kota Paris. Meskipun parasut tersebut gagal mengendalikan hempasan aerodinamik udara yang membuat peluncuran Garnerin sempat tidak terkendali, tapi akhirnya dia berhasil mendarat dengan selamat. Keberhasilan itu membuat Garnerin menjadi manusia pertama yang berhasil menggunakan parasut dengan melakukan lompatan dari sebuah benda terbang yang melayang di angkasa. Dan pada tahun 1799, istri Garnerin (Jeanne-Genevieve Garnerin) menjadi wanita pertama yang berhasil melakukan aksi terjun payung.
Terjun payung yang dilakukan oleh Garnerin masih menggunakan keranjang sebagai tempat duduk pengendara parasut. Parasutnya pun masih menggunakan kerangka sehingga disebut dengan istilah parasut kaku (Vented Parachute). Orang yang pertama kali berhasil membuat parasut tanpa kerangka yang selanjutnya dikenal sebagai parasut lemas (Limp Parachute) adalah Tom Baldwin dari Amerika pada tahun 1897. Dan pada tahun 1919, Leslie Irvin yang juga berasal dari Amerika yang pertama kali berhasil membuat parasut yang dapat dikendalikan.
Untuk selanjutnya terjun dari ketinggian di udara dengan menggunakan parasut banyak dilibatkan pada operasi militer. Setelah mengalami banyak hambatan, akhirnya pada tahun 1950 terjun payung diakui dunia sebagai salah satu cabang olah-raga yang juga menjadi sarana rekreasi. Sedangkan kejuaraan dunia olah-raga terjun payung yang pertama kali diadakan di Yugoslavia pada tahun 1951. Cabang olah-raga yang satu ini terus menyebar keseluruh dunia dan menjadi hobby yang sangat menantang. Parasut pun dikembangkan dengan spesifikasi dan fungsi yang makin canggih
2. Prinsip Kerja Parasut dan Cara Membuatnya
Parasut memanfaatkan gaya hambatan udara (Air drag Force) untuk memperlambat gerak. Hukum fisika yang berlaku di sini disebut Hukum Stoke’s. Hukum Stoke’s menyatakan, Bila ada sebuah benda pada melaju dalam suatu fluida (udara atau cairan), maka benda tersebut akan memperoleh gaya hambat
Parasut merupakan alat yang digunakan untuk memperlambat gerakan suatu objek di udara dengan menciptakan hambatan udara (drag) . Drag di dapat dari luas permukaan parasut, jadi semakin luas parasut maka semakin besar beban yang bisa di bawanya
Ada dua jenis parasut. Parasut berbentuk kubah (dome canopy) Yang kedua berbentuk segi empat yang biasanya digunakan untuk olah raga paralayang. Bahan untuk membuat parasut pertama kali adalah kanvas tetapi saat ini bahan untuk membuat parasut yang populer adalah nilon karena lebih elastis, lebih tahan, dan cukup murah.

Gambar 3 Parasut Kubah
Sebuah parasut paralayang terdiri dari dua permukaan paralel yang kuat dan saling dihubungkan dengan lembaran-lembaran vertikal. Bagian ini disebut ribs. Pada ribs ada lubang yang disebut crossport. Fungsinya, penyeimbang tekanan dan memudahkan parasut mengembang. Ribs membagi tubuh parasut menjadi beberapa sel yang ditandai dengan dua tali yang menjulur di masing-masing sisinya. Setiap sel punya anak yang jumlahnya bisa satu, dua, tiga atau lebih, tergantung dari jenis parasut. Sisi depan yang merupakan pintu sel ada leading edge. Sisi belakangnya disebut trailing edge. Pada permukaan bawah parasut atau intrados terdapat tali-tali yang menjulur ke bawah. Gabungan dari tali-tali itu disebut riser.
Dan riset inilah yang akan dihubungkan dengan harness. Ada dua kelompok tali yang dihubungkan dengan stabilizer, namanya brake atau tali kemudi (control line). Ujung dari tali kemudi dinamakan togel. Di tangan tali kemudi ini, kontrol gerak parasut dan rem difungsikan. Dan seorang penerbang harus paham betul bagian-bagian parasut tadi.

Gambar 4 Parasut Segi Empat (Parasut Olahraga)
3. Parasut Roket
Parasut roket berfungsi sebagai rem udara pada sebuah roket agar gerakan jatuh atau turun ke bawah setelah bahan bakar roket habis menjadi lebih lambat karena gravitasi jadi tidak langsung terjun ke bawah. Parasut roket biasanya dibuat dengan bahan yang tipis, kuat, anti air dan ringan.
Parasut roket sebenarnya tidak jauh berbeda dengan parasut pada umumnya hanya saja parasut dipasang pada sebuah roket.
Membutnya sangat mudah dan murah hanya memerlukan barang-barang bekas yang dirangkai dengan modal kreatifitas.
Peralatan:
- Gunting/Silet
- Jangka
Bahan:
- Kantong plastik atau sejenisnya
- Benang
Cara Membuat:

- Bentuk garis melingkar pada kantong plastik dengan menggunakan jangka. Berdiameter 70 mm sampai 300 mm sesuai dengan ukuran roket.
- Gunting kantong plastik sesuai dengan garis melingkar.
- Buat lubang-lubang kecil di tepi lingkaran dengan menggunakan ujung jangka. Buat sebanyak 8-16 lubang.
- Potong benang sepanjang 100-400 mm sebanyak lubang yang dibuat tadi.

Gambar 6 Parasut dari kantongan plastik
5. Masukkan dan ikat benang ke lubang-lubang parasut satu persatu.

Gambar 7 Parasut
6. Setelah semuanya terpasang kemudian rapikan benang dan ikat ujungbenang-benang menjadi satu.

Gambar 8 Parasut
7. Ikat tali parasut pada bagian luar atau dalam ruang muatan roke
8. Terakhir, lipat parasut dan masukkan ke dalam ruang muatan roket.
Tingkatan Penerbangan Parasut Roket

Gambar 9 Penerbangan Parasut Buatan

Gambar 10 Tingkatan Penerbangan Parasut Roket
Roket diluncurkan, didalam ruang muatan roket telah terdapat muatan berupa parasut mini Roket melakukan separasi di udara kemudian parasut mininya terbuka dan mengawali roket untuk turun perlahan di tanah.

Gambar 11 Parasut Mini Roket
Roket semakin mendekati permukaan tanah dan akan segera mengakhiri penerbangannya

Gambar 12 Parasut Mini Roket Mendarat
Roket akhirnya mendarat dengan baik di permukaan tanah dengan parasut mininya Sebelum digunakan pada roket sebaiknya parasut diujicoba terbang seperti pengujicobaan beban yang mampu dibawa oleh parasut, kestabilan parasut di udara dan pengujian lipatan parasut agar dapat menyakinkan bahwa parasut dapat terbuka dengan lipatan seperti itu. Caranya mudah cukup dilempar ke udara saja atau dijatuhkan dari tempat tinggi.
Bab III. Penutup
A. Kesimpulan
- Parasut merupakan alat yang digunakan untuk memperlambat gerakan suatu objek di udara dengan menciptakan hambatan udara (drag) . Ada dua jenis parasut. Parasut berbentuk kubah (dome canopy) Yang kedua berbentuk segi empat yang biasanya digunakan untuk olah raga paralayang.
- Parasut memanfaatkan gaya hambatan udara (Air drag Force) untuk memperlambat gerak. Hukum fisika yang berlaku di sini disebut Hukum Stoke’s. Hukum Stoke’s menyatakan, Bila ada sebuah benda pada melaju dalam suatu fluida (udara atau cairan), maka benda tersebut akan memperoleh gaya hambat. Semakin luas parasut maka semakin besar beban yang bisa di bawanya.
B. Saran
Pembaca sebaiknya mencari referensi yang lebih banyak lagi untuk memahami lebih jauh mengenai aplikasi mekanika fluida. Karena di dalam makalah ini sangat kekurangan referensi sehingga masih banyak kekurangan dalam penjelasan materinya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Kenali Bentuk dan Bagian-Bagian Penting Pada Sebuah Parasut. http://all-mistery.blogspot.com. Diakses pada tanggal 2 November 2014
Reyhanz. Beginilah Cara Kerja Parasut. http://hermawayne.blogspot.com. Diakses pada tanggal 22 November 2014
Sahwawi. Membuat Parasut Roket. Sahwawi Rocketry Blog. Diakses pada tanggal 22 November 2014
Septian Dozer, Edo. Terjun Payung. http://berita-iptek.blogspot.com. Diakses pada tanggal 22 November 2014