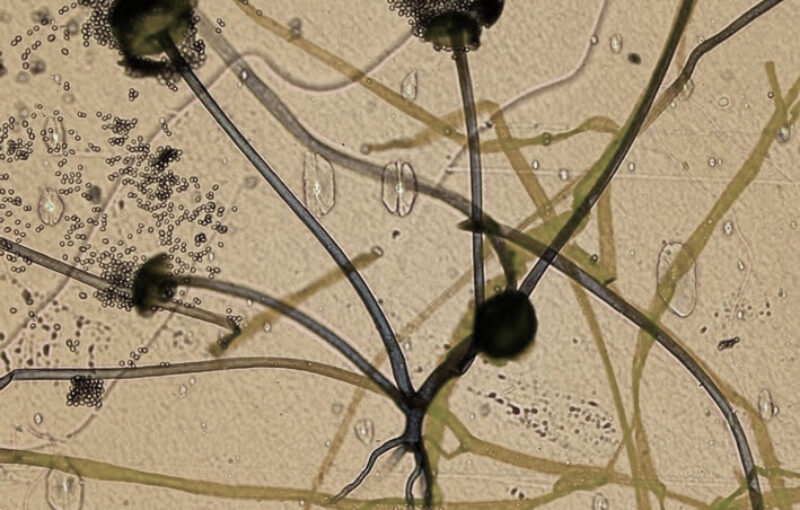Kolonialisme dan Imperialisme
Salah satu tujuan luhur dari bangsa Indonesia adalah adalah menolak segala bentuk penjajahan yang terjadi di atas dunia. Bentuk penjajahan yang paling banyak dilakukan adalah Kolonialisme dan Imperialisme.
Indonesia sendiri pernah menjadi negara jajahan Belanda dalam bentuk negara kolonial dalam bentuk Hindia-Belanda.
1. Pengertian Kolonialisme
Kolonialisme adalah suatu usaha untuk melakukan system permukiman warga dari suatu Negara diluar wilayah Negara induknya atau Negara asalnya.
2. Pengertian Imperialisme
Imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan imperium atau kekaisaran.
1. Dibidang Ilmu Pengetahuan
Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya teori heliosentris (tata surya) oleh Nicolaus Copernicus, seorang ahli ilmu pasti dan astronomi dari Polandia. Muncul pada tahun 1543 menjelaskan bahwa matahari sebagai pusat dari seluruh benda-benda antariksa dan bentuk bumi seperti bola. Pengalaman Marco Polo dari Venesia (Italia)
2. Di Bidang Teknologi
3. Di Bidang Sosial Ekonomi
1. Bangsa Portugis dan Spanyol
Bangsa Spanyol mulai menjelajahi samudera kea rah Timur pada abad 15-16.
· Vasco da Gama (1497-1498)
· Bartholomeus Diaz (1486)
· Pedro Alvares Cabrel (1500)
· Alfonso d’Albuquerque (1505)
· Franciscus Xaverius (1550)
· Cristophorus Columbus(1492)
· Magellan – del Cano (1519)
· Ferdinand Cortez (1519)
· Francisco Pizarro (1522-1532)
2. Bangsa Inggris
Pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, sekitar tahun 1607, telah terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran dari Inggris ke Amerika Utara. Pelaut Inggris yang terkenal adalah Sir Francis Drake (1577-1580)
3. Bangsa Belanda
Pelaut Belanda, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mengikuti jejak pelaut Eropa lainnya dalam menelusuri daerah-daerah sepanjang pantai barat Afrika dan Asia Selatan, serta berhasil mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Berdirinya VOC pada tahun 1602.
4. Bangsa Perancis
Beberapa alasan penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa adalah sebagai berikut.
a. Mencari daerah penghasil rempah-rempah secara langsung.
b. Mencari harta, serta mencari emas dan perak (gold).
c. Menyebarkan agama Nasrani (gospel).
d. Mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan.
Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
Bentuk praktik Kolonialisme dan Imperialisme seperti menguasai perdagangan secara tunggal (monopoli) dan merampas atau menjelajah suatu negeri.
1. Bangsa Portugis Menjajah Indonesia
Pada tahun 1512, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Fransisco Serrao mulai berlayar menuju Kepulauan Maluku. Bahkan pada tahun 1521, Antonio de Brito diberi kesempatan untuk mendirikan kantor dagang dan beneng Santo Paolo di Ternate sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Orang-orang Portugis yang semula dianggap sebagai sahabat rakyat ternate berubah menjadi pemeras dan musuh.
2. Bangsa Spanyol Menjelajah Indonesia
Pelaut Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 setelah terlebih dahulu singgah di Filipina disambut baik oleh rakyat Tidore. Bangsa Spanyol dimanfaatkan oleh rakyat Tidore untuk bersekutu dalam melawan rakyat Ternate. Maka pada tahun 1534, diterbitkan perjanjian Saragosa (tahun 1534) yang isinya antara lain pernyataan bahwa bangsa Spanyol memperoleh wilayah perdagangan di Filipina sedangkan bangsa Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku.
3. Bangsa Belanda Menjajah Indonesia
Proses penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia memakan waktu yang sangat lama, yaitu mulai dari tahun 1602 sampai tahun 1942. Penjelajahan bangsa Belanda di Indonesia, diawali oleh berdirinya persekutuan dagang Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indische Campagnie (VOC).
a. Masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)
Penjelajahan Belanda, Cornelisde Houtman, mendarat kali pertama di Indonesia pada tahun 1596. Pada tahun 1598, bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kali kedua dan dipimpin oleh Jacob Van Neck. Upaya Inggris untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin kuat diantara sesame pendatang dengan mendirikan dan menyaingi persekutuan dagang Inggris di India dengan nama East India Company (EIC). Pada tahun 1619, kedudukan VOC dipindahkan ke Batavia (sekarang Jakarta) dan diperintah oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen ditujukan untuk merebut daerah dan memperkuat diri dalam persaingan dengan persekutuan dagang milik Inggris (EIC) yang sedang konflik dengan Wijayakrama (penguasa Jayakarta) disebut sebagai “zaman kompeni”. VOC memperoleh piagam (charter), secara umum, menyatakan bahwa VOC diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan. Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan tidak dapat melaksanakan tugas dari pemerintah Belanda. Factor penyebab kemunduran VOC adalah sebagai berikut :
1) Banyaknya jumlah pegawai VOC yang korupsi.
2) Rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan.
3) Berlangsungnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah di Indonesia.
Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan pemerintah Belanda (saat itu republic Bataaf) mencabut hak-hak VOC. Pada tahun 1806, terjadi perubahan politik di Eropa hingga republic Bataaf dibubarkan dan berdirilah Kerajaan Belanda yang diperintah oleh Raja Louis Napoleon.
b. Masa Deandels (1808-1811)
Belanda pada saat itu, mengangkat Herman Willem Daendels (1808) sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Daendels dikenal sebagai penguasa yang disiplin dank eras sehingga mendapatkan sebutan “Marsekal Besi” atau “jenderal Guntur”. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels
1) Melakukan pembangunan fisik
(a) Membangun pabrik senjata.
(b) Membangun benteng pertahanan.
(c) Menarik penduduk pribumi untuk menjadi tentara.
(d) Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon.
(e) Membangun jalan raya dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur) sepanjang 1.000 km, yang kemudian terkenal dengan sebutan “Jalan Raya Daendels”.
2) Melakukan pembangunan ekonomi
(a) Memungut pajak hasil bumi dari rakyat (contingenten).
(b) Menjual tanah negara kepada pihak swasta asing.
(c) Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi (Preanger Stelsel).
(d) Mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil panennya kepada Belanda dengan harga murah (verplichte leverentie).
Akhirnya, pada tahun 1811, Herman Willem Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens.
c. Masa Janssens
Tugas sebagai Gubernur Jenderal, Janssens ternyata tidak secakap Daendels (baik dalam memerintah maupun dalam mempertahankan wilayah Indonesia). Janssens ternyata tidak siap untuk mengimbangi kekuatan dan serangan Inggris, sehingga Janssens menyerah pada 18 September 1811 dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian di Tuntang (Salatiga).
4. Bangsa Inggris Menjajah Indonesia (1811-1816)
Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (TSR) sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik di bidang ekonomi, social, dan budaya. Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia.
1. Masa Sistem Tanam Paksa
Pemerintah Belanda untuk menutup kekosongan kas keuangan negara, satu di antaranya adlah dengan menerapkan aturan tanam Paksa (Cultuurstelsel). Tanam paksa berasal dari bahasa Belanda yaitu Cultuurstelsel (system penanaman atau aturan tanam paksa). Aturan tanam paksa di Indonesia adalah Johannes Van Den Bosch
a. Isi Aturan Tanam Paksa
1) Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
2) Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
3) Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau dipabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
4) Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan
5) Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
6) Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
7) Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa
b. Pelaksanaan Aturan Tanam Paksa
Tanam paksa sudah dimulai pada tahun 1830 dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun 1850
Pada tahun 1860, menanam lada dihapuskan. Pada tahun 1865 dihapuskan untuk menanam nila dan the. Tahun 1870, hampir semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman kopi. Pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan didaerah Prianganjuga dihapuskan.
c. Dampak Aturan Tanam Paksa
d. Reaksi terhadap Pelaksanaan Aturan Tanam Paksa
Antara tahun 1850-1860, terjadi perdebatan. Kelompok yang menyetujui terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah dan pemegang saham perusahaan Netherlandsche handel maatsschappij (NHM). Pihak yang menentang terdiri atas kelompok dari kalangan agama dan rohaniawan
Pada tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda (Indonesia) mulai memasuki zaman liberal hingga tahun 1900.
2. Masa Liberalisme
Politik Pintu Terbuka di Indonesia berlangsung antara tahun 1870 hingga tahun 1900, periode ini disebut sebagai zaman berpaham kebebasan (liberalisme). Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan seperti Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) dan Undang-undang Gula (Suiker Wet)
a. Undang-undang Agararia (Agrarische Wet)
Undang Agraria berisi pernyataan bahwa semua tanah yang terdapat di Indonesia adalah milik pemerintah Hindia Belanda
b. Undang-Undang Gula (Suiker wet)
Undang-undang gula berisi pernyataan bahwa hasil tanaman tebu tidak boleh diangkut ke luar wilayah Indonesiadan hasil panen tanaman tebu harus di proses di pabrik-pabrik gula dalam negeri
Pada akhir abad ke-19, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin maju, termasuk kemajuan dibidang kesehatan.
F. Pengaruh Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Berbagai Daerah di Indonesia.
Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtmen pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang.
1. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis
Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dank e Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang.
a. Perlawanan Rakyat Malaka terhadap Portugis
Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuqauerque menyerang Kerajaan Malaka. Untuk menyerang colonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Falatehan dapat menguasai Banten,Suda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta (Jakarta)
b. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis
Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1629.
c. Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis
Bangsa Portugis kali pertama mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi, Tertnate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah.
Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam Benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor
2. Perlawanan Rakyat terhadap Belanda (VOC)
Persekutuan dagang Hindia Timur milik pemerintah Belanda di Indonesia adalah Vereenigde oost Indische Compagnie (VOC) yang berdiri tahun 1602.
a. Perlawanan Rakyat Mataram
1) Perlawanan Rakyat Mataram Pertama
Dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso.
2) Perlawanan Rakyat Mataram Ke dua
Dilaksanakan tahun 1629 dan dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia, dilanjutkan ke benteng Bommel tetapi belum berhasil.
3) Perlawanan Trunojoyo
Sultan Agung Hanyakrakusuma wafat pada tahun 1645, kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar Susuhunan Amangkurat I. tahun 1674 meletuslah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Trunojoyo, putra Bupati Madura. Trunojoyo mendapat dukungan dari para pengungsi Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong dan Montemarano mengakibatkan Amangkurat I terdesak dan melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda. Meninggal dunia di Tegalwangi (dekat kota Tegal). 1677, putra mahkota naik tahta sebagai raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Perjanjian kepada Belanda berupa Bandar di Semarang, hak perdagangan yang luas, seluruh daerah di Jawa Barat, disebelah selatan Batavia, dan pembayaran semua ongkos perang dengan jaminan beberapa Bandar di pantai utara pulau Jawa. Setelah Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukum mati (tahun 1679), Kerajaan Mataram selalu mendapat pengaruh dari pemerintah Hindia Belanda.
4) Perlawanan Untung Suropati
Untung Suropati adalah putra Bali yang menjadi prajurit kompeni di Batavia antara tahun 1686 sampai 1706, Untung Suropati dan kawan-kawannya menyingkir ke Mataram dan bekerja sama dengan Sunan Mas atau Amangkurat III untuk melakukan perlawanan terhadap Kompeni Belanda (VOC) dan dinobatkan menjadi Adipati dengan gelar Aria Wiranegara. Kekuasaan Untung Suropati meliputi Blambangan, Pasuruan, Probolinggo, Bangil, Malang, dan Kediri. 1705, Kompeni Belanda secara sepihak mengangkat pangeran Puger sebagai Sunan Pakubuwana I untuk menggantikan Amangkurat III atau Sunan Mas bergabung dengan Untung Suropati. 1706, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Untung Suropati gugur di Bangil dan Amangkurat III atau Sunan Mas tertangkap, diasingkan ke Sri Langka.
5) Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said
Tahun 1749, Pangeran Mangkubumi (adik dari Pakubuwana II) bekerjasama dengan Mas Said (Pangeran Samber Nyawa) melakukan perlawanan terhadap pakubuwana II dan VOC. 1749, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana dan membentuk pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana II dan Kompeni Belanda (VOC), mengalahkan pasukan kompeni. Pada tahun 1751, pasukan kompeni yang dipimpin Mayor De Clerx, dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (tahun 1755) dan Perjanjian Salatiga (tahun 1757).
b. Perlawanan Rakyat Banten
Perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa) dan putranya Pangeran Purbaya. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan. 1683, VOC menerapkan politik domba (devide et impera) antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sulatan Haji. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa menghasilkan kompensasi. 1750, terjadi perlawanan rakyat banten terhadap Sultan Haji.
c. Perlawanan Rakyat Makassar
Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin tahun 1654-1669. Abad ke-17 Makassar menjadi pesaing berat bagi Kompeni VOC pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Setelah mendapatkan berdagang, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Pertempuran antara rakyat Makassar dengan VOC terjadi. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654 diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan Makassar mengalami kegagalan. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666-1667, pasukan kompeni dibantu olehpasukan Raja Bone (Aru Palaka) dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Angakatan laut VOC, yang dipimpin oleh Spleeman. Pasukan Aru Palaka mendarat din Bonthain dan berhasil mendorog suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanudin. Penyerbuan ke Makassar dipertahankan oleh Sultan Hasanudin. Sultan Hasanudin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667.
Factor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC.
d. Perlawanan rakyat Maluku
Terjadi di Tidore
1) Perlawanan di Ternate
Pertama pada tahun 1635 yang dipimpin oleh Kakiali. 1646 kembali terjadi perlawanan rakyat Ternate terhadap VOC, yang dipimpin oleh Telukabesi. Pada tahun 1650, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Saidi mengalami kegagalan.
2) Perlawanan di Tidore
Tidore dipimpin oleh Kaicil Nuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda, mengusir Kolonial Inggris dari Tidore.
3) Perlawanan oleh Patimura
Bulan Mei 1817, meletus perlawanan rakyat Maluku di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Mattulessy atau Kapitan Pattimura. Benteng kompeni Duurstede di Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku. Meluas hingga ke Ambon dan ke pulau–pulau sekitarnya, dikuasai oleh Kapitan Pattimura, Anthony Rybok, Paulus-paulus Tiahahu, Martha Christina Tiahahu, Latumahina, Said Perintah dan Thomas Pattiwael, kewalahan perlawanan rakyat Pattimura pada tahun 1817 mendantangkan pasukan Kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh kapten Lisnet.
Oktober 1817, menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran, menangkap Kapitan Pattimura (tahun 1817) dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817.
3. Reaksi-reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Kolonialisme Belanda dalam Bentuk Perang Besar
a. Perang Padri (1821-1837)
Terjadi di Sumatera Barat atau di tanah Minangkabau. Perselisihan antara kaum Padri dengan kaum Adat yang kemudian mengundang campur tangan pihak Belanda.
Perang Padri pertama (tahun 1821-1825) dan perang Padri kedua (tahun 1830-1837)
1) Perang Padri Pertama
Di kota Lawas, berkembang ke daerah lainnya seperti Alahan Panjang. Kaum Padri dipimpi oleh Datok Bandaro bertempur melawan kaum Adat yang dipimpin oleh Datuk Jati. Setelah Datuk Bandaro meninggal dunia, pucuk pimpinan dipegang oleh Malim Basa (Tuanku Imam Bonjol) dan dibantu oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapuk. Tahun 1821, kaum Padri menyerbu pos Belanda di semawang dan mengacaukan kedudukan Belanda di daerah Lintau. Belanda membangun benteng nama Firt van der Capllen. Tahun 1822 didaerah Baso terjadi pertempuran antara Pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. 1823 terjadipertempuran lagi di Bonio dan Agam. Belanda dapat merebut benteng pertahanan kaum Padri. 1825, kedudukan Belanda mulai sulit karena harus berhadapan dengan kaum Padri dan juga harus menghadapi pasukan Diponegoro.
November 1825, Belanda dan Kaum Padri menandatangani perjanjian damai yang berisi tentang pengakuan Belanda atas beberapa daerah sebagai wilayah kaum Padri dan untuk sementara peperangan gelombang pertama berakhir.
2) Perang Padri Gelombang ke Dua
1829, di daerah pariaman. 1830, kaum Adat mulai banyak membantu kaum Padri dan kedua kaum tersebut menyadari bahwa perlunya kerja sama. Perang antara rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda.
1831, penyerangan terhadap belanda di daerah Muarapalam. 1832, dipimpin oleh Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Imam Bonjol melakukan penyerangan pos Belanda di Mangopo. 1833, terjadi pertempuran besar di daerah Agam. 1834 hingga tahun 1835, pemerintah Belanda mulai mengepung benteng Bonjol. Tahun 1837, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap benteng Bonjol. Pada tanggal 25 Oktkober 1837, benteng pertahanan Kota Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Minahasa hingga wafat dann dimakamkan di Pineleng.
b. Perang Diponegoro
Di lingkungan istana terdapat golongan yang memihak Belanda, banyak juga yang menentang Kolonial Belanda, seperti Pangeran Diponegoro (putra Sultan Hamengku Buwono III). Kecurigaan yang berlebihan ini pada akhirnya menimbulkan permusuhan dan peperangan yang disebut perang Diponegoro.
1) Penyebab Umum Perang Diponegoro
a. Semakin menderitanya rakyat akibat kerja rodi dan berbagai macam pajak
b. Semakin sempitnya wilayah Kerajaan Mataram akibat dikuasai Belanda.
c. Selalu ikut campurnya Belanda dalam urusan pemerintahan Kerajaan Mataram.
d. Masuknya budaya barat ke dalam keraton yang bertentangan dengan ajaran agama.
e. Kecewanya kaum bangsawan akan aturan Van der Capellen yang melarang usaha perkebunan swasta di wilayah Kerajaan Mataram.
f. Munculnya pejabat Kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi.
2) Penyebab Khusus Perang Diponegoro
Dipengaruhi oleh persoalan pribadi. Terjadi pada tahun 1825, tindakan sewenang-wenang Belanda yang telah memasang tonggak untuk membangun jalan raya yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Perang antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda dibantu oleh Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Kesultanan Yogyakarta.
Menggungakann strategi atau siasat perang gerilya, pusat pertahanan yang selalu berpindah-pindah seperti di Gua Selarong, Dekso, lereng Gunung Merapi, dan Bagelan(Purworejo). Terbukti bahwa pada tahun 1825 sampai 1826, pasukan diponegoro memperoleh kemenangan hingga dapat merebut daerah Pacitan, Purwodadi, dan Klaten.
Penggungaan sistem Benteng Stelsel oleh Belanda mempersulit pergerakan pasukan Diponegoro dan hubungan komunikasi antar pasukan. Pada tahun 1828, Kiai Mojo bersedia untuk diajak berunding oleh pihak Belanda namun gagal dan justru ia ditangkap dan diasingkan ke Minahasa sampai wafat pada tahun 1849. Jendral De Kock mengajak berunding Sentot Alibasa Prawirodirjo, Tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1829, Sentot Alibasa Prawirodirjo menyerah, ia dituduh memihak kaum Padri sehingga akhirnya ia diasingkan ke Cianjur dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu hingga wafat pada tahun 1855.
Pangeran Mangkubumi menyerah pada tahun 1829 dan putranya sendiri yang bernama Dipokusumo beserta patihnya menyerah pula pada tahun 1830. Jendral de kock ditanggapi positif oleh Pangeran Diponegoro dan disepakati bersama bahwa perundingan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1830 di kota Magelang. Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang dan Batavia kemudian diasingkan lagi ke Manado. Ia kembali dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 januari 1855
c. Perlawanan rakyat Aceh (1873-1904)
Aceh merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang kuat dan masih tetap bertahan hinga abad ke-19. berdasarkan Traktat London tahun 1824 bangsa Inggris dan Belanda yang sudah pernah berkuasa di Indonesia harus saling sepakat untuk menghormati keberadaan kerajaan Aceh.
Berdasarkan Perjanjian (Taktat) Sumatera tahun 1871 atau yang lebih dikenal dengan Traktat London ke-3, pihak Inggris melepas tuntutannya terhadap daerah Aceh. Kerajaan Aceh berusaha mencari bantuan ke Turki serta menghubungi Kedutaan Italia dan Kedutaan Amerika Serikat di Singapura. Sementara bantuan dari Turki belum datang, pada bulan Maret 1873, perangnya ke Kutaraja atau Banda Aceh di bawah pimpinan Jendral Kohler, berusaha merebut dan menduduki ibu kota dan Istana Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berhasil, tetapi dalam pertempuran tersebut Jendral Kohler tewas tertembak. Mengawali terjadinya perang Aceh yang berkepanjangan mulai tahun 1873 sampai 1904. pasukan Belanda melaksanakan operasi Konsentrasi Stelsel sambil menggertak para pemimpin Aceh agar menyerah. Beberapa pimpinan utama Aceh seperti Teuku Cik Di Tiro, Cut Nya’ Din, Panglima Polim, dan Cut Meutia (bersama-sama dengan rakyat Aceh) untuk melancarkan serangan umum.
Pada bulan Desember 1873, Belanda mengirim pasukan perang ke Aceh dengan kekuatan 8.000 personil dibawah pimpinan Mayor Jendral Van Swiesten. Akan tetapi upaya Belanda untuk menawan Sultan Mahmud Syah belum berhasil karena Sultan beserta para pejabat kerajaan telah menyingkir ke Luengbata. Setelah Sultan Mahmud Syah meninggal karena sakit, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Daudsyah.
Setelah Teuku Cik Di Tiro sebagai pemimpin utama Aceh Wafat. Pucuk pimpinan dilanjutkan oleh Teuku Umar dan Panglima Polim. Pada tahun 1893, Teuku Umar beserta pasukannya memanfatkan kelengahan Belanda dengan tujuan mendapatkan senjata. Disambut baik dan mendapat gelar Teuku Johan pahlawan. Pada tahun 1896, Teuku Umar bergabung kembali dengan rakyat Aceh dengan membangun markas pertahanan Meulaboh.
Peristiwa Teuku Umar yang berhasil menyiasati Belanda dipandang sebagai kesalahan besar Deykerhoff sebagai gubernur militer. Digantikan oleh Jendral Van Heutsz. Belanda memeberi tugas kepada Dr. Snock Hurgronje untuk menyelidiki perilaku masyarakat Aceh. Dr. Snock Hurgronje dalam menjalankan tugasnya menggunakan nama smaran, yaitu Abdul gafar.
Untuk mengalahkan Aceh, lebih cepat dan tepat, Belanda menggunakan Strategi sebagai berikut :
1. menghancurkan dan menangkap seluruh pemimpin dan ulama dari pusat
2. membentuk pasukan gerak cepat (marschose marechausse)
3. semua pemimpin dan ulama yang tertangkap harus menandatangani perjanjian
4. setelah melakukan operasi militer, Belanda mengikuti kegiatan perdamaian rehabilitasi (pasifikasi)
5. bersikap lunak terhadap para bangsawan.
Atas usulan Dr. Snock Hurgronje, pemerintah Belanda memberi tugas kepda Jendral militer Van Heutsz. Pada tahun 1899, pasukan gerak cepat pimpinanVan Heutsz, is gugur pada tahun 1899. dilanjutkan oleh istrinya Cut Nya’ Din, tetapi kemudian tertangkap dan diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya.
Belanda menyandera keluarga raja dan keluarga Panglima Polim. Perlawanan Aceh berikutnya dilanjutkan oleh Cut Meutia, tetapi perlawanan ini dapat dipadamkan dan pada tahun 1904 perang Aceh dinyatakan berakhir.
d. Perlawanan rakyat Bali
Keinginan Belanda untuk menguasai Bali dimualai sejak tahun 1841 dan seluruh raja di Bali dipaksa menandatangani perjanjian yang isinya agar raja di Bali mengakui dan tunduk kepada pemerintah Belanda.
Keinginan Belanda untuk menguasai Bali selalu tidak berhasil karena Bali masih bersifat konservatif (masih berlaku adat/ tradisi). Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di pantai Buileleng dan dikenakan hukum tawan karang, yaitu selalu turut campur urusan kerajaan di Bali dengan mengajukan tuntutan dengan isi sebagai berikut.
1) Membebaskan Belanda dari hukum Tawan Karang.
2) Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda.
3) Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda.
4) Semua raja di bali harus tunduk terhadap semua perintah colonial Belanda.
5) Sehingga pada tahun 1846 Belanda menyerang wilayah Bali Utara dan memaksa
Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian
1) Benteng Kerajaan Buleleng agar dibongkar.
2) Pasukan Belanda ditempatkan di Buleleng.
3) Biaya perang harus ditanggung oleh Raja Buleleng.
Pada tahun 1848, raja-raja di Bali tidak lagi mematuhi kehendak Belanda. Pos-pos pertahanan Belanda di Bali diserbu dan semua senjata dirampas oleh gusti Jelantik. Pada tahun 1849, pasukan belanda datang dari Batavia untuk menyerbu dan menguasai seluruh pantai Buleleng dan menyerbu benteng Jagaraga. Sejak runtuhnya Kerajaan Buleleng, perjuangan rakyat Bali mulai lemah. Meskipun demikian, Kerajaan Karangasem dan Klungkung masih berusaha melakukan perlawanan terhadap Belanda.
e. Perlawanan Rakyat Palembang (1819-1825)
Sultan Badaruddin dahulu pernah menjadi Sultan Palembang dan kemudian diturunkan secara paksa oleh pemerintah Inggris ketika masih berkuasa di Indonesia yaitu digantikan oleh Sultan Najamuddin. Tahun 1819 Sultan Badaruddin selalu menghalangi setiap kapal Belanda yang memasuki sungai Musi. Pada tahun 1821, Belanda dapat menguasai ibukota Palembang dan menangkap Sultan Badaruddin. Sultan Badaruddin diasingkan ke Ternate. Perlawanan rakyat Palembang sering terjadi pada tahun 1825.
f. Perlawanan Rakyat Banjar (1859-1863)
Yang menjadi daya tarik Belanda untuk menguasai Kalimantan Selatan yang saat itu diperintah oleh Sultan Hidayat. Untuk menguasai Banjarmasin adalah dengan melakukan operasi militer pada tahun 1859. Dalam pertempuran itu, Sultan Hidayat tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Upaya Belanda untuk menguasai Banjamasin mengalami kesulitan rakyat berupa untuk mempertahankan wilayahnya dan setiap kapal Belanda yang memasuki pedalaman Banjarmasin (melalui Sungai Barito) akan dibakar oleh rakyat setempat. Pada tahun 1863, pasukan Belanda melancarkan serangan bertubi-tubi ke seluruh wilayah Banjarmasin, sehingga Pangeran Antasari gugur.
g. Perlawanan Rakyat Tapanuli (1878-1907)
Sekitar tahun 1873, bangsa Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli Utara dengan alas an memadamkan aktivitas pejuang-pejuang Padri dan para pemimpin dari Aceh. Pada tahun 1878, Belanda mulai melancarkan gerakan militernya untuk menyerang daerah Tapanuli, sampai pada akhirnya meletuslah Perang Tapanuli. Perang Tapanuli yang diawali dengan operasi militer yang dilakukan oleh Jenderal Van Daalen di pedalaman Aceh tahun 1903-1904. Serdadu Belanda yang mulai berdatangan di daerah di Sumatera Utara dibendung oleh rakyat Tapanuli yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII.
4. Gerakan Sosial
a. Gerakan Protes Petani
Beberapa contoh gerakan protes yang terjadi di berbagai daerah,
1) Pemberontakan di Ciomas, lereng Gunung Salak, Jawa Barat (tahun 1886) pimpinan Arfan dan Muhammad Idris.
2) Pemberontakan di Condet, Jakarta (tahun 1913) pimpinan Entong Gendut, Maliki, dan Modern.
3) Pemberontakan di Surabaya (tahun 11916) pimpinan Sadikin.
4) Pemberontakan di Tangerang (tahun 1924) pimpinan Kaiin.
b. Gerakan Ratu Adil
Ketika Kerajaan Kediri di Jawa Timur mengalami zaman kejayaan (1135-1157), pada masa Raja Jayabaya terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dikumpulkan dalam suatu kitab berjudul Jongko Jangka Jayabaya. Gerakan ratu adil ini terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
c. Gerakan Keagamaan
Perilaku bangsa Eropa bertentangan dengan agama islam serta kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar penduduk pribumi sebagai berikut.
1) Monopoli perdagangan
2) Perbudakan atau kerja rodi.
3) Penjelajahan atau merampas negeri.
4) Praktik aturan tanam dan penyimpangannya.
5) Pemerasan atau penarikan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan rakyat.
6) Mabuk karena minuman keras dan gaya hidup mewah di atas penderitaan orang lain.
5. Penyebaran Agama Protestan dan Katolik Pada Masa Kolonial
Masuk dan berkembangnya agama Katolik dan Protestan di Indonesia sudah mulai sejak abad ke-16. Penyebaran agama dilakukan oleh para petugas yang disebut missie atau misionaris, sedangkan penyebaran agama Kristen di Indonesia banyak dilakukan para petugas gereja yang disebut zending.
a. Misionaris Portugis di Indonesia
Salah satu tujuan yang dilakukan para penjelajahan samudera adalah menyebarkan agama nasrani (gospel). Misionaris Portugis yang dikenal adalah Pater Fransiscus Xaverius dan Matteo Ricci. Fransiscus Xaverius adalah seorang misionaris yang mendarat di Maluku dan menyebarkan agama Katolik antara bulan Juni 1546 sampai April 1547.
b. Zending Belanda di Indonesia
Pada zaman Belanda, para petugas/penyebar agama Kristen (zending) menyebarkan agama Protestan di Indonesia. Sebagai bentuk pengabdian social, para zending membangun sekolah-sekolah keagamaan dan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Yang berjasa menyebarkan agama Protestan antara lain Ludwig ingwer Nommensen, Sebastian Danckaarts, Andrian Hulseb, dan Hernius menyebarkan agama Protestan di daerah Maluku, Sangir Talaud, Timor, Tapanuli, sebagian di Pulau Jawa, serta di Tapanuli (Sumatera Utara) pada tahun 1861.
6. Penyebaran Agama Islam Pada Masa Kolonial
Sejak Kerajaan Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511, para pedagang Islam yang berasal dari Gujarat dan Persia mengubah haluan dari jalur perdagangan yang semula melalui Selat Malaka berubah menjadi Selat Sunda.