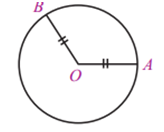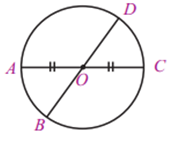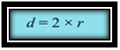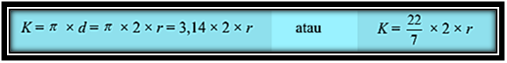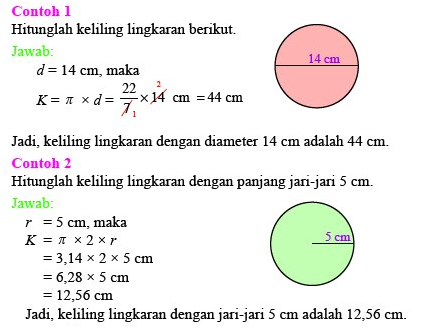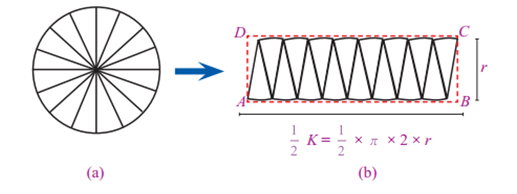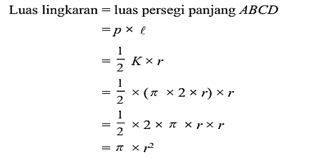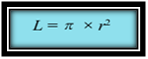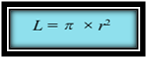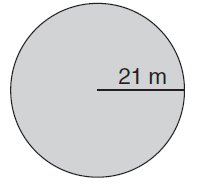Variasi Mengajar
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Harapan yang selalu dituntut guru adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan ini bukan hanya dikarenakan anak didik merupakan makhluk individu dengan segala keunikan, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan.
Ada tiga aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan yang lain, yaitu aspek intelektual, psikologi, dan biologis. Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal ini menjadi tugas yang cukup berat bagi guru dalam pengelolaan kelas. Akibat kegagalan guru dalam mengelola kelas, tujuan pengajaran akan sukar dicapai.
Tujuan pembelajaran dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti dengan pengelolaan kelas yang baik,. Tetapi pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan, ini disebabkan pada kondisi tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki dengan tiba-tiba. Suatu gangguan yang datang dengan tiba-tiba dan diluar kemampuan guru adalah kendala spontanitas dalam pengelolaan kelas akibatnya suasana akan terganggu dan konsentrasi anak didikpun akan pecah.
Masalah lain yang sering digunakan guru adalah masalah pendekatan, karena dapat mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar. Karena dapat mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar, maka guru tidak sembarangan memilih dan menggunakannya. Maka penting untuk mengenal suatu bahan untuk kepentingan pemilihan pendekatan.
Media sumber belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar. Kesulitan anak didik memahami konsep dan prinsip-prinsip tertentu dapat diatasi dengan bantuan alat bantu. Bahkan alat bantu diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik dari anak didik.
Dalam hal ini guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar siswa. Karena semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai.
Pengembangan variasi pengajaran salah satunya adalah memanfaatkan variasi alat bantu, dalam hal ini variasi media pandang, variasi media dengar, maupun variasi media taktil. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevensi KBM, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, dan mendorong anak didik untuk belajar.
Dalam proses belajar mengajar bila ada variasi guru dapat menunjukkan adanya perubahan dalam gaya mengajar, media yang digunakan berganti-ganti, dan ada perubahan dalam pola interaksi antara guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa. Variasi lebih bersifat proses daripada produk.
Tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standart keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan. Dalam mengajar, sering ditemukan mengkombinasikan beberapa macam metode. Penggabungan metode ini dimaksudkan untuk menggairahkan belajar anak didik. Dengan bergairahnya belajar, maka anak didik tidak akan merasa sukar dalam mencapai tujuan pengajaran. Guru yang telah berhasil dalam mengajar jika tercapai tujuan pembelajarannya. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat diketahui setelah diadakannya evaluasi.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:
- Aspek apa saja yang termasuk dalam pengembangan variasi mengajar?
- Apa saja aspek yang termasuk dalam keberhasilan belajar mengajar?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan aspek-aspek yang termasuk dalam pengembangan variasi mengajar.
2. Menjelaskan aspek-aspek yang termasuk dalam keberhasilan belajar mengajar.
Bab II. Pembahasan
A. Pengembangan Variasi Mengajar
1. Tujuan Variasi Mengajar
Penggunaan variasi terutama ditujukan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Tujuan mengadakan variasi mengajar yaitu:
a. Meningkatkan dan Memelihara Perhatian Siswa Terhadap Relevansi Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar perhatian dari siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan sangat dituntut. Sedikitpun tidak diharapkan adanya siswa yang tidak atau kurang memperhatikan penjelasan guru, karena itu akan menyebabkan tidak memahami pelajaran dari guru.
Faktor yang mempengaruhi siswa sukar mempertahankan perhatian terhadap materi yang diberikan guru adalah penjelasan guru yang kurang mengenai sasaran, situasi luar kelas yang dirasakan siswa lebih menarik daripada pelajaran yang disampaikan, siswa yang kurang menyenangi materi pelajaran.
Perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Karena itu, guru selalu memperhatikan variasi mengajarnya, apakah sudah dapat meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap materi yang dijelaskan atau belum.
Perhatian siswa dalam pelajaran yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran amat penting karena mempengaruhi keberhasilan tujuan belajar mengajar yang ditunjukan oleh penguasaan materi pelajaran pada setiap siswa. Indikator penguasaan siswa terhadap materi pelajaran adalah terjadinya perubahan di dalam diri siswa.
b. Memberikan Kesempatan Kemungkinan Berfungsinya Motivasi
Siswa tidak akan belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada dorongan kuat yang menggerakan siswa tersebut, dorongan tersebut disebut motivasi. Oleh sebab itu motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Motivasi setiap siswa berbeda terhadap suatu bahan pelajaran, oleh karena itu seorang guru selalu ingin memberikan motivasi terhadap siswa yang kurang memberikan perhatian terhadap materi pelajaran yang diberikan. Motivasi dapat dibedakan berdasarkan timbulnya yaitu:
- Motivasi Intrinsik, motivaasi yang timbul dari diri sendiri.
- Motivasi Ekstrinsi yaitu motivasi yang timbul akibat dorongan dari pihak luar dirinya.
Bagi siswa yang selalu memperhatikan pelajaran yang diberikan, bukanlah menjadi masalah bagi seorang guru karena siswa tersebut sudah mempunyai motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Siswa yang demikian biasanya dengan kesadarannya sendiri memperhatikan penjelasan guru.
Berbeda dengan siswa yang tidak mempunyai atau kurang motivasi dalam dirinya, maka motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. Di sini peran seorang guru lebih dituntut untuk menjadi motivator, yaitu sebagai alat yang mendorong siswa untuk berbuat, sebagai alat yang menentukan arah perbuatan, dan sebagai alat untuk menyeleksi perbuatan.
c. Membentuk Sikap Positif Terhadap Guru dan Sekolah
Tanggapan siswa kepada gurunya bermacam-macam, masalah akan muncul apabila ada siswa tertentu yang kurang senang terhadap gurunya , yang mengakibatkan bidang pelajaran yang dipegang oleh guru tersebut menjadi tidak disenangi.
Ketidaksukaan siswa terhadap guru tersebut mungkin terjadi karena:
- Guru tersebut kurang bervariasi dalam mengajar
- Gaya mengajar guru tidak sejalan dengan gaya belajar siswa
- Guru kurang dapat menguasai keadaan kelas
- Guru gagal menciptakan suasana belajar yang membangkitkan kreatifitas dan kegairahan belajar siswa
Hal ini kurang menguntungkan guru. Oleh sebab itu jadilah guru yang bijaksana yaitu guru yang pandai menempatkan diri dan pandai mengambil hati siswa dengan cara mempunyai gaya mengajar dan pendekatan yang sesuai dengan psikologis siswa misalnya disela-sela pelajaran diselingi humor dengan pendekatan edukatif.
d. Memberikan Kemungkian Pilihan dan Fasilitas Belajar Individual
Seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai ketrampilan yang mendukung dalam proses beajar mengajar. Penguasaan metode pelajaran yang dituntut kepada guru tidak hanya satu atau dua metode , tetapi lebih banyak lagi. Selain itu, seorang guru harus menguasai tiga keterampilan meliputi:
1) Metode
2) Media
3) Pendekatan
Sebagai seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai ketrampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Penguasaan metode mengajar yang dituntut kepada guru tidak hanya satu atau dua metode, tetapi lebih banyak dari itu. Penguasaan terhadap bagaimana menggunakan media merupakan ketrampilan lain yang juga harus dikuasai oleh guru. Demikian juga penguasaan terhadap berbagai pendekatan dalam mengajar dikelas. Penguasaan ketiga ketrampilan tersebut memudahkan bagi guru melakukan pengembangan variasi mengajar.
Fasilitas merupakan kelengkapan yang diperlukan disekolah. Fasilitas dapat berfungsi sebagai:
1) Sebagai alat bantu pengajaran
2) Sebagai alat peraga
3) Sebagai sumber belajar
Kelengkapan fasilitas belajar tersebut mempengaruhi guru dalam pemilihan metode pengajaran.
e. Mendorong anak didik untuk belajar
Menyediakan lingkungan belajar adalah tugas guru. Kewajiban belajar adalah tugas anak didik. Kedua kegiatan tersebut menyatu dalam sebuah interaksi pengajaran yang disebut interaksi edukatif. Lingkungan pengajaran yang kondusif adalah lingkungan yang mampu mendorong anak didik selalu belajar hingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Belajar memerlukan motivasi sebagai pendorong bagi anak didik adalah motivasi intrinsik yang lahir dari kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan.
Anak didik yang kurang senang menerima pelajaran tidak harus terjadi, karena hal itu sangat menghambat proses belajar mengajar, oleh sebab iu guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong anak didik untuk senang dan bergairah belajar. Untuk hal ini, cara akurat yang seharusnya dilakukan guru adalah mengembangkan variasi belajar, baik dalam gaya mengajar, dalam penggunaan media dan bahan pelajaran
2. Prinsip Penggunaan
Lingkungan yang kondusif dan menyenangkan dalam suasana belajar sangat diperlukan agar dapat menggariahkan belajar siswa dan merangsang siswa menjadi aktif. Salah satu upaya dari hal tersebut adalah dengan memperhatikan beberapa prinsip penggunaan variasi dalam mengajar.
Prinsip–prinsip penggunaan variasi mengajar adalah sebagai berikut:
a. Dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua variasi digunakan, selain juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk setiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar.
b. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan , sehingga saat proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu.
c. Penggunaan komponen variasi harus benar – benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Karena itu memerlukan penggunaan yang luwes , spontan , sesuai dengan umpan balik yang diterima oleh siswa.
Bentuk umpan balik ada dua yaitu :
1) Umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa.
2) Umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajar.
3. Komponen-komponen Variasi Mengajar
Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa komponen-komponen variasi mengajar itu dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu variasi gaya mengajar, variasi media dan bahan, serta variasi interaksi. Uraian yang mendalam dari ketiga komponen tersebut adalah berikut ini:
a. Variasi Gaya Mengajar
Dalam mengajar hendaknya menggunakan berbagai macam variasi gaya. Dengan variasi gaya tersebut, akan menjadikan siswa merasa tertarik terhadap penampilan mengajar guru. Variasi gaya mengajar guru ini meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
1) Variasi Suara
Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat. Suara guru pada saat menjelaskan materi pelajaran hendaknya bervariasi, baik dalam intonasi, volume, nada dan kecepatan. Jika suara guru senantiasa keras terus atau terlalu keras, justru akan sulit diterima, karena siswa menganggap gurunya seorang yang kejam, bila sudah begitu siswa diliputi oleh rasa cemas, ketakutan selama belajar. Masalah seperti ini yang harus dihindari bahkan ditiadakan. Tapi kalau suara guru terlalu lemah (biasanya guru wanita) akan terdengar tidak jelas oleh siswa dan tidak bisa menjangkau seluruh siswa di kelas, apalagi yang duduknya dideretan belakang.
Bila sudah begitu siswa akan meremehkan gurunya, perhatian siswa terhadap materi yang diberikan itupun kurang. Untuk itu guru menggunakan variasi suara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi suara guru senantiasa berganti-ganti, kadang meninggi, kadang cepat, kadang lambat, kadang rendah (pelan). Variasi suara bisa mempengaruhi informasi yang sangat biasa sekalipun, gunakanlah bisikan atau tekanan suara untuk hal-hal penting, gunakan kalimat pendek yang cepat untuk menimbulkan semangat.
2) Pemusatan Perhatian
Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang diajarinya, jika materi yang disampaikan oleh guru iru tidak menjadi perhatian siswa, maka bisa menimbulkan kebosanan, sehingga tidak lagi suka belajar. Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan bentuk kata-kata. Misalnya : “Perhatikan baik-baik”, “Jangan lupa ini dicatat dengan sungguh-sungguh” dan sebagainya.
Memang menarik perhatian siswa itu sangatlah tidak mudah apalagi dalam jumlah siswa yang banyak, agar perhatian itu tetap ada perlu adanya prinsip-prinsip yakni :
a) Perhatian seseorang tertuju atau diarahkan pada hal-hal yang baru, jenis rangsangan baru yang dapat menarik perhatian termasuk warna dan bentuk. Dalam pelajaran, seorang guru dapat menarik perhatian tentang kata-kata penting pada suatu bacaan dengan memberi warna merah atau digaris bawahi.
b) Perhatian seseorang tertuju atau terarah pada hal-hal yang dianggap rumit. Bagi guru yang harus diingat adalah suatu pelajaran tidak boleh tampak terlalu rumit dan guru tidak boleh mempersulit pelajaran yang sederhana dikarenakan semata-mata untuk menarik perhatian siswa.
c) Orang mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang dikehendakinya, yaitu hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk menimbulkan minat tersebut ada dua cara yakni dari diri sendiri dan dari luar dirinya. Dari luar bisa saja lingkungan, orang tua dan guru. Disini gurulah yang berhak menimbulkan atau membangkitkan minat belajar siswa baik dirumah maupun dikelas.
Dari ketiga prinsip ini guru harus mengetahui banyak tentang siswanya agar bisa mengarahkan perhatian siswa terhadap materi pelajaran, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi guru dalam memusatkan perhatian siswa bisa dengan memberikan kata-kata seperti : “coba perhatikan ini baik-baik”, karena materinya agak sulit dan sebagainya.
3) Kesenyapan atau Kebisuan Guru (Teaching Silence)
Kesenyapan adalah suatu keadaan diam secara tiba-tiba demi pihak guru ditengah-tengah menerangkan sesuatu. Adanya kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Dengan keadaan senyap atau diamnya guru secara tiba-tiba bisa menimbulkan perhatian siswa, sebab siswa begitu tahu apa yang terjadi dan demikian pula setelah guru memberikan pertanyaan kepada siswa alangkah bagusnya apabila diberi waktu untuk berfikir dengan memberi kesenyapan supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin ia hafal, sehingga bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik dan tepat.
Pemberian waktu bagi siswa digunakan untuk mengorganisasi jawabannya agar menjadi lengkap. Tapi jika seorang guru tidak memberikan kesenyapan atau waktu kepada siswa untuk berfikir dalam menjawab pertanyaannya siswa akan menjawab dengan asal alias asal bicara, sehingga jawabannya kurang tepat dengan pertanyaan. Untuk itu seyogyanya guru memberikan kesenyapan terhadap siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya supaya jawabannya sempurna dan tepat.
4) Kontak Pandang
Ketika proses belajar mengajar berlangsung, jangan sampai guru menunduk terus atau melihat langit-langit dan tidak berani mengadakan kontak mata dengan para siswanya dan jangan sampai pula guru hanya mengadakan kontak pandang dengan satu siswa secara terus menerus tanpa memperhatikan siswa yang lain. sebaliknya bila guru berbicara atau menerangkan hendaknya mengarahkan pandangannya keseluruh kelas atau siswa, sebab menatap atau memandang mata setiap anak disik atau siswa bisa membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Bertemunya pandang diantara mereka yang berinteraksi, sesungguhnya merupakan suatu etika atau sopan santun pergaulan karena menunjukkan saling perhatian diantara mereka.
Hal-hal yang harus dihindari guru selama presentasinya didepan kelas :
a) Melihat keluar ruang
b) Melihat kearah langit-langit
c) Melihat kearah lantai
d) Melihat hanya pada siswa tertentu atas kelompok siswa saja
e) Melihat dan menghadap kepapan tulis saat menjelaskan kecuali sambil menunjukkan sesuatu.
Hal-hal di atas bertujuan supaya bisa mengendalikan situasi kelas dengan baik. Untuk itu, pandanglah siswa-siswa anda secara merata tapi jangan berlebihan, gunanya pandangan mata, seorang guru adalah untuk menarik perhatian dan minat belajar siswa.
5) Perpindahan Posisi Guru
Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam menarik perhatian anak didik, dapat pula meningkatkan kepribadian guru dan hendaklah selalu diingat oleh guru, bahwa perpindahan posisi itu jangan dilakukan secara berlebihan. Bila dilakukan berlebihan guru akan kelihatan terburu-buru, lakukan saja secara wajar agar siswa bias memperhatikan. Perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka ke bagian belakang, dari sisi kiri ke sisi kanan, atau diantara anak didik dari belakang kesamping anak didik. Dapat juga dilakukan dengan posisi berdiri kemudian berubah menjadi posisi duduk dan diam di tempat lalu berjalan-jalan mengelilingi siswa dan sebagainya. Yang penting dalam perubahan posisi itu harus ada tujuannya, dan tidak sekedar mondar-mandir dan seorang guru janganlah melakukan kegiatan mengajar dengan satu posisi, misalnya saja saat menerangkan guru hanya berdiri didepan kelas saja atau duduk dikursi saja, tanpa ada pergantian atau variasi ini bisa menimbulkan kebosanan siswa.
b. Variasi Media dan Bahan ajaran
Tiap anak didik mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih enak dan senang membaca, ada yang lebih senang mendengarkan dulu baru membaca, dan sebaliknya. Misalnya, guru dapat memulai dengan berbicara lebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis, di lanjutkan dengan melihat contoh konkret. Ada tiga komponen dalam variasi penggunaan media, yaitu media pandangan, media dengar, dan media taktil.
1) Variasi media pandang
Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi seprti buku, majalah, globe, peta, majalah dinding, film, film strip, gambar grafik, model, demonstrasi, dan lain lain. Penggunaan yang lebih luas dari alat-alat tersebut akan memiliki keuntungan :
a) Membantu secara konkret konsep berpikir, dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat.
b) Dapat membuat hasil belajar yang riil yang akan mendorong kegiatan mandiri anak didik.
c) Mengembangkan cara berpikir berkesinambungan, seperti halnya dalam film.
d) Memberi pengalaman yang tidak mudah dicapai oleh alat lain.
e) Memberi frekuesi kerja lebih dalam dan variasi belajar.
2) Varasi media dengar
Pada umumnya dalam proses belajar mengajar dikelas suara guru adalah alat utama dalam komunikasi, dan ini pernah di singgung. Variasi dalam penggunaan media dengar memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan media pandangan. Yang dapat dipakai untuk itu di antaranya ialah pembicaraan anak didik, rekaman bunyi dan suara rekaman musik, rekaman drama, wawancara, bahkan rekaman suara ikan lumba-lumba, yang semuanya itu dapat memiliki relevansi dengan pelajaran.
3) Variasi media taktil
Komponen terakhir dari keterampilan menggukan variasi media dan bahan ajaran adalah penggunaan media yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajaran. Dalam hal ini akan melibatkan anak didik dalam kegiatan penyusunan dan pembuatan model yang hasilnya dapat disebutkan sebagai “media taktil” ataupun kelompok kecil. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok kecil. Contoh: dalam bidang studi ipa dapat membuat model kincir angin.
c. Variasi Interaksi
Pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya, mulai dari gerakan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Yang mana ini semua dilakukan untuk menghindari kebosanan dalam belajar. Adapun jenis pola interaksi (gaya interaksi) dapat digambarkan sebagai berikut:
- Pola guru, murid : komunikasi sebagai aksi satu arah.
- Pola guru, murid, guru : ada kebalikan (feedback) bagi guru, tidak ada interaksi antara siswa.
- Pola guru, murid, murid: ada balikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain.
- Pola guru murid, murid guru , murid, murid : interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid (komunikasi sebagai transaksi, multi arah)
- Pola melingkar: setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban, tidak diperkenankan berbicara dua kali apabila setiap siswa belum mendapat giliran.
Bila dilihat dari sudut kegiatan anak didik, maka dapat berbentuk: mendengarkan ceramah guru, mengajukan pendapat pada diskusi kelompok, membaca secara keras atau pelan, melihat film, bekerja di laboratorium baik bahasa maupun alam, bekerja atau belajar bebas, atau juga dapat menciptakan kegiatan sendiri.
B. Keberhasilan Belajar Mengajar
1. Pengertian Keberhasilan
Sebelum mengetahui pengertian keberhasilan belajar mengajar maka terlebih dahulu mengetahui pengertian belajar, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan ( Moh. Surya, 1992, 23). Morgan, seperti dikutip Tim Penulis Psikologi Pendidikan (1993: 60) ringkasnya mengatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tesebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar, menyebaban siswa semakin sadar, akan kemampuan dirinya (Dimyati dan Mudjiono, 2002:22).
Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu tindakan sadar yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan dalam diri mereka atas stimulasi lingkungan dan proses mental mereka sehingga bertambah pengetahuannya.
2. Pengertian Mengajar
Jerome S. Brunner dalam bukunya Toward a theory of instruction mengemukakan bahwa mengajar adalah menyajikan ide, problem atau pengetahuan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh setiap siswa (Uzer Usman dan Lilis Setyawati, 1993: 5). Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (1998: 150) mengemukakan yang dimaksud dengan mengajar ialah memberikan pengetahuan atau melatih kecakapan-kecakapan atau keterampilan-ketrampilan kepada anak-anak. Jadi, mengajar bukan sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan mengandung makna yang lebih luas dan kompleks, yaitu terjadinya komunikasi dan interaksi manusiawi dengan berbagai aspeknya.
3. Pengertian Keberhasilan Belajar Mengajar
Keberhasilan Belajar Mengajar menurut Moh Uzer Usman dan Lilis Setyawati dalam buku Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar (1993: 7-8) mengemukakan sebagai berikut. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, bahwa setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofinya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila TIK tersebut dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan satu satuan bahasan kepada siswa. Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil.
4. Indikator Keberhasilan Belajar Mengajar
Keberhasilan belajar merupakan prestasi peserta didik yang dicapai dalam proses belajar mengajar. Untuk mengatahui keberhasilan belajar tersebut terdapat beberapa indikator yang dapat dijasikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak.
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006: 106) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar, di antaranya yaitu: (1) daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok, dan (2) perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus (TIK) telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok.
Lebih lanjut Zaenal Arifin (2009: 298) menyatakan bahwa indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari berbagai jenis perbuatan atau pembentukan tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku itu di antaranya adalah: (1) kebiasaan, yaitu cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar, (2) keterampilan, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat kegiatan otot dan digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf, (3) akumulasi persepsi, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar, seperti pengenalan simbol, angka dan pengertian, (4) asosiasi dan hafalan, yaitu seperangkat ingatan mengenai seseuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja atau wajar maupun asosiasi tiruan, (5) pemahaman dan konsep, yaitu jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional, (6) sikap, yaitu pemahaman, perasaan, dan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap sesuatu, (7) nilai, yaitu tolak ukur untuk membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik, serta (8) moral dan agama, moral merupakan penerapan nilai-nilai dalam kaitannya dengan kehidupan sesama manusia, sedangkan agama adalah penerapan nilai-nilai yang trasedental dan ghaib (konsep tuhan dan keimanan).
Berdasarkan uraian di atas, maka indikator keberhasilan belajar peserta didik dapat diketahui dari kemampuan daya serap peserta didik terhadap bahan pengajaran yang telah diajarkan serta dari perbuatan atau tingkah laku yang telah digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, baik secara indvidual maupun kelompok.
5. Penilaian Keberhasilan
Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan kedalam jenis penilaian sebagai berikut:
a. Tes Formatif
Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam bahan tertentu.
b. Tes Subsumatif
Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya para siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor.
c. Tes Sumatif
Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode pembelajaran tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat (ranking) atau sebagai ukuran mutu sekolah.
Dalam praktek penilaian di madrasah Aliyah, ulangan yang lazim dilaksanakan itu dapat dianggap sebagai tes subsumatif, sebab ruang lingkup dan tujuan ulangan tersebut sama dengan tes sub sumatif. Namun demikian, hasil tes ataupun ulangan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan gambaran tentang keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan itu dilihat dari segi keberhasilan proses dan keberhasilan produk.
Sejalan dengan itu Zaenal Arifin (2009: 20) berpendapat bahwa untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik dapat digunakan tes hasil belajar, yang digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) tes formatif, yaitu penilaian yang yang digunakan untuk mengukur suatu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap peserta didik terhadap pokok bahasan tersebut, dan (2) tes sumatif, yaitu tes yang diadakan untuk mengukur daya serap peserta didik terhadap bahan pokok-pokok yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran yang tujuannnya untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar peserta didik dalam sautu periode belajar tertentu.
Pengukuran keberhasilan belajar dengan menggunakan tes hasil belajar hanya dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan teoritis. Sedangkan menurut Zaenal Arifin (2009: 152) untuk mengukur aspek keterampilan digunakan tes perbuatan, serta perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi diukur dengan teknik non tes.
Lebih lanjut Zaenal Arifin (2009: 152) mengatakan bahwa teknik non tes dapat diaplikasikasn dengan berbagain cara, diantaranya adalah: (1) observasi (observation) yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu, (2) wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik, (3) skala sikap (attitude scale) yaitu bentuk penilaian non tes yang dilakukan dnegan cara peserta didik memilih pernyataan-pernyaat positif dan negatif, (4) dafar cek (check list) adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati, (5) skala penilaian (rating scale) adalah daftar cek penilaian non tes yang penilainya hanay dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu, sedangkan dalam skala penilaian fenomena-fenomena yang akan dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan, (6) angket (quetioner) adalah alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau infoermasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal, (7) studi kasus (case study) adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekoalh yang memiliki kasus tertentu, (8) catatan insidental (anecdotal records) adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan, (9) sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka, dan (10) inventori kepribadian adalah alat penilaian non tes yang hampir serupa dengan tes kepribadian, bedanya pada inventori jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah, melainkan jawaban peserta didik dikatakan benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahawa keberhasilan belajar peserta didik dapat dinilai dengan tiga cara, yakni (1) tes untuk mengukur aspek kognitif, (2) tes perbuatan untuk untuk mengukur aspek keterampilan, dan (3) non tes untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi.
6. Tingkat Keberhasilan
Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana prestasi (hasil) belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal inilah keberhasilan proses mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Istimewa/maksimal: Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai para siswa.
b. Baik sekali/optimal: Apabila sebagian besar (76% s.d.99%) bahan pembelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.
c. Baik/minimal: Apabila bahan pembelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d.75% saja dikuasai oleh siswa.
d. Kurang: Apabila bahan pembelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa.
Dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap siswa dalam pembelajaran dan persentase keberhasilan dalam mencapai TIK tersebut, dapatlah diketahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan siswa dan guru.
7. Program Perbaikan
Taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai upaya. Salah satunya adalah sehubungan dengan kelangsungan proses belajar mengajar itu sendiri yang antara lain adalah: apakah proses belajar mengajar berikut pokok bahasan baru, mengulang seluruh pokok bahasan baru saja diajarkan atau mengulang sebagian pokok bahasan yang baru saja diajarkan, atau bagaimana?
Jawaban terhadap pertanyaan tesebut hendaknya didasarkan pada taraf atau tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang baru saja dilaksanakan.
a. Apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, satau bahkan maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru.
b. Apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (dibawah taraf minimal), maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan (remedial).
Pengukuran tentang taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar ini teryata berperan penting. Karena itu, pengukurannya harus betul-betul syahih (valid), andal (reliabel), dan lugas (objektif). Hal ini mungkin tercapai bila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah, aturan, hukum, atau ketentuan penyusunan butir tes.
Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengulang pokok bahasan seluruhnya
b. Mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai
c. Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama
d. Memberikan tugas-tugas khusus
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan
Jika ada guru yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berhasil dalam mengajar, adalah ungkapan seorang guru yang sudah putus asa dan jauh dari kepribadian seorang guru. Mustahil setiap guru tidak ingin berhasil dalam mengajar. Apalagi jika guru itu hadir dalam dunia pendidikan berdasarkan tuntutan hati nurani. Panggilan jiwanya pasti akan merintih atas kegagalan mendidik dan membian anak didiknya.
Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan, sampai-sampai seorang guru berusaha sekuat tenaga dan pikiran mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan sistematik. Namun terkadang keberhasilan yang dicita-citakan, tetapi malah kegagalan yang ditemui, disebabkan oleh berbagai faktor penghambatnya. Sebaliknya, jika keberhasilan itu menjadi kenyataan, maka berbagai faktor itu juga sebagai pendukungya. Berbagai faktor tersebut antara lain adalah:
a. Tujuan
Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yanga akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari proses belajar mengajar berpangkal dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
Karena sebagai pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam setiap kali kegiatan belajar mengajar, maka guru selalu diwajibkan merumuskan tujuan pembelajarannya. Guru hanya merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK), karena Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) sudah tersedia di dalam GBPP. Inilah langkah pertama yang harus guru lakukan dalam menyusun rencana pengajaran.
Tujuan Pembelajaran Khusus ini harus dirumuskan secara operasional dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
1) Secara spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai.
2) Membatasi dalam keadaan mana perubahan perilaku diharapkan dapat terjadi (kondisi perubahan perilaku).
3) Secara spesifik menyatakan kriteria perubahan perilaku dalam arti menggambarkan standar minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil yang dicapai.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) adalah wakil dari Tujuan Pembelajaran Umum (TPU). Agar TPK dapat mewakili TPU perlu dipikirkan beberapa petunjuk (indikator) suatu TPU. lndikator suatu TPU itu banyak, namun dalam hal ini hendaknya yang dipilih yang betul-betul penting, sehingga dapat mewakili (representatif) TPU.
Contoh rumusan TPK berdasarkan ciri-ciri dan indikator terpilih: “Dengan menggunakan peta siswa dapat menunjukkan tiga daerah objek wisata di Kalimantan Selatan dengan tepat dan benar.”
Bila TPK tersebut dianalisis, dapatlah diketahui unsur-unsur berikut:
1) Audience :Siswa
2) Behavior :Dapat menunjukkan tiga daerah objek wisata di
Kalimantan Selatan
3) Condition :Dengan menggunakan peta
4) Degree :Dengan tepat dan benar.
Perumusan TPK yang bermacam-macam akan menghasilkan hasil belajar atau perubahan perilaku anak yang bermacam-macam pula. Itu berarti keberhasilan proses belajar mengajar bervariasi juga. Perilaku yang mana yang hendak dihasilkan, menghendaki perumusan TPK yang sesuai dengan perilaku yang hendak dihasilkan. Bila perilaku yang hendak dicapai guru adalah agar anak dapat membaca, maka perumusan TPK-nya harus mendukung tercapainya keterampilan membaca yang diinginkan itu. Bila perilaku yang hendak dicapai guru adalah agar anak dapat menu lis, maka perumusan TPK-nya harus mendukung tercapainya keterampilan menulis yang diinginkan. Baik keterampilan membaca maupun menulis adalah perilaku (behavior) yang hendak dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar. Bila kedua keterampilan tersebut dikuasai oleh anak, maka guru dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasiIan belajar mengajar dalam setiap kali pertemuan kelas. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasiIan belajar mengajar dalam setiap kali pertemuan kelas.
b. Guru
Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.
Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk mengantarkan anak didik menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan berkepribadian. Dari kepribadian itulah mempengaruhi pola kepemimpinan yang guru perlihatkan ketika melaksanakan tugas mengajar di kelas.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seorang guru di bidang pendidikan dan pengajaran. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdiannya. Kalaupun ditemukan kesulitan hanya pada aspek-aspek tertentu. Hal itu adalah suatu hal yang wajar. Jangankan bagi guru pemula, bagi guru yang sudah berpengalaman pun tidak akan pernah dapat menghindarkan diri dari berbagai masalah di sekolah. Hanya yang membedakannya adalah tingkat kesulitan yang ditemukan. Tingkat kesulitan yang ditemukan guru semakin hari semakin berkurang pada aspek tertentu seiring dengan bertambahnya pengalaman sebagai guru.
Guru yang bukan berlatar belakang pendidikan keguruan dan ditambah tidak berpengalaman mengajar, akan banyak menemukan masalah di kelas. Terjun menjadi guru mungkin dengan tidak membawa bekal berupa teori-teori pendidikan dan keguruan. Seperti kebanyakan guru pemula jiwanya juga labil, emosinya mudah terangsang dalam bentuk keluhan dan berbagai bentuk sikap lainnya, tetapi dengan semangat dan penuh ide untuk suatu tugas.
Berbagai permasalahan yang dikemukakan di depan adalah aspek-aspek yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Paling tidak, keberhasilan belajar mengajar yang dihasilkan bervariasi. Kevariasian ini dilihat dari tingkat keberhasilan anak didik menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam setiap kali pertemuan kelas. Variasi hasil produk ini patokannya adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap anak didik.
c. Anak Didik
Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang tuanyalah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Kepercayaan orang tua anak, diterima oleh guru dengan kesadaran dan penuh keikhlasan. Maka jadilah guru sebagai pengemban tanggungjawab yang diserahkan itu.
Tanggungjawab guru tidak hanya terdapat seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup banyak. Anak yang dalam jumlah yang cukup banyak itu tentu saja dari latar belakang kehidupan sosial keluarga dan masyarakat yang berlainan. Karenanya, anak-anak berkumpul di sekolah pun mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Kepribadian mereka ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka bicara, ada yang kreatif, ada yang keras kepala, ada yang manja, dan sebagainya. Intelektual mereka juga dengan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Biologis mereka dengan struktur atau keadaan tubuh yang tidak selalu sama. Karena itu, perbedaan anak pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis ini mempengaruhi kegiatan belajar mengajar.
Anak yang dengan ciri-ciri mereka masing-masing itu berkumpul di dalam kelas, dan yang mengumpulkannya tentu saja guru atau pengelola sekolah. Banyak sedikitnya jumlah anak didik di kelas akan mempengaruhi pengelolaan kelas. jumlah anak didik yang banyak di kelas, misalnya 30 sampai 45 orang, cenderung lebih sukar dikelola, karena lebih mudah terjadi konflik di antara mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mengajar. Apalagi bila anak-anak yang dikumpulkan itu sudah terbiasa kurang disiplin.
Anak yang menyenangi pelajaran tertentu dan kurang menyenangi pelajaran yang lain adalah perilaku anak yang bermula dari sikap mereka karena minat yang berlainan. Hal ini mempengaruhi kegiatan belajar anak. Biasanya pelajaran yang disenangi, dipelajari oleh anak dengan senang hati. Sebaliknya, pelajaran yang kurang disenangi jarang dipelajari oleh anak, sehingga tidak heran bila isi dari pelajaran itu kurang dikuasai oleh anak. Akibatnya, hasil ulangan anak itu jelek.
Sederetan angka yang terdapat di buku rapor adalah bukti nyata dari keberhasilan belajar mengajar. Angka-angka itu bervariasi dari angka lima sampai angka sembilan. Hal itu sebagai bukti bahwa tingkat penguasaan anak terhadap bahan pelajaran berlainan untuk setiap bidang studi. Daya serap anak bermacam-macam untuk dapat menguasai setiap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Karena itu, dikenallah tingkat keberhasilan yang maksimal (istimewa), optimal (baik sekali), minimal (baik), dan kurang untuk setiap bahan yang dikuasai oleh anak didik.
Dengan demikian, dapat diyakini bahwa anak didik adalah unsur manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar berikut hasil dari kegiatan itu, yaitu keberhasilan belajar mengajar.
d. Kegiatan Pengajaran
Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Maka guru adalah orang yang menciptakan Iingkungan belajar bagi kepentingan belajar anak didik. Anak didik adalah orang yang digiring ke dalam lingkungan belajar yang telah diciptakan oleh guru. Gaya mengajar guru berubah mempengaruhi gaya belajar anak didik. Tetapi di sini gaya mengajar guru lebih dominan mempengaruhi gaya belajar anak didik. Gaya-gaya mengajar, menurut Muhammad Ali (1992; 59), dapat dibedakan ke dalam empat macam. yaitu gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional.
Strategi penggunaan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil belajar mengajar. Hasil pengajaran yang dihasilkan dari penggunaan metode ceramah tidak sama dengan hasil pengajaran yang dihasilkan dari penggunaan metode tanya jawab atau metode diskusi. Demikian juga halnya dengan hasil pengajaran yang dihasilkan dari penggunaan metode problem solving berbeda dengan hasil pengajaran yang dihasilkan dari penggunaan metode resitasi.
Jarang ditemukan guru hanya menggunakan satu metode dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan rumusan tujuan yang guru buat tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari dua rumusan tujuan. ltu berarti menghendaki penggunaan metode mengajar harus lebih dari satu metode. Metode mengajar yang satu untuk mencapai tujuan yang satu, sementara metode mengajar yang lain untuk mencapai tujuan yang lain. Bermacam-macam penggunaan metode mengajar akan menghasilkan hasil belajar mengajar yang berlainan kualitasnya. Penggunaan metode ceramah misalnya, adalah strategi pengajaran untuk mencapai tujuan pada tingkat yang rendah. Berbeda dengan penggunaan metode problem solving. Penggunaan metode ini tentu saja untuk mencapai tujuan pengajaran pada tingkat yang tinggi. Jadi, penggunaan metode mengajar mempengaruhi tinggi rendahnya mutu keberhasilan belajar mengajar.
e. Bahan dan Alat Evaluasi
Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan pelajaran itu sudah dikemas dalam bentuk buku paket untuk dikonsumsi oleh anak didik. Setiap anak didik dan guru wajib mempunyai buku paket tersebut guna kepentingan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Bila tiba masa ulangan, semua bahan yang telah diprogramkan dan harus selesai dalam jangka waktu tertentu dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan item-item soal evaluasi. Gurulah yang membuatnya dengan perencanaan yang sistematis dan dengan penggunaan alat evaluasi. Alat-alat evaluasi yang umumnya digunakan tidak hanya benar-salah (true-false) dan pilihan ganda (multiple-choice), tapi juga menjodohkan (matching), melengkapi (completion), dan essay.
Masing-masing alat evaluasi itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Menyadari akan hal itu, jarang ditemukan pembuatan item-item soal yang hanya menggunakan satu alat evaluasi. Tetapi guru sudah menggabungnya lebih dari satu alat evaluasi. Benar-salah (B-S) dan pilihan ganda adalah bagian dari tes objektif. Maksudnya, objektif dalam hal pengoreksian, tapi belum tentu objektif dalam jawaban yang dilakukan oleh anak didik. Karena sifat alat ini mengharuskan anak didik memilih jawaban yang sudah disediakan dan tidak ada alternatif lain di luar dari alternatif itu, maka bila anak didik tidak dapat menjawabnya, dia cenderung melakukan tindakan spekulasi, pengambilan sikap untung-untungan ketimbang tidak berisi. Bila benar untung, bila salah tidak menjawab soal. Strategi lainnya lagi adalah anak didik melakukan kerja sama dengan teman-temannya yang kebetulan duduk berdekatan. Kerja samanya teratur rapi dan terkadang guru kurang dapat mengontrolnya. Sebab dalam melakukan kerja sama itu mereka menggunakan sandi-sandi tertentu yang hanya kelompok mereka itulah yang dapat mengetahuinya. Sandinya misalnya, dalam bentuk kode acungan jempol, gerakan tubuh, atau isyarat melalui benda yang sudah disepakati sebelum ulangan dilaksanakan, dan sebagainya.
Pembuatan item soal dengan memakai alat tes objektif dapat menampung hampir semua bahan pelajaran yang sudah dipelajari oleh anak didik dalam satu semester, tapi kelemahannya terletak pada penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran bersifat semu, suatu penguasaan bahan pelajaran yang masih samar-samar. Jika alternatif itu tidak dicantumkan, kemungkinan besar anak didik kurang mampu memberikan jawaban yang tepat.
Alat tes dalam bentuk essay dapat mengurangi sikap dan tindakan spekulasi pada anak didik. Sebab alat tes ini hanya dapat dijawab bila anak didik betul-betul menguasai bahan pelajaran dengan baik. Bila tidak, kemungkinan besar anak didik tidak dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Kelemahan alat tes ini adalah dari segi pembuatan item soal tidak semua bahan pelajaran dalam satu semester dapat tertampung untuk disuguhkan kepada anak didik pada waktu ulangan. Essay memang alat tes yang tidak objektif, karena dalam penilaiannya, kalaupun ada standar penilaian, masih terpengaruh dengan selera guru. Apalagi bila tulisan anak didik tidak mudah terbaca, kejengkelan hati segera muncul dan pemberian nilai tanpa pemeriksaan pun dilakukan.
Maraknya tindakan spekulatif pada anak didik barangkali salah satu faktor penyebabnya adalah teknik penilaian yang berlainan dengan rumus penilaian menurut kesepakatan para ahli. Untuk tes objektif mempunyai rumus penilaian masing-masing. Jadi, ke sanalah rujukan standar penilaian itu, bukan membuat rumus penilaian yang cenderung mendatangkan sikap dan tindakan spekulatif pada anak didik. Bahkan pembuatan soal pun harus bergerak dari yang mudah, sedang, hingga ke yang sukar, dengan proporsi tertentu. Membuat rumus penilaian sendiri tidak dilarang. Sekali lagi, tidak dilarang. Selama pembuatannya menutup jalur-jalur spekulatif pada anak didik.
Berbagai permasalahan yang telah dikemukakan tersebut mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Validitas dan reliabilitas data dari hasil evaluasi itulah yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Bila alat tes itu tidak valid dan tidak reliable, maka tidak dapat dipercaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar mengajar.
f. Suasana Evaluasi
Selain faktor tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, serta bahan dan alat evaluasi, faktor suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Semua anak didik dibagi menurut kelas masing-masing. Besar kecilnya jumlah anak didik yang dikumpulkan di dalam kelas akan mempengaruhi suasana kelas. Sekaligus mempengaruhi suasana evaluasi yang dilaksanakan. Sistem silang adalah teknik lain dari kegiatan mengelompokkan anak didik dalam rangka evaluasi. Sistem ini dimaksudkan untuk mendapatkan data hasil evaluasi yang benar-benar objektif.
Karena sikap mental anak didik belum semuanya siap untuk berlaku jujur, maka dihadirkanlah satu atau dua orang pengawas atau guru yang ditugaskan untuk mengawasinya. Selama pelaksanaan evaluasi, selama itu juga seorang pengawas mengamati semua sikap, gerak-gerik yang dilakukan oleh anak didik. Pengawasan yang dilakukan itu tidak hanya duduk berlama-lama di kursi, tapi dapat berjalan dari muka ke belakang sewaktu-waktu, sesuai keadaan.
Sikap yang merugikan pelaksanaan evaluasi dari seorang pengawas adalah membiarkan anak didik melakukan hubungan kerja sama di antara anak didik. Pengawas seolah-olah tidak mau tau apa yang dilakukan oleh anak didik selama ulangan. Tidak peduli apakah anak didik nyontek, membuka kertas kecil yang berisi catatan yang baru diambil dari balik pakaian, atau membiarkan anak didik bertanya jawab dalam upaya mendapatkan jawaban yang benar. Lebih merugikan lagi adalah sikap pengawas yang dengan sengaja menyuruh anak didik membuka buku atau catatan untuk mengatasi ketidakberdayaan anak didik dalam menjawab item-item soal, Dengan dalih, karena koreksinya sistem silang, malu kebodohan anak didik diketahui oleh sekolah lain.
Suasana evaluasi yang demikian tentu saja, disadari atau tidak, merugikan anak didik untuk bersikap jujur dengan sungguh-sungguh belajar di rumah dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan. Anak didik merasa diperlakukan secara tidak adil, mereka tentu kecewa, mereka sedih, mereka berontak dalam hati, mengapa harus terjadi suasana evaluasi yang kurang sedap dipandang mata itu. Di manakah penghargaan pengawas atas jerih payahnya belajar selama ini. Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang berkecamuk di dalam diri anak didik.
Dampak di kemudian hari dari sikap pengawas yang demikian itu, adalah mengakibatkan anak didik kemungkinan besar malas belajar dan kurang memperhatikan penjelasan guru ketika belajar mengajar berlangsung, Hal inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi pada diri anak didik. Inilah dampak yang merugikan terhadap keberhasilan belajar mengajar.
DAFTAR PUSTAKA
Bahari, Syaiful Djamarah dan Zain, Aswan. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta
Uzer, Moh Usman dan Setiawati, Lilis. 1993. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
Sari, sekar. 2012. Variasi Mengajar. (http://sekarsarisekar.blogspot.com/2012/11/variasi-mengajar_29.html, diakses 3 Oktober 2014)
Syarmila. 2013. Pengembangan Variasi Mengajar. (http://ummuaim.blogspot.com/2013/12/pengembangan-variasi mengajar.html, diakses 3 oktober 2014)