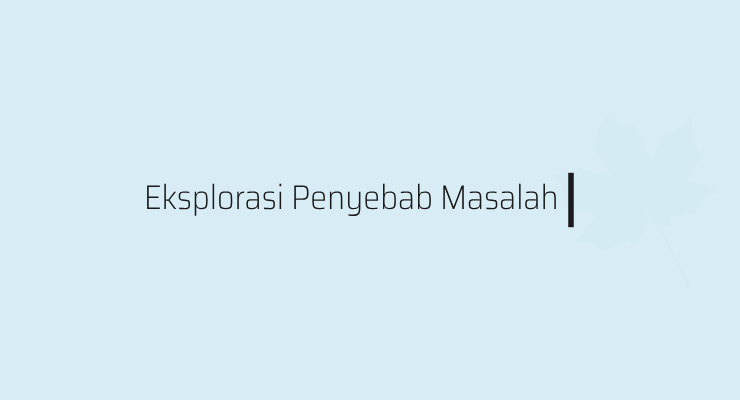Eksplorasi Penyebab Masalah dalam Pembelajaran merupakan salah satu kompetensi penting bagi guru porfesional. Kompetensi ini adalah keterampilan seorang guru dalam memahami masalah apa saja yang ada di dalam kelas dan masalah apa saja yang penting untuk diselesaikan.
Daftar isi
Eksplorasi Penyebab Masalah
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah adalah upaya yang dilakukan dalam mengetahui masalah yang ada di dalam kelas. Langkah ini dilakukan sebelum akhirnya guru menyusun rancangan pembelaajran invotaif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas.
Contoh Eksplorasi Penyebab Masalah
Untuk mengisi LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah, kita dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:
Contoh hasil isian LK 1.2 Eksplorasi Penyebab masalah adalah sebagai berikut
| No | Masalah yang telah diiidentifikasi | Hasil eksplorasi penyebab masalah | Analisis eksplorasi penyebab masalah |
| 1 | Motivasi belajar siswa rendah | Hasil kajian literaturSardiman (2018), siswa terlihat memiliki motivasi belajar jika telah menunjukkan beberapa sikap sebagai berikut: 1. Semangat dan rajin dalam menghadapi tugas. 2. Gigih saat menghadapi kesulitan. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam penyelesaian persoalan. 4. Tidak mudah jenuh pada tugas yang sama. 5. Mampu bertahan ada argumennya apabila sudah merasa yakin pada suatu hal. Widodo (2020) motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh: 1. Faktor internal, terdiri dari: fisik, psikologis 2. Faktor eksternal, terdiri dari: sosial, keluarga, lingkungan pembelajaran, guru, sumber belajar, fasilitas belajar. Khafid (2021) motivasi belajar dipengaruhi oleh: 1. Minat siswa 2. Manfaat materi bagi kehidupan siswa 3. Kreatifitas guru dalam menyampaikan pembelajaran 4. Strategi/teknik/metode pembelajaran guru 5. Perhatian orang tua 6. Sarana dan prasarana pembelajaran 7. Suasana pembelajaran Menurut Permatasari (2018:87): Faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik secara internal adalah kurangnya perhatian peserta didik pada saat mengikuti pelajaran, sedangkan secara eksternal disebabkan oleh lingkungan sekolah seperti kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, kurangnya media dan sumber belajar, kurangnya penegakan disiplin sekolah dan lingkungan belajar yang kurang mendukung. Hasil wawancara : 1. Siswa merasa jenuh belajar dikelas disebabkan metode mengajar yang kurang menarik. 2. Guru belum menggunakan metode mengajar yang tepat, sehingga materi yang diajarkan kurang menarik bagi siswa. | Setelah dianalisis masalah motivasi belajar siswa rendah dikarenakan : 1. Guru kurang mendapatkan pelatihan tentang cara menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diberikan. 2.Guru belum memiliki cukup waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan. 3. Tuntutan kurikulum tidak sejalan dengan kondisi lapangan, sehingga sering guru hanya mengejar materi selesai diajarkan meski siswa belum mengerti dengan materi tersebut. 4. Guru kurang kreatif dalam menata ruang kelas menjadi ruangan yang menarik dan nyaman untuk digunakan. 5. Kurangnya perhatian orang tua terhadap motivasi peserta didik. |
| 2 | Kurangnya Hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran | Hasil kajian literatur Pusitaningtyas (2016): komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau ide oleh seseorang kepada orang lain baik dengan bahasa atau melalui media tertentu yang diantara keduanya sudah terdapat kesamaan makna sehingga saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Ketut : Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling berbagi informasi dari suatu tempat, orang, ataupun kelompok. Dengan tujuan memberikan suatu informasi dan mengkomunikasian kepada audiens kita. Komunikasi guru dan orang tua harus tetap bersinergi dalam mendudukan pendidikan anak didiknya. Menurut Nur Diana (dalam Mansur 2005: 92) pada level ini, anak-anak baru saja mulai mengembangkan karakter mereka melalui perkembangan sikap, moral, sosial, emosi dan karakteristik keagamaan. Pengembangan nilai-nilai ini dapat dicapai dengan optimal jika adanya keharmonisan antara pendidikan anak-anak di rumah dan di sekolah, yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua dan peran guru Dewi (2014): Pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri (guru) dengan penerima materi (murid/siswa). Adapun beberapa rancangan proses kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran serta metode pembelajaran. Djamaluddin (2019) : Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hasil wawancara: 1. Orang tua yang sibuk berkerja sehingga kurang memperhatikan kegiatan anak disekolah. 2. Orang tua hanya bertanya seputar kegiatan disekolah, tidak mencari solusi bersama terkait anak yang bermasalah. | Setelah dianalisis masalah kurangnya hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran dikarenakan : 1. Orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan pola belajar anaknya.2. Orang tua yang sibuk berkerja tidak bisa hadir jika diundang rapat disekolah.3. Orang tua kurang perhatian terhadap masalah anaknya disekolah terkait pembelajaran disekolah. |
| 3 | Guru belum memahami pembelajaran inovatif | Hasil kajian literatur Pembelajaran inovatif merupakan proses pembelajaran yang dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar mampu belajar. Siswa harus menempatkan diri dengan baik, siswa tidak boleh hanya diam, tapi harus berusaha memotivasi dirinya sendiri agar berkembang. Pembelajaran inovatif akan membangkitkan semangat siswa untuk menjadi yang terbaik (Ismail, 2003; Burhanuddin, 2014; dan Komara, 2014). Model pembelajaran inovatif yang berikutnya adalah model modifikasi tingkah laku dikembangkan berdasarkan teori behavioristik. Model ini memandang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh hubungan sebab-akibat atau stimulus dan respon antara individu dengan lingkungan. Respon positif akan memberikan penguatan yang positif terhadap siswa (Koesnandar, 2020:38). Pembelajaran inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh guru lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu menfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. Tujuan utama dari inovasi pembelajaran adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana temasuk struktur dan prosedur organisasi agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Sedangkan manfaat diadakannya inovasi diantaranya dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat mengujicobakan inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, menumbuhkembangkan semangat dalam bekerja (Indria Hapsari, 2021:190). Hasil wawancara: 1. Guru belum mengikuti pelatihan tentang pembelajaran inovatif. 2. Guru metode yang digunakan monoton. | Setelah dianalisis masalah guru belum memahami pembelajaran inovatif dikarenakan : 1. Guru belum mengikuti pelatihan tentang pembelajaran inovatif. 2. Metode yang digunakan guru masih monoton. 3. Guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran. 4. Kegiatan belajar mengajar masih terpusat pada guru |
| 4 | Anak belum bisa menyebutkan huruf dilingkungan sekolah | Hasil kajian literatur Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (2000: 707) kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Menurut Robbins (dalam Susanto, 2011: 97) kemampuan adalah suatu kapasitas berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tertentu. Soehardi (2003: 24), mengemukakan bahwa kemampuan adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang diperoleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu kesanggupan atau kekuatan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang diperoleh melalui belajar untuk menyelesaikan tugasnya. Madyawati (2016: 23) mengemukakan bahwa perkembangan bahasa mencakup empat kemampuan yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Perkembangan membaca sebagai salah satu dasar yang harus dimiliki anak terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan usia dan karakteristik perkembangannya. Menurut Keraf (1996: 24) membaca adalah suatu proses yang kompleks yang meliputi kegiatan yang melibatkan fisik dan mental. Membaca juga diartikan sebagai proses pemberian makna simbol visual. Menurut Sholifah dan Nurhenti D. Simatupang (2016), menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan perkembangan kognitif khususnya mengenai lambang bilangan belum mencapai tingkat perkembangan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dan kurang bervariasi dalam penggunaan media pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung serta kegiatan yang kurang bervariasi dan menoton. Menurut Yusuf (dalam Khafid, 2008:47) Lingkungan sekolah tempat peserta didik memperoleh pendidikan kedua, juga dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan pelatihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Hasil wawancara : 1. Ketersediaan buku bacaan anak yang masih kurang di sekolah. 2. Fasilitas perpustakaan dan pojok báca belum mendukung. 3. Guru tidak memanfaatkan pojok baca yang ada disekolah. | Setelah dianalisis masalah Anak belum bisa menyebutkan huruf dilingkungan sekolah dikarenakan : 1. Guru kurang membiasakan anak untuk menyebutkan huruf-huruf dilingkungan sekolah. 2. Guru tidak memanfaatkan pojok baca yang sudah disediakan. 3. Sarana mendukung literasi membaca masih kurang. |
| 5 | Guru belum menggunakan HOTS dalam pembelajaran | Hasil kajian literaturMenurut Ariyana& Bestari (dalam Cahya Rohim:2019) HOTs atau keterampilan berfikir tingkat tinggi adalah proses berfikir yang mendalam tentang pengolahan informasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks dan melibatkan keterampilan menganalsis, mengevaluasi dan mencipta. Untuk mengukur keterampilan berfikir tingkat tinggi yang merupakan kemampuan yang bukan hanya sekedar mengingat atau merujuk tanpa melakukan analisis dapat digunakan instrument soal berupa soal berbasis HOTs (Ariyana & Bestary, 2018:11). Rahman (2018): Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik. Hasil wawancara :1. Guru belum mengetahui HOTS dalam pembelajaran.2. Guru belum mendapatkan pelatihan tentang HOTS dalam pembelajaran. | Setelah dianalisis masalah guru belum menggunakan HOTS dalam pembelajaran dikarenakan : 1. Guru belum mengetahui HOTS dalam pemebalajran. 2. Guru belum mendapatkan pelatihan HOTS dalam pembelajaran. 3. Guru tidak membiasakan anak untuk bereksplorasi atau aktif bertanya saat pembelajaran berlangsung. |
| 6 | Guru belum menguasai TIK dalam pembelajaran | Hasil kajian literaturInformasi yaitu data yang didapat untuk tujuan tertentu, atau dengan kata lain data yang diolah sehingga lebih berguna bagi yang memanfaatkannya. Sedangkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu keadaan yang nyata (Istiyarti, 2014:65) Menurut Alo Liliweri (dalam Istiyarti, 2014:66) Komunikasi adalah suatu aktivitas yang melayani hubungan antara pengirim dengan penerima pesan melampau ruang dan waktu. Nikolopoulou dan Gialamas (2016) mengelompokkan tantangan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dari tiga aspek, yaitu kurangnya dukungan (lack of support), kurangnya kepercayaan (lack of confidence), dan kurangnya perlengkapan (lack of equipment). Proses pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Sebagai institusi, sekolah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam proses pembelanjaran anggaran di setiap tahunnya. Banyak sekolah yang masih berpikir bahwa fasilitas yang terpenting dikembangkan hanya fasilitas fisik saja. Padahal jika diprogramkan adanya infrastruktur TIK maka sebuah sekolah akan mempunyai arah yang jelas dalam pengembangan TIK (Istiyarti, 2014:67) Hasil wawancara: 1. Guru belum memiliki leptop sehingga belum bisa menguasai TIK. 2. Sarana dan prasarana TIK disekolah belum ada. 3. Guru belum ada keinginan untuk belajar TIK. | Setelah dianalisis masalah Guru belum menguasai TIK dalam pembelajaran dikarenakan : 1. Guru belum memiliki leptop sehingga belum menguasai dengan baik masalah TIK. 2. Masih monoton menjadikan buku sebagai sumber belajar. 3. Contoh-contoh materi tema yang diajarkan hanya disampaikan secara lisan. |