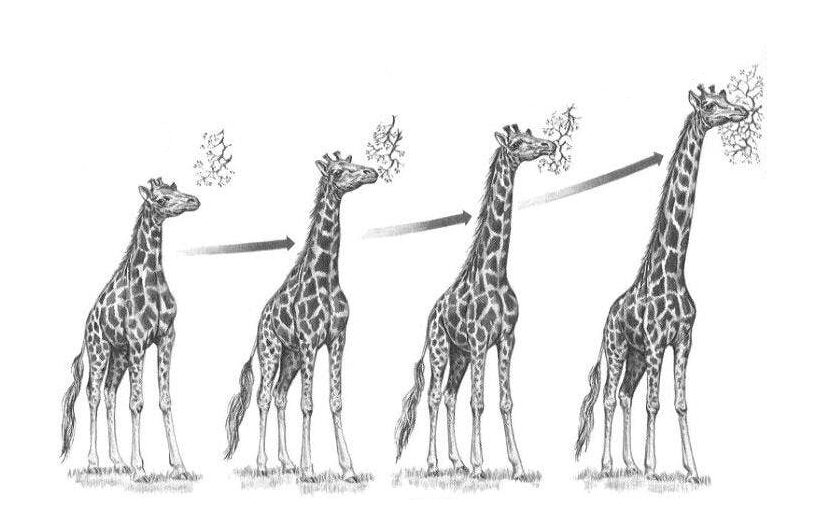Kerajaan Mughal India
Malam ini sepertia biasa browsing internet dan membaca review film dan menemukan sebuah film yang berbau sejarah kejayaan Islam abad 16 di India. Film ” Jodhaa Akbar ” yang lumayan panjang durasinya 3 jam lebih namun kepuasaan batin terbayar setelah menikmatinya sampai abis.
Beberapa saat aku jadi ingat makalahku dulu saat aku kuliah tentang Kerajaan Mughal di India, waktu itu mata kuliah ” Sejarah Kebudayaan Islam “. Belajar lagi jadinya… hehehhe…nih dia makalahnya….simak yukk
Harun Nasution membagi sejarah Islam kepda tiga periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Cikal bakal kekuasaan Islam di India bermula pada periode klasik yaitu pada masa Bani Umayyah dibawah kekuasaan khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu pada periode 705-715 M.
Pada periode pertengahan, muncul tiga kerajaan besar, yakni kerajaan Usmani di turki, kerajaan Shafawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan termuda dari ketiga kerajaan tersebut, berdiri seperempat abad setelah berdirinya kerajaan Shafawi di Persia. Kerajaan Mughal membawa keharuman terhadap sejarah umat Islam, dimana pada saat itu segenap dunia Islam mengalami kemunduran. Kerajaan Mughal sempat membuat bangsa lain tercengang, umat lain menjadi segan karena kegagahan dan kegigihan sultan-sultannya yang membangun suatu kerajaan Islam di wilayah belahan Timur dunia.
Maka pada makalah ini pemakalah coba memaparkan tentang fakta sejarah yang berkaitan dengan kerajan Mughal di India, yaitu diantaranya dengan Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal politik dan pemerintahan, Ekonomi dan perdagangan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan kemajuan yang telah dicapai pada masa kerajaan tersebut dan penyebab keruntuhan kerajaan tersebut.
A. Dinasti Islam Di India Sebelum Pendirian Dinasti Mughal
Sejak zaman Nabi SAW, India telah memiliki sejumlah pelabuhan sehingga terjadi interaksi antara India dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, dagang dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan sehingga raja Kadangalur, Cheraman Perumal, memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin, dan ia sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Umar ibn Khatab, Mughirah berusaha menaklukan Sind, tapi usahanya gagal (246-644).
Pada zaman Usman ibn Affan dan Ali ibn Thalib, dikirim utusan untuk mempelajari adat-istiadat dan jalan-jalan menuju India. Pada zaman Mu’awiyah I, Muhammad ibn Qasim berhasil menaklukan dan diangkat menjadi amir Sind dan Punjab. Kepemimpinan di Sind dan Punjab dipegang oleh Muhammad ibn Qasim setelah berhasil memadamkan perampokan-perampokan terhadap umat Islam disana. Karena pertikaian internal (antara al Hajjaj dan Sulaiman), dinasti ini melemah; dan ketika keadaan lemah, dinasti ini ditaklukan oleh dinasti Gazni.
Pada zaman Al-Ma’mum (khalifah dinasti Bani Abbas), diangkat sejumlah amir untuk memimpin daerah-daerah. Diantara yang dipercaya untuk diangkat menjadi amir adalah Asad ibn Saman utuk daerah Transoxsiana. Ia diangkat menjadi amir setelah berhasil membantu khalifah Bani Abbas dalam menaklukan dinasti Safahari yang berpusat di Khurasan.
Dinasty Samani (874-999) mengangkat Alpatigin menjadi amir di Khurasan. Alpatigin kemudian digantikan oleh anaknya, Ishak. Ishak dikudeta Baltigin; Baltiqin diganti oleh Firri; dan Firri dijatuhkan oleh Subuktigin. Subuktigin menguasai Gazna dan kemudian mendirikan dinasti Gaznawi (963-1191 M). Dinasty gaznawi ditaklukan oleh dinasti Guri (1191). Setelah meninggal, Muhammad Gurri diganti oleh panglimanya, Quthbuddin Aibek (karena Muhammad Guri tidak memiliki anak laki-laki). Quthbuddin Aibek menjadi sultan sejak tahun 1206 M. Sejak itu berdirilah kesultanan Delhi terdiri atas :
- Dinasti Mamluk di Delhi (1206-1290)
- Dinasti Khalji (1290-1320)
- Dinasti Tughluq (1320-1414 M)
- Dinasti Sayyed (1414-1451 M)
- Dinasti Lodi (1451-1526 M).
B. Asal usul Kerajaan Mughal
Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke- 16 hingga abad ke- 19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Lenk, penguasa Islam asal Mongol.
Babur adalah nama kecil dari Zaharuddin, yang artinya singa, ia lahir pada hari Jum’at 24 Februari 1483. Ayahnya bernama Umar Mirza menjadi amir di Fergana, turunan lagsung dari Miransyah putra ketiga dari Timur Lenk. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Jengis Khan. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. namun demikian ia sangat pemberani sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Dia mendapat latihan sejak dini, sehingga memungkinkannya untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar.
Ia berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting dia Asia Tengah pada saat itu. Pertama kali ia mengalami kekalahan untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian berkat bantuan Ismail I, Raja Safawi, sehingga pada tahun 1494, Babur berhasil menaklukan kota Samarkand, dan pada dengan Tahun 1504 menaklukan Kabul, ibukota Afganistan. Dari Kabul Babur melanjutkan ekspansi ke India yang pada saat itu diperintah Ibrahim Lodi.
Ibrahim Lodi (cucu sultan lodi), sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya.[9] Ketika itu kewibawaan kesultanan sedang merosot, karena ketidak mampuannya memimpin, atas dasar itulah Alam Khan keluarga Lodi yang lain mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur (1482-1530 M). Permintaan itu langsung diterima oleh Babur dan bersama pasukannya menyerang Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 M terjadilah pertempuran yang sangat dasyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh, dan Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan mendirikannya pemerintahannya.
Setelah mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Di pihak lain raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur dan di Afganistan, golongan yang setia pada keluarga Ibrahim Lodi mengangkat saudara kandung Ibrahim, Mahmud Lodi menjadi Sultan. Sultan Mahmud Lodi bergabung dengan raja-raja Hindu tersebut. Kali ini berarti harus berhadapan dengan pasukan koalisi, namun Babur tetap dapat mengalahkan pasukan koalisi itu dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 M. Akan tetapi ia tidak lama menikmati hasil perjuangannya. Ia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1530 M pada usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. [11] Setelah Babur meninggal, Zahirudin Babur digantikan oleh anaknya, Nashiruddin Humayun (1530-1539M).
Humayun dalam menjalankan roda pemerintahanya banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa pemerintahanya negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Diantara tantangan yang muncul adalah Bahadur Syah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, Bahadur Syah melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai. Pada tahun 1540 M terjadi pertempuran dengan Syer Khan di Kanauj, dalam peperangan ini Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia ia mengenal tradisi Syi’ah, bahkan sering dibujuk untuk memasukinya, begitu pula dengan anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Di sini pula ia membangun kekuatan militer yang telah hancur, dan berkat bantuan Syah Tahmasph yang memberikan pasukan militer sebanyak 14.000 tentara, maka pada tahun 1555, Humayun mencoba merebut kembali kekuasaannya dengan menyerbu Delhi yang pada saat itu diperintah Sikandar Sur. Akhirnya, ia bisa menaklukan kota ini dan ia memerintah kembali pada tahun 1556 M.
Kemudian Humayyun digantikan oleh anaknya, Abu al-Fath Jalal al-Din Muhammad Akbar. Lebih dikenal dengan sebutan Akbar, dilahirkan di Amarkot, 15 Oktober 1542 M. dan memerintah (1556-1605 M) dari usia 14 tahun. Akbar sebagai wali sultan yang masih muda maka diangkatlah Bairam Khan. Bairam seorang yang cakap, namun bukan orang yang bijaksana.
Akbar adalah seorang laki-laki yang memiliki naluri kerajaan yang kuat ”seorang raja katanya, harus selalu sungguh-sunguh terhadap penaklukan; jika tidak, maka negeri tetangganyalah yang akan mengangkat senjata terhadapnya. Prinsip tersebut membuat Akbar bertekad menjadi penguasa tertinggi di India yang tak dapat digugat. Pada tahun 1605 M. Akbar meninggal dunia. Masa kepemimpinan Akbar adalah puncak kejayaan kerajaan Mughal, tidak hanya dalam bidang politik dan militer saja, tapi juga dibidang ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, administrasi, dan keagamaan. Kemajuan yang telah dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh tiga sultan berikutnya, yaitu Jehangir (1605-1628M), Syah Jehan (1628-1658 M), dan Aurangzeb (1658-1707 M). tiga Sultan penerus Akbar ini memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya.[15]
Berikut ini akan dirinci fase-fase pemerintahan Mughal :
a. 1526-1530 M dipimpin oleh Zahiruddin Muhammad Babur
b. 1530-1556 M dipimpin oleh Humayun
c. 1556-1605 M dipimpin oleh Akbar Syah I
d. 1605-1627 M dipimpin oleh Jahangir
e. 1627-1658 M dipimpin oleh Syah Jehan
f. 1658-1707 M dipimpin oleh Aurangzeb (Alamgir I)
g. 1707-1712 M dipimpin oleh Bahadur Syah I
h. 1712-1713 M dipimpin oleh Jihandar Syah
i. 1713-1719 M dipimpin oleh Farrukh Siyar
j. 1719-1748 M dipimpin oleh Muhammad Syah
k. 1748-1754 M dipimpin oleh Ahmad
l. 1754-1759 M dipimpin oleh Alamgir II
m. 1759-1806 M dipimpin oleh Alam II
n. 1806-1837 M dipimpin oleh Akbar II
o. 1837-1858 M dipimpin oleh Bahadur Syah II[16]
C. Kemajuan Kerajaan Mughal
Kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar, keberhasilan Ekspansi Militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India yakni kota Kabul dan Turkistan oleh pemerintahan kerajaan Mughal India.
Kita dapat merinci kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal yang dicapai oleh masing-masing raja yang memiliki kemajuan masing-masing sebagai berikut:
Politik dan Pemerintahan
a. Akbar membentuk sitem pemerintahan militeristik. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipah Salar (kepala komandan). Sedang wilayah listrik dipercayakan kepada Faudjar (komandan). Jembatan-jembatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran, pejabat-pejabat itu harus mengikuti latihan kemiliteran.[18]
b. Akbar juga menerapkan politik Sulukhul (toleransi universal). Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukanya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Politik ini dapat menciptakan kerukunan masyarakat India yang sangat beragam.[19]
c. Untuk undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat Din Ilahi yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia Kristen dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang.[20]
d. Pada masa pemerintahan Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam diluar India. Sejumlah penguasa Islam telah mengirim duta atau perwakilan negara mereka ke Delhi, misalnya Syarif Makkah, raja-raja Persia, Balkh, Bukhara dan Kasgar; para gubernur Turki Basrah, Yaman dan Hadmarut, para pemimpin negeri Maghiribi dan Raja Arbesinia.[21]
Bidang ekonomi dan perdagangan
Untuk mengelola ekonomi pertanian pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat local, yang dinamakan muqaddam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan, dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan, tetapi jika tidak loyal maka pejabat lokal berhak menyitanya.[22]
Bidang Pendidikan dan Iptek
Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu, dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan..[23]
Bidang Seni dan Budaya
a. Seni Budaya dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa sultan Syah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik, seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal, yang merupakan bangunan indah, yang dimaksudkan sebagai tanda cinta kasihnya kepada istri tercinta Mumtaz Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa Lampau di India. Selain itu juga Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami’ di Delhi, serta takhta Merak, yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang.[24]
b. karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi menghasilkan karya besar berjudul Padmavat, sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan yang bernama Abu Fadl dengan karyanya bernamma Akbar Nama dan Aini Akhbari, yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figure pemimpinnya.[25]
Akbar mensponsori ajaran Din Illahi, yaitu ajaran campuran berbagai unsur kepercayaan Hindu dan tasawuf dari unsure syi’ah.
G. Kemunduran dan Kehancuran kerajaan Mughal
Setelah satu setengah abad dinasti Mughal berada dalam kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian Aurangzeb Satu persatu penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi.
Pengganti Aurangzeb adalah Mu’azzam, setelah ia meninggal tahta digantikan anaknya Azhim al-syah. Akan tetapi di tentang Zulkifar Khan, anak ‘Asad Khan (wazir Aurangzeb. Azaim al-syah meninggal tahun 1712 M. ia digantikan oleh anaknya Jihandar Syah, tetapi ia disingkirkan oleh adiknya sendiri Faruq Syah pada tahun 1713M. Jadi dalam dua tahun saja telah terjadi empat kali pergantian sultan. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kondisi kerajaan Mughal saat itu.
Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing.. disintegrasi mulai terjadi, satu persatu daerah kekuasaan Mughal mulai melepaskan diri. Keadaan ini diperparah lagi dengan datangnya ancaman baru yang lebih kuat, yaitu datangnya perusahaan Inggris (EIC) yang memiliki senjata modern melawan pemerintahan Mughal. Peperangan berlarut-larut. Akhirnya, Syah Alam membuat perjanjian damai dengan melepaskan daerah Oudh, Bengal dan Orisa kepada Inggris.
Pada saat tiga sultan berkuasa yaitu, Syah Alam, Akbar II dan Bahadur Syah, Inggris diberi kepercayaan untuk mengembangkan usahanya. Dengan jaminan memberikan fasilitas kehidupan Istana dan keluarganya.pada saat terjadinya krisis EIC mengalami kerugian dan Inggrispun mulai mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa tertekan, maka terjadilah pemberontakan rakyat dibawah pimpinan sultan Bahadur Syah pada bualan Mei 1857 M.
Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah, karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa Hindu dan Muslim. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam kepada pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Syah, sultan Mughal terakhir diusir dari istana (1858 M). dengan demikian, berakhirlah sejarah kekuasaaan kerajaan Mughal di India.[26]
Ada beberapa factor yang menyebabkab kekuasaan kerajaan Mughal itu mundur pada satu setengah abad terakhir, dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 M, yaitu:
Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritime Mughal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri.
Kemerosotan moral dan hidup mewah dikalangan elite politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
Kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya
Semua sultan pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. [27]
H. Kesimpulan
Dari uaraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pendiri kerajaan Mughal adalah Zahirudin Muhammad Babur, berasal dari keturunan Timur Lenk dan Jengis Khan. Kerajaan Mughal berdiri pada tahun 932 H/1526M. Di India corak pemerintahannya militeristik yang absolute.
Kerajaan Mughal membawa beberapa kemajuan dalam Islam, baik dalam bidang politik, militer, seni, dan juga dalam bidang ekonomi khususnya. Peninggalan yang dikenal sampai sekarang dari kerajaan Mughal (salah satu keajaiban dunia) Taj Mahal.
Setelah Aurangzeb meninggal dunia kemunduran mulai menggerogoti kerajaan Mughal, para penggantinya pada umumnya lemah sehingga tidak dapat memulihkan kejayaan yang pernah dicapai oleh para pendahulunya. Kemunduran Mughal berlangsung terus-menerus sehingga sampailah kepada pintu gerbang kehancuran pada tahun 1858 M.
Gaya hidup yang feodalistik dan penerapan syariat Islam yang dikehendaki pemerintahan Mughal menimbulkan reaksi keras dari umat hindu yang merupakan penduduk mayoritas.
Penyerbuan aliansi Hindu-Sikh, penyerbuan Nadir Syah, Ahmad Duran dan kolonial Inggris merupakan pukulan berat bagi Mughal. Serbuan Inggris akhirnya mengakhiri kerajaan Mughal dengan segala kejayaannya.
[1]Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985), jilid, h. 85
[2]Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pres, 2000), h. 145
[3] Jaih mubarok, sejarah peradaban islam, (bandung: cv pustaka islamika, 2008), h. 241-242
[4] Ibid, h. 242.
[5] Jaih mubarok, op.cit, h. 243
[6] Tim Editor, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tth), h.281
[7] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pres, 2000), h. 147
[8] K. Ali , Sejarah Islam Tarikh Pramodern, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 528-530
[9] Jaih mubarok, op.cit, h.243
[10]Tim Editor, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tth), h.282
[11]Badri Yatim, op.cit, 148
[12] Jaih mubarok, op.cit, h.243
[13] Mahmud Nasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: Rosda Karya),h.300
[14]Abu Su’ud, Islamologi Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam peradaban Umat manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 116
[15]Badri Yatim, op.cit, h. 150
[16] Tim Editor, op.cit,h. 290
[17] K. Ali, op.cit, h.533-534
[18] Badri Yatim, op.cit,h. 149
[19] K.Ali, op.cit, h. 534
[20] Tim Editor, op.cit,h.297
[21] Abu Su’ud, op.cit,h.118
[22] Ira, op.cit, h. 699
[23] Ira, op.cit, h. 700
[24]Abu Su’ud, op.cit, h. 117
[25]Badri Yatim, op.cit , h. 151
[26]Badri Yatim, op.cit, h. 159-162
[27]Ibid, h. 163