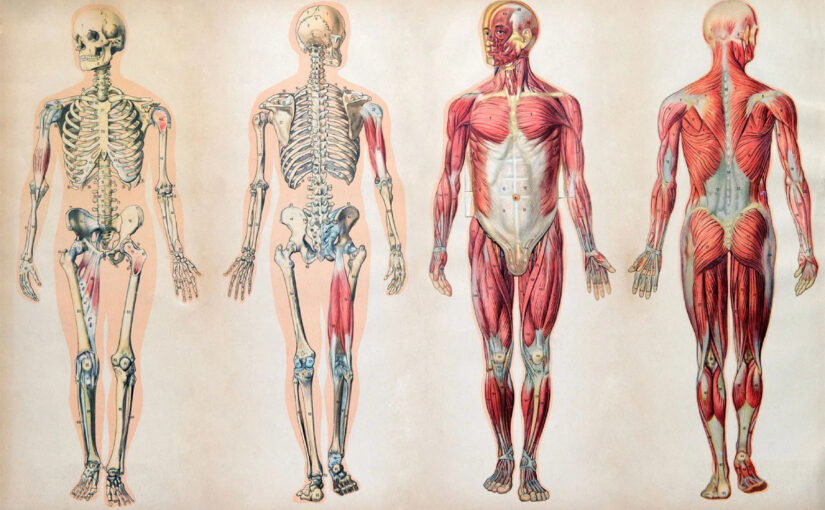Asal usul kehidupan di Bumi dapat ditinjau dari Teori Evolusi Biologi. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan Senyawa Basa dan Asam Nitrogen yang merupakan zat kimia organik kemudian berubah menjadi mahluk ber sel satu pertama.
Evolusi Biologi
Terbentuknya sel pertama kali di bumi diperkirakan terjadi sekitar 4 milyar tahun yang lalu. Sel yang terbentuk adalah sel heterotrof, yaitu sel yang memakan bahan makanan yang terdapat di sup prabiotik. Sel heterotrof ini melakukan respirasi anaerobik karena kadar oksigen waktu itu sangat rendah, tidak memiliki membran inti (prokariotik), tidak memiliki organelorganel seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma dan mampu bereproduksi melalui pembelahan sel. Sel primitif yang terbentuk pertama kali ialah sel prokariotik, yaitu sel sederhana yang tidak memiliki membran inti, hanya memiliki membran sel. Sitoplasma yang mengandung DNA, dan RNA, serta zat-zat organik dari lingkungannya sebagai makanan. Sel ini tidak mengandung mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi. Sehingga, sel ini bersifat anaerobik. Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu yang miskin akan oksigen.
A. Asal-Usul Autotrof
Sel heterotrof primitif terus berkembangbiak sehingga bahan makanan berupa bahan organik terus menipis. Kondisi demikian memaksa sel membuat makanannya sendiri melalui adaptasi terhadap lingkungannya dengan cara membran plasmanya melekuk ke dalam, membentuk lembaran-lembaran fotosintetik untuk menangkap energi sinar guna membuat zat organik dari zat anorganik. Munculah sel autotrof sebagai akal bakal sel tumbuhan yang memungkinkan terjadinya fotosintesis.
Proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Makin banyak sel autotrof, makin banyak karbondioksida yang diperlukan dan makin banyak pula oksigen yang dikeluarkan. Proses fotosintes menyebabkan kadar gas karbondioksida di atmosfer makin berkurang. Sementara itu kadar oksigen semakin bertambah. Terbentuknya sel autotrof ini diperkirakan berlangsung selama 2 milyar tahun yang lalu.
B. Asal-Usul Sel Eukariotik
Organisme eukariotik diduga muncul sekitar 1,5 milyar tahun yang lalu. Organisme eukariotik diduga berasal dari organisme prokariotik yang melakukan evolusi, karena dalam sel prokariotik terdapat DNA. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat organisme sehingga perlu dilindungi. Membran sel mengalami pelekukan ke dalam sehingga mengelilingi DNA. Membran bagian dalam bersatu membentuk membran nukleus dalam. Sedangkan, bagian luar menjadi membran nukleus luar. Jadi membran yang mengelilingi DNA merupakan membran rangkap.
Hipotesis ini berdasarkan kenyataan saat ini bahwa membran nukleus merupakan membran rangkap, dan membran luar nukleus memiliki hubungan secara langsung dengan membran sel melalui Retikulum Endoplasma (RE). Hubungan ini merupakan sisa-sisa membran plasma yang melekuk ke dalam. Dengan terbentuknya membran nukleus, terbentuklah sel eukariotik yang merupakan hasil evolusi dari sel prokariotik.
Asal-Usul Mitokondria
Mitokondria merupakan organel pernapasan sel. Kamu telah mengetahui bahwa sel pertama yang terbentuk adalah sel heterotrof yang merupakan sel anaerobik. Mengingat energi yang dihasilkan kecil, organisme berevolusi agar dihasilkan energi yang cukup banyak dengan cara melakukan respirasi secara aerobik melalui daur krebs. Jadi, respirasi aerobik muncul setelah respirasi anaerobik.
Jadi, yang terbentuk pertama kali adalah sel prokariotik anaerobik yang berevolusi menjadi sel prokariotik aerobik. Dengan demikian, terdapat beberapa macam sel, yaitu sel prokariotik anaerobik, sel prokariotik aerobik, dan sel eukariotik anaerobik. Selanjutnya, sel eukariotik anaerobik “menelan” sel prokariotik aerobik. Sel prokariotik itu hidup di dalam sel eukariotik dan melakukan simbiosis mutualisme sebagai sel inang, sel eukariotik mendapatkan energi dari sel prokariotik, sedangkan sebagai simbion, sel prokariotik mendapatkan asam piruvat dari sel inang.
Dalam perkembangan selanjutnya, sel prokariotik tersebut berubah menjadi mitokondria, yaitu organel penghasil energi yang terdapat di dalam sel. Simbiosis antara sel prokariotik aerobik dengan sel eukariotik anaerobik yang demikian itu dikenal sebagai endosimbions. Dasar dari dugaan ini dikarenakan pada saat ini:
- Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar diduga berasal dari membran sel inang yang melekuk ke dalam ketika menelan sel bakteri aerobik. Sedangkan, membran dalam diduga berasal dari membran bakteri aerobik.
- Masih adanya bakteri aerobik yang memiliki mesosom sebagai penghasil energi. Diduga, sel prokariotik aerobik mirip dengan bakteri aerobik.
- DNA mitokondria mirip dengan DNA prokariotik.
- Polipeptida yang disintesis dalam mitokondria digunakan sendiri oleh mitokondria tersebut. Polipeptida ini berbeda dengan Polipeptida sel inang.
- Mitokondria mampu membelah diri seperti halnya bakteri. Untuk lebih memahami tentang asal-usul sel eukariotik, mari cermati Gambar 6.14 di bawah ini.
Mitokondria (mitochondrion’, plural:mitochondria’) atau kondriosom (chondriosome) adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah “pembangkit tenaga” bagi sel.
Mitokondria merupakan salah satu bagian sel yang paling penting karena di sinilah energi dalam bentuk Adenosina trifosfat dihasilkan.Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam.Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan cristae.Di dalam Mitokondria terdapat ‘ruangan’ yang disebut matriks, dimana beberapa mineral dapat ditemukan.Sel yang mempunyai banyak Mitokondria dapat dijumpai di jantung, hati, dan otot.
Keberadaan mitokondria didukung oleh hipotesis endosimbiosis yang mengatakan bahwa pada tahap awal evolusi sel eukariot bersimbiosis dengan prokariota (bakteri) [Margullis, 1981].Kemudian keduanya mengembangkan hubungan simbiosis dan membentuk organel sel yang pertama.Adanya DNA pada mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya.Hipotesis ini ditunjang oleh beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri. Ukuran mitokondria menyerupai ukuran bakteri, dan keduanya bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Hal yang utama adalah keduanya memiliki DNA berbentuk lingkar.Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri yang berbeda dengan sistem genetik inti.Selain itu, ribosom dan rRNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibandingkan dengan yang dikode oleh inti sel eukariot [Cooper, 2000].
Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs.
Klorofil
Klorofil adalah kelompok pigmenfotosintesis yang terdapat dalam tumbuhan, menyerap cahaya merah, biru dan ungu, serta merefleksikan cahaya hijau yang menyebabkan tumbuhan memperoleh ciri warnanya. Terdapat dalam kloroplas dan memanfaatkan cahaya yang diserap sebagai energi untuk reaksi-reaksi cahaya dalam proses fotosintesis.
Klorofil A merupakan salah satu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrof.Klorofil B terdapat pada ganggang hijau chlorophyta dan tumbuhan darat.Klorofil C terdapat pada ganggang coklat Phaeophyta serta diatome Bacillariophyta.Klorofil d terdapat pada ganggang merah Rhadophyta.Akibat adanya klorofil, tumbuhan dapat menyusun makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari.
Bagian-bagian Chloroplast.
Kloroplas atau Chloroplast adalah plastid yang mengandung klorofil.Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesistumbuhan.Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel.Bila ada, maka tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastid.Pada tumbuhan tingkat tinggi umumnya berbentuk cakram (kira-kira 2 x 5 mm, kadang-kadang lebih besar), tersusun dalam lapisan tunggal dalam sitoplasma tetapi bentuk dan posisinya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya.Pada ganggang, bentuknya dapat seperti mangkuk, spiral, bintang menyerupai jaring, seringkali disertai pirenoid.
Kloroplas matang pada beberapa ganggang ,biofita dan likopoda dapat memperbanyak diri dengan pembelahan. Kesinambungan kloroplas terjadi melalui pertumbuhan dan pembelahan proplastid di daerah meristem.Secara khas kloroplas dewasa mencakup dua membran luar yang menyalkuti stroma homogen, di sinilah berlangsung reaksi-reaksi fase gelap.Dalam stroma tertanam sejumlah grana, masing-masing terdiri atas setumpuk tilakoid yang berupa gelembung bermembran, pipih dan diskoid (seperti cakram).Membran tilakoid menyimpan pigmen-pigmen fotosintesis dan sistem transpor elektron yang terlibat dalam fase fotosintesis yang bergantung pada cahaya.Grana biasanya terkait dengan lamela intergrana yang bebas pigmen.
Prokariota yang berfotosintesis tidak mempunyai kloroplas, tilakoid yang banyak itu terletak bebas dalam sitoplasma dan memiliki susunan yang beragam dengan bentuk yang beragam pula.Kloroplas mengandung DNA lingkar dan mesin sistesis protein, termasuk ribosom dari tipe prokariotik.
Asal Usul Kloroplas
Seperti halnya mitokondria, kloroplas juga terbentuk melalui endosimbiosis.Pada awal pertengahan kehidupan telah terbentuk sel autotrof yang diduga mirip dengan Cyanobakteri (bakteri biru) pada masa sekarang ini.Sel purba heterotrof yang bernapas secara aerobik dan memiliki membran inti, menelan sel autotrof yang mampu berfotosintesis.
Sel autotrof yang hidup di dalamnya mendapatkan karbon dioksida dan air dari sel inangnya, sementara itu sel inang mendapatkan oksigen dan hasil-hasil fotosintesis.Sel autotrof ini akhirnya menjadi kloroplas.Terbentuklah sel berkloroplas, berinti, memiliki mitokondria, yang merupakan cikal bakal sel tumbuhan.
Hipotesis endosimbiosis kloroplas ini dikemukakan berdasarkan kenyatan pada saat ini, bahwa:
- Kloroplas memiliki membran rangkap dan membran luarnya mirip dengan struktur membran sel.
- Ada beberapa fotosintetik (cyanobakteria) yang memiliki membrane fotosintetik, yang mirip dengan tilakoid pada kloroplas.
- Didalam kloroplas terdapat DNA yang juga dijumpai pada bakteri fotosintetik.
- Kloroplas dapat bertambah banyak melalui pembelahan, seperti halnya bakteri.
Struktur Kloroplas Kloroplas terdiri atas dua bagian besar, yaitu bagian amplop dan bagian dalam.Bagian amplop kloroplas terdiri dari membran luar yang bersifat sangat permeabel, membran dalam yang bersifat permeabel serta merupakan tempat protein transpor melekat, dan ruang antar membran yang terletak di antara membran luar dan membran dalam. Bagian dalam kloroplas mengandung DNA , RNAs, ribosom, stroma (tempat terjadinya reaksi gelap), dan granum. Granum terdiri atas membran tilakoid (tempat terjadinya reaksi terang) dan ruang tilakoid (ruang di antara membran tilakoid).Pada tanaman C3, kloroplas terletak pada sel mesofil.Contoh tanaman C3 adalah padi (Oryza sativa), gandum (Triticum aestivum), kacang kedelai (Glycine max), dan kentang (Solanum tuberosum).Pada tanaman C4, kloroplas terletak pada sel mesofil dan bundle sheath cell.Contoh tanaman C4 adalah jagung (Zea mays) dan tebu (Saccharum officinarum).
Genom Kloroplas Kloroplas pada tanaman tingkat tinggi merupakan evolusi dari bakteri fotosintetik menjadi organel sel tanaman. Genom kloroplas terdiri dari 121 024 pasang nukleotida serta mempunyai inverted repeats (2 kopi) yang mengandung gen-gen rRNA (16S dan 23S rRNAs) untuk pembentukan ribosom. Genom kloroplas mempunyai subunit yang besar yaitu penyandi ribulosa biphosphate carboxylase.Protein yang terlibat di dalam kloroplas sebanyak 60 protein. 2/3nya diekspresikan oleh gen yang terdapat di inti sel sementara 1/3nya diekspresikan dari genom kloroplas.
SOAL!!
1. Jelaskan mekanisme fisiologis proses difusi dan osmosis di dalm sel ?
2. Jelaskan informasi tentang : mitokondria,lisosom,retikulum endoplasma,badan golgi,dan sentriol.
Jawaban :
1. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif mencakup osmosis dan difusi. Difusi dibedakan menjadi difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa.Osmosis adalah kasus khusus dari transpor pasif, dimana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis, dikenal larutan hipertonik (larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi), larutan hipotonik (larutan dengan konsentrasi terlarut rendah), dan larutan isotonik (dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama). Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Dalam proses osmosis, pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air terikat (tertarik) ke molekul gula (terlarut), sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik, memiliki lebih banyak molekul air yang bebas (tidak terikat oleh molekul terlarut), sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran.Oleh sebab itu, dalam osmosis aliran netto molekul air adalah dari larutan hipotonik ke hipertonik. Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Perubahan bentuk sel terjadi jika terdapat pada larutan yang berbeda. Sel yang terletak pada larutan isotonik, maka volumenya akan konstan. Dalam hal ini, sel akan mendapat dan kehilangan air yang sama. Banyak hewan-hewan laut, seperti bintang laut (Echinodermata) dan kepiting (Arthropoda) cairan selnya bersifat isotonik dengan lingkungannya. Jika sel terdapat pada larutan yang hipotonik, maka sel tersebut akan mendapatkan banyak air, sehingga bisa menyebabkan lisis (pada sel hewan), atau turgiditas tinggi (pada sel tumbuhan). Sebaliknya, jika sel berada pada larutan hipertonik, maka sel banyak kehilangan molekul air, sehingga sel menjadi kecil dan dapat menyebabkan kematian. Pada hewan, untuk bisa bertahan dalam lingkungan yang hipo- atau hipertonik, maka diperlukan pengaturan keseimbangan air, yaitu dalam proses osmoregulasi.
Difusi
a. difusi dipermudah dengan saluran protein Substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membrane plasma. Substansi-substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang di bentuk oleh protein.Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral.
b. difusi dipermudah dengan protein pembawa proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu salauran dan mengikat substansi yang ditranspor. Protein ini disebut protein pembawa.Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa.
Diffusi : gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi tinggi (hipertonik) ke konsentrasi rendah (hipotonik). Molekul-molekul gas seperti oksigen dan karbon dioksida selalu bergerak sepanjang waktu, demikian pula mulekul-molekul cairan atau zat lain seperti gula yang terlarut dalam air. Sebagai akibat dari gerakan ini, molekul-molekul itu akan tersebar merata mengisi ruang yang ada. Proses ini disebut difusi. Berbagai ion dan molekul-molekul seperti glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol berdifusi lebih lambat.Molekul-molekul yang tidak bermuatan dan molekul lemak yang terlarut dapat bergerak melewati membran lebih cepat. Proses difusi gas, cairan atau zat-zat terlarut terjadi dari daerah kerapatan tinggi menuju daerah kerapatan rendah atau nol (mengandung sedikit molekul zat atau tidak ada), sehingga kerapatannya menjadi sama di mana – mana. Apakah peristiwa difusi akan terjadi atau tidak, tergantung apakah membran sel meluluskan meolekul melaluinya atau tidak. Hal ini sesuai dengan membran sel yang selektif permiabel.Molekul-molekul kecil seperti molekul H2O, CO2 dan O2 dapat dengan mudah dan cepat melalui membran, sehingga difusi cenderung untuk mempersamakan kerapatan atau konsentrasi molekul-molekul di dalam dan di luar sel sepanjang waktu.
Misal pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat pernafasan, penyebaran setetes tinta dalam air.
Osmosis : proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah (hipotonik) ke daerah yang berkonsentrasi tinggi (hipertonik) melalui membran semipermiabel. Membran semipermiabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya.
Osmosis pada sel tumbuhan di sebelah luar terdapat dinding sel dan di dalamnya terdapat protoplasma dan vakoula.Vakoula ini dilapisi oleh lapisan proplasma yang sifatnya semipermiabel.Cairan protoplasma sel tumbuhan ini umumnya merupakan cairan yang hipertonik dibandingkan dengan dengan cairan disekelilingnya.Sel tumbuhan mengambil air dari sekelilingnya secara osmosis, air masuk vakuola dan menekan protoplasma. Protoplasma menekan dinding sel. Osmosis dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Jika terlalu banyak air masuk ke dalam sel, sel akan menggembung, bahkan mungkin dapat pecah. Tekanan pada dinding sel tersebut dinamakan takanan turgor.Karena turgor dinding sel sedikit mengembang.Waktu dinding sel mengembang secara secara maksimum dikatakan sel mempunyai turgor penuh atau turgid penuh. Keadaan menjadi sebaliknya jika sel diletakkan dalam suatu larutan yang yang bersifat hipertonik, maka air akan keluar dari sel. Bila air sel banyak keluar, maka isi sel terlepas dari dinding sel. Peristiwa telepasnya protoplasma dari dinding sel disebut plasmolisis.
2. a)Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah “pembangkit tenaga” bagi sel.
Keberadaan mitokondria didukung oleh hipotesis endosimbiosis yang mengatakan bahwa pada tahap awal evolusi sel eukariot bersimbiosis dengan prokariot (bakteri) [Margullis, 1981].Kemudian keduanya mengembangkan hubungan simbiosis dan membentuk organel sel yang pertama.Adanya DNA pada mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya.Hipotesis ini ditunjang oleh beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri. Ukuran mitokondria menyerupai ukuran bakteri, dan keduanya bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Hal yang utama adalah keduanya memiliki DNA berbentuk lingkar.Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri yang berbeda dengan sistem genetik inti.Selain itu, ribosom dan rRNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibandingkan dengan yang dikode oleh inti sel eukariot [Cooper, 2000].
Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs.
b)Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik.Di dalamnya, organel ini memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase.Semua enzim tersebut aktif pada pH 5.Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi.
Pada tumbuhan organel ini lebih dikenal sebagai vakuola, yang selain untuk mencerna, mempunyai fungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman.
c)RETIKULUM ENDOPLASMA (RE) adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik.
Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis.Kantung ini disebut cisternae.Fungsi retikulum endoplasma bervariasi, tergantung pada jenisnya. Retikulum Endoplasma (RE) merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma melipiti separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. (kata endoplasmik berarti “di dalam sitoplasma” dan retikulum diturunkan dari bahasa latin yang berarti “jaringan”).
Pengertian lain menyebutkan bahwa RE sebagai perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplsma.
Lubang/saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya.
Ada tiga jenis retikulum endoplasma:
RE kasar Di permukaan RE kasar, terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom.Ribosom ini berperan dalam sintesis protein.Maka, fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat sintesis protein.RE halus Berbeda dari RE kasar, RE halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. RE halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. RE sarkoplasmik RE sarkoplasmik adalah jenis khusus dari RE halus. RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik.Yang membedakan RE sarkoplasmik dari RE halus adalah kandungan proteinnya.RE halus mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium.RE sarkoplasmik berperan dalam pemicuan kontraksi otot.
RE halus berfungsi dalam berbagai macam proses metabolisme, trmasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun
“RE berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri”
Jaring-jaring endoplasma adalah jaringan keping kecil-kecil yang tersebar bebas di antara selaput selaput di seluruh sitoplasma dan membentuk saluran pengangkut bahan.Jaring-jaring ini biasanya berhubungan dengan ribosom (titik-titik merah) yang terdiri dari protein dan asam nukleat, atau RNA.Partikel-partikel tadi mensintesis protein serta menerima perintah melalui RNA tersebut (Time Life, 1984).
Jadi fungsi RE adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetic antara inti sel dengan sitoplasma.
Fungsi Retikulum Endoplasma
• Menjadi tempat penyimpan Calcium, bila sel berkontraksi maka calcium akan dikeluarkan dari RE dan meuju ke sitosol
• Memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel.
(RE kasar)
• Mensintesis lemak dan kolesterol, ini terjadi di hati
(RE kasar dan RE halus)
• Menetralkan racun (detoksifikasi) misalnya RE yang ada di dalam sel-sel hati.
• Transportasi molekul-molekul dan bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain (RE kasar dan RE halus)
d)Badan Golgi
Mikrograf badan Golgi, terlihat sebagai tumpukan cincin setengah lingkaran berwarna hitam di bagian bawah gambar.Sejumlah vesikel bulat terlihat di sekitar organel ini.
Badan Golgi (disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom) adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa.Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal.Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi.Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom.
Badan Golgi ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi.
Struktur
Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya.Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel.
Badan golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Dari tubulus dilepaskan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim–enzim pembentuk dinding sel.
Permukaan badan golgi dibagi menjadi 2 yaitu cis-face dan trans-face. cis-face berhadapan langsung dengan retikulum endoplasma.
Fungsi
Skema transpor di dalam badan Golgi. 1. Vesikel retikulum endoplasma, 2. Vesikel eksositosis, 3.Sisterna, 4.Membran sel, 5.Vesikel sekresi.
Fungsi badan golgi:
1. Membentuk kantung (vesikula) untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain.
2. Membentuk membran plasma. Kantung atau membran golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma.
3. Membentuk dinding sel tumbuhan
4. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom.
5. Tempat untuk memodifikasi protein
6. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel
7. Untuk membentuk lisosom
Dalam badan golgi terdapat variasi coated vesicle, antara lain
Clathrin-coated adalah yang pertama ditemukan dan diteliti.tersusun dari clathrin dan adaptin. interaksi lateral antara adaptin dengan clatrin membentuk formasi tunas. jika tunas clathrin sudah tumbuh, protein yang larut dalam sitoplasma termasuk dynamin akan membentuk cincin di setiap leher tunas dan memutusnya.
COPI-coated memaket tunas dari bagian pre-golgi dan antar cisternae. beberapa protein COPI-coat memperlihatkan sekuens yang bermiripan dengan adaptin, dapat diduga berasal dari evolusi yang bermiripan.
COPII-coated memaket tunas dari retikulum endoplasma.
terdapat 2 protein dalam badan golgi. Protein Snare V-snare menuju T-snare dan akan bergabung. T-snare adalah protein yang ada di target sedangkan V-snare adalah vesikel snare. V-snare akan mencari T-snare dan kemudian akan berfusi menjadi satu. Protein Rab termasuk ke dalam golongan GTP-ase.protein Rab memudahkan dan mengatur kecepatan pelayaran vesikel dan pemasangan v-snare dan t-snare yang diperlukan pada penggabungan membran.
e)Sentrosom (Sentriol)
Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel (Mitosis maupun Meiosis). Sentrosom bertindak sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis.
Struktur ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron.
Pengertian Sel:
Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis.
Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional yang fundamental dari makhluk hidup.
Sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup.
Sejarah penemuan sel
Pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri.Kata sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga/ruangan.
Teori Sel dari SCHLEIDEN (1838) dan SCHWAHN (1839) ® Setiap organisme hidup tersusun dari sel-sel
Ukuran Sel
Sel Ukurannya sangat kecil untuk melihatnya diperlukan mikroskop
Contoh:
Sel Prokriotik : 1 – 10 mm
Sel Eukariotik : 10 – 100 mm
Karakteristik Dasar Sel
Sel sangat kompleks namun teratur
Sel memiliki program genetik dan memiliki cara untuk menggunakannya
Sel mampu memperbanyak diri
Sel membutuhkan,memperoleh dan menggunakan energi
Sel melakukan reaksi kimiawi
Sel mampu merespon terhadap berbagai rangsangan
Sel mampu mengatur diri
Struktur sel
Secara umum setiap sel memiliki
Membran sel
Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis lipid (lipid bilayer) dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel.
Struktur Membran Sel
Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida membran merupakan 2 lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Komponen muchus membran sel semipermanen di lapisan membran
Dua Lapis Lipid
Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid, selain itu terdapat senyawa lipid seperti sfingomyelin, kolesterol, dan glikolipida.Fosfolipid memiliki dua bagian yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik.Bagian hidrofobik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak sedangkan bagian hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Penamaan fosfolipid dan sifat masing-masing akan bergantung pada jenis gugus tambahan yang dimiliki oleh fosfolipid. Jenis-jenis fosfolipid penyusun membran sel antara lain adalah : fosfokolin (pc), fosfoetanolamin (pe), fosfoserin (ps), dan fosfoinositol (pi). Secara alami di alam fosfolipid akan membentuk struktur misel (struktur menyerupai bola) atau membran lipid 2 lapis. Karena strukturnya yang dinamis maka komponen fosfolipid di membran dapat melakukan pergerakan dan perpindahan posisi. Pergerakan yang terjadi antara lain adalah pergerakan secara lateral (Pergerakan molekul lipid dengan tetangganya pada monolayer membran) dan pergerakan secara flip flop (Tipe pergerakan trans bilayer).
Protein integral membran
Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus 2 lapisan lipid / transmembran.Protein integral memiliki domain membentang di luar sel dan di sitoplasma.Bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein, hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak diantaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel. Di sintesis di RE, gula dimodifikasi di badan golgi
Sistem transpor membran
Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik (CO2, O2), dan molekul polar yang sangat kecil (air, etanol). Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar (glukosa), ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel.Banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transpor pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus dan transpor aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus.
Transpor pasif
Transpor pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya.Transpor pasif ini bersifat spontan.Difusi, osmosis dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transpor pasif.Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengkonsumsi O2 masuk. Osmosis merupakan difusi pelarut melintasi membran selektif yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlarut total (dari hipotonis ke hipertonis). Difusi terfasilitasi juga masih dianggap ke dalam transpor pasif karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya.
Transpor aktif
Transpor aktif merupakan kebalikan dari transpor pasif dan bersifat tidak spontan.Arah perpindahan dari transpor ini melawan gradien konsentrasi.Transpor aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transpor aktif ialah channel protein dan carrier protein, serta ionophore .yang termasuk transpor aktif ialah coupled carriers, ATP driven pumps, dan light driven pumps. Dalam transpor menggunakan coupled carriers dikenal dua istilah, yaitu simporter dan antiporter. Simporter ialah suatu protein yang mentransportasikan kedua substrat searah, sedangkan antiporter mentransfer kedua substrat dengan arah berlawanan.ATP driven pump merupakan suatu siklus transpor Na+/K+ ATPase. Light driven pump umumnya ditemukan pada sel bakteri. Mekanisme ini membutuhkan energi cahaya dan contohnya terjadi pada Bakteriorhodopsin.
Sitoplasma
Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma.Pada sitoplasma terdapat kerangka sel (sitoskeleton), berbagai organel dan vesikuli serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula,Menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta Perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel.Walaupun semua sel memiliki sitoplasma, setiap jaringan maupun spesies memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda antara satu dengan yang lain.
Inti sel atau nukleus.
Nukleus merupakan organel pertama yang ditemukan, yang pertama kali dideskripsikan oleh Franz Bauer pada 1802 dan dijabarkan lebih detil oleh ahli botani Skotlandia, Robert Brown pada tahun 1831.
Inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik.Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri.
Elemen struktural utama nukleus adalah membran inti, suatu membran lapis ganda yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan bagian inti dengan sitoplasma sel, serta lamina inti, suatu struktur dalam nukleus yang memberi dukungan mekanis seperti sitoskeleton yang menyokong sel secara keseluruhan.Secara garis besar, membran inti terdiri atas tiga bagian, yaitu membran luar, ruang perinuklear, dan membran dalam.Membran luar dari nukleus berkesinambungan dengan retikulum endoplasma (RE) kasar dan bertaburan dengan ribosom. Sifat membran inti yang tak permeabel terhadap sebagian besar molekul membuat nukleus memerlukan pori inti agar molekul dapat bergerak melintasi membran. Pori nukleus bagaikan terowongan yang terletak pada membran nukleus yang berfungsi menghubungkan nukleoplasma dengan sitosol. Fungsi utama dari pori nukleus adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Molekul yang keluar, kebanyakan mRNA, digunakan untuk sintesis protein. Pori nukleus tersusun atas 4 subunit, yaitu subunit kolom, subunit anular, subunit lumenal, dan subunit ring. Subunit kolom berfungsi dalam pembentukan dinding pori nukleus, subunit anular berguna untuk membentuk spoke yang mengarah menuju tengah dari pori nukleus, subunit lumenal mengandung protein transmembran yang menempelkan kompleks pori nukleus pada membran nukleus, sedangkan subunit ring berfungsi untuk membentuk permukaan sitosolik (berhadapan dengan sitoplasma) dan nuklear (berhadapan dengan nukleoplasma) dari kompleks pori nukleus.
Meskipun bagian dalam nukleus tidak mengandung badan yang dibatasi oleh membran, isi nukleus tidak seragam dan memiliki beberapa badan subnukleus yang terbentuk dari protein-protein unik, molekul RNA, serta gugus DNA.Contoh utama dari badan subnukleus adalah nukleolus, yang terutama terlibat dalam pembentukan ribosom.Setelah diproduksi oleh nukleolus, ribosom diekspor ke sitoplasma untuk menjalankan fungsi translasi mRNA.
Sitoplasma dan inti sel bersama-sama disebut sebagai protoplasma. Sitoplasma berwujud cairan kental (sitosol) yang di dalamnya terdapat berbagai organel yang memiliki fungsi yang terorganisasi untuk mendukung kehidupan sel. Organel memiliki struktur terpisah dari sitosol dan merupakan “kompartementasi” di dalam sel, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi yang tidak mungkin berlangsung di sitosol. Sitoplasma juga didukung oleh jaringan kerangka yang mendukung bentuk sitoplasma sehingga tidak mudah berubah bentuk.
Organel-organel yang ditemukan pada sitoplasma adalah
mitokondria (kondriosom)
badan Golgi (diktiosom)
retikulum endoplasma
plastida (khusus tumbuhan, mencakup leukoplas, kloroplas dan kromoplas)
vakuola (khusus tumbuhan)
Mitokondria
Mitokondria (mitochondrion’, plural: mitochondria’) atau kondriosom (chondriosome) adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah “pembangkit tenaga” bagi sel.
Mitokondria merupakan salah satu bagian sel yang paling penting karena di sinilah energi dalam bentuk ATP [Adenosine Tri-Phosphate] dihasilkan. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam.Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan cristae.Di dalam Mitokondria terdapat ‘ruangan’ yang disebut matriks, dimana beberapa mineral dapat ditemukan.Sel yang mempunyai banyak Mitokondria dapat dijumpai di jantung, hati, dan otot.
Keberadaan mitokondria didukung oleh hipotesis endosimbiosis yang mengatakan bahwa pada tahap awal evolusi sel eukariot bersimbiosis dengan prokariot (bakteri) [Margullis, 1981].Kemudian keduanya mengembangkan hubungan simbiosis dan membentuk organel sel yang pertama.Adanya DNA pada mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya.Hipotesis ini ditunjang oleh beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri. Ukuran mitokondria menyerupai ukuran bakteri, dan keduanya bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Hal yang utama adalah keduanya memiliki DNA berbentuk lingkar.Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri yang berbeda dengan sistem genetik inti.Selain itu, ribosom dan rRNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibandingkan dengan yang dikode oleh inti sel eukariot [Cooper, 2000].
Struktur
Struktur umum suatu mitokondrion
Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memilki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak, misalnya sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 µm dan panjang 0,5 – 1,0 µm. Struktur mitokondria terdiri dari empat bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran [Cooper, 2000].
Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram-negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transpor lipid ke matriks untuk menjalani β-oksidasi menghasilkan Asetil KoA.
Membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan membran luar terdiri dari 20% lipid dan 80% protein.Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks, disebut krista [Lodish, 2001]. Stuktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transpor yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam.
Ruang antar membran yang terletak diantara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi β-oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik, yang dikenal dengan DNA mitkondria (mtDNA), ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik serta ion-ion seperti magnesium, kalsium dan kalium
Fungsi mitokondria
Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika piruvat di transpor dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien yaitu sekitar tiga puluh molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi, sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan dua molekul ATP. Proses pembentukan energi atau dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas lima tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Proses pembentukan ATP melibatkan proses transpor elektron dengan bantuan empat kompleks enzim, yang terdiri dari kompleks I (NADH dehidrogenase), kompleks II (suksinat dehidrogenase), kompleks III (koenzim Q – sitokrom C reduktase), kompleks IV (sitokrom oksidase), dan juga dengan bantuan FoF1 ATP Sintase dan Adenine Nucleotide Translocator (ANT) [Wallace, 1997].
Siklus Hidup Mitokondria
Mitokondria dapat melakukan replikasi secara mandiri (self replicating) seperti sel bakteri.Replikasi terjadi apabila mitokondria ini menjadi terlalu besar sehingga melakukan pemecahan (fission).Pada awalnya sebelum mitokondria bereplikasi, terlebih dahulu dilakukan replikasi DNA mitokondria. Proses ini dimulai dari pembelahan pada bagian dalam yang kemudian diikuti pembelahan pada bagian luar. Proses ini melibatkan pengkerutan bagian dalam dan kemudian bagian luar membran seperti ada yang menjepit mitokondria. Kemudian akan terjadi pemisahan dua bagian mitokondria [Childs, 1998].
DNA mitokondria
Mitokondria memiliki DNA tersendiri, yang dikenal sebagai mtDNA (Ing. mitochondrial DNA).MtDNA berpilin ganda, sirkular, dan tidak terlindungi membran (prokariotik).Karena memiliki ciri seperti DNA bakteri, berkembang teori yang cukup luas dianut, yang menyatakan bahwa mitokondria dulunya merupakan makhluk hidup independen yang kemudian bersimbiosis dengan organisme eukariotik.Teori ini dikenal dengan teori endosimbion.Pada makhluk tingkat tinggi, DNA mitokondria yang diturunkan kepada anaknya hanya berasal dari betinanya saja (mitokondria sel telur).Mitokondria jantan tidak ikut masuk ke dalam sel telur karena letaknya yang berada di ekor sperma.Ekor sperma tidak ikut masuk ke dalam sel telur sehingga DNA mitokondria jantan tidak diturunkan.
Badan golgi
Badan Golgi (disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom) adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal.Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi.Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom.
Badan Golgi ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi.
Struktur
Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel.
Badan golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Dari tubulus dilepaskan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim–enzim pembentuk dinding sel.
Badan Golgi merupakan suatu bagian sel yang hampir serupa dengan Retikulum Endoplasma.Hanya saja, Badan Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang juga ditutupi oleh membran.Badan Golgi mempunyai 2 bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis menerima vesikel-vesikel [vesicle] yang pada umumnya berasal dari Retikulum Endoplasma Kasar. Vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan di dalam Badan Golgi dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan dan lain sebagainya. Ruangan-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju bagian trans. Di bagian inilah ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan membentuk vesikel, dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau ke luar sel.
Fungsi badan golgi:
1. Membentuk kantung (vesikula) untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain.
2. Membentuk membran plasma. Kantung atau membran golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma.
3. Membentuk dinding sel tumbuhan
4. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom.
5. Tempat untuk memodifikasi protein
6. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel
7. Untuk membentuk lisosom
Dalam badan golgi terdapat variasi coated vesicle, antara lain
Clathrin-coated adalah yang pertama ditemukan dan diteliti. tersusun dari clathrin dan adaptin. interaksi lateral antara adaptin dengan clatrin membentuk formasi tunas. jika tunas clathrin sudah tumbuh, protein yang larut dalam sitoplasma termasuk dynamin akan membentuk cincin di setiap leher tunas dan memutusnya.
COPI-coated memaket tunas dari bagian pre-golgi dan antar cisternae. beberapa protein COPI-coat memperlihatkan sekuens yang bermiripan dengan adaptin, dapat diduga berasal dari evolusi yang bermiripan.
COPII-coated memaket tunas dari retikulum endoplasma.
terdapat 2 protein dalam badan golgi. Protein Snare V-snare menuju T-snare dan akan bergabung. T-snare adalah protein yang ada di target sedangkan V-snare adalah vesikel snare. V-snare akan mencari T-snare dan kemudian akan berfusi menjadi satu. Protein Rab termasuk ke dalam golongan GTP-ase.protein Rab memudahkan dan mengatur kecepatan pelayaran vesikel dan pemasangan v-snare dan t-snare yang diperlukan pada penggabungan membran.
Retikulum endoplasma
Retikulum Endoplasma (RE, atau endoplasmic reticula) adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik.
Retikulum Endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran.Di sekitar Retikulum Endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol atau cytosol.Retikulum Endoplasma sendiri terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nm (nanometer, 10-9 meter).Membran ini berhubungan langsung dengan selimut nukleus atau nuclear envelope.
Pada bagian-bagian Retikulum Endoplasma tertentu, terdapat ribuan ribosom atau ribosome. Ribosom merupakan tempat dimana proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Bagian ini disebut dengan Retikulum Endoplasma Kasar atau Rough Endoplasmic Reticulum. Kegunaan daripada Retikulum Endoplasma Kasar adalah untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Kebanyakan protein tersebut tidak diperlukan sel dalam jumlah banyak dan biasanya akan dikeluarkan dari sel. Contoh protein tersebut adalah enzim dan hormon.Sedangkan bagian-bagian Retikulum Endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut Retikulum Endoplasma Halus atau Smooth Endoplasmic Reticulum. Kegunaannya adalah untuk membentuk lemak dan steroid.Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari Retikulum Endoplasma Halus terdapat di beberapa organ seperti hati.
Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis.Kantung ini disebut cisternae.Fungsi retikulum endoplasma bervariasi, tergantung pada jenisnya. Retikulum Endoplasma (RE) merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma melipiti separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. (kata endoplasmik berarti “di dalam sitoplasma” dan retikulum diturunkan dari bahasa latin yang berarti “jaringan”).
Pengertian lain menyebutkan bahwa RE sebagai perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplsma.Lubang/saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya.
Ada tiga jenis retikulum endoplasma:
RE kasar Di permukaan RE kasar, terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein.Maka, fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat sintesis protein.RE halus Berbeda dari RE kasar, RE halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. RE halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. RE sarkoplasmik RE sarkoplasmik adalah jenis khusus dari RE halus. RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik.Yang membedakan RE sarkoplasmik dari RE halus adalah kandungan proteinnya.RE halus mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium.RE sarkoplasmik berperan dalam pemicuan kontraksi otot.
RE halus berfungsi dalam berbagai macam proses metabolisme, trmasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun
“RE berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri”
Jaring-jaring endoplasma adalah jaringan keping kecil-kecil yang tersebar bebas di antara selaput selaput di seluruh sitoplasma dan membentuk saluran pengangkut bahan. Jaring-jaring ini biasanya berhubungan dengan ribosom (titik-titik merah) yang terdiri dari protein dan asam nukleat, atau RNA.Partikel-partikel tadi mensintesis protein serta menerima perintah melalui RNA tersebut (Time Life, 1984).
Jadi fungsi RE adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetic antara inti sel dengan sitoplasma.
Fungsi Retikulum Endoplasma
Menjadi tempat penyimpan Calcium, bila sel berkontraksi maka calcium akan dikeluarkan dari RE dan menuju ke sitosol
• Memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel.
(RE kasar)
• Mensintesis lemak dan kolesterol, ini terjadi di hati
(RE kasar dan RE halus)
• Menetralkan racun (detoksifikasi) misalnya RE yang ada di dalam sel-sel hati.
• Transportasi molekul-molekul dan bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain (RE kasar dan RE halus)
plastida (khusus tumbuhan, mencakup leukoplas, kloroplas dan kromoplas)
Plastida adalah organel pada sel tumbuhan (dalam arti luas, Viridoplantae). Organel ini paling dikenal dalam bentuknya yang paling umum, kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada kenyataannya, plastida dikenal dalam berbagai bentuk:
proplastida, bentuk belum “dewasa”
leukoplas, bentuk dewasa tanpa mengandung pigmen, ditemukan terutama di akar
kloroplas, bentuk aktif yang mengandung pigmen klorofil, ditemukan pada daun, bunga, dan bagian-bagian berwarna hijau lainnya
kromoplas, bentuk aktif yang mengandung pigmen karotena, ditemukan terutama pada bunga dan bagian lain berwarna jingga
amiloplas, bentuk semi-aktif yang mengandung butir-butir tepung, ditemukan pada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk tepung, seperti akar, rimpang, dan batang (umbi) serta biji.
elaioplas, bentuk semi-aktif yang mengandung tetes-tetes minyak/lemak pada beberapa jaringan penyimpan minyak, seperti endospermium (pada biji)
etioplas, bentuk semi-aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas terhadap lingkungan kurang cahaya; etioplas dapat segera aktif dengan membentuk klorofil hanya dalam beberapa jam, begitu mendapat cukup pencahayaan.
Plastida adalah organel vital pada tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis, sintesis asam-asam lemak, serta beberapa fungsi sehari-hari sel.
Secara evolusi plastida dianggap sebagai prokariota yang bersimbiosis ke dalam sel eukariota dan kemudian kehilangan sifat otonomi penuhnya. Teori endosimbiosis ini mirip dengan yang terjadi terhadap mitokondria namun introduksi plastida dianggap terjadi lebih kemudian.
vakuola (khusus tumbuhan)
Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan (cell sap dalam bahasa Inggris). Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya.Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah.
Pada sel daun dewasa, vakuola mendominasi sebagian besar ruang sel sehingga seringkali sel terlihat sebagai ruang kosong karena sitosol terdesak ke bagian tepi dari sel.
Bagi tumbuhan, vakuola berperan sangat penting dalam kehidupan karena mekanisme pertahanan hidupnya bergantung pada kemampuan vakuola menjaga konsentrasi zat-zat terlarut di dalamnya. Proses pelayuan, misalnya, terjadi karena vakuola kehilangan tekanan turgor pada dinding sel. Dalam vakuola terkumpul pula sebagian besar bahan-bahan berbahaya bagi proses metabolisme dalam sel karena tumbuhan tidak mempunyai sistem ekskresi yang efektif seperti pada hewan. Tanpa vakuola, proses kehidupan pada sel akan berhenti karena terjadi kekacauan reaksi biokimia.
Sentriol
Sentriol merupakan organel tak bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel ini berukuran kecil , jumlahnya sepasang dan letaknya dekat membrane inti dalam posisi tegak lurus antar keduanya. Organel ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelendong pembelahan pada saat terjadi pembelahan sel.
Lisosom ® Digesti nutrisi, bahan-bahan asing dan organel-organel yang rusak
Mikrobodi ® Berbagai proses metabolisme seperti memecahkan H2O2
Ribosom ® Sintesa Polipeptida / protein
Cincin kontraktil hanya ditemukan pada sel hewan. Cincin kontraktil terbentuk pada saat pembelahan sel, tepatnya pada tahap sitokinesis atau pembagian sitoplasma sel anak.Pembagian siitoplasma berlangsung setelah pembagian materi inti (kriokinesis) selesai. Pada sel tumbuhan , setelah pembagian materi inti selesai maka dinding sel baru terbentuk tanpa adanya cincin kontraktil.
Sitoskeleton ® Memelihara bentuk sel; melekatkan/pertautkan organel-organel; pergerakan organel dalam sel; gerakan sel (termasuk silia, flagella, dan sentriol pada sel hewan)
Dinding Sel ® Memelihara bentuk sel dan menyokong rangka. Proteksi permukaan sel. Mengikat sel-sel jaringan (terdapat pada tumbuhan, jamur dan beberapa protista)
Beberapa senyawa penyusun dinding sel, antara lain:
a. Hemiselulosa
Hemiselulosa merupakan polisakarida yang tersusun atas glukosa, xilosa, manosa dan asam glukoronat. Di dalam dinding sel, hemiselulosa berfungsi sebagai perekat antar mikrofibril selulosa.
b. Pektin
Pektin merupakan polisakarida yang tersusun atas galaktosa, arabinosa, dan asam galakturonat.
c. Lignin
Lignin hanya dijumpai pada dinding sel yang dewasa dan berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan.
d. Kutin
Kutin merupakan suatu selubung atau lapisan pada permukaan atas daun atau batang dan berfungsi untuk mencegah dehidrasi akibat penguapan dan melindungi kerusakan sel akibat patogen dari luar.
e. Protein dan lemak
Di dalam dinding sel ditemukan dalam jumlah yang sedikit.
Permukaan/membran sel (pada Hewan) ® proteksi permukaan; Mengikat sel-sel dalam jaringan
Penghubung Sel ® Komunikasi antar sel; mengikat sel-sel dalam jaringan
Perbedaan Sel Hewan dan Tumbuhan
Sel tumbuhan dan sel hewan
Sel tumbuhan
Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan.
Mempunyai bentuk yang tetap.Mempunempunyai dinding sel [cell wall] dari selulosa.
Mempunyai vakuola [vacuole] atau rongga sel yang besar.
Tidak Mempunyai sentrosom [centrosome].Tidak memiliki lisosom [lysosome].Nukleus lebih kecil daripada vakuola.
Sel hewan
Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan.
Tidak mempunyai bentuk yang tetap.
Tidak mempunyai dinding sel [cell wall].
Tidak mempunyai vakuola [vacuole], walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola (tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan).Yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel atau [vesicle].
Mempunyai sentrosom [centrosome].
Memiliki lisosom [lysosome].
Nukleus lebih besar daripada vesikel.
Siklus sel
Siklus sel adalah proses duplikasi secara akurat untuk menghasilkan jumlah DNA kromosom yang cukup banyak dan mendukung segregasi untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berulang (siklik)
Pertumbuhan dan perkembangan sel tidak lepas dari siklus kehidupan yang dialami sel untuk tetap bertahan hidup. Siklus ini mengatur pertumbuhan sel dengan meregulasi waktu pembelahan dan mengatur perkembangan sel dengan mengatur jumlah ekspresi atau translasi gen pada masing-masing sel yang menentukan diferensiasinya.
Fase pada siklus sel
Fase S (sintesis): Tahap terjadinya replikasi DNA
Fase M (mitosis): Tahap terjadinya pembelahan sel (baik pembelahan biner atau pembentukan tunas)
Fase G (gap): Tahap pertumbuhan bagi sel.
Fase G0, sel yang baru saja mengalami pembelahan berada dalam keadaan diam atau sel tidak melakukan pertumbuhan maupun perkembangan. Kondisi ini sangat bergantung pada sinyal atau rangsangan baik dari luar atau dalam sel. Umum terjadi dan beberapa tidak melanjutkan pertumbuhan (dorman) dan mati.
Fase G1, sel eukariot mendapatkan sinyal untuk tumbuh, antara sitokinesis dan sintesis.
Fase G2, pertumbuhan sel eukariot antara sintesis dan mitosis.
Fase tersebut berlangsung dengan urutan S > G2 > M > G0 > G1 > kembali ke S. Dalam konteks Mitosis, fase G dan S disebut sebagai Interfase.
Regenerasi dan diferensiasi sel
Regenerasi sel adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel yang bertujuan untuk mengisi ruang tertentu pada jaringan atau memperbaiki bagian yang rusak.
Diferensiasi sel adalah proses pematangan suatu sel menjadi sel yang spesifik dan fungsional, terletak pada posisi tertentu di dalam jaringan, dan mendukung fisiologis hewan. Misalnya, sebuah stem cell mampu berdiferensiasi menjadi sel kulit.
Saat sebuah sel tunggal, yaitu sel yang telah dibuahi, mengalami pembelahan berulang kali dan menghasilkan pola akhir dengan keakuratan dan kompleksitas yang spektakuler, sel itu telah mengalami regenerasi dan diferensiasi.
Empat proses esensial pengkonstruksian embrio
Regenerasi dan diferensiasi sel hewan ditentukan oleh genom. Genom yang identik terdapat pada setiap sel, namun mengekspresikan set gen yang berbeda, bergantung pada jumlah gen yang diekspresikan.Misalnya, pada sel retina mata, tentu gen penyandi karakteristik penangkap cahaya terdapat dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada ekspresi gen indera lainnya.
Pengekspresian gen itu sendiri mempengaruhi jumlah sel, jenis sel, interaksi sel, bahkan lokasi sel. Oleh karena itu, sel hewan memiliki 4 proses esensial pengkonstruksian embrio yang diatur oleh ekspresi gen, sebagai berikut:
Proliferasi sel
menghasilkan banyak sel dari satu sel
Spesialisasi sel
menciptakan sel dengan karakteristik berbeda pada posisi yang berbeda
Interaksi sel
mengkoordinasi perilaku sebuah sel dengan sel tetangganya
Pergerakan sel
menyusun sel untuk membentuk struktur jaringan dan organ
Pada embrio yang berkembang, keempat proses ini berlangsung bersamaan. Tidak ada badan pengatur khusus untuk proses ini. Setiap sel dari jutaan sel embrio harus membuat keputusannya masing-masing, menurut jumlah kopi instruksi genetik dan kondisi khusus masing-masing sel.
Sel tubuh, seperti otot, saraf, dsb. tetap mempertahankan karakteristik karena masih mengingat sinyal yang diberikan oleh nenek moyangnya saat awal perkembangan embrio
Sel-sel khusus
Sel Tidak Berinti, contohnya trombosit dan eritrosit (Sel darah merah). Di dalam sel darah merah, terdapat Haemoglobin sebagai pengganti nukleus (inti sel).
Sel Berinti Banyak, contohnya Paramecium sp dan sel otot
Sel hewan berklorofil, contohnya euglena sp. Euglena sp adalah hewan uniseluler berklorofil.
Sel pendukung, contohnya adalah sel xilem. Sel xilem akan mati dan meninggalkan dinding sel sebagai “tulang” dan saluran air. Kedua ini sangatlah membantu dalam proses transpirasi pada tumbuhan.
1. Jelaskan mekanisme fisiologis proses difusi dan osmosis di dalm sel ?
2. Jelaskan informasi tentang : mitokondria,lisosom,retikulum endoplasma,badan golgi,dan sentriol.
Jawaban :
1.
Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif mencakup osmosis dan difusi. Difusi dibedakan menjadi difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa.Osmosis adalah kasus khusus dari transpor pasif, dimana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis, dikenal larutan hipertonik (larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi), larutan hipotonik (larutan dengan konsentrasi terlarut rendah), dan larutan isotonik (dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama). Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Dalam proses osmosis, pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air terikat (tertarik) ke molekul gula (terlarut), sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik, memiliki lebih banyak molekul air yang bebas (tidak terikat oleh molekul terlarut), sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran.Oleh sebab itu, dalam osmosis aliran netto molekul air adalah dari larutan hipotonik ke hipertonik. Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Perubahan bentuk sel terjadi jika terdapat pada larutan yang berbeda. Sel yang terletak pada larutan isotonik, maka volumenya akan konstan. Dalam hal ini, sel akan mendapat dan kehilangan air yang sama. Banyak hewan-hewan laut, seperti bintang laut (Echinodermata) dan kepiting (Arthropoda) cairan selnya bersifat isotonik dengan lingkungannya. Jika sel terdapat pada larutan yang hipotonik, maka sel tersebut akan mendapatkan banyak air, sehingga bisa menyebabkan lisis (pada sel hewan), atau turgiditas tinggi (pada sel tumbuhan). Sebaliknya, jika sel berada pada larutan hipertonik, maka sel banyak kehilangan molekul air, sehingga sel menjadi kecil dan dapat menyebabkan kematian. Pada hewan, untuk bisa bertahan dalam lingkungan yang hipo- atau hipertonik, maka diperlukan pengaturan keseimbangan air, yaitu dalam proses osmoregulasi.
Difusi
a. difusi dipermudah dengan saluran protein Substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membrane plasma. Substansi-substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang di bentuk oleh protein.Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral.
b. difusi dipermudah dengan protein pembawa proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu salauran dan mengikat substansi yang ditranspor. Protein ini disebut protein pembawa.Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa.
Diffusi : gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi tinggi (hipertonik) ke konsentrasi rendah (hipotonik). Molekul-molekul gas seperti oksigen dan karbon dioksida selalu bergerak sepanjang waktu, demikian pula mulekul-molekul cairan atau zat lain seperti gula yang terlarut dalam air. Sebagai akibat dari gerakan ini, molekul-molekul itu akan tersebar merata mengisi ruang yang ada. Proses ini disebut difusi. Berbagai ion dan molekul-molekul seperti glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol berdifusi lebih lambat.Molekul-molekul yang tidak bermuatan dan molekul lemak yang terlarut dapat bergerak melewati membran lebih cepat. Proses difusi gas, cairan atau zat-zat terlarut terjadi dari daerah kerapatan tinggi menuju daerah kerapatan rendah atau nol (mengandung sedikit molekul zat atau tidak ada), sehingga kerapatannya menjadi sama di mana – mana. Apakah peristiwa difusi akan terjadi atau tidak, tergantung apakah membran sel meluluskan meolekul melaluinya atau tidak. Hal ini sesuai dengan membran sel yang selektif permiabel.Molekul-molekul kecil seperti molekul H2O, CO2 dan O2 dapat dengan mudah dan cepat melalui membran, sehingga difusi cenderung untuk mempersamakan kerapatan atau konsentrasi molekul-molekul di dalam dan di luar sel sepanjang waktu.
Misal pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat pernafasan, penyebaran setetes tinta dalam air.
Osmosis : proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah (hipotonik) ke daerah yang berkonsentrasi tinggi (hipertonik) melalui membran semipermiabel. Membran semipermiabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya.
Osmosis pada sel tumbuhan di sebelah luar terdapat dinding sel dan di dalamnya terdapat protoplasma dan vakoula.Vakoula ini dilapisi oleh lapisan proplasma yang sifatnya semipermiabel.Cairan protoplasma sel tumbuhan ini umumnya merupakan cairan yang hipertonik dibandingkan dengan dengan cairan disekelilingnya.Sel tumbuhan mengambil air dari sekelilingnya secara osmosis, air masuk vakuola dan menekan protoplasma. Protoplasma menekan dinding sel. Osmosis dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Jika terlalu banyak air masuk ke dalam sel, sel akan menggembung, bahkan mungkin dapat pecah. Tekanan pada dinding sel tersebut dinamakan takanan turgor.Karena turgor dinding sel sedikit mengembang.Waktu dinding sel mengembang secara secara maksimum dikatakan sel mempunyai turgor penuh atau turgid penuh. Keadaan menjadi sebaliknya jika sel diletakkan dalam suatu larutan yang yang bersifat hipertonik, maka air akan keluar dari sel. Bila air sel banyak keluar, maka isi sel terlepas dari dinding sel. Peristiwa telepasnya protoplasma dari dinding sel disebut plasmolisis.
2. a)Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah “pembangkit tenaga” bagi sel.
Keberadaan mitokondria didukung oleh hipotesis endosimbiosis yang mengatakan bahwa pada tahap awal evolusi sel eukariot bersimbiosis dengan prokariot (bakteri) [Margullis, 1981].Kemudian keduanya mengembangkan hubungan simbiosis dan membentuk organel sel yang pertama.Adanya DNA pada mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya.Hipotesis ini ditunjang oleh beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri. Ukuran mitokondria menyerupai ukuran bakteri, dan keduanya bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Hal yang utama adalah keduanya memiliki DNA berbentuk lingkar.Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri yang berbeda dengan sistem genetik inti.Selain itu, ribosom dan rRNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri dibandingkan dengan yang dikode oleh inti sel eukariot [Cooper, 2000].
Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs.
b)Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik.Di dalamnya, organel ini memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase.Semua enzim tersebut aktif pada pH 5.Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi.
Pada tumbuhan organel ini lebih dikenal sebagai vakuola, yang selain untuk mencerna, mempunyai fungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman.
c)RETIKULUM ENDOPLASMA (RE) adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik.
Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis.Kantung ini disebut cisternae.Fungsi retikulum endoplasma bervariasi, tergantung pada jenisnya. Retikulum Endoplasma (RE) merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma melipiti separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. (kata endoplasmik berarti “di dalam sitoplasma” dan retikulum diturunkan dari bahasa latin yang berarti “jaringan”).
Pengertian lain menyebutkan bahwa RE sebagai perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplsma.
Lubang/saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya.
Ada tiga jenis retikulum endoplasma:
RE kasar Di permukaan RE kasar, terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom.Ribosom ini berperan dalam sintesis protein.Maka, fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat sintesis protein.RE halus Berbeda dari RE kasar, RE halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. RE halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. RE sarkoplasmik RE sarkoplasmik adalah jenis khusus dari RE halus. RE sarkoplasmik ini ditemukan pada otot licin dan otot lurik.Yang membedakan RE sarkoplasmik dari RE halus adalah kandungan proteinnya.RE halus mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium.RE sarkoplasmik berperan dalam pemicuan kontraksi otot.
RE halus berfungsi dalam berbagai macam proses metabolisme, trmasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun
“RE berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri”
Jaring-jaring endoplasma adalah jaringan keping kecil-kecil yang tersebar bebas di antara selaput selaput di seluruh sitoplasma dan membentuk saluran pengangkut bahan.Jaring-jaring ini biasanya berhubungan dengan ribosom (titik-titik merah) yang terdiri dari protein dan asam nukleat, atau RNA.Partikel-partikel tadi mensintesis protein serta menerima perintah melalui RNA tersebut (Time Life, 1984).
Jadi fungsi RE adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetic antara inti sel dengan sitoplasma.
Fungsi Retikulum Endoplasma
• Menjadi tempat penyimpan Calcium, bila sel berkontraksi maka calcium akan dikeluarkan dari RE dan meuju ke sitosol
• Memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel.
(RE kasar)
• Mensintesis lemak dan kolesterol, ini terjadi di hati
(RE kasar dan RE halus)
• Menetralkan racun (detoksifikasi) misalnya RE yang ada di dalam sel-sel hati.
• Transportasi molekul-molekul dan bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain (RE kasar dan RE halus)
d)Badan Golgi
Mikrograf badan Golgi, terlihat sebagai tumpukan cincin setengah lingkaran berwarna hitam di bagian bawah gambar.Sejumlah vesikel bulat terlihat di sekitar organel ini.
Badan Golgi (disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom) adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa.Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal.Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi.Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom.
Badan Golgi ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi.
Struktur
Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya.Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel.
Badan golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Dari tubulus dilepaskan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim–enzim pembentuk dinding sel.
Permukaan badan golgi dibagi menjadi 2 yaitu cis-face dan trans-face. cis-face berhadapan langsung dengan retikulum endoplasma.
Vesikel:
1. Vesikel retikulum endoplasma, 2. Vesikel eksositosis, 3.Sisterna, 4.Membran sel, 5.Vesikel sekresi.
Fungsi badan golgi:
1. Membentuk kantung (vesikula) untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain.
2. Membentuk membran plasma. Kantung atau membran golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma.
3. Membentuk dinding sel tumbuhan
4. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom.
5. Tempat untuk memodifikasi protein
6. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel
7. Untuk membentuk lisosom
Dalam badan golgi terdapat variasi coated vesicle, antara lain
Clathrin-coated adalah yang pertama ditemukan dan diteliti.tersusun dari clathrin dan adaptin. interaksi lateral antara adaptin dengan clatrin membentuk formasi tunas. jika tunas clathrin sudah tumbuh, protein yang larut dalam sitoplasma termasuk dynamin akan membentuk cincin di setiap leher tunas dan memutusnya.
COPI-coated memaket tunas dari bagian pre-golgi dan antar cisternae. beberapa protein COPI-coat memperlihatkan sekuens yang bermiripan dengan adaptin, dapat diduga berasal dari evolusi yang bermiripan.
COPII-coated memaket tunas dari retikulum endoplasma.
terdapat 2 protein dalam badan golgi. Protein Snare V-snare menuju T-snare dan akan bergabung. T-snare adalah protein yang ada di target sedangkan V-snare adalah vesikel snare. V-snare akan mencari T-snare dan kemudian akan berfusi menjadi satu. Protein Rab termasuk ke dalam golongan GTP-ase.protein Rab memudahkan dan mengatur kecepatan pelayaran vesikel dan pemasangan v-snare dan t-snare yang diperlukan pada penggabungan membran.
e)Sentrosom (Sentriol)
Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel (Mitosis maupun Meiosis). Sentrosom bertindak sebagai benda kutub dalam mitosis dan meiosis.
Struktur ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron.
Simbiosis berasal dari bahasa Yunani sym yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan.Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan.
Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis.[1] Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion[1].
Ada beberapa bentuk simbiosis yakni:
• Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh:
o Tanaman benalu dengan inangnya
o Tali putri dengan inangnya
o cacing perut dan cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia[1]
• Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama mahkluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya:
o Ikan Remora dan Ikan Hiu
o Bunga Sepatu dan Lebah
o Burung Jalak dan Kerbau.
o Jenis jamur tertentu dan jenis alga tertentu membentuk likenes
o Bunga dengan kupu-kupu[1]
• Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh:
o Ikan badut dengan anemon laut
o Tumbuhan pakis dengan anggrek dan tumbuhan inangnya.
• Simbiosis Amensalisme, yaitu saat satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan.[2]
• Kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan, biasanya terjadi melalui kompetisi dalam memperebutkan makanan.[2]
• Simbiosis netralisme, dimana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antar kedua spesies tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian bagi keduanya.[2]
Simbiosis dapat dibedakan menjadi dua kategori berbeda.
• Ektosimbiosis
• Endosimbiosis
• B. TEORI ENDOSIMBIOSIS
• Para pakar biologi sel sependapat bahwa mitokondria berasal dari bakteri aerobik yang mengadakan endosimbiosis dengan eukariot anaerobik. Endosimbiosis adalah jika
• organisme dari suatu species hidup didalam organisme dari
• species yang lain. Proses yang terjadi adalah sel-sel bakteri aerobik tertelan oleh sel eukariot anaerobik namun bakteri aerobik tidak mengalami pencernaan. Bakteri aerobik yang tertelan selanjutnya hidup di dalam sel eukariot. Eukariot mensuplai bakteri dengan proteksi dan komponen-komponen karbon, sedangkan bakteri mensuplai eukariot dengan energi ATP. Beberapa bukti yang mendukung teori tersebut adalah:(i) Mitokondria dapat menggandakan diri menyerupai pembelahan biner pada bakteri, (ii) DNA mitokondria menyerupai DNA prokariot, berupa molekul sirkular tunggal dan ribosom pada mitokondria dibuat dari sub unit dengan koofisien sedimentasi yang lebih menyerupai ribosom prokariot dibandingkan dengan eukariot, (iii) Ukuran mitokondria hampir sama dengan ukura bakteri. (iv) Mitokondria memiliki membran ganda, memiliki kemi-ripan dengam membran sejumlah prokariota, dan (v) urut- an DNA pada mitokondria tertutup dan memiliki kemiripan dengan DNA proteobakteril (vi) Mitokondria memiliki kemiripan fisik dengan prokariota.
Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari selpada tahun 1850 oleh Kollicker melalui pengamatannya padajaringan otot lurik serangga.Ia menemukan adanya granula-granula dengan struktur yang bebas dan tidak berhubungansecara langsung dengan struktur internal sel. Pada tahun 1890,Altmann mengidentifikasi granula-granula tersebut dan Iaberikan nama bioblast.
Istilah
tersebut diganti denganmitokondria (Yunani:mito yang berarti benang danchondrio nyang berarti granula) sebab penampakan granula-granulatersebut menyerupai benang bila diamati dengan menggunakanmikroskop cahaya.
Pada tahun 1900, Michaelis menunjukkan bahwa didalam mitokondria berlangsung reaksi-reaksi oksidatif.Padatahun 1911, Warburg menemukan bahwa mitokondriamengandung enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksioksidatif sel. Pada tahun 1911, Kingsbury mendu-kung bahwamitokondria merupakan tempat spesifik untuk reaksi-reaksioksidasi.Pada tahun 1930, Sir Hans Krebs menjelaskanbeberapa reaksi siklus asam trikarboksilat atau daur Krebs.Dari tahun 1950, Lehninger, Green, Kennedy, dan Hogeboomdan lain-lain menunjukkan secara jelas reaksi-reaksi sepertioksidasi asam lemak, fosforilasi oksidatif serta sifat-sifat lainmitokondia (Sheeler dan Bianchii, 1983).
C. STRUKTUR MITOKONDRIA
Mitokondria dijumpai baik pada sel hewan maupun padasel tumbuhan. Ukuran mitokondria kira-kira sama denganukuran rata-rata bakteri basil. Mitokondria hati secara umumagak memanjang dengan diameter kira-kira 0,5-1,0µm danpanjang kira-kira 3µm. Umumnya panjang mitokondria dapatmencapai 7µm (Sheeler & Bianchi, 1983; Thorpe, 1984).
Di dalam sel mitokondria terletak secara acak sepertipada hati atau tersusun teratur dengan pola-pola tertentuseperti pada sel sperma.Contoh yang paling umum adalahsusunan yang teratur dari mitokondria diantara serabut-serabutdi dalam otot lurik.Mitokondria umumnya ditemukan padatempat-tempat di dalam sel yang membutuhkan energi dalamjumlah yang besar, misalnya pada otot lurik dan flagel sperma.
Untuk melaksanakan fungsinya, sangat tergantung pada
persediaan ATP yang dihasilkan oleh mitokondria
susunan mitokondria pada ekor sel sperma (Thorpe, 1984
Susunan mitokondria pada sel otot lurik (Thorpe, 1984)
Jumlah mitokondria per sel sangat bervariasi diantara berbagai tipe sel, mulai dari nol sampai ratusan ribu. Algae tak berwarna,Leucothrix danVitreoscilla, tidak memiliki mitokondria. Spermatozoa tertentu dan flagella seperti
Chromulina hanya mengandung satu mitokondria per sel. Hati memiliki mitokondria rata-rata 800 per sel dan beberapa telur landak laut dan amoeba raksasa Chaos chaos mengandung 500.000 mitokondria per sel. Dalam beberapa hal, tampaknya terdapat hubungan antara jumlah mitokondria per sel dan keperluan metabolisme sel.
Mitokondria dibatasi oleh membran ganda, yaitu membran dalam dan membran luar.Setiap membran memiliki ciri khas sebagai unit membran.Membran dalam tidak berhubungan dengan membran luar.Membran dalam membagi organel menjadi dua bagian yaitu matriks dan ruang antar membran.
Matriks berisi cairan menyerupai gel, sedangkan ruang antar membran berisi cairan yang encer. Membran dalam memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan membran luar, karena membran dalam terlipat-lipat dan masuk ke dalam matriks membentuk tonjolan-tonjolan yang dinamakan krista. Dengan demikian, secara struktural terdapat perbedaan antara membran dalam dengan membran luar.Selain itu, membran dalam berbeda dengan membran luar dari segi permiabilitasnya.Membran luar permiabel terhadap berbagai substansi yang mempunyai berat molekul berkisar 5.000 dalton.Sebaliknya permiabilitas membran dalam terbatas, khususnya terhadap substansi-substansi dengan berat molekul berkisar 100-150 dalton (Sheeler & Bianchi, 1983).
Struktur morfologi mitokondria yang paling bervariasi adalah krista. Dalam satu tipe sel, mereka pada umumnya uniform dan khas pada sel. Akan tetapi, susunan dari bentuk- bentuk yang berbeda terdapat dalam tipe-tipe sel yang berbeda.
Umumnya mitokondria memiliki krista yang berbentuk
lamella atau tubuler. Pada bentuk lamella, krista relatif sejajar
dan teratur, sedang pada krista yang berbentuk tubular
memperlihatkan tubulus-tubulus yang terorientasi pada matriks. Pada beberapa mitokondria, susunan tubulusnya teratur, misalnya pada Amoeba Chaos chaos.
Menurut Sheeler & Bianchi (1983), struktur mitokondria dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (i) krista susunannya menyerupai lembaran misalnya krista pada mitokondria sel hati, (ii) krista dengan susunan yang sangat rapat menyerupai tumpukan uang logam misalnya pada mitokondria sel ginjal, dan (iii) krista dengan susunan seperti jala yang dibentuk oleh saluran-saluran yang saling beranastomosis.
Gambar 11.5 Struktur krista mitokondria (Sheler dan Bianchii,1983)
D. KOMPOSISI KIMIA MITOKONDRIA
Pada mitokondria utuh, air merupakan komponen utama yang dominan dan ditemukan di seluruh mitokondria kecuali dalam lapisan bilayer lipida.Air selain berperan dalam reaksi- reaksi kimia, juga berperan sebagai medium fisik dimana metabolit dapat berdifusi diantara sistim-sistim enzim.
Komponen utama mitokondria adalah protein. Persentase protein yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah membran dalam yang ada.Membran dalam terdiri atas protein, baik protein enzimatik maupun protein struktural.Pada beberapa mitokondria, membran dalam mengandung kira-kira 60% dari total protein organel. Berdasarkan distribusi enzim di dalam mitokondria hati tikus, telah terbukti bahwa membran dalam mengandung 21% dari total protein mitokondria dan membran luar 40%. Menurut perhitungan ini, kurang lebih 67% protein terdapat pada matriks dan biasanya ditemukan dalam ruang intraseluler.
Protein mitokondria dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk terlarut dan bentuk tidak terlarut. Protein terlarut terutama terdiri atas enzim-enzim matriks dan protein
Perbedaan distribusi lipida memiliki arti penting, baik dari segi struktural maupun fungsional. Namun secara detail belum jelas.
Sejumlah molekul organik sederhana yang berbeda berasosiasi dengan membran mitokondria.Beberapa dari molekul ini adalah molekul redoks yang ikut serta dalam transpor elektron.Ubiquinon (koenzim Q), flavin (FMN dan FAD), dan nukleotida piridin (NAD+) secara normal terikat membran, dan kadang-kadang berasosiasi pada hampir sebahagian besar membran dalam.
E. KOMPARTEMEN ENZIM
Kurang lebih 100 enzim telah diidentifikasi berhubungan dengan mitokondria.Kira-kira 37% dari enzim-enzim tersebut adalah oksidoredoks, 11% enzim ligase dan kurang dari 9% enzim hidrolase.Pada membran dalam, terdapat suksinat dehidrogenase yang merupakan enzim maker, enzim-enzim transfer elektron dan fosforilasi oksi-datif berasosiasi dengan membran dalam.