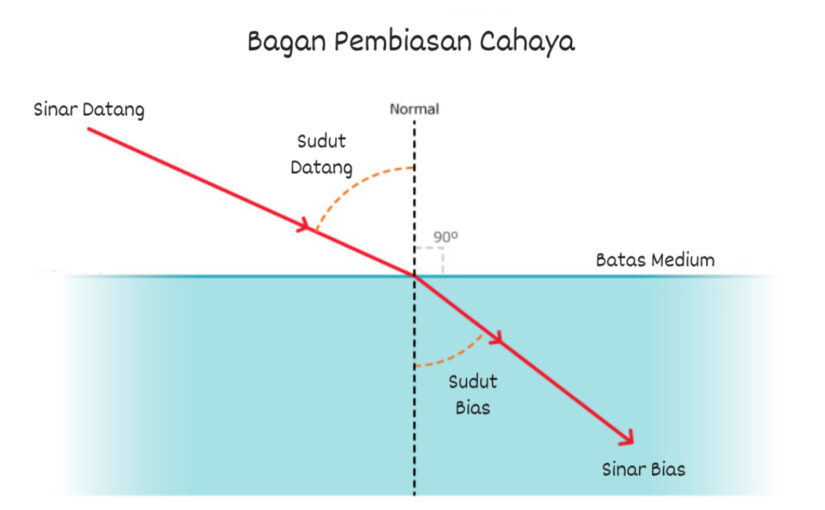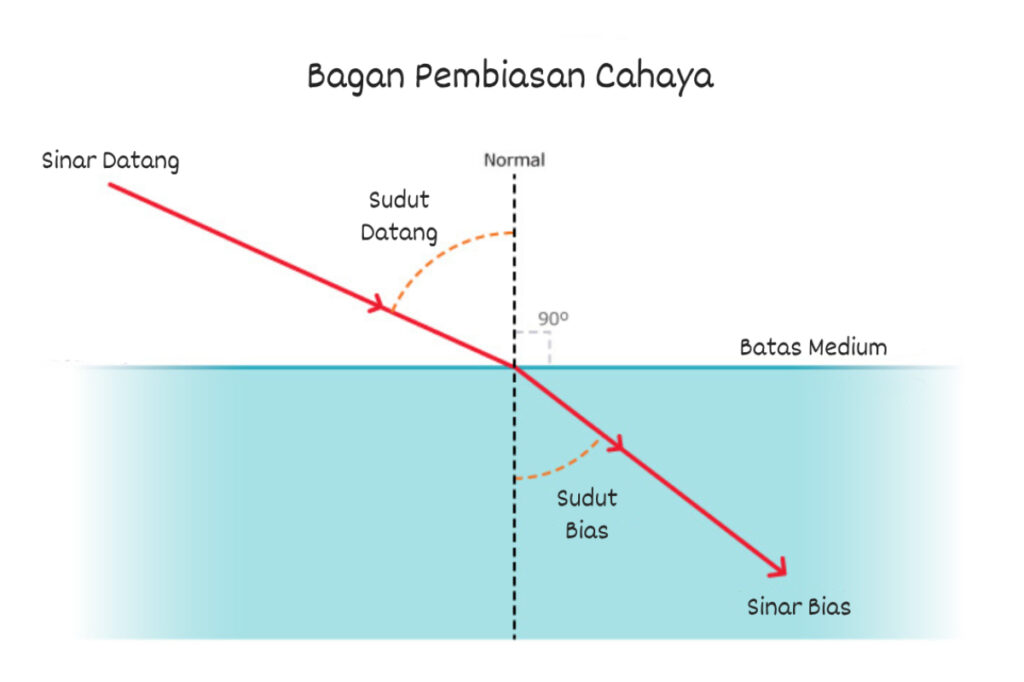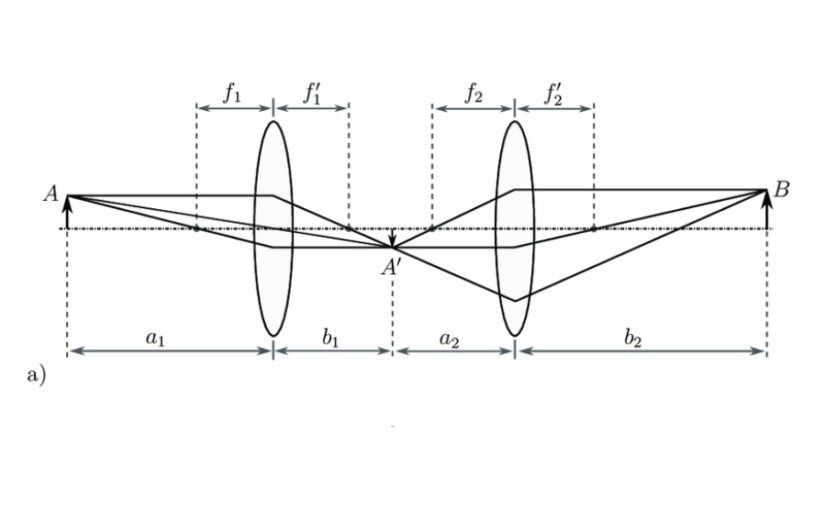Daftar isi
Praktikum Fisika Hukum Newton
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan atau mengubah benda. Gaya juga merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Misalnya, saat kita mendorong ataupun menarik meja artinya kita telah member gaya pada meja tersebut. Dalam hal ini terjadi peristiwa gerak benda atau yang biasa kita kenal daalam Hukum Newton.
Hukum Newton merupakan Hukum dalam fisika yang pertama kali di cteuskan oleh ilmuwan bernama Sir Isaac Newton mengenai sifat gerak benda. hukkumNewton tidak bisa dibuktikan dari prinsip-prinsip lain, selain itu Hukum Newton memungkinkan kita untuk dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar dari mekanika klasik.
Pada umumnya kebanyakan dari masyarakat melihat gaya yang ditimbulkan dengan ssangat sederhana. Padahal di dalamnya ada banyak tentang pennjelasan ilmiah. Seperti pengaruh gaya gesek, gaya gravitasi, gaya normal, dan arah gaya yang bekerja pada suatu objek.
Interaksi antara benda-benda tersebut akan dibahas dalam dua kajian tentang gerak, yaitu Kinemaika dan Dinamika. Kinematika membahas tentang gerak benda tanpa membahas tentang apapun penyebabnya. Sedangkan Dinamika membahas tentang gerak benda dengan memperhatikan penyebab geraknya.
B. Rumusan Masalah
- Bagaimana gerak suatu benda berdasarkan kajian kinematika?
- Bagaimana analisis koefisien gesek kinetis dan statis antara dua permukaan berdasarkan kajian dinamika?
B. Tujuan Percobaan
- Mendeskripsikan percepatan dari gerak suatu benda berdasarkan kajian gerak kinematika
- Menganalisis nilai koefisien gesek kinetis dan statis antara dua permukaan berdasarkan kajian dinamika.
Bab II. Kajian Pustaka
Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang ekerja pada sebuah benda adalah terjadinya perubahan gerak pada benda tersebut. Mekanika yang mempelajari gerak sebuah partikel yang memperhatikan gaya penyebabnya dinamakan dinamika partikel. Dinamika partikel tertuang di dalam Hukum Newton.
Jika kita sedang naik sebuah bus yang bergerak dengan kelajuan tetap kemudian tiba-tiba di rem, maka kita akan terdorong ke depan. Demikian juga sebaliknya jika kita sedang duduk diam di dalam sebuah bus, kemudian bus di gerakkan dengan tiba-tiba, tentu kita akan terdorong ke belakang. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya sifat lembam benda. Jika gaya resultan pada sebuah benda adalah nol, maka vektor kecepatan benda tidak berubah. Benda yang mula-mula diam akan tetap diam; benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama atau konstan. Benda hanya akan mengalami perceepatan atau perlambatan jika padanya bekerja suatu resultan yang bukan nol. Hukum ke-1 ini sering disebut dengan “Hukum Kelembaman” atau inertia low.
Dari pernyataan tersebut maka diperoleh syarat berlakunya Hukum I Newton jika :
∑F = 0 ……..(1)
Gaya merupakan penyebab perubahan gerak pada benda. Perubahan gerak benda yang dimaksudkan disini dapat berarti perubahan kelajuannya atau perubahan kecepatannya. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu disebut percepatan. Bila gaya resultan F bekerja pada suatu benda dengan massa m tidak sama dengan nol, maka benda tersebut mengalami percepatan ke arah yang sama dengan gaya. Percepatan a berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan F dalam Newton, m dalam kilogram, dan a dalam m/s2. Perbandingan ini dapat dituliskan sebagai suatu persamaan :
∑F = m.a …… (2)
Bila persamaan ini atau yang lainnya yang diturunkan dari persamaan ini digunakan, maka F, m dan a harus menggunakan satuan-satuan gaya yang benar. Percepatan a mempunyai arah yang sama dengan F. Persamaan vektor F = m.a dapat ditulis dalam suku-suku komponen-komponen berikut :
∑Fx = max
∑Fy = may
∑Fz = maz ….. (3)
Dimana gaya-gaya adalah komponen-komponen dan gaya eksternal yang bekerja pada benda.
Gb. 1.1 seorang anak yang naik papan beroda saling menarik tali yang diikatkan pada tembok
Ternyata pada sat orang tersebut menarik tali ke arah kiri, orang beserta papan beroda bergerak ke kanan. Hal itu karena orang mendapat gaya tarik dari tali yang arahnya ke kanan yang besarnya sama dengan gaya tarik yang diberikan oleh orang tersebut. Hal ini terjadi karena pada saat orang memberi aksi pada tali, timbul reaksi dari tali pada orang dengan besar yang sama dan arah berlawanan. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Hukum tersebut dapat diartikan bahwa gaya aksi-reaksi hanya terjadi jika sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi.
Faksi = – Freaksi
Konsep Gaya Aksi – Reaksi :
- Gaya aksi dan reaksi sama besar, tetapi berlawanan arah
- Pasangan gaya aksi-reaksi ada jika terdapat dua benda yang berinteraksi
- Gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda.
Jika kita melepaskan seuah benda dari atas permukaan tanah, maka benda tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan jika kita melempar sebuah benda bertikal ke atas, maka benda tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Percepatan yang timbul pada gerakan benda diatas disebut percepatan gravitasi bumi yang diberi lambang g.
Percepatan gravitasi bumi pada suatu titik yang berjarak r dari pusat bumi dinyatakan dengan
g = G ………… (4)
dengan :
g = percepatan gravitasi bumi (m/s2)
G = konstanta gravitasi (Nm1/kg2)
M = massa bumi (kg)
r = jari-jari bumi (m)
Pembahasan gerak kinematika, dapat menggunakan persamaan berikut :
s = vo t + ½ at2 …….. (5)
Apabila ditinjau dari sistem alat seperti diatas maka persamaan yang sesuai sebagai berikut :
m2.g – fk (m1 + m2) a ……. (6)
Sehingga penentuan koefisien gesek dapat diperoleh dari persamaan :
fk = μk . N ….. (7)
Lain dengan menentukan koefisien gesek statis, kita harus mempertimbangkan kerja sistem yang “tepat akan bergerak” dimana dapat menggunakan persamaan :
F = fs …… (8)
fs = μs . N ….. (9)
dengan :
s = panjang lintasan (m)
vo = kecepatan awal (m/s)
a = percepatan (m/s2)
t = waktu tempuh (s)
m1 = massa benda 1 (kg)
m2 = massa benda 2 (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
F = gaya yang bekerja (N)
N = gaya normal benda
fk = gaya gesek kinetis
μk = koefisien gesek kinetis
fs = gaya gesek statis
μs = koefisien gesek statis
Gaya gesek statis maksimum sama besar dengan gaya kecil yang di perlukan untuk memulai menggerakkan benda. Begitu benda bergerak maka gaya gesek yang bekerja diantara permukaan mengecil, sehingga hanya diperlukan gaya yang kecil untuk menjaga kecepatan konstan.
Bab III. Metode Praktikum
A. Alat dan Bahan
Kit papan luncur 1 set
Beban secukupnya
Neraca 1 buah
Mistar 1 buah
Stopwatch 1 buah
3.2. Rancangan Percobaan
3.3. Variabel Percobaan
3.2.1 Penentuan Percepatan Benda dan Koefisien Gesek Kinetis
Variabel manipulasi : massa benda 2
Variabel kontrol : massa benda 1, jarak
Variabel respon : waktu
3.2.2 Penentuan Koefisien Gesek Statis
Variabel manipulasi : massa benda 1
Variabel kontrol : jarak
Variabel respon : massa benda 2
3.4. Langkah Percobaan
Penentuan Percepatan Benda dan Koefisien Gesek Kinetis
- Mempersiapkan beban yangs udah ditimbang
- Menyusun rangkaian sistem sesuai rancangan percobaan
- Menetapkan jarak (s) lintasan tempuh
- Memulai gerak trolly dengan melepas beban serta memulai perhitungan waktu
- Mengentikan stopwatch ketika jarak tempuh sudah terlampaui
- Melakukan pengulangan data minimal 3 kali
- Melakukan langkah diatas dengan memanipulasi variabel massa beban yang berbeda.
Penentuan Koefisien Gesek Statis
- Mempersiapkan beban yang sudah ditimbang
- Menyusun alat seperti pada rangkaian
- Mempersiapkan sistem agar bekerja “benda tepat akan bergerak”
- Melakukan pengulangan data minimal 5 kali.
Bab IV. Hasil dan Pembahasan
A. Data
4.1.1 Penentuan Percepatan Benda dan Koefisien Gesek Kinetis
| Perc.Ke- | m1 ± 0,05 gram | m2 ± 0,05 gram | s ± 0,05 cm | t ± 0,005 s | a (cm/s2) | μk |
| 1. | 71,30 | 30,00 | 40,00 | 1,150 | 60,60 | 0,334 |
| 1,930 | 92,49 | 0,289 | ||||
| 1,100 | 66,10 | 0,326 | ||||
| 2. | 35,00 | 1,250 | 51,30 | 0,414 | ||
| 1,190 | 56,50 | 0,406 | ||||
| 1,250 | 51,30 | 0,414 | ||||
| 3. | 40,00 | 1,210 | 54,64 | 0,475 | ||
| 1,030 | 75,47 | 0,443 | ||||
| 1,130 | 62,65 | 0,463 | ||||
| 4. | 45,00 | 0,910 | 96,60 | 0,473 | ||
| 0,830 | 116,00 | 0,441 | ||||
| 0,730 | 150,40 | 0,386 | ||||
| 5. | 50,00 | 0,840 | 113,40 | 0,500 | ||
| 0,690 | 168,00 | 0,415 | ||||
| 0,690 | 168,00 | 0,415 |
4.1.2 Penentuan Koefisien Gesek Statis
| Perc. Ke- | m1 ± 0,05 gram | m2 ± 0,05 gram | μs |
| 1. | 71,60 | 25,00 | 0,349 |
| 2. | 90,50 | 28,30 | 0,312 |
| 3. | 98,20 | 30,00 | 0,305 |
| 4. | 100,50 | 33,60 | 0,334 |
| 5. | 112,80 | 35,00 | 0,310 |
4.2 Analisis
Berdasarkan data hasil percobaan pertama diperoleh nilai waktu tempuh yang dilalui oleh benda satu diatas meja yang disambung dengan tali dan di beri lima massa benda yang berbeda-beda dengan masing-masing tiga kali pengulangan. Pada percobaan ini jarak merupakan kontrol dan kami mengontrol jarak sejauh 40 cm. Waktu yang diperoleh untuk massa benda 2 sebesar 30,00 gram yaitu 1,150 s; 1,930 s; dan 1,100 s. Respon waktu untuk massa benda 2 35,00 gram berturut-turut yaitu 1,250 s; 1,190 s; 0,730 s. Dan respon waktu untuk massa benda 2 sebesar 40,00 gram yaitu 1,210 s; 1,030 s; dan 1,130 s. Respon waktu untuk massa benda 2 sebesar 45,00 gram yaitu 0,910 s; 0,830 s; dan 0,730 s. Dan respon waktu untuk massa benda 2 sebesar 50 gram yaitu 0,840 s; 0,690 s; dan 0,690 s. Rata-rata waktu berturut-turut yaitu 1,060 s; 1,230 s; 1,123s; 0,823 s; dan 0,740 s.
Rata-rata waktu tersebut semakin kecil karena benda yang dimanipulasi bertambah besar massanya. Sehingga balok (benda 1) lebih cepat melalui jarak sepanjang 40 cm. Dari data tersebut, selanjutnya dapat diperoleh nilai percepatan gerak dan koefisien desek kinetisnya menggunakan rumus :
s = vo t + ½ at2
s = 0 t + ½ at2
s = ½ at2
a =
∑F = m.a
w2 – fk = (m1+ m2) a
m2g – μk.N = (m1+ m2) a
m2g – ((m1+m2)a) = μk m1 g
μk =
Percobaan selanjutnya yaitu menganalisis massa benda 1 dan massa benda 2. Dari data massa benda yang diperoleh, maka akan didapatkan keofiisen gesek statis dengan rumus :
F = fs
w2 = μs m1 g
m2 g = μs m1 g
μs =
μs =
Koefisien gesek statis dihitunh dengan mengukur massa kedua benda ketika benda 1 tepat akan bergerak. Saat melakukan percobaan ini, pada awalnya balok tetap diam dan tidak bergerak. Artinya belum ada gaya tarik dari beban dua. Dan belum ada gaya gesek yang terjadi antara balok (benda 1) dengan permukaan meja. Untuk mengetahui adanya gaya gesek statis pada benda kita memberi sedikit usikan kepada benda 1 dengan menkatuhkan sesuatu disekitrnya. Ketika benda bergerak (sesaat) disitulah terjadi gaya gesek statis dan dapat dimukan koefisien gesek statis … Sedangkan apabila ketika diberi usikan benda bergerak dan terus melaju berarti itu merupakan gesek kinetis. Dari percobaan, massa benda 2 leboh kecil dari nilai massa benda 1 dan koefisien gesek statisnya diperoleh dengan nilai rata-rata 0,32.
PERTANYAAN
Sebuah balok bermassa 10 kg ditempatkan pada lintasan sepanjang 5 meter. Salah satu ujung lintasan dinaikkan setinggi 3 meter. Koefisien gesek statis dan kinetik antara permukaan benda dan permukaan lintasan masing-masing bernilai 0,7 dan 0,5. Apakah benda diam atau bergerak? Berikan penjelasan ! Dan apabila bergerak, berapakah percepatannya? (g=10 m/s2)
JAWABAN
Diketahui :
m = 5 kg
s = 5 m
h = 3 m
μs = 0,7
μk = 0,5
Ditanya :
a. Apakah benda diam atau bergerak?
b. Jika benda bergerak, berapakah percepatannya?
Jawab :
= 0,6
= 37o
F = W sin
= mg sin
= 10.10 sin 37o
= 100 x 0,6 = 60 N
fs = μs . N
= 0,7 . 60 N
= 42
a. F > fs à benda bergerak
b. a = 1 m/s2
Bab V. Penutup
5.1 Simpulan
Dari data percobaan yang di dapat, maka dapat ditarik simpulan bahwa gerak suatu benda di pengaruhi oleh gaya seperti percepatan. Percepatan ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga semakin besar massa benda akan semakin kecil percepatannya. Terdapat gaya gesek yang terjadi di antara dua benda yang saling bersentuhan, massa beban mempengaruhi percepatan suatu benda untuk bergerak. Pada gaya gesek statis, koefisien gesek statis dapat diperoleh dengan membagi massa benda kedua dengan massa benda pertama.
5.2 Saran
Saran untuk praktikan selanjutnya agar lebih tanggap dan lebih teliti saat melakukan percobaan. Sast menentukan koefisien gesek kinetis praktikan juga harus terampil dan tepat dalam menggunakan stopwatch. Karena menggunakan stopwatch manual memungkinkan data yang diperoleh kurang akurat. Saran untuk asisten yaitu agar mendampingi praktikan agar apabila ada kesulitan bisa ditanyakn ke asisten dan cepat mendapat solusi. Sehingga waktu praktikum bisa dimaksimalkan untuk praktikum (melakukan percobaan).
DAFTAR PUSTAKA
Breche, Frederick J. tanpa tahun. Teori dan Soal-soal Fisika Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga.
Lohat, Alexander San. 2009. Hukum II Newton. (online), (http://iapfuntan.files.wordpress.com/2010/10/hukum-ii-newton.pdf , diunduh pada 29 Oktober 2016)
Widodo, Tri. 2003. Fisika untuk SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan Bepartemen Pendidikan Nasional.