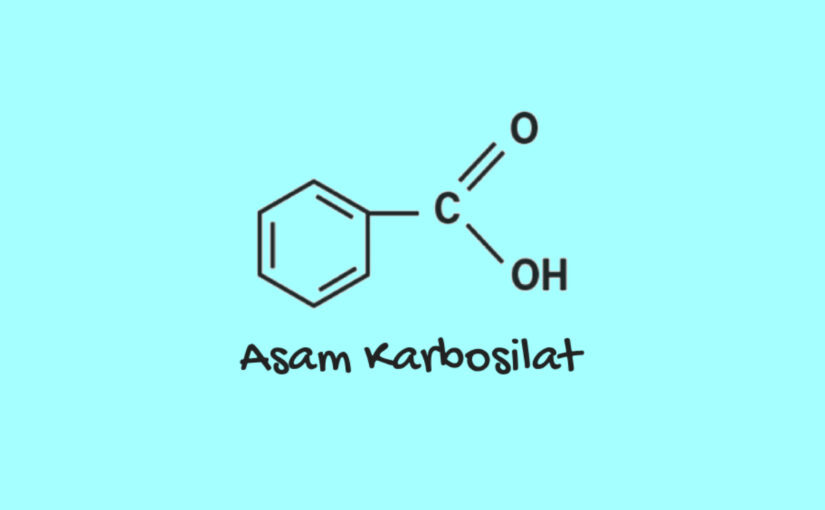Peran pancasila dalam konteks ketatanegaran negara kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting. Tidak hanya sebagai dokumen yang menjadi dasar negara akan tetapi nilai-nilai luhur yang tergantung dalam Pancasila sangat penting dalam menjadi perekat kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa.
Sayangnya pada Praktiknya, ada banyak praktik pemerintahan yang dianggap menyimpan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Padahal dalam konteks ketatanegaran, seluruh peraturan yang dibuat di semua level harus sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 tanpa terkecuali.
Daftar isi
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.
Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri.
Untuk itulah dalam makalah ini, kami mengambil judul “Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia”
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini, kami merumuskan beberapa masalah, yaitu :
- Apa pengertian dari pancasila sebagai konteks ketatanegaraan NKRI?
- Apakah definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara?
- Bagaimana UUD 1945 itu ?
- Apa saja yang terkait dengan Pembukaan UUD 1945?
- Bagaimanakah sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945?
- Bagaimanakah kelembagaan negara menurut UUD 1945?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
- Mengetahui pengertian pancasila dalam kontek ketatanegaraan NKRI
- Mengetahui definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara
- Mengetahui UUD 1945?
- Mengetahui apa saja yang terkait dengan pembukaan UUD 1945
- Menegtahui sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945
- Mengetahui kelembagaan negara menurut UUD 1945
Bab II. Pembahasan
A. Pengertian Pancasila dalam Konteks Ketatangeraan RI
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar filsafat Negara (Philosofische gronslai). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.
Pancasila adalah dasar falsafat Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap warga Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa berikut:
- Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
- Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
- Ir. Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.
Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
B. Defenisi UUD/Konstitusi, Kedudukan UUD 1945, Sifat Serta Fungsinya
1. Defenisi UUD/Konstitusi
Dalam ketatanegaraan, istilah UUD sering digunakan pula dengan istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau untuk saling menggantikan. Secara harfiah, istilah konstitusi dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti membentuk, dan diartikan sebagai “pembentuk suatu negara”. Sedangkan Indonesia menggunakan istilah UUD yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dari belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar (Grond) dari segala hukum dalam suatu negara.
Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (convensi). Dengan demikian konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakan bangun yang disebut “negara”.
2. Kedudukan UUD 1945
Undang-Undang dasar mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan structural dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sebagai landasan structural dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berisi aturan atau ketentuan pokok ketatanegaraan, bahkan lebih dari itu, yaitu untuk menjamin suatu system atau bentuk Negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya maka UUD harus merupakan hukum Negara tertinggi.
Dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD 1945, yang merupakan deklarasi bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang memuat pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara serta bentuk Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan staasfundamentalnorm (kaidah Negara yang fundamental), dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.
3. Sifat UUD 1945
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam negara di Indonesia, ia berisikan pola dasar dalam berkehidupan di Indonesia. Negara dengan segala fungsi dan tujuannya berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan berbagai cara, oleh karena itu sebagai pengintegrasian dari kekuatan politik, negara mempunyai bermacam-macam sifat, seperti memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Dengan sifat memaksa, negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah untuk ditaatinya semua keputusan. Walaupun alasannya untuk mewujudkan tujuan bersama, sifat memaksa yang dimiliki oleh negara dapat disalahgunakan ataupun melampaui batas yang mungkin dapat menyengsarakan rakyatnya. Untuk mencegah adanya kemungkinan tersebut, konstitusi atau UUD disusun dan ditetapkan.
Dalam teori konstitusi (UUD) dikenal sifat dari UUD yaitu luwes atau (fleksibel) atau kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis. Untuk menentukan apakah setiap UUD itu luwes atau kaku dipakai ukuran sebagai berikut:
1. Cara mengubah konstitusi
Ada dua cara mengubah UUD, pertama, UUD diubah dengan cara prosedur yang biasa, sebagaiman mengubah dan membuat UU biasa. dalam hal ini UUD itu memiliki sifat luwes (fleksibel). Seperti konstitusi inggris. Kedua, perubahan UUD yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah kaku (rigid).
Seperti orde baru telah menjadi sakral atau suci dengan memberi yang sangat sulit untuk diubah dengan mengeluarkan ketetapan MPR tentang Referendum.
2. Tertulis dan tidak tertulis
Suatu konstitusi disebut tertulis apabila iya tertulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal dalam konvensi-konvensi atau UU biasa.
Dalam teori hukum, sifat konstitusi dibedakan atas fleksibel dan rigid, yang dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan luwes dan kaku. Ada dua kriteria tolak ukurnya yaitu cara pembuatan/perubahan dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan zaman (Kusnardi, dan Ibrahim, 1983:75). Suatu konstitusi disebut luwes apabila pembuatan dan perubahannya sama dengan pembuatan dan perubahan undang-undang biasa. Kriteria kedua dilihat dari kemampuan dalam mengikuti perkembangan zaman. Apabila konstitusi masih tetap mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat, konstitusi tersebut dapat dikatakan bersifat luwes, dan apabila sebaliknya maka konstitusi tersebut disebut kaku.
4. Fungsi UUD 1945
Sebagaimana fungsi konstitusi pada umumnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya dapat disebutkan antara lain: membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, untuk melindungi hak asasi manusia, dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintahan berjalan dengan tertib dan lancar. Di samping itu, apabila dilihat dari substansi materi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehidupan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dibedakan atas:
- Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan system pemerintahan Negara, di dalamnya termasuk pengaturan system pemerintahan Negara, didalamnya termasuk pengaturan system tentang kedudukan, wewenang, dan saling hubungan antara kelembagaan Negara.
- Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara Negara dan warga Negara dan penduduknya serta berbagi konsepsi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, social budaya, dan hokum.
C. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Naskah UUD 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Naskah tersebut secara resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Antara Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya merupakan satu kebulatan yang utuh, dimana antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan.
Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas :
- Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea,
- Batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
- Serta penjelasan yang terdiri dari atas penjelasan umum dan penjelasan khusus, yaitu penjelasan pasal demi pasal.
UUD merupakan hukum dasar tertulis yang bukan satu-satunya hukum dasar, disampingnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. UUD bersifat singkat, sifat singkatnya itu dikarenakan :
- UUD itu sudah cukup, apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-gars besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melakukan tugasnya.
- UUD yang singkat itu menguntungkan bagi negara seperti Indonesia yang masih harus berkembang, harus hidup secara dinamis, dan masih akan terus mengalami perubahan.
Semangat para penyelenggara negara dalam menyelenggarakan UUD 1945 sangat penting, oleh karena itu setiap penyelenggara negara, selain mengetahui teks UUD 1945, juga harus menghayati semangat UUD 1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.
D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
1. Makna pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia
Apabila UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di Dunia.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah yang menjadi landasan dan peraturan hukum yang tertinggi bagi hukum-hukum lainnya, termasuk hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi). Pokok-pokok kaidah Negara fundamental itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sbb:
1. Dasar-dasar pembentukan Negara
- Tujuan Negara, yang menyatakan Negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan.
- Asas politik Negara, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia yang berbentuk Republic dan berkedaulatan Rakyat
- Asas Kerohanian Negara, yaitu dasar falsafah Negara pancasila yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hokum Indonesia.
2. Ketentuan diadakannya UUD Negara
Ketentuan ini dapat terlihat kalam kalimat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Indonesia
2. Makna Alenia-Alenia Pembukaan UUD 1945
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” merupakan bunyi alenia pertama pembukaan UUD 1945 yang menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah “kemerdekaan lawan penjajahan”. Alenia ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, karena dalam alinea pertama terdapat letak moral luhur dari pernyataan Indonesia. Alenia ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari perjuangan. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau bertentangan dengan pernyataan diatas juga harus secara sadar ditentang oleh Bangsa Indonesia.
“Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” merupakan bunyi alenia ke dua yang menunjukan kebangsaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Alenia ini juga menunjukan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :
- Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan
- Momentum yng telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” merupakan bunyi dari alenia ke tiga yang menjadi motivasi riil dan materiil Bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, menjadi motivasi spiritualnya, karena menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah SWT, serta menunjukan ketaqwaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa serta merupakam suatu pengukuhan dari Proklamasi Kemerdekaan.
“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan Yang maha dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” merupakan bunyi dari alenia ke empat yang merumuskan dengan padat sekali tujuan dari prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Dengan rumusan yang panjang dan padat, alenia keempat Pembukaan Undang-Undang dasar sekaligus menegaskan :
- Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu seperti yang tertuang dalam alenia ke empat tersebut.
- Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan Rakyat.
- Negara Indonesia mempunyai dasar filsafah Pancasila.
4. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan UUD 1945 itu sendiri, bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam UUD, yaitu dalam pasal-pasalnya.
Ada 4 pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam, yaitu :
- Pokok pikiran pertama menunjukan pokok pikiran persatuan, dengan pengertian yang lazim, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan maupun perorangan.
- Pokok pikiran yang kedua adalah kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bangsa.
- Pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral Rakyat yang luhur.
5. Hubungan Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pasal UUD 1945
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD 1945, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :
a. Ditinjau dari isi pengertian yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945
- Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.
- Dari alenia keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal dan organis dengn Pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa aspek :
- UUD itu ditentukan akan ada
- Apa yang diatur oleh UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan
- Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila)
b. Ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945
Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :
- Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam “Pembukaan” itu mengehendaki persatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
- Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Itulah hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945.
c. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negara Republik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Pasal-pasal UUD 1945.
E. Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945
Secara garis besar gambaran tentang sistem pemerintahan negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut :
1. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2).
Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya sebatas melantik (pasal 3 ayat 3 dan pasal 8 ayat 3). Dengan demikian hanya dengan GBHN, UUD 1945 tidak lagi mengenal istilah GBHN sebagai produk MPR. Kewenangan terbesar MPR adalah menetapkan dan mengubah UUD (pasal 3 ayat 1) selain mengenai Pembukaan UUD dan bentuk Kesatuan Negara Republik Indonesia (pasal 37 ayat 5).
2. Sistem Konstitusional
Sistem konstitusional dalam UUD 1945 tercermin dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2).
- MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat 3).
- Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD (pasal 4 ayat 1).
- Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah atau berjanji memegang teguh UUD (pasal 9 ayat 1).
- Hak-hak DPR ditentukan oleh UUD (pasal 20A).
- Setiap UU yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD 9pasal 24C ayat1).
- Kewenangan lembaga negara ditentukan oleh UUD (pasal 24C ayat 1).
- Putusan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD (pasal 24C ayat 2).
3. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)
4. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD (pasal 4 ayat 1).
Namun dalam kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi.
Presiden memegang tanggungjawab atas jalannya pemerintahan menurut UUD, dan Presiden diberi kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Preisden.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1), oleh karena itu kedudukan menteri sangat tergantung pada Presiden (pasal 17 ayat 2)
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Presiden selaku kepala negara mempunyai kekuasan yang sangat luas, meskipun tidak bersifat mutlak. Kekuasaan kepala negara yang tidak tak terbatas itu adalah dimana kontrol DPR atas berbagai kewenangan presiden sangatlah dominan.
8. Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1). NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah.
A. Kelembagaan Negara menurut UUD 1945
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR yang dipilih melalui pemilu, dengan suara terbanyak dan sedikitnya MPR bersidang sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3)
2. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (pasal 5). Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun. Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah :
- WNI sejak kelahirannya
- Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- Tidak pernah menghianati negara
- Mampu secaraa jasmani dan rohani untuk melakukan kewajibannya
- Syarat-syarat lainnya akan diatur dengan UU (pasal 6Syarat-syarat lainnya akan diatur dengan UU (pasal 6).
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Keanggotaan DPR dipilih oleh pemilu dengan suara terbanyak. DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, untuk itu DPR diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas (pasal 20).
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Anggota DPD juga dipilih oleh pemilu dengan suara terbanyak dari setiap provinsi. DPD bersidang paling sedikitnya sekali dalam setahun. DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya sesuai dengan bidangnya.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU biasa ditugaskan dalam rangka Pemilu agar terselenggara sesuai asas (luberjurdil).
6. Bank Sentral
Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (pasal 23D).
7. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindklanjuti (pasal 23E).
8. Mahkamah Agung (MA)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
9. Komisi Yudisial
Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim.
10. Mahkamah Konstitusi
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengkaji UU terhadap UUD, dan lain-lain.
Bab III. Penutup
A. Kesimpulan
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar filsafat Negara (Philosofische gronslai). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.
Dengan menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia.
B. Saran
Kepada semua pembaca khususnya mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) atau siapa saja yang menyempatkan membaca makalah ini bila mendapat kekeliruan terhadap materi kami harap bisa meluruskannya dan memakluminya. Maka kami banyak berharap kepada para pembaca untuk tidak segan memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada kami.
DAFTAR PUSTAKA
Karsadi, dkk.2014. Pancasila di Perguruan Tinggi: Bentuk Moral, Karakter dan Budaya Bangsa. Kendari: FKIP-Universitas Halu Oleo
Safiun, La Ode. 2014. Modul Pendidikan Pancasila. Kendari : FKIP-Universitas Halu Oleo
Sugiarto, Ahmad. 2013. Makalah Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan NKRI. http://pend-pancasila.blogspot.com/2013/12/makalah-pancasila-dalam-konteks.html. Diakses pada tanggal 20 November 2014.
Tim Pengajar Mata Kuliah Umum. 2014. Buku Ajar Pancasila. Kendari: Universitas Halu Oleo