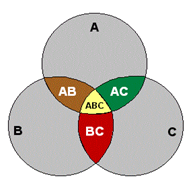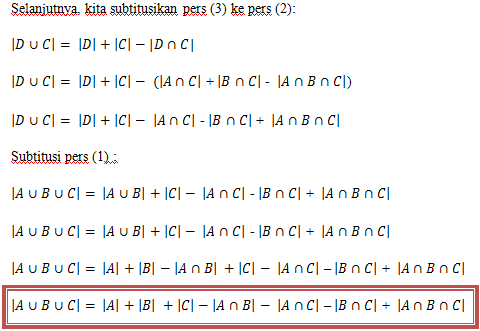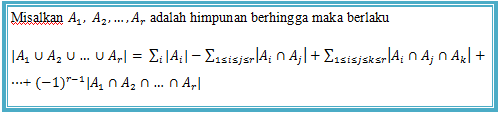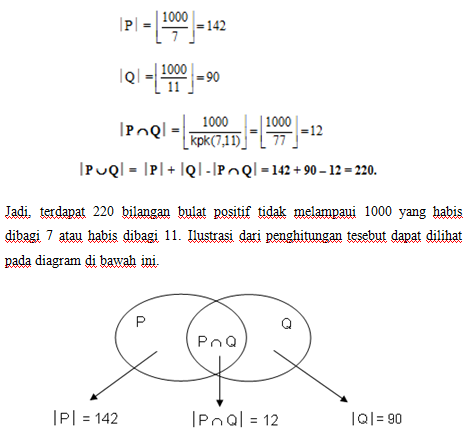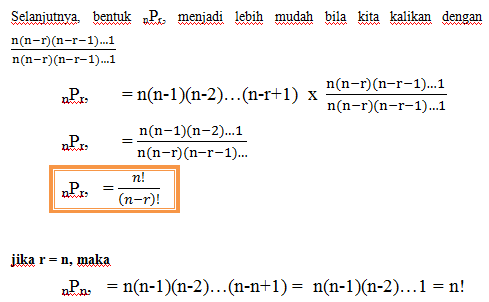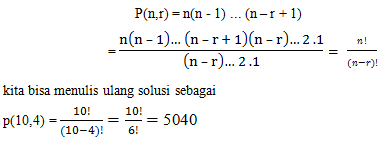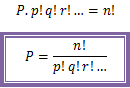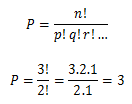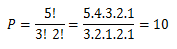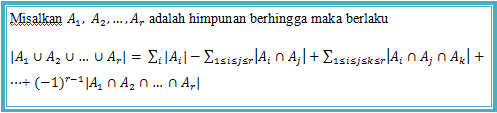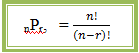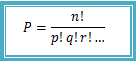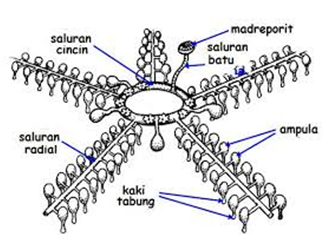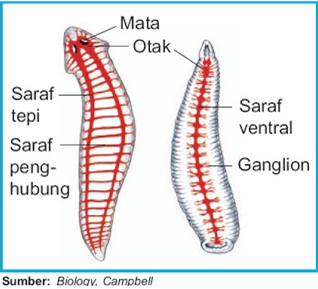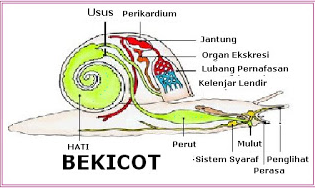Sejarah Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan memiliki sumbangsih yang panjang. Mulai dari zaman nusantara sampai masa Kemerdekaan.
Daftar isi
Sejarah Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pada waktu islam berkembang diseluruh kepulauan Indonesia, Kerajaan majapahit yang beragama hindu diperintah oleh Brawija putera Angka Wijaya. Kerajaan tersebut kemudian mengalami keruntuhan, dan raja yang merobohkan kerajaan Majapahit ialah Raden Patah dengan delapan menterinya Yaitu sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus, Ngundung Dan Sunan Demak. Mulai itulah agama islam disebar diseluruh Indonesia dan salah satunya ialah Kalimatan.
Di Kalimantan awalnya banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Budha. Namun, karena penyebaran agama Islam yang mulai pesat dan luas hingga merambah ke daerah Kalimantan, maka banyak muncul Kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berdiri. Entah karena Kerajaan Hindu-Budha yang beralih memeluk agama Islam, atau juga kerajaan-kerajaan yang telah berhasil ditaklukan dan mendirikan Kerajaan Islam sendiri.
Beberapa Kerajaan Islam yang ada di Kalimantan diantaranya ialah Kesultanan Pasir, Kesultanan Sambas, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kartanegara dan lainnya. Oleh sebab itu hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul Sejarah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, Khususnya Kalimantan Selatan.
B. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini ialah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh guru pengajar. Selain itu pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan ilmu serta pengetahuan tentang sejarah kerajaan-Kerajaan Islam yang ada di Kalimantan.
C. Rumusan Masalah
Yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini diantaranya ialah :
- Bagaimana awal mulanya Kerajaan Islam di Kalimantan?
- Kerajaan-Kerajaan apa saja yang bercorak Islam di Kalimantan?
- Peta Penyebaran Kerajaan Islam di Kalimantan?
Bab II. Pembahasan
A. Awal Mula Kerajaan Islam di Kalimantan
Kerajaan Islam di Kalimantan awal mulanya terjadi karena Kerajaan Hindu berperang dengan kerajaan Islam, tetapi akhirnya kerajaan hindu menyerah diantaranya kerajaan hindu di Candi Laras dan Candi Agung di Tanjung Pura. Sebagian rakyat memeluk agama Islam termasuk sebagian rakyat dayak di pantai-pantai. Rakyat dayak yang telah masuk Islam, ialah yang sering disebut sebagai dayak melayu, yang kebanyakkan di kuala kapuas, tumpung laung (barito) dan beberapa kampung melayu, sebenarnya mereka tetap suku dayak , hanya sudah memeluk agama islam.
Pangeran Samudra (suriansyah) pernah meminta seorang puteri bernama Biang Lawai untuk dijadikan istri. Biang Lawai, adalah adik Patih Dadar, Patih Muhur, dan mengijin perkawinan, hanya dengan perjanjian tidak akan di Islamkan. Mula-mula oleh Pangeran Samudra, disanggupi, tetapi sesudah sampai istana, putri itu dikabarkan diislamkan. Kabar tersebut sampai kepada Patih Muhur bersaudara, menimbulkan amarah Patih Rumbih dari Kahayan , Patih Muhur dari Bakumpai (barito) ilmu gaib, berhasil merampas saudaranya kembali, Biang Lawai, dari istana sultan dan dibawanya ke Sungai katan.
Pangeran samudra memerintah balatentaranya untuk mencari perempuan tersebutdipedelaman. Tetapi karena balatentara patihn muhur sangat hebat, maka mundur lah balatentara sultan.
Patih muhur dan patih rumbih mundur dan membuat pertahanandi taliu dikampung tundai. Sesudah itu mereka mundur lagi membuat pertahanan didanau karam bersebrangan dengan negeri goha kahayan. Mereka menyebrangi danau tersebut dan dipasang dundang, bambu yang diruncingkan dibawah jembatans ehingga sewktu-wktu jembatan tersebut dapat diputuskan jika balatentara sultan lewatatas jembatan dan luka-luka terkena bambu yang diruncingkan dibawahnya. Perahu-perahu mereka dapat dirampas oleh patih rumbih ditengelamkan . sekarang tempat tersebut dinamai berayar yang artinay “berlayar”.
Diantara tempat pertempuran-pertempuran tersebut dengan bentengnya ialah sungai muhur (barito), parabingan, (pangkoh) bukit rawi, tewang pajagen, tewah, hulu kaspuas dan lain-lain.
Tentang tersebarnya agama islam dari banten kedaerah kalimantan dapat kita baca artikel kerajaan islam dari banten di karang an R. Muchtadi dalam almanak muhamadyah 1357 H (1938) hlm. 166 dan 169, antara lain ditulis : aliudin sultan banten bergelar abu mufakir muhamad aliudin, dia beramah tamah dengan kompeni, dan mendapat kebebasan sisa utang kerajaan banten sebanyak 60.000 ringgit, bekas menempuh landak (tahun 1698 ditentukan , bahwa landak dan sukadana diserahkan pada kompeni. Daerah pantai barat kalimantan diperintah oleh sultan abdurahman yang mendirikan kota pontianak.
Sultan muhamad aliudin hanya berputera seorang saja dan meninggal ketika masih kanak-kanak tahun1786. Sultan zainal abidin dari banten memasuki landak, matan. Tahun 1699. Kapal kompeni /VOC dan 75 pecalang banten berlayar kesukadana diperintahkan oleh sultan agung (pangeran agung), keponakan sultan banten yang bergelar panebahan.
Sultan landak didibantu oleh orang bugis dapat merebut kembali daerahnya sehingga panebahan dapat dipukul mundur , dengan keluarganya melarikan diri ke anyer (banten). Landak dipegaruhi selama 80 tahun (1699-1778).
B. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan
Adapun Kerajaan-Kerajaan Islam yang ada di Kalimantan yaitu :
1. Kesultanan Pasir
Dahulunya rakyat dayak pasir, diperintahkan oleh kepala-kepala dari rakyat dayak sendiri . ada seorang kepala suku dayak yang sangat berpengaruh, yang bernama tamanggung tokio, mengusulkan agar didaerah daerah dikepali oleh sorang kepala suku dan untuk itu diminta sultan yang dekat tempat tinggalnya. Mereka telah berangkat dengan perahu yang penuh bermuatan emas dan perak, yang dianugrahkan kepada nya kepada raja yang baru, mereka telah pergi ke utara dan selatan, tetapi tak ada mendapat seorangpun yang dipandang cakap. Tamanggung tokio sangatlah sedih sampai tidak minum dan makan , kemudian dalam mimpinya ia melihat seorang tua yang berkata kepadanya:
Untuk mendapat raja, baiklah engkau pergi kelaut, dan disitu engkau memperoleh sepotong bambu, yang ruasnya tarapung apung dilaut ambilah bambu itu, dan bungkuslah dengan sutra kuning, karena didalam bambu itu ada sebutir telur yang harus dirabun diberi asap dupa, menyan dan garu. Dan dari telur itu nanti akan dilahirkan seorang raja perempuan.
Pada esokkan harinya sesudah dia bangun, tamanggung tokio menuruti pesan perempuan dalam mimpinya. Sesudah 3 hari 3 malam telur itu didupakan, maka terbelah dua lah buluh itu dan dari telur itu pecah pula dan dilahirkan seorang bayi puteriyang cantik jelita. Anak itu sama sekali tidak mampu menyusu, setelah berusaha dapatlah ia diberi makanan dengan susu kerbau putih: lambat laun menjadi akil balig.
Puteri inilah yang diangkat jadi raja *(ratu pasir), dan waktu ia berumur 15 tahun ia telah dinikahnkan, tetapi malang sekali ia tidak mendapat keturunan sihingga harus diceraikan beberapa kali.
Seterusnya sesudah kawin yang ketujuh kali, belum juga mempunyai anak, kebetulan datang lah seorang arab dari jawa (gresik), terus dikawin kan dengan sang puteri. orang yang dari gresik tersebut dicarinya dukun agar membuang sari bambu yang ada pada sang puteri sehingga bisa melahirkan 2 puteri dan satu putera. Puetri yang tertua dikawinkan dengan seorang arab yang membawa agama islam dipasir (1600). Yang putera sesudah ibunda mangkat, mengantikan duduk disingasana. Inilah cerita ringkas dari raja pasir, yang berasal dari sebutir telur dan bersuamikan putera arab dari jawa.
2. Kesultanan Banjar
Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin (berdiri 1520, masuk Islam 24 September 1526, dihapuskan Belanda 11 Juni 1860, pemerintahan darurat/pelarian berakhir 24 Januari 1905) adalah sebuah kesultanan wilayahnya saat ini termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya (kabupaten Banjar). Ketika beribukota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi.
Ketika ibukotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribukota di kota Negara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.
3. Kesultanan Kota Waringin
Kerajaan Kotawaringin adalah sebuah kerajaan Islam (kepangeranan cabang Kesultanan Banjar) di wilayah yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah yang menurut catatan istana al-Nursari (terletak di Kotawaringin Lama) didirikan pada tahun 1615 atau 1530, dan Belanda pertama kali melakukan kontrak dengan Kotawaringin pada 1637, tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya sesuai dengan Hikayat Banjar dan Kotawaringin (Hikayat Banjar versi I) yang bagian terakhirnya saja ditulis tahun 1663 dan di antara isinya tentang berdirinya Kerajaan Kotawaringin pada masa Sultan Mustain Billah. Pada mulanya Kotawaringin merupakan keadipatian yang dipimpin oleh Dipati Ngganding.
Kerajaan Pagatan (1750). Kerajaan Pagatan (1775-1908) adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran sungai Kusan, sekarang wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah Tanah Kusan bertetangga dengan wilayah kerajaan Tanah Bumbu (yang terdiri atas negeri-negeri: Batu Licin, Cantung, Buntar Laut, Bangkalaan, Tjingal, Manunggul, Sampanahan).
4. Kesultanan Pontianak
Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjungpura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tome Pires (1512-1551). Tanjungpura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa, bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pate atau mungkin adipati kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Pati Unus. Tanjungpura dan Lawe (daerah Sukadana) menghasilkan komoditi seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu, demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan yang murah. Pada abad ke-17 kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC.
Demikian pula Kotawaringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa Kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim (Hadramaut) yang di antaranya dating ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca al- Qur’an, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka di antaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mampawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas Kecil sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus ibn Abdurrahman al-Aydrus yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu Syarif Idrus ibn Abdurrahman al-Aydrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak para pedagang yang berdatangan dari berbagai negeri.
5. Kesultanan Sambas
Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Propinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Borneo (Kalimantan) dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di Pulau Borneo atau Kalimantan ini telah ada paling tidak sebelum abad ke-14 M sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Pada masa itu Rajanya mempunyai gelaran “Nek” yaitu salah satunya bernama Nek Riuh. Setelah masa Nek Riuh, pada sekitar abad ke-15 M muncul pemerintahan Raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat Raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 M (1530 M) datang serombongan besar Bangsawan Jawa (sekitar lebih dari 500 orang) yang diperkirakan adalah Bangsawan Majapahit yang masih hindu melarikan diri dari Pulau Jawa (Jawa bagian timur) karena ditumpas oleh pasukan Kesultanan Demak dibawah Sultan Demak ke-3 yaitu Sultan Trenggono.
6. Kesultanan Kartanegara
Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura (Martapura) merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta yakni putera mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan gelar H. Adji Mohamad Salehoeddin II pada tanggal 22 September 2001.
7. Kesultanan Berau
Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri.
Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur. Sejarahnya kemudian pada keturunan ke-13, Kesultanan Berau terpisah menjadi dua yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.
8. Kesultanan Sambaliung
Kesultanan Sambaliung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, dimana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Baddit Dipattung atau yang lebih dikenal dengan Aji Suryanata Kesuma raja Berau pertama. Sampai dengan generasi ke-9, yakni Aji Dilayas. Aji Dilayas mempunyai dua anak yang berlainan ibu. Yang satu bernama Pangeran Tua dan satunya lagi bernama Pangeran Dipati.
Kemudian, kerajaan Berau diperintah secara bergantian antara keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati (hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang bahkan kadang-kadang menimbulkan insiden). Raja Alam adalah cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit dari Pangeran Tua, atau generasi ke-13 dari Aji Surya Nata Kesuma. Raja Alam adalah sultan pertama di Tanjung Batu Putih, yang mendirikan ibukota kerajaannya di Tanjung pada tahun 1810. (Tanjung Batu Putih kemudian menjadi kerajaan Sambaliung).
9. Kerajaan Tidung
Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan (Kalkan/Kalka) adalah kerajaan yang memerintah Suku Tidung di utara Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu.
10. Kesultanan Bulungan
Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731, dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amiril Mukminin (1731–1777), dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931-1958).
C. Peta Penyebaran Kerajaan Islam di Kalimantan
Penyebaran Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.
Bab III. Penutup
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mulanya Kerajaan Islam di Kalimantan terjadi karena Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha dapat ditaklukkan oleh kerajaan Islam sehingga agama Islam menyebar hingga ke seluruh Nusantara, salah satunya Kalimantan. Di Kalimantan, Kerajaan Islam juga menyebar akibat kekalah Kerajaan Hindu-Budha yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Islam.
Salah satu Pangeran yang berjasa dalam penyebaran Kerajaan Islam di Kalimantan Ialah Pangeran samudera. Hal itu terjadi karena pangeran Samudera menikahi seorang Puteri dari Kerajaan Hindu-Budha yang kemudian diIslamkanoleh Pengeran samudera dan hal itu mengakibatkan kemarahan dari saudara-saudara sang Puteri dan mengakibatkan terjadi perperangan dan pertumpahan darah. Dari sanalah kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar akibat kekalah kerajaan Hind-Budha tersebut.
Adapun Kerajaan-Kerajaan Islam yang ada di Kalimantan yaitu Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kesultanan Beruk, Kesultanan Pontianak, Kerajaan Tidung, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kertanegara, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Bulungan.
B. Saran
Setelah beberapa paparan dan kesimpulan yang dijabarkan, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu semoga dengan mengetahui sejarah perkembangan Islam di Kalimantan kita dapat menghormati dan menghargai hasil jerih payah mereka dalam menegakkan Islam di daerah Kalimantan walaupun harus berkorban nyawa dalam memerangi kerajaan Hindu-Budha yang pernah menguasai daerah-daerah di Kalimantan.
DAFTAR PUSTAKA
Wildian, Anggita. 2014. Sejarah Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan. http://anggitwildian.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-kerajan-kerajaan-islam-di.html . Diakses tanggal 14 November 2015 pukul 10.00 Wita.
Anonim. 2015. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan.http://www.gurusejarah.com/2015/01/kerajaan-kerajaan-islam-di-kalimantan.html. Diakses tanggal 14 November 2015 pukul 10.00 Wita.