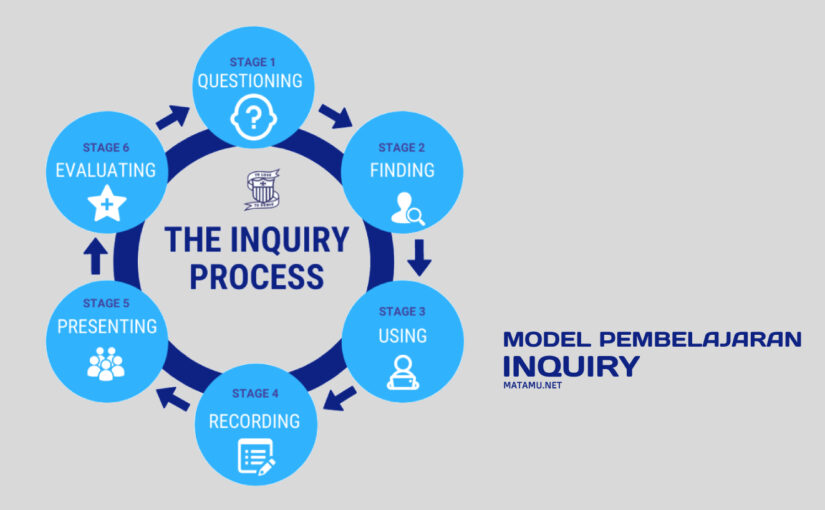Remedial
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam proses belajar mengajar di suatu institusi pendidikan, masing-masing individu memiliki caranya masing-masing untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam belajar. Beberapa ketrampilan belajar pun dipakai guna memenuhi tujuan dari pendidikan tersebut. Namun tidak jarang seorang siswa mengalami kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh beberapa factor yang mengganggu dirinya dalam belajar. Banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar misalnya tidak mampu menyerap bahan pembelajaran dengan baik, tidak dapat konsentrasi dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes dan sebagainya.
Siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti itu akan memiliki resiko hasil yang didapatkan dari proses belajar kurang maksimal. Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mengatasi masalah-masalahbelajar tersebut, setiap satuan pendidikan perlu menyelenggarakan program pembelajaran remedial atau perbaikan. Mengingat pentingnya pemahaman menyeluruh konsep dasar dari kurikulum ini, maka penulis tergerak untuk menyusunnya menjadi sebuah makalah yang khusus mengungkap mengenai hal tersebut.
B. Rumusan Makalah
- Apakah pengertian dari model pengajaran remedial dan KKM?
- Apa saja langkah dalam evaluasi belajar dan hasil penilaian?
- Apa saja tujuan dan fungsi model pengajaran remedial?
- Apa saja bentuk dan aspek pengajaran remedial?
- Apa saja prinsip dasar pengajaran remedial?
- Apa saja pendekatan dalam pengajaran remedial di Sekolah?
- Bagaimana proses pengajaran remedial?
- Apa saja keterbatasan dalam pengajaran remedial?
C. Tujuan
Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
- Untuk mengetahui pengertian dari model pengajaran remedial.
- Untuk mengetahui tujuan dan fungsi model pengajaran remedial.
- Untuk mengetahui bentuk dan aspek pengajaran remedial.
- Untuk memahami prinsip dasar pengajaran remedial.
- Untuk mengetahui pendekatan dalam pengajaran remedial di Sekolah.
- Untuk memahami proses pengajaran remedial.
- Untuk mengetahui keterbatasan dalam pengajaran remedial.
Bab II. Pembahasan
A. Pengertian Model Pengajaran Remedial
According to Sharma (2009: 22), remedial teaching as the name suggest, is the teaching that is undertaken for providing remedial education to those who are in need of such education for overcoming their deficiencies, weakness and difficulties related with the learning activities pertaining to some area or aspects of a particular subject.
Menurut Sharma (2009: 22), pengajaran remedial seperti namanya, adalah pengajaran yang dilakukan untuk memberikan pendidikan remedial kepada mereka yang membutuhkan pendidikan semacam itu untuk mengatasi kekurangan mereka, kelemahan dan kesulitan terkait dengan kegiatan pembelajaran. berkaitan dengan beberapa area atau aspek dari subjek tertentu.
According to Jangid and Inda (2016: 98), remedial teaching methods are innovative teaching strategy designed to improve the storage and retrieval of information from long-term memory. Remedial education is education which is designed to bring students who are lagging behind up to the level of achievement realized by their peers. Remedial Teaching means that help is offered to students who need pedagogical or didactic assistance. These are often children who function at a lower than average level because of a certain learning- or behavioral problem/disorder. However, remedial teaching can also be offered to pupils who accomplish at a higher than average level, they also can do with the extra attention and care.
Menurut Jangid dan Inda (2016: 98), metode pengajaran remedial adalah strategi pengajaran yang inovatif yang dirancang untuk meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dari memori jangka panjang. Pendidikan remedial adalah pendidikan yang dirancang untuk membawa siswa yang tertinggal ke tingkat pencapaian yang direalisasikan oleh rekan-rekan mereka. Pengajaran remedial berarti bahwa bantuan ditawarkan kepada siswa yang membutuhkan bantuan pedagogis atau didaktik. Ini sering anak-anak yang berfungsi pada tingkat yang lebih rendah daripada rata-rata karena masalah / gangguan belajar-atau perilaku tertentu. Namun, pengajaran remedial juga dapat ditawarkan kepada siswa yang mencapai tingkat di atas rata-rata, mereka juga dapat melakukan dengan perhatian dan perhatian ekstra.
According to Kumar (2016: 36-38), the term remedial is employed in a broader sense to connote teaching which is developmental in its scope. Though our schools possess pupils who do not have any particular defects or faults which need correction, there are a group of students who urgently need assistance in developing increased competence in reading and the other fundamental processes. In their case, it is not primarily a problem of re-teaching or the remedying of errors, but it is rather teaching them for the first time those basic skills which are solely needed and are apparently lacking. Remedial teaching involves taking a pupil where one is and starting from that point leading one to greater achievement. It is just effective teaching in which the learner and his/her needs occupy the focal point. Remedial teaching is an integral part ofall good teaching. It takes the pupil at his own level and by intrinsic methods of motivation leads him to increased standards of competence. It is based upon careful diagnosis of defects and in general to the needs and interest of pupils.
Menurut Kumar (2016: 36-38), istilah perbaikan digunakan dalam arti yang lebih luas untuk berkonotasi pengajaran yang berkembang dalam lingkupnya. Meskipun sekolah kami memiliki murid yang tidak memiliki cacat atau kesalahan tertentu yang perlu diperbaiki, ada sekelompok siswa yang sangat membutuhkan bantuan dalam mengembangkan peningkatan kompetensi dalam membaca dan proses mendasar lainnya. Dalam kasus mereka, ini bukan masalah utama pengajaran ulang atau perbaikan kesalahan, tetapi lebih kepada mengajarkan mereka untuk pertama kalinya ketrampilan dasar yang hanya dibutuhkan dan kelihatannya kurang. Pengajaran remedial melibatkan mengambil murid di mana satu dan mulai dari titik itu mengarah satu ke prestasi yang lebih besar. Ini hanya pengajaran yang efektif di mana pembelajar dan kebutuhannya menempati titik fokus. Pengajaran remedial adalah bagian integral dari semua pengajaran yang baik. Dibutuhkan murid di tingkat sendiri dan dengan metode motivasi intrinsik membawanya ke peningkatan standar kompetensi. Hal ini didasarkan pada diagnosis defek yang cermat dan secara umum terhadap kebutuhan dan minat siswa.
Menurut Masbur (2012: 348-361), Pengajaran remedial (remedial teaching) secara etimologis berasal dari kata remedy (Inggris) yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, pengulangan. Sedangkan teaching adalah mengajar, cara mengajar atau mengajarkan. Pengajaran remedial secara terminologis adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan.
Pengajaran remedial menurut Abd. Rachmat Abror adalah bentuk pengajaran perbaikan yang diberikan kepada seseorang siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dihadapinya. Menurut Abin Syamsuddin, pengajaran remedial adalah sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa (dengan kerakter) tertentu lebih mampu meningkatkan prestasi seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, pengajaran remedial adalah suatu bentuk khusus pengajaran yang bersifat menyembuhkan, membetulkan atau membuat menjadi baik.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengajaran remedial adalah suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
Menurut Malawi dan Kardawati (2018: 230-231), remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/ hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang optimal. Dalam hal ini, penilaian merupakan assessment as learning.
Menurut al-Taubany dan Suseno (2017: 362-367), Program remedial adalah progam pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu.
Menurut Slamet (2015: 100-103), remedial teaching atau pengajaran remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat penyembahan atau membetulkan atau dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. Dalam memberikan pengajaran remedial kepada siswa berkesulitan belajar, harus dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima dengan jelas. Pengajaran remedial merupakan salah satu wujud pengajaran khusus yang sifatnya memperbaiki prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran remedial digunakan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, pengajaran remedial secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang berkaitan dengan perbaikan pada diri orang atau suatu pemberian pada anak sekolah yang terutama ditujukan kepada anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar.
Dari kedua pendapat di atas jelaslah bahwa pembelajaran remedial ditujukan kepada siswa yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar dan bersifat menyembuhkan dan membetulkan anak yang mengalami berkesulitan belajar menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini yang dimaksud pembelajaran remedial adalah pengajaran yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan bersifat penyembahan dan pembetulan siswa agar hasil belajarnya menjadi lebih baik.
Menurut Sukinahiska (2016: 59), Re-teaching, yaitu pengajaran remedial yang dilaksanakan dengan mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa yang memerlukan bantuan dengan cara penyajian yang berbeda.Menyuruh siswa mempelajari bahan yang sama dari buku pelajaran, buku paket atau sumber-sumber bacaan yang lain.Memberikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh siswa.Bimbingan yang diberikan secara individu maupun kelompok kecil oleh guru atau pembimbing (siswa yang telah tuntas dan dapat dipercaya untuk menerangkan atau membantu temannya yang belum tuntas).
Menurut Darmadi (2017: 384-385), pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pada prinsipnya, pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan hkusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan atau lambat mencapai kompettensi.
According to Munene (2017: 47), remedial education is a part of education which is concerned with the prevention, investigation and treatment of learning difficulties from whatever source they may emanate and which hinder normal development of pupils (Eldah, 2005). Remedial education is given to children who function at a lower than average level because of certain learning or behavioral problem, but it can also be offered to pupils who achieve at higher than average level.
Menurut Munene (2017: 47), pembelajaran remedial adalah bagian dari pendidikan yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan dan perawatan kesulitan belajar dari sumber apa pun yang mungkin mereka berasal dan yang menghambat perkembangan normal siswa (Eldah, 2005). Pendidikan remedial diberikan kepada anak-anak yang berfungsi pada tingkat yang lebih rendah dari rata-rata karena masalah belajar atau perilaku tertentu, tetapi juga dapat ditawarkan kepada siswa yang mencapai pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata.
According to Singh (2004: 16-17), remedial teaching organized in various ways has a potentially important role. There has been quite a rapid expansion of remedial teaching servicesince the late 1940s when public concern grew about the large number of backward readers in schools. Some remedial teachers work in schools with groups and individuals who need extra help, especially early in the junior school. In a few cases they work in centres which children attend several times a week. More frequently they are peripatetic teachers visiting a numberof schools to teach groups and in some well organized services giving advice on materials and methods, undertaking surveys and other services. Their work should be closely integrated with the school pshychological services. Sometimes they work in and from child guidance centres.
Menurut Singh (2004: 16-17), pengajaran remedial yang diselenggarakan dengan berbagai cara memiliki peran yang berpotensi penting. Sudah ada ekspansi yang cepat dari layanan pengajaran perbaikan sejak akhir 1940-an ketika perhatian publik tumbuh tentang banyaknya pembaca terbelakang di sekolah. Beberapa guru remedi bekerja di sekolah dengan kelompok dan individu yang membutuhkan bantuan tambahan, terutama di awal sekolah menengah pertama. Dalam beberapa kasus mereka bekerja di pusat-pusat yang anak-anak menghadiri beberapa kali seminggu. Lebih sering mereka adalah guru-guru yang bergerak mengunjungi sejumlah sekolah untuk mengajar kelompok-kelompok dan dalam beberapa layanan yang terorganisasi dengan baik memberikan nasihat tentang bahan dan metode, melakukan survei dan layanan lainnya. Pekerjaan mereka harus terintegrasi erat dengan layanan psikologi sekolah. Terkadang mereka bekerja di dan dari pusat bimbingan anak.
According to Jangid and Inda (2016: 98-99), there are a unit variety of reasons why a student would possibly would like remedial education. Some students attend schools of poor quality and do not receive adequate grounding in mathematics and language to organize them for school or life. Other students might have transferred in and out faculties’ of colleges or missed school plenty, making gaps in their education that contribute to the lack of information in core subjects. Students can also have learning disorders and other problems that have impaired their ability to find out. In remedial education, people are usually given assessments to determine their level of competency. Based on test results, the pupils are placed in classes which are most likely to provide benefits. Classes are often little, with a spotlight on high teacher-student interaction, and that they will occur at the hours of darkness or throughout the day to accommodate various needs. Within the course of the category, the teacher can bring students up to hurry in order that they need skills comparable to those of their peers.
Menurut Jangid dan Inda (2016: 98-99), ada berbagai macam alasan mengapa seorang siswa mungkin ingin mendapatkan pendidikan perbaikan. Beberapa siswa menghadiri sekolah dengan kualitas buruk dan tidak menerima landasan yang cukup dalam matematika dan bahasa untuk mengatur mereka untuk sekolah atau kehidupan. Siswa lain mungkin telah mentransfer masuk dan keluar fakultas ‘perguruan tinggi atau melewatkan banyak sekolah, membuat kesenjangan dalam pendidikan mereka yang berkontribusi pada kurangnya informasi dalam mata pelajaran inti. Siswa juga dapat memiliki gangguan belajar dan masalah lain yang mengganggu kemampuan mereka untuk mencari tahu. Dalam pendidikan remedi, orang biasanya diberikan penilaian untuk menentukan tingkat kompetensi mereka. Berdasarkan hasil tes, siswa ditempatkan di kelas yang paling mungkin memberikan manfaat. Kelas sering sedikit, dengan sorotan pada interaksi guru-siswa yang tinggi, dan bahwa mereka akan terjadi pada jam kegelapan atau sepanjang hari untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Dalam kursus kategori, guru dapat membawa siswa ke atas terburu-buru agar mereka membutuhkan keterampilan yang sebanding dengan rekan-rekan mereka.
Menurut al-Taubany dan Suseno (2017: 362-367), setiap guru berharap peserta didiknya dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Berdasarkan Permendikbud No.65 tentang Standar Proses, No.66 Tahun 2013 tentang standar penilaian, setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu ( kemampuan awal, ecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar , gaya belajar), maka progam pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/hak anak. Dalam program pembelajaran remedial guru akan membantu peserta didik, untuk memehami kesulitan belajar yang dihadapinya, mengatasi kesulitannya tersebut dengan memperbaiki cara belaja dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal.
Mengacu pada Permendikbud No.65 dan No.66 Tahun 2013: “Hasil penilaian autentik dapat diguanakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan atau pelayanan konseling. Penilaian yang dimaksud tidak tepaku pada hasil tes pada KD tertentu. Penilaian juga bias dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Pembelajaran remedial dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan pada penguasaan materi pada KD tertentu sedang berlangsung. Guru dapat langsung melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kesulitan perseta didik tersebut, tanpa menunggu hasil tes. Program pembelajaran remedial dilaksanakan di luar jam pelajaran efektif atau ketika proses pembelajara berlangsung.
Program pembelajaran remedial dilaksanakann sampai peserta didk menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Ketika peserta didik telah mencapai kompetensi minimalnya, maka pembelajaran remedial tidak perlu dilanjutkan.
According to Chou (2016: 1061), stated that remedial instruction helps students overcome learning 3difficulties, and this learning theory is grown from the cognitive revolution. Immediate and adaptive remedial instruction system helps student’s learning, and the greatest advantage is that it provides immediate feedbacks for the errors (Hsiao et al., 2016). Through the quasi experimental research and design, Dai and Huang (2015) applied three different types of teaching model of remedial teaching on vocational high school students with bad mathematics grades. It has been found that these three methods can improve students’ mathematics grades; e-learning instruction model helps the most, followed by blended learning model, and the least helpful is the traditional instruction model.
Menurut Chou (2016: 2106), menyatakan bahwa instruksi remedial membantu siswa mengatasi pembelajaran kesulitan, dan teori belajar ini tumbuh dari revolusi kognitif. Sistem pembelajaran remedi adaptif membantu pembelajaran siswa, dan keuntungan terbesarnya adalah bahwa ia menyediakan umpan balik langsung untuk kesalahan (Hsiao et al., 2016). Melalui quasiexperimental penelitian dan desain, Dai dan Huang (2015) menerapkan tiga jenis model pengajaran pengajaran remedial pada siswa sekolah menengah kejuruan. Telah ditemukan bahwa ketiga metode ini dapat meningkatkan nilai matematika siswa; Model pembelajaran e-learning sangat membantu, diikuti oleh model pembelajaran campuran, dan paling tidak membantu adalah model instruksi tradisional.
B. Pengertian KKM
Menurut Malawi dan Kardawati (2018: 230-231), kriteria ketuntasan minimal yang selajutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kopentensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3(tiga) aspek: karakteristik peserta didik, karakteristik mata pembelajaran, dan kondisi satuan pendidikan pada proses pencapaian kompetensi.
Menurut Prayitno (2009: 418-419), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan acuan untuk menetapkan seorang peserta didik/siswa secara minimal memenuhi persyaratan penguasaan atas materi pelajaran tertentu. Misalnya, untuk mata pelajaran IPS di suatu SMP KKM-nya adalah 70. Hal ini berarti bahwa seorang siswa di SMP tersebut dinyatakan tuntas dalam mata pelajaran IPS apabila ia menguasai 70% dari seluruh materi IPS yang dibelajarkan; penguasaan di bawah 70% berarti belum tuntas. Pertanyaannya adalah: apa artinya tuntas dan belum tuntas itu? Mengapa 70% dianggap tuntas, padahal tuntas maknanya adalah habis-habisan tanpa tersisa? Dalam perngertia habis-habisan, tanpa tersisa itu, tuntas berkonotasi 100%. Dengan demikian, ketuntasan penguasaan materi IPS di satuan pendidikan (SMP) itu semestinya adalah 100%. Penguasaan di bawah 100% adalah penguasaan yang belum tuntas. Dengan demikian, KKM dengan nilai atau 70 itu sebenarnya belum tuntas.
Agaknya, latar belakang disusun dan ditetapkannya KKM dengan nilai atau harga tertentu (yang setiap kali dapat berubah) adalah karena anggapan bahwa tidak semua siswa mampu mencapai penguasaan 100% atas materi pelajaran; oleh karenanya, perlu diambil patokan untuk menetapkan siswa yang lulus dan tidak lulus dalm mata pelajaran tertentu. Patokan yang dimaksudkan itu biasanya diambil dari penguasaan rata-rata semua siswa yang mengikuti mata pelajaran tersebut pada akhir mata pelajaran (biasanya dalam satuan waktu satu semester). Pengusaan rata-rata itu tidak sama untuk berbagai kondisi yang berbeda; oleh karenanya KKM itupun dapat tidak sama, terutama berkaitan dengan kompleksitas dan kesulitan materi pelajaran, kualitas intake (yaitu tingkat kemampuan dasar atua potensi siswa yang mengikuti mata pelajaran), dan kualitas prasaran dan sarana. Makin kompleks dan sulit materi pelajaran, makin rendah kualitas intake, serta makin rendah kualitas prasaran dan sarana, maka patokan berupa KKM makin diturunkan.
Memperhatikan bberapa pertimbangan dalam penetapn KKM di atas, beberapa catatan dapat diberikan, sebagai berikut. Pertama, dalam penetapan KKM, matapelajaran-matapelajaran yang ada diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, misalnya mata pelajaran yang sulit, sedang, dan mudah. Misalnya, pelajaran Matematika dan IPA diklasifikasikan sulit, Bahahsa sedang, IPS mudah. Pertanyaannya: atas dasar apa klasifikasi itu ditetapkan ? Padahal, sukar dan mudah-nya materi pelajaran tidak semata-mata terletak pada kondisi inheren materi itu sendiri, melainkan terutama sekali ditentukan oleh kondisi operasional pembelajaran yang melibatkan peranan peserta didik dan kondisi lingkungan. Peranan guru sangan dominan untuk menjadikan suatu materi pelajaran menjadi mudah atau sulit dipelaraji siswa.
C. Langkah-Langkah Evaluasi Proses dan hasil Penilaian:
Menurut Astiti (2017: 17-18), langkah-langkah evaluasi proses dan hasil penilaian dapat dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:
- Menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar. Hal ini dilakukan dengan merumuskan tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar, menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai (kognitif, afektif, psikomotor), memilih dan menentukan Teknik yang akan digunakan.
- Menghimpun data. Tahap ini dilakukuan dengan melakukan pengukuran yaitu menggunakan instrument penilaian yang telah disusun untuk memperoleh data terkait.
- Melakukan verifikasi data. Verifikasi data perlu dilakukan agar kita dapat memisahkan data yang “baik” yaitu data yang akan memperjelas gambaran mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dari data yang “kurang baik” yaitu data yang akan mengaburkan gambaran mengenai peserta didik.
- Mengolah dan menganalisis data. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun.
- Melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan proses verbalisasi terhadap makna yang terkandung pada data yang telah diolah dan dianalisis.
- Menindaklanjuti hasil evaluasi berdasarkan data yang telah dihumpun, diolah, dianalisis dan disimpulkan maka dapat dilakukan pengambilan keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut yang konkret dari seluruh kegiatan penilaian.
D. Tujuan dan Fungsi Model Pengajaran Remedial
According to Singh (2004: 16-17), remedial teaching organized in various ways has a potentially important role. There has been quite a rapid expansion of remedial teaching servicesince the late 1940s when public concern grew about the large number of backward readers in schools. Some remedial teachers work in schools with groups and individuals who need extra help, especially early in the junior school. In a few cases they work in centres which children attend several times a week. More frequently they are peripatetic teachers visiting a numberof schools to teach groups and in some well organized services giving advice on materials and methods, undertaking surveys and other services. Their work should be closely integrated with the school pshychological services. Sometimes they work in and from child guidance centres.
As Sampson (1968) points out in reporting the result of a survey of remedial teaching, the original aim of remedial teaching was to remedy education retardation, i.e., children who were failing educationally but normal in ability. It soon became apparent the remedial teachers could not concentrate on ‘und‘r-functioning’ children and, as Sampson’s survey shows, remedial teachers have been trying to help schools cope with children who are backward because of social and cultural limitations, lowish ability and emotional difficulties. Some of these children need special education rather than remedial teaching. The remedy for junir high school children who are show to acquire basic educational skills is not twice-weekly sessions with a remedial teacher but the provision of good teaching, smaller classes, an active child-centred approach emphasizing language development an experience. Remedial teaching has sometimes been used as a palliative, whereas more radical remedies are needed. This is not to say that remedial teaching, especially when it includes an advisory element, does not provide a very useful service. But the training and experience of remedial theachers should perhaps be focused increasing on the children who have specific and severe learning disabilities-children for whom something more than good teaching seems to be needed.
Menurut Singh (2004: 16-17), pengajaran remedial yang diselenggarakan dengan berbagai cara memiliki peran yang berpotensi penting. Sudah ada ekspansi yang cepat dari layanan pengajaran perbaikan sejak akhir 1940-an ketika perhatian publik tumbuh tentang banyaknya pembaca terbelakang di sekolah. Beberapa guru remedi bekerja di sekolah dengan kelompok dan individu yang membutuhkan bantuan tambahan, terutama di awal sekolah menengah pertama. Dalam beberapa kasus mereka bekerja di pusat-pusat yang anak-anak menghadiri beberapa kali seminggu. Lebih sering mereka adalah guru-guru yang bergerak mengunjungi sejumlah sekolah untuk mengajar kelompok-kelompok dan dalam beberapa layanan yang terorganisasi dengan baik memberikan nasihat tentang bahan dan metode, melakukan survei dan layanan lainnya. Pekerjaan mereka harus terintegrasi erat dengan layanan psikologi sekolah. Terkadang mereka bekerja di dan dari pusat bimbingan anak.
Sebagai Sampson (1968) menunjukkan dalam melaporkan hasil survei pengajaran remedial, tujuan asli dari pengajaran remedial adalah untuk memperbaiki retardasi pendidikan, yaitu, anak-anak yang gagal dalam pendidikan tetapi normal dalam kemampuan. Segera menjadi jelas bahwa guru-guru perbaikan tidak dapat berkonsentrasi pada anak-anak yang ‘tidak berfungsi’ dan, seperti yang ditunjukkan survei Sampson, guru-guru remedial telah berusaha membantu sekolah mengatasi anak-anak yang terbelakang karena keterbatasan sosial dan budaya, kemampuan rendah dan kesulitan emosional. Beberapa dari anak-anak ini membutuhkan pendidikan khusus daripada pengajaran remedial.
Obat untuk anak-anak junir sekolah menengah yang menunjukkan untuk memperoleh keterampilan pendidikan dasar bukanlah sesi dua kali seminggu dengan guru remedial tetapi penyediaan pengajaran yang baik, kelas yang lebih kecil, pendekatan yang berpusat pada anak yang aktif menekankan perkembangan bahasa sebuah pengalaman. Pengajaran remedial terkadang digunakan sebagai paliatif, sedangkan pengobatan yang lebih radikal dibutuhkan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pengajaran remedial, terutama ketika itu termasuk elemen penasehat, tidak memberikan layanan yang sangat berguna. Tetapi pelatihan dan pengalaman guru-guru perbaikan mungkin harus difokuskan pada peningkatan anak-anak yang memiliki ketidakmampuan belajar yang spesifik dan berat – anak-anak yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari pengajaran yang baik.
According to Jangid and Inda (2016: 98-99), there are a unit variety of reasons why a student would possibly would like remedial education. Some students attend schools of poor quality and do not receive adequate grounding in mathematics and language to organize them for school or life. Other students might have transferred in and out faculties’ of colleges or missed school plenty, making gaps in their education that contribute to the lack of information in core subjects. Students can also have learning disorders and other problems that have impaired their ability to find out. In remedial education, people are usually given assessments to determine their level of competency. Based on test results, the pupils are placed in classes which are most likely to provide benefits. Classes are often little, with a spotlight on high teacher-student interaction, and that they will occur at the hours of darkness or throughout the day to accommodate various needs. Within the course of the category, the teacher can bring students up to hurry in order that they need skills comparable to those of their peers.
Menurut Jangid dan Inda (2016: 98-99), ada berbagai macam alasan mengapa seorang siswa mungkin ingin mendapatkan pendidikan perbaikan. Beberapa siswa menghadiri sekolah dengan kualitas buruk dan tidak menerima landasan yang cukup dalam matematika dan bahasa untuk mengatur mereka untuk sekolah atau kehidupan. Siswa lain mungkin telah mentransfer masuk dan keluar fakultas ‘perguruan tinggi atau melewatkan banyak sekolah, membuat kesenjangan dalam pendidikan mereka yang berkontribusi pada kurangnya informasi dalam mata pelajaran inti. Siswa juga dapat memiliki gangguan belajar dan masalah lain yang mengganggu kemampuan mereka untuk mencari tahu. Dalam pendidikan remedi, orang biasanya diberikan penilaian untuk menentukan tingkat kompetensi mereka. Berdasarkan hasil tes, siswa ditempatkan di kelas yang paling mungkin memberikan manfaat. Kelas sering sedikit, dengan sorotan pada interaksi guru-siswa yang tinggi, dan bahwa mereka akan terjadi pada jam kegelapan atau sepanjang hari untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Dalam kursus kategori, guru dapat membawa siswa ke atas terburu-buru agar mereka membutuhkan keterampilan yang sebanding dengan rekan-rekan mereka.
Menurut Masbur (2012: 348-361), tujuan pengajaran remedial tidak berbeda dengan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya.
Adapun fungsi pengajaran remedial antara lain:
1. Fungsi korektif
Fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa dan kesulitan belajar siswa tersebut.
2. Fungsi pemahaman
Fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru, siswa dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa.
3. Fungsi penyesuaian
Fungsi penyesuaian yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih baik lebih besar. Tuntutan disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan sehingga termotivasi untuk belajar.
Adapun pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara relevan dengan tingkat yang dimiliki siswa dikarenakan faktor individual siswa dalam memahami suatu bidang studi. Maka fungsi penyesuaian ini memungkinkan individual siswa dengan karakter tertentu dapat termotivasi untuk belajar.
4. Fungsi pengayaan
Fungsi pengayaan yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam atau dengan singkat prestasi belajarnya lebih kaya. Adanya daya dukung fasilitas teknis, serta sarana penunjang yang diperlukan. Sasaran pokok fungsi ini ialah agar hasil remedial itu lebih sempurna dengan diadakannya pengayaan.
Semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin dalam ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun semakin meningkat.
5. Fungsi terapetik
Fungsi terapetik yaitu secara langsung ataupun tidak, pengajaran perbaikan dapat memperbaiki atau menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang penyampaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadi.
Menurut Abujundi dan Setiawati (2018: 55-56), pengajaran remedial, bertujuan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sekurang-kurangnya sesuai dengan derajat ketuntasan minimum. Pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi, yaitu:
- Fungsi korektif yang memungkinkan terjadinya perbaikan hasil belajar dan perbaikan segi-segi kepribadian siswa.
- Fungsi pemahaman yang memungkinkan siswa memahami kemampuan dan kelemahannya serta memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa.
- Fungsi penyesuaian yang memungkinkan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.
- Fungsi pengayaan yang memungkinkan siswa menguasai materi lebih banyak dan mendalam. Sememungkinkan guru mengembangkan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik siswa.
- Fungsi akseleratif yang memungkinkan siswa mempercepat proses belajarnya dalam menguasai materi yang disajikan dan yang terakhir.
- Fungsi terapeutik yang memungkinkan terjadinya perbaikan segi-segi kepribadian yang menunjang keberhasilan belajar.
Menurut Slamet (100-103), tujuan pembelajaran remedial adalah agar siswa dapat:
- Memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi dan kesulitannya.
- Mengubah dan memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik sesuai dengan jenis kesulitannya.
- Memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar.
- Mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya.
- Mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik.
- Melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan
Sedangkan, fungsi pembelajaran remedial, yaitu:
- Fungsi korektif yakni mengadakan perbaikan atau pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa.
- Fungsi Penyesuaian yakni membuat siswa mampu memahami diri dalam kemampuan dan keterampilannya.
- Fungsi pengayaan yakni pengajuan perbaikan yang diharapkan mampu memperkaya pengetahuan.
- Fungsi percepatan yakni perbaikan diharapkan akan dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran
According to Sharma (2005: 218-221), if the goal of developmental and of remedial teaching is the same, the background and attributes of the teachers involved ought to be similar. In fact, more often that not, the same classroom teacher handles, whatever, remedial teaching is done as well as the developmental teaching in a given classroom. Yet as the notion of differentiated roles for teacher becomes more widely accepted an implemented, discussion of differences between developmental and remedial teachers ca be more than academic.
Menurut Sharma (2005: 218-221), jika tujuan pengembangan dan pengajaran remedial adalah sama, latar belakang dan atribut para guru yang terlibat haruslah serupa. Bahkan, lebih sering bahwa tidak, guru kelas yang sama menangani, apa pun, pengajaran remedial dilakukan serta pengajaran perkembangan di kelas yang diberikan. Namun karena gagasan peran yang berbeda untuk guru menjadi lebih diterima secara luas, diskusi tentang perbedaan antara guru pengembangan dan remedial lebih dari sekadar akademik.
E. Bentuk dan Aspek Pengajaran Remedial
Menurut Malawi dan Kardawati (2018: 231), Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara:
- Pemberian bimbingan secara individu
- Pemberian bimbingan secara kelompok
- Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda
- Pemanfaatan tutor sebaya
According to Sharma (2009: 22-25), remedial teaching as the name suggest, is the teaching that is undertaken for providing remedial education to those who are in need of such education for overcoming their deficiencies, weakness and difficulties related with the learning activities pertaining to some area or aspects of a particular subject.
Organisation of Remedial Teaching. Remedial teaching in the subject physical or life sciences can take various forms like below
- Class teaching
- Group tutorial teaching
- Individual tutorial teaching
- Supervised tutorial teaching
- Auto-instructional teaching
- Informal teaching
Let us discuss now all these forms and aspects of remedial teaching.
- Class Teaching. In this system or schedule of remedial teaching, the usual composition and structure of the class is not disturbed. The teacher here teaches a particular lesson/ unit, emphasizes a point again and again, repeats the experiments or uses some specific teaching aid in order to remove the difficulties and deficiencies of the learners in terms of the acquisition of the desired learning experiences. The class as a whole is benefitted through such type of remedial teaching It proves particularly useful in the removal of the weakness and learning difficulties of the general nature.
- Group Tutorial Teaching. Here the students of the class are divided into some homogeneous groups called turorial groups on the basis of their common learning difficulties and identical weakness or deficiencies in the acquisition of the learning experiences in some or the other areas or aspects of the subject. These groups are then taught separately by the same teacher or different teachers according to the nature of the difficulties and deficiencies. The tutor incharge of a tutorial group then tries to solve the difficulties of the learners, hovewer, collectively on a group basis. The weak areas or aspects of the curriculum identified through diagnostic testing are properly attended by the teacher according to the needs and requirement of the pupils of the group. In case, it is related to particular work, due care and proper attention is now paid by the teacher over his own demonstration work as well as on the practical and project work done by the students in their respective groups.
The group tutorial teaching proves advantageous over the class teaching in mnay aspects. Here the students who heve common problems and difficulties in their learning are more helped in overcoming their difficulties and deficiencis. It makes the task of teaching-learning quite interested and goal oriented. In class teaching there remains a lot of chances that the time ang energy of many of the students who do not suffer with a certain learning deficiency or difficulty will go in vain by attending to the remedial teaching not at all needed by them. Moreover, the number of students in group turorial teaching is comparatively reduced. It results in making the task of the teaching more convenient, and effective for providing better coaching and practice in terms of the needed remedial education.
3. Individual Tutorial Teaching. In this schedule every learner, who feels learning difficulty of one or the other nature, is attended individually for overcoming his deficiencies or weakness. It is one to one coaching, help and guidance that is rendered by the teacher to the learner as and when needed by him in oerder to actualize his potentialities to the maximum. Therefore in this type of remedial teaching, maximum consideration may be provided to the principle of individual difference in the direction of the best results in the task of teaching and learning. Here the students may progress according to their own pace, abilities and capacities and get adequate help, individual attention and reinforcement for coping up with their deficiencies and difficulties on the path of learning.
4. Supervised Tutorial Teaching. In this schedule of remedial teaching the responsibility of overcoming the learning difficulties and removing deficiencies in some learning areas is handed over to the learners themselves. They have to work at their own for removing their difficulties and deficiencies. The role of the teacher is confined to observe and supervise the learning activities and provide as much help as necessary to carry on them on their path of self learning and self correction. This type of supervision can be made on the individual as well as tutuorial group levels. The students may opt to work in the group or individually for solving their difficulties and overcoming their learning deficiencies.
5. Auto-Instructional Teaching. This type of remedial teaching consists of auto-instructional programmes and activities. Here the learner is provided with basic auto-instructinal and self learning material and equipments like programmed learning text books and packages, auto-learning modules, teaching machines and computer assisted programmed instuctions etc. This material helps the pupil to gain sufficient practice and drill work in the areas of his weakness and acquire necessary confidence in overcoming his difficulties and deficiencies through the well programmed self-instructional material.
6. Informal Teaching. Informal science education and teaching suitably planned and assimilated with the formal science education of the scholl may go in a big way to act as a source and means of remedial education to the needy students. The activities connected with such informal education in the form of excurcions or trips, collecting material for the science museum, improvising science apparatus, working on useful scientific projects, engaging in the scientific hobbies, establishing acquarium, vivarium, terrarium, botanical garden, zoo and nature study corner in the school campus and participating in the science club activities, etc. Make the study of science a joyful event. These activities suit the diversified interest of the students and provide unique and special opportunities to learn and practise the facts and principles of science. The learning difficulties arised out of the lack of interest, non-availability of direct and first hand learning experience, deficiencies in the methodology of teaching, psychological needs and problems of the learners and host of pother reasons may be easily overcome through the organisation of useful non-formal activities of scientific interest in the schools.
Menurut Sharma (2009: 22-25), pengajaran remedial seperti namanya, adalah pengajaran yang dilakukan untuk memberikan pendidikan remedial kepada mereka yang membutuhkan pendidikan semacam itu untuk mengatasi kekurangan mereka, kelemahan dan kesulitan terkait dengan kegiatan pembelajaran. berkaitan dengan beberapa area atau aspek dari subjek tertentu.
Organisasi Pengajaran Remedial. Pembelajaran remedial dalam subjek ilmu fisik atau kehidupan dapat mengambil berbagai bentuk seperti di bawah ini
1. Pengajaran kelas
2. Mengajar tutorial kelompok
3. Pengajaran tutorial individu
4. Mengawasi pengajaran tutorial
5. Ajaran otomatis instruksional
6. Mengajar informal
Mari kita diskusikan sekarang semua bentuk dan aspek pengajaran remedial ini.
1. Pengajaran Kelas. Dalam sistem atau jadwal pengajaran remedial ini, komposisi dan struktur kelas yang biasa tidak terganggu. Guru di sini mengajarkan pelajaran / unit tertentu, menekankan satu titik lagi dan lagi, mengulangi percobaan atau menggunakan beberapa alat bantu mengajar khusus untuk menghilangkan kesulitan dan kekurangan peserta didik dalam hal perolehan pengalaman belajar yang diinginkan. Kelas secara keseluruhan diuntungkan melalui jenis pengajaran remedial. Hal ini terbukti sangat berguna dalam menghilangkan kelemahan dan kesulitan belajar secara umum.
2. Pengajaran Tutorial Kelompok. Di sini para siswa kelas dibagi menjadi beberapa kelompok homogen yang disebut kelompok turorial atas dasar kesulitan belajar bersama mereka dan kelemahan atau kekurangan yang sama dalam perolehan pengalaman belajar di beberapa atau area lain atau aspek dari subjek. Kelompok-kelompok ini kemudian diajarkan secara terpisah oleh guru yang sama atau guru yang berbeda sesuai dengan sifat kesulitan dan kekurangannya. Tutor yang lebih besar dari kelompok tutorial kemudian mencoba untuk memecahkan kesulitan peserta didik, hovewer, secara kolektif atas dasar kelompok. Area lemah atau aspek kurikulum yang diidentifikasi melalui tes diagnostik dihadiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan murid kelompok. Dalam hal, itu terkait dengan pekerjaan tertentu, perhatian dan perhatian yang tepat sekarang dibayar oleh guru atas pekerjaan demonstrasi sendiri serta pada kerja praktis dan proyek yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok masing-masing.
Pengajaran tutorial kelompok terbukti menguntungkan atas pengajaran kelas dalam aspek mnay. Di sini para siswa yang memiliki masalah umum dan kesulitan dalam belajar mereka lebih terbantu dalam mengatasi kesulitan dan kekurangan mereka. Itu membuat tugas belajar mengajar cukup tertarik dan berorientasi pada tujuan. Di kelas mengajar tetap ada banyak peluang bahwa waktu dan energi dari banyak siswa yang tidak menderita dengan kekurangan belajar tertentu atau kesulitan akan sia-sia dengan menghadiri pengajaran remedial yang tidak dibutuhkan sama sekali oleh mereka. Selain itu, jumlah siswa dalam pengajaran turorial kelompok relatif berkurang. Ini menghasilkan tugas mengajar menjadi lebih nyaman, dan efektif untuk memberikan pelatihan dan praktik yang lebih baik dalam hal pendidikan remedial yang dibutuhkan.
3. Pengajaran Tutorial Individu. Dalam jadwal ini setiap pelajar, yang merasa kesulitan belajar dari satu atau yang lain, dihadiri secara individu untuk mengatasi kekurangan atau kelemahannya. Ini adalah 1-1 pelatihan, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh guru kepada pelajar sebagai dan ketika diperlukan oleh dia di oerder untuk mengaktualisasikan potensi ke maksimum. Oleh karena itu dalam jenis pengajaran remedial, pertimbangan maksimum dapat diberikan kepada prinsip perbedaan individu dalam arah hasil terbaik dalam tugas mengajar dan belajar. Di sini para siswa dapat maju sesuai dengan kecepatan, kemampuan, dan kemampuan mereka sendiri dan mendapatkan bantuan yang memadai, perhatian dan penguatan individu untuk mengatasi kekurangan dan kesulitan mereka pada jalur pembelajaran.
4. Pengajaran Tutorial yang diawasi. Dalam jadwal pengajaran remedial tanggung jawab mengatasi kesulitan belajar dan menghilangkan kekurangan di beberapa area pembelajaran diserahkan kepada peserta didik itu sendiri. Mereka harus bekerja sendiri untuk menghilangkan kesulitan dan kekurangan mereka. Peran guru dibatasi untuk mengamati dan mengawasi kegiatan pembelajaran dan memberikan bantuan sebanyak yang diperlukan untuk meneruskannya pada jalur belajar mandiri dan koreksi diri. Jenis pengawasan ini dapat dilakukan pada individu maupun tingkat kelompok tutuorial. Para siswa dapat memilih untuk bekerja dalam kelompok atau secara individu untuk memecahkan kesulitan mereka dan mengatasi kekurangan belajar mereka.
5. Pengajaran Instruksional Otomatis. Jenis pengajaran remedial ini terdiri dari program dan aktivitas instruksi otomatis. Di sini peserta didik diberikan materi dan peralatan pembelajaran otomatis dasar dan belajar mandiri seperti buku teks dan paket belajar yang diprogram, modul pembelajaran otomatis, mesin pengajar dan komputer yang diprogram dengan panduan, dll. Materi ini membantu siswa mendapatkan latihan yang cukup dan melatih kerja. di area kelemahannya dan mendapatkan kepercayaan yang diperlukan dalam mengatasi kesulitan dan kekurangannya melalui materi pembelajaran mandiri yang terprogram dengan baik.
6. Pengajaran Informal. Pendidikan sains informal dan pengajaran yang direncanakan sesuai dan diasimilasikan dengan pendidikan sains formal dari scholl dapat berjalan dengan cara besar untuk bertindak sebagai sumber dan sarana pendidikan remedial bagi siswa yang membutuhkan. Kegiatan yang terkait dengan pendidikan nonformal dalam bentuk excurcions atau perjalanan, mengumpulkan materi untuk museum sains, improvisasi aparatur sains, bekerja pada proyek ilmiah yang berguna, terlibat dalam hobi ilmiah, mendirikan acquarium, vivarium, terarium, kebun raya, kebun binatang dan sudut belajar alam di kampus sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan klub sains, dll. Jadikan pelajaran sains sebagai acara yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan minat yang beragam dari para siswa dan memberikan kesempatan unik dan khusus untuk belajar dan mempraktekkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip sains. Kesulitan belajar timbul karena kurangnya minat, tidak tersedianya pengalaman pembelajaran langsung dan langsung, kekurangan dalam metodologi pengajaran, kebutuhan psikologis dan masalah peserta didik dan tuan rumah alasan pother dapat dengan mudah diatasi melalui organisasi yang bermanfaat. kegiatan non-formal dari minat ilmiah di sekolah-sekolah.
2.1.5 Prinsip Dasar Model Pengajaran Remedial
According to Kumar (2016: 36-38), remedial teaching consists of remedial activities taking place along with the regular teaching outside the regular class teaching and usually conducted by a special teacher. The type of remedial treatment given to the students depends on the character of the diagnosis made. If physical factors are responsible, remedial attention should be provided.
The following are the general principles of remedial teaching:
1. Individual consideration of the backward pupil with recognition of his mental, physical and educational characteristics.
2. Thorough diagnosis with a pretest.
3. Early success for the pupil in his backward subject or subjects by use of suitable methods and materials.
4. Dissipation of emotional barriers through early success, praise, continuous help, sympathetic consideration of his difficulties and sustained interest.
5. The need for a new orientation towards the backward subject through new methods involving play way approaches, activities and appropriately graded materials.
6. Frequent planned remedial lessons.
7. Co-operation with the parents.
Menurut Kumar (2016, 36-38), pengajaran remedial terdiri dari aktivitas-aktivitas perbaikan yang terjadi bersamaan dengan pengajaran reguler di luar pengajaran kelas reguler dan biasanya dilakukan oleh seorang guru khusus. Jenis perawatan remedial yang diberikan kepada siswa tergantung pada karakter diagnosis yang dibuat. Jika faktor fisik bertanggung jawab, perhatian perbaikan harus diberikan.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip umum pengajaran remedial:
1. Pertimbangan individu dari murid terbelakang dengan pengakuan mentalnya, fisik dan karakteristik pendidikan.
2. Diagnosis menyeluruh dengan pretest.
3. Keberhasilan awal untuk murid dalam subjek terbelakang atau subjek dengan menggunakan yang sesuai metode dan materi.
4. Disipasi hambatan emosional melalui keberhasilan awal, pujian, bantuan berkelanjutan, pertimbangan simpatik atas kesulitan dan minatnya yang berkelanjutan.
5. Kebutuhan akan orientasi baru terhadap subjek yang terbelakang melalui metode-metode baru melibatkan pendekatan cara bermain, kegiatan dan materi yang dinilai secara tepat.
6. Pelajaran remedial yang sering direncanakan.
7. Bekerjasama dengan orang tua.
Menurut al-Taubany dan Suseno (2017: 362-367), beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, yaitu:
1. Adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai denga daya tangkap, kesempatan dan gaya masing-masing
2. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya melibatkat keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan pesrta didk dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya.
3. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
4. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan terhadap kepada peserta didk mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan yang berlarut-larut.
5. Pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing- masing.
Menurut Darmadi (2017: 384-385), berdasarkan pembelajaran dalam KTSP (Depdiknas 2008). Bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai pelayan khusus pembelajaran remedial memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Adaptif. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkin peserta di didik untuk belajar sesuai kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual pesrta didik.
2. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan pesrta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan kegiatan peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapat monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya.
3. Flesibelitas dalam Metode Pembelajaran dan Penilaian. Bahwa dalam pembelajaran remedial perlu digunakan sebagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
4. Pemberian Umpan Balik Segera Mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik.
5. Kesinambungan dan Ketersediaan Pemberian Pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial adalah satu kesatuan, dengan demikian program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan.
2.1.6 Pendekatan Dalam Pelaksanaan Remedial di Sekolah
Menurut Masbur (2012: 348-361), ada beberapa pendekatan belajar dalam pelaksanaan remedial dengan harapan dapat membantu siswa dalam memecahkan berbagai masalah. Menurut Saiful Bahri Djamarah adalah baik pendekatan yang bersifat umum maupun pendekatan yang bersifat keagamaan (khusus). Antara lain yaitu:
1. Pendekatan individual
Pendekatan individual merupakan interaksi antara guru-siswa secara individual dalam proses belajar mengajar. Pendekatan individual adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan caranya. Jadi pendekatan individual adalah pendekatan bersifat perorang, yaitu dikarenakan perbedaan individual siswa atau mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dari satu siswa dengan siswa lain baik dari cara mengemukakan pendapat, daya serap maupun tingkat kecerdasan dan sebagainya. Persoalan kesulitan belajar lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok dibutuhkan.
2. Pendekatan kelompok
Pendekatan kelompok adalah adanya interaksi diantara anggota kelompok dengan harapan terjadi perbaikan pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas adanya guru membentuk kelompok kecil. Kelompok tersebut umumnya terdiri dari 3-8 orang siswa. Dalam pembelajaran kelompok kecil, guru memberikan bantuan atau bimbingan kepada tiap kelompok lebih intensif. Pendekatan kelompok bertujuan membina dan menumbuhkan sikap sosial anak didik, hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo socius, yakni makhluk yang cenderung hidup bersama.
Siswa dibiasakan hidup bersama, bekerja sama dalam kelompok, akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang mempunyai kelebihan mau membantu mereka yang mempunyai kekuranga.
3. Pendekatan bervariasi
Pendekatan bervariasi adalah bermacam-macam pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar agar terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Pendekatan ini terjadi karena siswa mempunyai tingkat motivasi yang berbeda, pada satu sisi siswa memiliki motivasi yang rendah, tetapi pada sisi yang lain mempunyai motivasi yang tinggi. Maka pendekatan bervariasi ini sebagai alat yang dapat guru gunakan untuk kepentingan pengajaran.
4. Pendekatan edukatif
Edukatif adalah sesuatu yang bersifat mendidik dan segala hal yang berkenaan dengan pendidikan. Pendekatan edukatif yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru, baik dari setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan, dengan tujuan untuk mendidik siswa agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial dan norma agama.
Adapun yang penting untuk diingat adalah bahwa pendekatan individual, pendekatan kelompok, dan pendekatan bervariasi harus berdampingan dengan pendekatan edukatif, dengan tujuan untuk mendidik siswa.
5. Pendekatan pengalaman
Pengalaman merupakan suatu kejadian atau perbuatan yang pernah terjadi pada masa dahulu dan mempunyai nilai atau manfaat untuk masa depan. Pendekatan pengalaman yaitu suatu pendekatan yang pembelajarannya harus dilandaskan pada pengalaman siswa sebelumnya. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik daripada sekadar bicara, dan tidak pernah berbuat sama sekali.
6. Pendekatan pembiasaan
Pembiasaan adalah suatu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan relatif menetap. Pendekatan dengan proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif.
7. Pendekatan emosional
Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Emosi atau perasaan adalah sesuatu yang peka. Emosi seperti halnya juga perasaan merupakan suatu suasana hati yang membentuk suatu kontinum atau garis. Kontinum ini bergerak dari ujung yang paling positif yaitu sangat senang sampai dengan ujung yang paling negatif yaitu sangat tiadak senang. Emosi akan memberi tanggapan (respons) bila ada rangsangan (stimulus) dari luar diri seseorang. Rangsangan itu misalnya ceramah, sindiran, pujian, ejekan, anjuran, perintah, sikap dan perbuatan.
Emosi mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pendekatan emosional dimaksud di sini adalah suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Maka metode mengajar yang perlu dipertimbangkan adalah metode ceramah, bercerita, sosiodrama.
8. Pendekatan rasional
Pendekatan rasional ialah pembelajaran yang berpotensi untuk menumbuhkan daya pikir sendiri pada siswa guna memahami, mengamalkan, dan meyakini konsep-konsep dalam pembelajaran remedial. Pendekatan rasional yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis dan sistematis.
Pendekatan dengan menggunakan kemampuan berfikir secara logis dan sistematis. Dengan kekuatan akalnya manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Untuk mendukung pemakaian pendekatan ini, maka metode mengajar yang perlu diberikan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, latihan dan pemberian tugas.
9. Pendekatan fungsional
Pendekatan fungsional adalah suatu pendekatan atau suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya untuk mengisi kekosongan intelektual, tetapi diharapkan berguna untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswa menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam mempertahankan kelangsungan hidup.
Dalam hal ini diperlukan penggunaan metode mengajar, antara lain metode latihan, pemberian tugas, ceramah, tanya jawab dan demonstrasi.
10. Pendekatan keagamaan
Pendekatan keagamaan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran umum dapat menyatu dengan nilai-nilai agama. Hal ini dimaksud agar nilai budaya ilmu tidak sekuler, seperti mata pelajaran biologi dapat dihubungkan dengan masalah agama dalam surat Yasin ayat 34, bahwa pelajaran biologi tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama.
11. Pendekatan kebermaknaan
Pendekatan kebermaknaan adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mempunyai arti atau dapat lebih berarti bagi siswa. Bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran, menjadi lebih bermakna bagi siswa jika berhubungan dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan pengalaman, minat, tata nilai dan masa depan yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pengajaran dan pembelajaran untuk membuat pelajaran lebih bermakna bagi siswa.
Menurut Abujundi dan Setiawati (2018: 55-56), beberapa pendekatan dalam pengajaran remedial pada akhirnya dikembangkan oleh guru ke dalam berbagai strategi pelayanan pengajaran remedial, yaitu:
1. Pendekatan kuratif, pendekatan yang dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. Tiga strategi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu strategi pengulangan, pengayaan dan pengukuhan serta strategi percepatan.
2. Pendekatan preventif, pendekatan yang ditujukan kepada siswa yang pada awal kegiatan belajar telah diduga akan mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan, yaitu kelompok homogen, individual, kelas khusus.
3. Pendekatan yang bersifat pengembangan, pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan siswa harus diketahui guru sedini mungkin agar dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Metode yang dipakai dalam pengajaran remedial harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa metode yang dapat dipergunakan adalah metode pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, tutor sebaya, dan pengajaran individual (Chrisnajanti, 2002: 83).
2.1.7 Langkah Pembelajaran Remedial
2.1.7.1 Hal yang Dibutuhkan Untuk Pengajaran Remedial
According to Kumar (2016: 36-38) Teaching involves communication. That is, messages are being sent at one end and received at the other. When the messages are received as they are transmitted, then effective communication is believed to have taken place. Sometimes the message may not get across at all or may reach the other end in a garbled, distorted and unrecognizable version. In such instances a ‘gap’ develops between ‘teaching’ and ‘learning’. Frequently the learner has not learnt what the teacher intended him to learn. In this case, a message is received, but it is not the one which was sent out Several problems arise in dealing with this situation. First of all, the teacher has to find out if the message received by the student IS the one sent out. For that, the teacher has to rely on the feedback from the student what he has received. Usually the student finds it hard to express what he has received and this give the teacher the impression that learning has not taken place at all. So the teacher tries to get the message across through repetition. But if the message received is a wrong one, it has to be ‘cancelled’ before the correct one can be ‘written in’ in order not to create problems of interference. This is one of the functions of remediation.
It can be inferred that diagnosis is an important factor in imparting teaching .Teaching will be incomplete without diagnosis and remedial teaching. Individuals differ in abilities. Pupils of different levels of ability are likely to be present in a class of forty or fifty. Slow learners, fast learners and average learners — all have to be catered to in different ways. The highly talented should be provided with additional work which requires higher intelligence level and whereas the slow learners have to be specially cared for in order to bring them to the level of the average student. It is valid to consider insight-formation, application, consolidation and revision.
Ideally, new learning should not be permitted until wrong learning has been cancelled and corrected. This is, however, impractical since remediation is a slow and laborious process. A thing once learnt is difficult to cancel, whether correct or incorrect. Remediation, hence, has to go on simultaneously with the other teaching functions. The more teaching a learner has had, the more he may be in need of remediation.
The possible causes of failure in learning can be due to interference from concepts previously learnt or over generalization on the basis of previous learning. These errors of learning are caused by the learner taking an active part in the process of learning They tend to adopt a particular learning strategy .Here; the learner tries to simplify the task of learning or transfers hisprecious learning to a new situation. The teacher is in no way responsible for these errors. He can probably do nothing to prevent them.
The appropriate strategy of remediation can be determined by the types of errors which have to be dealt with. ‘They need classifying into groups and types as all the individual errors cannot be dealt with practically. Remedial teaching is basically cognitive. The aim is to make the learner conscious about the rules; of concept attainment and his own use of it. A teacher cannot consider remediation as a ‘follow-up’ or an optimal activity.
Yang Diperlukan Untuk Pengajaran Remedial:
Mengajar melibatkan komunikasi. Artinya, pesan sedang dikirim di satu ujung dan diterima di ujung yang lain. Ketika pesan diterima saat dikirimkan, maka komunikasi yang efektif diyakini telah terjadi. Kadang-kadang, pesan itu mungkin tidak akan tersebar sama sekali atau mungkin mencapai ujung yang lain dalam versi yang kacau, terdistorsi dan tidak dapat dikenali. Dalam hal-hal semacam itu, ‘celah’ berkembang di antara ‘pengajaran’ dan ‘pembelajaran’. Seringkali pembelajar tidak belajar apa yang diinginkan guru untuk dipelajari. Dalam hal ini, pesan diterima, tetapi bukan pesan yang dikirim. Beberapa masalah muncul dalam menangani situasi ini. Pertama-tama, guru harus mencari tahu apakah pesan yang diterima oleh siswa IS yang dikirim. Untuk itu, guru harus bergantung pada umpan balik dari siswa apa yang telah diterimanya. Biasanya siswa sulit mengungkapkan apa yang telah diterimanya dan ini memberi kesan pada guru bahwa pembelajaran tidak terjadi sama sekali. Jadi, guru mencoba menyampaikan pesan melalui pengulangan. Tetapi jika pesan yang diterima salah, itu harus ‘dibatalkan’ sebelum yang benar dapat ‘ditulis dalam’ agar tidak menimbulkan masalah gangguan. Ini adalah salah satu fungsi remediasi.
Dapat disimpulkan bahwa diagnosis merupakan faktor penting dalam menanamkan pengajaran. Pengajaran akan tidak lengkap tanpa diagnosis dan pengajaran remedial. Individu berbeda dalam hal kemampuan. Murid tingkat kemampuan yang berbeda cenderung hadir di kelas empat puluh atau lima puluh. Pelajar lambat, cepat belajar dan rata-rata peserta didik – semua harus dilayani dengan cara yang berbeda. Yang sangat berbakat harus diberikan pekerjaan tambahan yang membutuhkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan sedangkan pelajar yang lambat harus dirawat secara khusus untuk membawa mereka ke tingkat rata-rata siswa. Ini sah untuk mempertimbangkan pembentukan wawasan, aplikasi, konsolidasi dan revisi.
Idealnya, pembelajaran baru tidak boleh diizinkan sampai pembelajaran yang salah telah dibatalkan dan diperbaiki. Hal ini, bagaimanapun, tidak praktis karena remediasi adalah proses yang lambat dan melelahkan. Suatu hal yang pernah dipelajari sulit untuk dibatalkan, apakah benar atau salah. Remediasi, karenanya, harus berjalan bersamaan dengan fungsi pengajaran lainnya. Semakin banyak pengajaran yang dimiliki seorang pembelajar, semakin dia membutuhkan perbaikan.
Kemungkinan penyebab kegagalan dalam belajar dapat disebabkan oleh interferensi dari konsep yang sebelumnya dipelajari atau generalisasi berlebihan atas dasar pembelajaran sebelumnya. Kesalahan pembelajaran ini disebabkan oleh peserta didik yang mengambil bagian aktif dalam proses pembelajaran. Mereka cenderung mengadopsi strategi pembelajaran tertentu. pembelajar mencoba menyederhanakan tugas belajar atau mentransfer pembelajarannya yang penuh kesungguhan ke situasi baru. Guru sama sekali tidak bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dia mungkin tidak bisa melakukan apa pun untuk mencegahnya.
Strategi remediasi yang tepat dapat ditentukan oleh jenis kesalahan yang harus ditangani. “Mereka perlu mengklasifikasikan ke dalam kelompok dan jenis karena semua kesalahan individu tidak dapat ditangani secara praktis. Pengajaran remedial pada dasarnya bersifat kognitif. Tujuannya adalah untuk membuat pelajar sadar tentang aturan; pencapaian konsep dan penggunaannya sendiri. Seorang guru tidak dapat menganggap remediasi sebagai ‘tindak lanjut’ atau kegiatan yang optimal.
2.1.7.2 Persiapan Materi Pengajaran Remedial
According to Kumar (2016: 36-38) Preparation of remedial materials for a child is a crucial aspect of corrective teaching. Remedial materials prepared should meet the following criteria:
1. The difficulty of the remedial material should be geared to the child’s readiness and maturity in the subject or skill to be improved. A set of remedial materials should provide a wide range of difficulty, covering several grades.
2. The remedial measures should be designed to correct the pupils’ individual difficulties. Through the use of observation, interview and diagnostic testing materials, the teacher would have analyzed the work of the backward children in order to locate the specific retaining needs. An adequate amount of remedial materials must be provided which is designed to correct the specific difficulties identified.
3. The remedial materials should be self-directive. Children may differ widely as to the teaching al materials needed to correct their difficulties. The remedial measures must permit individual rates of progress.
4. A method should be provided for recording individual progress.
5. When the child has an opportunity to record his 1 her successes on a progress record, he I she is given an additional incentive to achieve.
Persiapan Bahan Remedial:
Persiapan bahan-bahan perbaikan untuk anak adalah aspek yang sangat penting dari pengajaran korektif. Bahan remedial yang disiapkan harus memenuhi kriteria berikut:
a. Kesulitan bahan remedial harus disesuaikan dengan kesiapan anak dan kedewasaan dalam subjek atau keterampilan yang harus ditingkatkan. Satu set bahan perbaikan harus menyediakan berbagai kesulitan, mencakup beberapa kelas.
b. Langkah-langkah perbaikan harus dirancang untuk memperbaiki kesulitan individu murid. Melalui penggunaan observasi, wawancara dan materi pengujian diagnostik, guru akan menganalisis pekerjaan anak-anak yang terbelakang untuk menemukan yang spesifik mempertahankan kebutuhan. Sejumlah bahan perbaikan yang memadai harus disediakan dirancang untuk memperbaiki kesulitan spesifik yang diidentifikasi.
c. Bahan-bahan perbaikan harus direktif sendiri. Anak-anak mungkin berbeda secara luas dengan mengajarkan materi yang diperlukan untuk memperbaiki kesulitan mereka.
d. Langkah-langkah perbaikan harus memungkinkan tingkat kemajuan individu.
e. Suatu metode harus disediakan untuk merekam kemajuan individu. Ketika anak itu memiliki kesempatan untuk merekam 1 kesuksesannya pada catatan kemajuan, dia saya dia diberi insentif tambahan untuk mencapainya.
2.1.7.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Remedial
Al-Taubany & Hadi Suseno. (2017: 362-367) Langkah-langkah pembelajaran remedial secara umum dimulai dari identifikasi permasalahan, melakukan perencanaan, melaksanakan program remedial, dan diakhiri dengan penilaian autentik. Uraian langkah-langkah tersebut akan dipaparkan berikut ini.
1. Identifikasi Permasalahan Pembelajaran
Penting untuk memahami bahwa “tidak ada dua individu yang persis sama di dunia ini,” begitu juga penting untuk memahami bahwa peserta didik pun memiliki beragam variasi baik kemampuan, kepribadian, tipe dan gaya belajar maupun latar belakang social budaya. Oleh karenanya guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan permasalahan pembelajaran.
Secara umum identifikasi awal bias dilakukan melalui: (a) observasi (selama proses pembelajaran): (b) penilaian autentik (bisa melalui tes/ulangan harian atau penilaian proses).
Permasalahan pembelajaran dapat dikategorikan kedalam tiga focus perhatian sebagai berikut:
a. Permasalahan pada keunikan peserta didik.
b. Permasalahan pada materi ajar.
c. Permaslahan pada strategi belajar.
2. Perencanaan
Setelah melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan belajar anak, guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik dan mulai untuk membuat perencanaan.
Dengan melihat bentuk kebutuhan dan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik, guru bias merencanakan kapan waktu dan cara yang tepat untuk melakukan pembelajaran remedial. Pada prinsipnya pembelajaran remedial bias dilakukan:
a. Segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran.
b. Menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif.
Dalam perencanaan guru perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial, seperti:
a. Menyiapkan media pembelajaran.
b. Menyiapkan contoh-contoh dan alternative aktifitas.
c. Menyiapkan materi-materi dan alat pendukung.
3. Pelaksanaan
Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial. Ada tiga focus penekanan:
a. Penekanan pada keunikan peserta didik.
b. Penekanan pada alternative contoh dan aktivitas terkait materi ajar.
c. Penekanan pada strategi/metode pembelajaran.
4. Penilaian Autentik
Penilaian autentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian, bila peserta didk belum mencapai kompetensi minimal yang diterapkan guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkannya atau melakukan identifikasi terhadap peserta didik dengan lebih seksama. Apabola peserta didik berhasil mencapai atau melampaui tujuan yang ditetapkan, guru berhasil memberikan pengajaran remedial yang kaya dan bermakna bagi peserta didik, hal ini bias diterapkan sebagai rujukan bagi rekan guru lainnya atau bisa diperkaya lagi. Apabila ditemukan kasus khusus di luar kompetensi guru, guru dapat mengkonsultasikan dengan orangtua untuk selanjutnya dilakukan konsultasi dengan ahli.
Menurut kadarwati dan malawi (2017:230) Adapun langkah-langkah pengajaran remedial menurut diknas, sebagai berikut :
1. Menandai anak yang mengalami kelemahan.
2. Meneliti tentang prestasi hasil belajar yang lain.
3. Mencari latar belakang penyebab kesulitan anak dalam memahami pelajaran.
4. Memberi pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal latihan.
5. Bila langkah no 4 tidak maksimal maka anak tersebut harus dibiasakan memberi beberapa soal agar terbiasa.
6. Memberikan pengajaran remedial atau pengulangan pada bahan ajar tertentu yang belum dikuasai siswa.
Menurut Malawi, dkk (2018: 164-165). Langkah pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu:
1. Identifikasi permasalahan pembelajaran, yang dilakukan berdasarkan hasil analisis penilaian harian, tugas, Permasalahan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi permasalan pada peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran.
2. Penyusun perencanaan berdasarkan permasalahan (keunikan peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran).
3. Hasil penilaian melalui penilaian harian, penguasaan dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan (remedial) dan pengayaan (enrichment). Penilaian yang dimaksud tidak dapat terpaku pada hasil tes (penilaian harian) pada KD tertentu.
4. Pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik mengusaia KD yang ditentukan.
5. Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual, kelompok, atau kelasikal. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial yitu: pembelajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanyajawab, kerja kelompok, dan tutor sebaya.
6. Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial, diantara lain: memberikan tambahan penjelasan atau cintoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang telah lalu, menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran dilakukan penilaian, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai KD yamg ditetapkan.
7. Guru kelas melakukan identifikasi terhadap kesulitan peserta didik, kemudian membuat perencanaan pembelajaran remedial meliputi penentuan materi ajar, penetapan metode, pemilihan media, dan penilaian.
Menurut Masbur (2012: 348-361), Untuk memperlancar pengajaran remedial dengan sempurna sehingga hasil yang diinginkan tercapai lebih baik, maka pelaksanaan harus melalui langkah-langkah yang tepat dan sistematis. Adapun prosedur pengajaran remedial yaitu:
1. Meneliti kembali kasus
Meneliti kembali kasus adalah mendiagnosis kasus kesulitan belajar dengan kriteria di bawah minimal yang dicapai dari hasil belajarnya. Meneliti kembali kasus dengan permasalahannya merupakan tahapan paling fundamental dalam pengajaran remedial karena merupakan landasan titik tolak langkah-langkah berikutnya.
Adapun tujuan penelitian kembali kasus ini adalah agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut, serta cara dan kemungkinan pemecahannya. Berdasarkan atas penelitian kasus akan dapat ditentukan siswa-siswa yang perlu mendapatkan pengajaran remedial. Kemudian ditentukan besarnya kelemahan yang dialami dan dalam bidang studi apa saja mengalami kelemahan.
2. Menentukan tindakan yang harus dilakukan
Menentukan tindakan yang harus dilakukan yaitu menentukan alternatif pilihan yang relevan dengan karakteristik kasus yang ditangani. Langkah ini merupakan lanjutan dari langkah pertama. Dari hasil penelaah dan penelitian kembali kasus yang dilakukan pada langkah pertama itu akan diperoleh karakteristik kasus yang ditangani tersebut, yaitu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu berat, cukup, dan ringan. Dikatakan kasus berat jika siswa belum memiliki cara belajar yang baik, juga memiliki hambatan emosional. Kasus yang cukup adalah jika siswa telah mampu menemukan pola belajar tetapi belum dapat berhasil karena ada hambatan psikologis. Sedangkan pada kasus ringan jika siswa belum menemukan cara belajar yang baik.
Setelah karakteristik harus ditentukan, maka tindakan pemecahan perlu dipikirkan, yaitu sebagai berikut:
a. Kalau kasusnya ringan, tindakan yang ditentukan adalah memberikan pengajaran remedial.
b. Kalau kasusnya cukup dan berat, maka sebelum diberikan pengajaran remedial harus diberi layanan konseling lebih dahulu, yaitu untuk mengatasi hambatan-hambatan emosional yang mempengaruhi cara belajarnya.
3. Pemberian layanan bimbingan dan konseling.
Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh guru/ konselor kepada siswa melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar siswa memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melihat dan menemukan masalahnya serta mampu menyelasaikan masalahnya sendiri. Memberikan arahan atau interaksi antara guru dan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi hambatan mental emosional dalam menghadapi kegiatan belajar.
Pelayanan bimbingan dan konseling yaitu untuk memberikan jasa, manfaat atau kegunaan, ataupun keuntungan-keuntungan tertentu kepada individu-individu yang menggunakan pelayanan tersebut. Tujuan dari layanan ini adalah mengusahakan terciptanya kesehatan agar siswa yang menjadi kasus itu terbebas dari hambatan mental emosional dan ketegangan batinnya, kemudian siap sedia kembali menghadapi kegiatan belajar secara wajar dan realistis.
4. Pelaksanaan pembelajaran remedial
Pelaksanaan pembelajaran remedial merupakan suatu program yang diberikan guru untuk memperbaiki prestasi belajar siswa yang dibawah kriteria ketuntasan minimal. Program ini sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa (dengan karakter) tertentu lebih mampu meningkatkan prestasi seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan.
Sasaran pokok pada langkah ini adalah peningkatan prestasi maupun kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan ketentuan keberhasilan yang telah ditetapkan.
5. Melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi belajar
Melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi adalah dengan mengadakan tes terhadap perubahan pribadi siswa untuk mengetahui proses pengajaran remedial secara menyeluruh.
Langkah ini adalah melakukan pengukuran terhadap perubahan pada diri siswa yang diberikan pengajaran remedial. Apakah ia sudah mencapai apa yang direncanakan pada kegiatan pelaksanaan remedial atau belum. Maka untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan pengukuran terhadap prestasinya kembali dengan alat post-tes atau tes sumatif yang seperti dipergunakan pada proses belajar mengajar yang sesungguhnya.
6. Melakukan re-evaluasi dan re-diagnostik
Melakukan re-evaluasi dan re-diagnostik adalah menafsirkan dengan membandingkan kriteria seperti pada proses belajar mengajar yang sesungguhnya. Adapun dari hasil penafsiran itu dapat terjadi 3 kemungkinan dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:
a. Kasus menunjukkan peningkatan prestasi yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka selanjutnya diteruskan ke program berikutnya.
b. Kasus menunjukkan peningkatkan prestasi, namun belum memenuhi kriteria yang
diharapkan, maka diserahkan pada pembimbing untuk diadakan pengayaan.
c. Kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam hal prestasi, maka perlu didiagnosis lagi untuk mengetahui letak kelemahan pengajaran remedial untuk selanjutnya diadakan ulangan dengan alternatif yang sama.
7. Pengayaan (Tugas Tambahan)
Pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Langkah ini sama dengan langkah ketiga dan bersifat pilihan (optimal) yang kondisional. Sasaran pokok langkah ini ialah agar hasil remedial itu lebih sempurna dengan tindakan pengayaan. Adapun prosedur pelaksanaan remedial menurut Muhammad Entang adalah identifikasi kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kesulitan belajar tidak akan bermanfaat apabila tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang dapat membantu para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sebelum mengambil tindakan-tindakan tersebut seorang guru perlu merencanakan cara yang menurut pertimbangannya akan dapat membantu siswa. Rencana yang disusun hendaknya didasarkan pada hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kesulitan belajar.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan pembelajaran remedial berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditentukan agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar sehingga menemukan letak kesulitan belajar pada diri siswa dan melaksanakan pembelajaran remedial.
Menurut Malawi, dkk (2018: 164-165). Langkah pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu:
1. Identifikasi permasalahan pembelajaran, yang dilakukan berdasarkan hasil analisis penilaian harian, tugas,. Permasalahan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi permasalan pada peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran.
2. Penyusun perencanaan berdasarkan permasalahan (keunikan peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran).
3. Hasil penilaian melalui penilaian harian, penguasaan dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan (remedial) dan pengayaan (enrichment). Penilaian yang dimaksud tidak dapat terpaku pada hasil tes (penilaian harian) pada KD tertentu.
4. Pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik mengusaia KD yang ditentukan.
5. Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual, kelompok, atau kelasikal. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial yitu: pembelajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanyajawab, kerja kelompok, dan tutor sebaya.
6. Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial, diantara lain: memberikan tambahan penjelasan atau cintoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang telah lalu, menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran dilakukan penilaian, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai KD yamg ditetapkan.
7. Guru kelas melakukan identifikasi terhadap kesulitan peserta didik, kemudian membuat perencanaan pembelajaran remedial meliputi penentuan materi ajar, penetapan metode, pemilihan media, dan penilaian.
Perencanaan pengajaran remedial terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh guru diantaranya yaitu diagnosis kesulitan belajar siswa, penelaahan kembali kasus, pemilihan alternatif tindakan, pemberian layanan khusus, dan menyusun program pengajaran remedial. Guru belum melakukan identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui analisis perilaku secara individual, namun guru telah melakukan identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika melalui analisis prestasi yaitu dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Langkah selanjutnya adalah melokalisasi letak kesulitan siswa, hal tersebut dilakukan guru dengan melihat hasil pekerjaan siswa. Siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas diperiksa hasil pekerjaannya untuk mencari tahu letak kesulitan. Kesulitan banyak dilakukan siswa pada soal pembagian dengan angka yang besar (Kurnia, 2016: 1.365-1.366).
2.1.8 Kelemahan Pengajaran Remedial
According to Kumar (2016: 36-38), In Remedial teaching, the teacher is constantly reminded of a principle, which is frequently overlooked in other teaching situations. To a remedial teacher, learning rather than teaching is the goal. The growth of each individual rather than the change in group averages is the criterion of success. Hence the teacher needs a rich background in child psychology and educational diagnosis in order to successfully tackle the variety of individual problems which the child presents themselves.
A major problem in remedial teaching is the dearth of effective teaching al materials. Most of the published materials have been designed for group teaching. Only a small percentage can be adapted for individual teaching. If the material is graded carefully and provided for ample practice on each of the basic steps, the teacher can adapt it for individual use by providing self-directive teaching for pupils. The teacher who understands the objectives to be attained, the analysis of individual difficulties, the types of materials needed, and the techniques essential for correction can adapt some published materials and develop additional supplementary materials which will be appropriate for corrective teaching .
Many teachers who attempt remedial teaching are faced ‘with unusually large classes or with a large percentage of children in the class who are educationally backward. A beginning teacher with a large number of pupils in need of remedial teaching has to limit one’s work to three or four pupils whose needs are greatest. As the teacher gains experience in this program he/she will be able to extend remedial teaching to all the children who need them.
Keterbatasan Pengajaran Remedial:
Dalam pengajaran Remedial, guru secara konstan diingatkan akan sebuah prinsip, yang sering diabaikan dalam situasi pengajaran lainnya. Bagi seorang guru remedial, belajar daripada mengajar adalah tujuannya. Pertumbuhan setiap individu daripada perubahan rata-rata kelompok adalah kriteria keberhasilan. Oleh karena itu, guru membutuhkan latar belakang yang kaya dalam psikologi anak dan diagnosis pendidikan agar berhasil mengatasi berbagai masalah individual yang dialami oleh anak itu sendiri.
Masalah utama dalam pengajaran remedial adalah kurangnya bahan ajar yang efektif. Sebagian besar materi yang dipublikasikan telah dirancang untuk pengajaran kelompok. Hanya sebagian kecil yang dapat diadaptasi untuk pengajaran individual. Jika materi dinilai dengan hati-hati dan disediakan untuk latihan yang cukup pada masing-masing langkah dasar, guru dapat menyesuaikannya untuk penggunaan individu dengan memberikan pengajaran self-directive untuk siswa. Guru yang memahami tujuan yang akan dicapai, analisis kesulitan individu, jenis bahan yang diperlukan, dan teknik yang penting untuk koreksi dapat menyesuaikan beberapa materi yang diterbitkan dan mengembangkan bahan tambahan tambahan yang akan sesuai untuk pengajaran korektif.
Banyak guru yang mencoba mengajar remedial dihadapkan ‘dengan kelas yang luar biasa besar atau dengan persentase besar anak-anak di kelas yang berpendidikan kebelakang. Seorang guru pemula dengan sejumlah besar murid yang membutuhkan pengajaran remedial harus membatasi pekerjaannya kepada tiga atau empat murid yang kebutuhannya paling besar. Ketika guru memperoleh pengalaman dalam program ini dia akan dapat memperpanjang pengajaran remedial untuk semua anak yang membutuhkannya.
Remedial teahing is often left to part-tie teachers or volunteers with no training or knowledge in the field and the total time devoted to such teaching sometimes amounts to no more than thirty minutes each week. It is not surprising that for many children the outcomes are disappointing. This failure might need to be seen, however, as resulting from a lak of appropriate and sufficient instruction for the children at risk, rather than evidence that working with children induvidually
The traditional withdrawal model of remedial teaching:
1. Often have a diet of worksheets or exercises rather than sustained reading practice and guide reading.
2. Have a fragramented kearning experience.
3. Engage in much less purposeful reading and writing activity.
4. Receive little or no instruction in using effective reading comprehension strategies because the focus is entirely on low-level skill development.
Some school now proudly proclaim that they never remove children from the mainstream for remedial teaching. teacher provides everything with occasional advice from a visiting consultant or support teacher. The conclusion that effective intervention from children with reading difficulties requires:
1. Highly trained professionals.
2. A program in which children are taught the specific skills
3. An effective teaching approach that accelerates children acquisitin of skills
4. The main goal of leading children towards independences learning
There is still an essential place for remedial tution in a withdrawal setting before adopting any doctrinaire policy that prohibits withdrawal of children from class, teachers expressed satisfaction with the system and children made significantly better progress in reading (Westwood, 2001: 95-97).
Terjemahannya:
Pengajaran remedial sering dibiarkan terpisah dengan guru atau sukarelawan tanpa pelatihan atau pengetahuan di lapangan dan total waktu yang dihabiskan untuk mengajar semacam itu, kadang-kadang jumlahnya tidak lebih dari tiga puluh menit setiap minggu. Tidak mengherankan bahwa bagi banyak anak, hasilnya mengecewakan. Kegagalan ini mungkin perlu dilihat, bagaimanapun sebagai hasil dari sejumlah pembelajaran yang tepat dan memadai untuk anak-anak lebih berisiko, dari pada anak-anak yang bekerja secara induvidual.
Model penarikan tradisional dari pengajaran remedial:
1. Seringkali memiliki kekurangan lembar kerja atau latihan dari pada praktik membaca yang berkelanjutan dan panduan membaca.
2. Memiliki pengalaman keingintahuan yang terbingkai.
3. Terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis yang kurang bermanfaat.
4. Menerima sedikit atau tidak ada pembelajaran dalam menggunakan strategi pemahaman bacaan yang efektif karena fokus sepenuhnya pada pengembangan keterampilan tingkat rendah.
Beberapa sekolah sekarang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membatasi anak-anak dari arus utama untuk pengajaran remedial. guru menyediakan segala sesuatunya dengan hasil saran sesekali mendatangkan kunjungan konsultan atau dukungan yang membangun.
Kesimpulan bahwa intervensi efektif dari anak-anak dengan kesulitan membaca membutuhkan:
1. Profesional yang sangat terlatih.
2. Program di mana anak-anak diajarkan keterampilan khusus
3. Sebuah pendekatan pengajaran yang efektif yang mempercepat anak-anak memperoleh keterampilan
4. Tujuan utama memimpin anak-anak menuju pembelajaran mandiri
Masih ada tempat penting untuk memperbaiki dalam segi pengaturan penarikan sebelum mengadopsi kebijakan doktriner yang melarang pengulangan pembelajaran bagi anak-anak dari kelas, guru menyatakan puas dengan sistem dan anak-anak memiliki kemajuan yang jauh lebih baik dalam membaca (Westwood, 2001: 95-97).
This study proposed and developed a Remedial-Instruction Decisive path (RID path) to diagnose individual student learning situation. The RID path systematically guides study activities. The system analyses the current learning status of each student and then determines their study processes. Student learns concepts under the planned process. Study outcomes are stored in an evaluated conceptual graph, and the evaluated conceptual graph representing the learning patterns, which include the concepts of learning failure and success held by each student.
SPRT is extremely suitable for the proposed system, since the concepts involved are not complicated, and the testing items are all associated to certain concepts. SPRT can be used to determine whether a learner has mastered a concept by asking a few questions, and increases the accuracy of the test results of the conceptual graph. In analysing student learning outcomes, this study attempts to identify and transfer the numerical score to the labelled score. Traditional examinations include only two results, correct and incorrect. This arrangement is insufficient for remedial instruction. The main focus of the diagnosis in the proposed system is on student learning status, and test score is unimportant.Thus, the dichotomy method is unsuitable.
From the SPRT test outcome, this study classifies the numerical score into three levels: pass concept node, fail concept node, and partial concept node.
1. Pass node: the student has mastered the concept represented by the node, that is the student is proficient in the concept.
2. Fail node: the student has not mastered the concept represented by the node, that is the student is not proficient in the concept. The concept is assumed to be a concept that the student is missing.
3. Partial node: The limited questions cannot judge the proficiency of the student. The student may have partially understood the teaching material. Thus, the student should continue learning.
Three main components of this system are described as follows:
1. User interface: For convenience, teachers do not need to handle student learning progress in diagnostic and remedial instructionTeachers only need to set the parameters of the conceptual graph and select the learning material and items.
2. Learning-related database: The proposed system includes four main databases: item bank, teaching material, the conceptual graph of a specialist and evaluated conceptual graphs. A specialist conceptual graph presents the structure and learning sequence of a single course topic.
3. Remedial instruction module: Student learning outcomes are identified using the item bank database and SPRT. This study presents a ‘RID path’ strategy to identify the missing concepts of students and guiding their learning.
Student learning situations can be diagnosed using the conceptual graph. The evaluated conceptual graph representing student knowledge structure can be obtained from the data in the conceptual graph and the student SPRT results. Each student has a unique evaluated conceptual graph indicating their learning outcomes (Jong, etc; 2004: 380-383).
Terjemahannya:
Penelitian ini mengusulkan dan mengembangkan jalur Tuntas Perbaikan-Instruksi (jalur RID) untuk mendiagnosis situasi belajar siswa secara individual. Jalur RID secara sistematis memandu kegiatan belajar. Sistem ini menganalisis status pembelajaran saat ini dari setiap siswa dan kemudian menentukan proses belajar mereka. Siswa belajar konsep di bawah proses yang direncanakan. Hasil belajar disimpan dalam grafik konseptual yang dievaluasi, dan grafik konseptual yang dievaluasi mewakili pola pembelajaran, yang mencakup konsep kegagalan belajar dan keberhasilan yang dipegang oleh setiap siswa.
SPRT sangat cocok untuk sistem yang diusulkan, karena konsep yang terlibat tidak rumit, dan item pengujian semuanya terkait dengan konsep tertentu. SPRT dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang pembelajar telah menguasai konsep dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dan meningkatkan keakuratan hasil tes dari grafik konseptual. Dalam menganalisis hasil belajar siswa, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan mentransfer skor numerik ke skor berlabel. Ujian tradisional hanya mencakup dua hasil, benar dan salah. Pengaturan ini tidak cukup untuk instruksi perbaikan. Fokus utama diagnosis dalam sistem yang diusulkan adalah aktif
Status belajar siswa, dan nilai tes tidak penting. Jadi, metode dikotomi tidak sesuai. Dari hasil tes SPRT, penelitian ini mengklasifikasikan skor numerik menjadi tiga tingkatan: simpul konsep lulus, simpul konsep gagal, dan simpul konsep parsial.
1. Pass node: siswa telah menguasai konsep yang diwakili oleh node, yaitu siswa yang mahir dalam konsep.
2. Konsep gagal simpul: siswa belum menguasai konsep yang diwakili oleh node, yaitu siswa tidak mahir dalam konsep. Konsep ini diasumsikan sebagai konsep bahwa siswa tersebut hilang.
3. Simpul parsial: Pertanyaan terbatas tidak dapat menilai kemahiran siswa. Murid mungkin memahami materi pengajaran secara parsial. Dengan demikian, siswa harus terus belajar.
Tiga komponen utama dari sistem ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Antarmuka pengguna: Untuk kenyamanan, guru tidak perlu menangani kemajuan belajar siswa dalam diagnostik dan instruksi perbaikan Para guru hanya perlu mengatur parameter grafik konseptual dan memilih bahan dan item pembelajaran.
2. Database yang berhubungan dengan pembelajaran: Sistem yang diusulkan mencakup empat database utama: bank item, bahan ajar, grafik konsep spesialis dan grafik konseptual yang dievaluasi. Grafik konseptual khusus menyajikan struktur dan urutan pembelajaran dari satu topik saja.
3. Modul instruksi remedial: Hasil belajar siswa diidentifikasi menggunakan database bank item dan SPRT. Penelitian ini menyajikan strategi ‘jalur RID’ untuk mengidentifikasi konsep siswa yang hilang dan memandu pembelajaran mereka.
Situasi belajar siswa dapat didiagnosis menggunakan grafik konseptual. Grafik konseptual yang dievaluasi yang mewakili struktur pengetahuan siswa dapat diperoleh dari data dalam grafik konseptual dan hasil SPRT siswa. Setiap siswa memiliki grafik konseptual yang dievaluasi unik yang menunjukkan hasil belajar mereka (Jong, dkk. 2004: 380-383).
2.2 Kajian Kritis
2.2.1 Pengertian
2.2.1.1 Pengertian Model Pengajaran Remedial
Pengajaran remedial adalah bentuk pengajaran perbaikan yang diberikan kepada seseorang siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dihadapinya. Menurut Abin Syamsuddin, pengajaran remedial adalah sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa (dengan kerakter) tertentu lebih mampu meningkatkan prestasi seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan.
2.2.1.2 Pengertian KKM
Kriteria ketuntasan minimal yang selajutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kopentensi lulusan. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3(tiga) aspek: karakteristik peserta didik, karakteristik mata pembelajaran, dan kondisi satuan pendidikan pada proses pencapaian kompetensi
2.2.2 Langkah-Langkah Evaluasi Proses dan Hasil Penilaian
Langkah-langkah evaluasi proses dan hasil penilaian dapat dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:
1. Menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar.
2. Menghimpun data.
3. Melakukan verifikasi data.
4. Mengolah dan menganalisis data.
5. Melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan.
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi.
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Model Pengajaran Remedial
Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya.
Pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi korektif yang memungkinkan terjadinya perbaikan hasil belajar dan perbaikan segi-segi kepribadian siswa.
2. Fungsi pemahaman yang memungkinkan siswa memahami kemampuan dan kelemahannya serta memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa.
3. Fungsi penyesuaian yang memungkinkan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.
4. Fungsi pengayaan yang memungkinkan siswa menguasai materi lebih banyak dan mendalam. Sememungkinkan guru mengembangkan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik siswa.
5. Fungsi akseleratif yang memungkinkan siswa mempercepat proses belajarnya dalam menguasai materi yang disajikan dan yang terakhir.
6. Fungsi terapeutik yang memungkinkan terjadinya perbaikan segi-segi kepribadian yang menunjang keberhasilan belajar.
2.2.4 Bentuk dan Aspek Pengajaran Remedial
Bentuk dan aspek pengajaran remedial ini.
1. Pengajaran Kelas. Dalam sistem atau jadwal pengajaran remedial ini, komposisi dan struktur kelas yang biasa tidak terganggu. Kelas secara keseluruhan diuntungkan melalui jenis pengajaran remedial. Hal ini terbukti sangat berguna dalam menghilangkan kelemahan dan kesulitan belajar secara umum.
2. Pengajaran Tutorial Kelompok. Di sini para siswa kelas dibagi menjadi beberapa kelompok homogen yang disebut kelompok turorial atas dasar kesulitan belajar bersama mereka dan kelemahan atau kekurangan yang sama dalam perolehan pengalaman belajar di beberapa atau area lain atau aspek dari subjek.
3. Pengajaran Tutorial Individu. Dalam jadwal ini setiap pelajar, yang merasa kesulitan belajar dari satu atau yang lain, dihadiri secara individu untuk mengatasi kekurangan atau kelemahannya. Ini adalah 1-1 pelatihan, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh guru kepada pelajar sebagai dan ketika diperlukan oleh dia di oerder untuk mengaktualisasikan potensi ke maksimum.
4. Pengajaran Tutorial yang diawasi. Dalam jadwal pengajaran remedial tanggung jawab mengatasi kesulitan belajar dan menghilangkan kekurangan di beberapa area pembelajaran diserahkan kepada peserta didik itu sendiri.
5. Pengajaran Instruksional Otomatis. Jenis pengajaran remedial ini terdiri dari program dan aktivitas instruksi otomatis. Di sini peserta didik diberikan materi dan peralatan pembelajaran otomatis dasar dan belajar mandiri seperti buku teks dan paket belajar yang diprogram.
6. Pengajaran Informal. Pendidikan sains informal dan pengajaran yang direncanakan sesuai dan diasimilasikan dengan pendidikan sains formal dari scholl dapat berjalan dengan cara besar untuk bertindak sebagai sumber dan sarana pendidikan remedial bagi siswa yang membutuhkan.
2.2.5 Prinsip Dasar Model Pengajaran Remedial
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengajaran remedilal:
a. Adaptif.
b. Interaktif.
c. Berbagai metode pembelajaran dan penilaian.
d. Pemberian umpan balik sesegera mungkin.
e. Berkesinambungan.
2.2.6 Pendekatan Dalam Pelaksanaan Remedial di Sekolah
Pendekatan yang bersifat umum maupun pendekatan yang bersifat keagamaan (khusus). Antara lain yaitu:
1. Pendekatan individual suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan caranya.
2. Pendekatan kelompok adanya interaksi diantara anggota kelompok dengan harapan terjadi perbaikan pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar.
3. Pendekatan bervariasi bermacam-macam pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar agar terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Pendekatan ini terjadi karena siswa mempunyai tingkat motivasi yang berbeda.
4. Pendekatan edukatif sesuatu yang bersifat mendidik dan segala hal yang berkenaan dengan pendidikan.
5. Pendekatan pengalaman suatu kejadian atau perbuatan yang pernah terjadi pada masa dahulu dan mempunyai nilai atau manfaat untuk masa depan.
6. Pendekatan pembiasaan suatu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan relatif menetap.
7. Pendekatan emosional suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Maka metode mengajar yang perlu dipertimbangkan adalah metode ceramah, bercerita, sosiodrama.
8. Pendekatan rasional pembelajaran yang berpotensi untuk menumbuhkan daya pikir sendiri pada siswa guna memahami, mengamalkan, dan meyakini konsep-konsep dalam pembelajaran remedial.
9. Pendekatan fungsional suatu pendekatan atau suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya untuk mengisi kekosongan intelektual, tetapi diharapkan berguna untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Pendekatan keagamaan suatu pendekatan yang dilakukan dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran umum dapat menyatu dengan nilai-nilai agama.
11. Pendekatan kebermaknaan pendekatan dalam pembelajaran yang mempunyai arti atau dapat lebih berarti bagi siswa. Bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran, menjadi lebih bermakna bagi siswa jika berhubungan dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan pengalaman, minat, tata nilai dan masa depan.
2.2.7 Langkah Pembelajaran Remedial
1. Identifikasi permasalahan pembelajaran.
2. Penyusun perencanaan berdasarkan permasalahan (keunikan peserta didik, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran).
3. Hasil penilaian melalui penilaian harian, penguasaan dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan (remedial) dan pengayaan (enrichment).
4. Pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik mengusaia KD yang ditentukan.
5. Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual, kelompok, atau kelasikal.
6. Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial, diantara lain: memberikan tambahan penjelasan atau cintoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang telah lalu, menggunakan berbagai jenis media.
7. Guru kelas melakukan identifikasi terhadap kesulitan peserta didik, kemudian membuat perencanaan pembelajaran remedial meliputi penentuan materi ajar, penetapan metode, pemilihan media, dan penilaian.
2.2.8 Kelemahan Pengajaran Remedial
Dalam pengajaran Remedial, guru secara konstan diingatkan akan sebuah prinsip, yang sering diabaikan dalam situasi pengajaran lainnya. Bagi seorang guru remedial, belajar daripada mengajar adalah tujuannya. Pertumbuhan setiap individu daripada perubahan rata-rata kelompok adalah kriteria keberhasilan. Oleh karena itu, guru membutuhkan latar belakang yang kaya dalam psikologi anak dan diagnosis pendidikan agar berhasil mengatasi berbagai masalah individual yang dialami oleh anak itu sendiri.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pengajaran remedial adalah bentuk pengajaran perbaikan yang diberikan kepada seseorang siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dihadapinya.
2. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya.
3. Pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi, yaitu: a) fungsi korektif, b) fungsi pemahaman, c) fungsi penyesuaian, d) fungsi pengayaan, e) fungsi akseleratif, f) fungsi terapeutik
4. Bentuk dan aspek pengajaran remedial ini yaitu pengajaran kelas, pengajaran tutorial kelompok, pengajaran tutorial individu, pengajaran tutorial yang diawasi, pengajaran instruksional otomatis, dan pengajaran informal.
5. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengajaran remedilal yaitu adaptif, interaktif, berbagai metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan berkesinambungan.
3.2 Saran
Semoga dengan adanya makalah ini, para pembaca bisa lebih mengetahui tentang Pengajaran Model Remedial. Terlebih khusus lagi kepada mereka calon guru, semoga bisa menjadi bahan pelajaran yang baik, dan semoga bisa diterapkan nanti ketika kita sudah bekerja menjadi seorang guru.