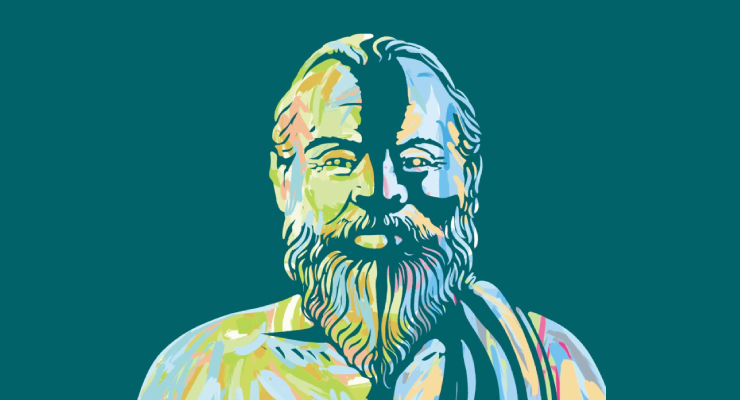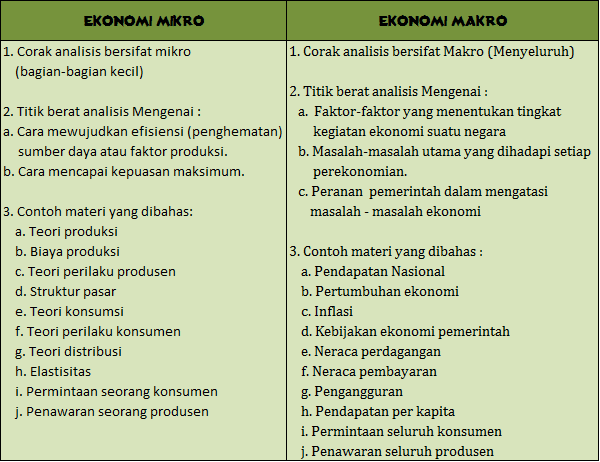Salah satu sumbangan pemikiran Socrates adalah upaya mengenal manusia dengan memahami alam semesta. Ketidaktahuan akan berbuah pada perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan. Pemilkiran-pemikiran ia tuangkan dalam bentuk dialog-dialog yang kebanyakan menggunakan nama gurunya sebagai tokoh dalam dialog tersebut.
Pemikiran Socrates
A. Riwayat Hidup (470 – 399 SM)
Socrates lahir di Athena, Yunani sekitar tahun 470 SM. Ia lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung dan ibunya seorang bidan. Awalnya, Socrates tumbuh menjadi seorang pematung sebagaimana bapaknya. Namun seiring dengan waktu, Socrates lebih tertarik dengan pembentukan watak dan pemikiran dibandingkan dengan pembuat wujud manusia.
Socrates dikenal sebagai pribadi yang cerdas, baik, jujur, arif dan adil. Ia menyampaikan pemikirannya menggunakan meyode tanya jawab (dialog) dan sederhana. Hal ini yang membuat banyak orang bersimpati kepadanya, khususnya dari golongan muda. Namun bagi golongan tua dan konservatif, Socrates kurang disenangi karena dianggap merusak tatanan dan nilai-nilai moral yang ada.
Dituduh Atheis
Salah satu pemikiran Socrates yang paling kontroversial di zamanya adalah menolah mitos yang ada di Yunani. Hal ini termaasuk menolah mengauki dewa-dewa dan tuhan-tuhan yang diagungkan pada masa tersebut.
Sejalan dengan pemikirannya, Socrates akhidrnya diadili di pengadilan Athena dengan tuduhan melawan tuhan dan mencoba membuat agamanya sendiri. Dalam proses pengadilan, ia menyampaikan pembelaan yang kelak dikemudian hari ditulis ulang oleh Plato dengan naskah yang berjudul Apologi.
Dalam tuduhan tersebut, Plati mengisahkan bahwa Socrates dituduh menolak agama yang diakui oleh negara bahkan cenderung mengajarkan agama baru yang ia buat sendiri. Melathus, salah satu tokoh Athena pada masa tersebut menuduh Socrates adalah orang yang tidak bertuan. Melathus juga menentang pendapat Socrates yang menganggap bahwa Matahari adalah Batu dan Bulan adalah tanah.
Socrates membantah tuduhan tersebut dengan bertanya kepada Meltahus, siapakah orang yang memperbaiki pada pemuda? Melathus menjawab, Mula-mula para Hakim lalu semua orang kecuali socrates. Socrates lalu merespon jawab tersebut dengan ucapat selamat karena Athena memiliki nasib yang baik dimana ada banyak orang yang berusahan memperbaiki pemuda (generasi muda) dan orang-orang baik tersebut lebih pantas dijadikan teman bergaul dibandingkan dengan orang-orang jahat. Oleh karena itu, Malethus seharunya mengajar dia (Socrates) bukanya menyernya ke pengadilan. (Atollah, 2019)
Masa hidupnya hampir sejalan dengan perkembangan sofisme di Athena. Pada hari tuanya, socrates melihat kota tumpah darahnya mulai mundur, setelah mencapai puncak kebesaran yang gilang-gemilang.
Lebih lanjut, Plato mengisahkan pembelaan Socrates yang mempunyai nada agama. Ia pernah menjadi tentara, dan tetap pada pos ini selama ia diperintahkan untuk tak meninggalkannya. Kini, Tuhan menyuruh saya untuk menaikkan tugas amanat filosof untuk mengenal diri saya dan orang lain, dan tentu sangat memalukan jika kau meninggalkan pos ini sekarang seperti halnya pula pada waktu peperangan dan pertempuran. Lebih baik mati daripada takut mati tapi pada akhirnya mati juga. Kalau dia diminta untuk berhenti merenung dan mengadakan penyelidikan agar dia selamat dari maut, ia tentu menjawab, “Wahai warga Athena! Aku menghormati dan mencintai kamu, tetapi aku akan lebih tunduk kepada Tuhan daripada kamu, dan selama hayat dikandung badan dan aku memiliki kekuatan, aku tak akan berhenti mengerjakan dan mengerjakan filsafat, menganjurkan setiap orang yang ku temui. Karena itu, ketahuilah bahwa ini adalah perintah Tuhan; dan aku percaya bahwa tak ada kebaikan lebih besar bagi negara daripada pengabdianku kepada Tuhan.” (Ahmad Syadali dan Mudzakir, 2004 : 66 – 67)
Dalam proses pengadilan diputuskan bahwa Socrates dinyatakan bersalah dengan suara 280 melawan 220. Ia dituntut hukuman mati dengan cara meminum racun.
Karya
Secara historis, filsafat Socrates mengandung pertanyaan karena Socrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, Xenophone (430-357) SM, dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal diantaranya adalah penggambaran Socrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sorates. Nama Plato sendiri hanya muncul tiga kali dalam karya-karyanya sendiri yaitu dua kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus.
Pemikiran
Seseorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya pertanyaan ini: “Apakah tujuan hidup itu?” atau “Untuk apa aku peroleh dan mempunyai ilmu pengetahuan?” Khusus tentang fungsi Kongrit filsafat dan ilmu pengetahuan, yang mengkhususkan diri ke dunia ide pemikiran dipandang tidak banyak memberikan jawaban nyata atas persoalan kehidupan, hanya melayang-layang di awang-awang. Benarkah demikian? Tentu saja banyak sekali variasi jawaban dari dua peryataan di atas, tergantung latar belakang kehidupan dan pendidikan serta pandangan dunianya.
Pada masa Yunani Kuno, pertanyaan-pertanyaan itu berusaha dijawab oleh Socrates. Socrates kerap disebut jarang mempunyai ajarannya sendiri yang tertulis. Kebanyakan orang lebih menekankan pada metode kebidanan dan ironinya yang mengusik status quo ketika itu hingga ia dihukum mati. Atau walupun ada ajaran aslinya, namun telah bercampur baur dengan pandangan murid-muridnya, terutama Plato.
Seperti para sofis pada zamannya ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya dan mengarahkan perhatiannya pada manusia. Perbedaannya dengan kaum sofis, Socrates tidak memungut biaya apapun, menolak relatifisme dan yakin ada kebenaran obyektif dan juga tidak mendorong orang mengikuti pemikirannya melainkan hanya mendorong orang untuk mengetahui dan menyadari dirinya sendiri. Metode yang digunakan cukup unik dan mengusik ketentraman penguasa ketika itu. Ia bukannya mengajarkan atau menjawab sesuatu, tetapi bertanya hal-hal mengenai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya jarang dipertanyakan. Secara induktif, ia menanyakan definisi umum tentang sesuatu, misalnya apakah keadilan itu? Apakah kedermawanan itu? Metode ini adalah metode kebidanan dimana Socrates hanya membantu membidani kelahiran gagasan murid-muridnya saja. Metode ini memakai gaya ironi di mana sengaja ia menanyakan hal-hal yang membingungkan sehingga penjawabnya menjawab hal yang bertentangan.
Jawaban mereka pertama-tama dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk hipotesa, hipotesa itu dipertanyakan lagi dan dianalisis lagi oleh penjawab. Demikian seterusnya. Socrates melakukan itu semua tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan Dewa Apollo di Orakel Delphi: bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dari Socrates, maka ia pun mulai bertanya-tanya. Akhirnya Socrates menyadari bahwa dirinya bijaksana karena ia tahu bahwa ia tidak tahu.
Secara sistematis, alur pemikiran Socrates dapat digambarkan sebagai berikut:
- Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan (eaudaemonia)
- Kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan (arate)
- Untuk mengetahui apa dan bagaimana arate kita itu, harus kita ketahui dengan pengetahuan(episteme
- Jadi keutumaan (arate) adalah pengetahuan (episteme)
Pemikiran Filsafat
Adapun falsafah pemikiran Socrates, diantaranya adalah pernyataan tentang adanya kebenaran obyektif, yaitu yang tidak bergantung kepada aku dan kita. Dalam membenarkan kebenaran yang objektif, ia menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika. Dialektika berasal dari kata Yunani yang berarti bercakap-cakap atau berdialog.
Menurut Socrates, ada kebenaran objektif, yang tidak bergantung kepada aku dan kita. Untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode tertentu. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisis pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan benar. Ia bertanya kepada negarawan, hakim, tukang, pedagang, dan sebagainya. Menurut Xenophone, ia bertanya tentang benar-salah, adil-dzalim, berani-pengecut, dan lain-lain kepada siapapun yang menurutnya patut ditanya. Socrates selalu menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis, dan dengan jawaban yang lebih lanjut, ia menarik konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban tersebut. Jika ternyata hipotesis pertama tidak dapat dipertahankan, karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, hipotesis itu diganti dengan hipotesis yang lain, lalu hipotesis kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain, dan begitu seterusnya. Sering terjadi, percakapan itu berakhir dengan apoira (kebingungan). Akan tetapi, tidak jarang, dialog itu menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. (Ahmad Syadali dan Mudzakir, 2004:66-67)
Dari metode dialektikanya, ia menemukan dua penemuan metode yang lain, yakni induksi dan definisi. Ia menggunakan istilah induksi manakala pemikiran bertolak belakang dari pengetahuan yang khusus, lalu menyimpulkannya dengan pengertian yang umum. Pengertian umum diperoleh dari mengambil sifat-sifat yang sama (umum) dari masing-masing kasus khusus dan ciri-ciri khusus yang tidak disetujui bersama disisihkan. Ciri umum tersebut dinamakan ciri esensi dan semua ciri khusus itu dinamakan ciri eksistensi. Suatu definisi dibuat dengan menyebutkan semua ciri esensi suatu objek dengan menyisihkan semua ciri eksistensinya. Demikianlah jalan untuk memperoleh definisi tentang suatu persoalan. (Ahmad Syadali dan Mudzakir, 2004:66-67)
Socrates dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, arif dan bijaksana. Namun, ia tak pernah mengaku mempunyai kearifan dan kebijaksanaan, ia hanya mengaku sebagai penggemar kearifan atau amateur kebijaksanaan, bukan profesional dan tidak mengambil bayaran atau kebendaan dari apa yang ia gemari seperti kaum sofis pada zamannya.
Konon dewa yang berada di tempat peribadatan bagi kaum Yunani di Delphi menyatakan dengan cara luar biasa bahwa ia adalah orang yang paling arif di negeri Yunani. Ia menafsirkan bisikan dewa itu sebagai persetujuan atas cara agnotism yang menjadi titik-tolak dari filsafatnya: “only thing I know, and that is I know nothing”. Memang, filsafat bermula jika seseorang belajar bagaimana meninjau kembali kepercayaan yang telah sejak kecil dianut, meninjau kembali keyakinan dan meragukan aksioma pengetahuan.
Bagaimana kepercayaan-kepercayaan menjadi keyakinan, apa tidak ada tujuan tertentu dan maksud rahasia dibelakang yang menyebabkan kelahirannya, dan menaruhnya dalam baju yang merahasiakan hakikat sebenarnya? Tidak ada filsafat yang sebenarnya sebelum pikiran menengok dan menyelidiki lebih mendalam. Berfilsafat yang terbaik adalah melakukan kajian filosofis atas filsafat itu sendiri.
Paham etika Socrates merupakan kelanjutan dari metode yang ia temukan (induksi da definisi). Sayangnya, Socrates tidak pernah menulis pemikiran falsafahnya sendiri. Untuk mengetahuinya, kita dapat memperolehnya dari murid-muridnya. (Ahmad Syadali dan Mudzakir, 2004:66-67)
Socrates bergaul dengan semua orang, tua dan muda, kaya dan miskin. Ia seorang filosof dengan corak sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa Socrates adalah orang yang sangat adil, ia tak pernah berlaku dzalim. Ia pandai menguasai dirinya, sehingga ia tak pernah memuaskan hawa nafsu dengan merugikan kepentingan umum. Socrates seorang yang cerdas dan bermoral. Ia senantiasa memikirkan perbedaan baik dan buruk, sehingga kehidupan manusia lebih terjamin dari ketentraman dan kedamaian.
Tabiat Socrates tercermin dalam pernyataannya sebagai berikut, “padang rumput dan pohon kayu tak memberi pelajaran apapun kepadaku, manusia ada”. Ia memerhatikan yang baik dan yang buruk, yang terpuji dan tercela. Suatu saat ia didapati di tanah lapang dimana banyak orang berkumpul, tidak lama ia berada di pasar. Ia berbicara dengan semua orang, menanyakan apa yang dibuatnya. Ia ingin mengetahui sesuatu dari orang yang mengerjakan sesuatu. Ia selalu bertanya, sungguh-sungguh bertanya, karena ia ingin tahu. Ia bercakap dengan seorang tukang, bertanya tentang pertukangannya. Ia bertanya kepada seorang pelukis tentang apa yang dikatakan indah. Kepada prajurit atau ahli perang, ia tanyakan, apa yang dikatakan berani. Pertanyaan itu mulanya mudah dan sederhana. Setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Dari pertanyaan biasa, lalu ia membawanya kepada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Akhirnya, orang yang menganggap tahu tadi dihadapkannya pada tanggung jawab tentang pengetahuannya. Tidak jarang terjadi bahwa dia yang mulanya membanggakan pengetahuannya, mengaku tidak tahu lagi. Lalu Socrates, yang mengaku tak tahu, merasa bahwa ia lebih banyak tahu dari mereka yang menganggap dirinya mengetahui.
Tujuan Socrates adalah mengajar orang mencari kebenaran. Sikap itu merupakan suatu reaksi terhadap ajaran sofisme yang merajalela pada waktu itu. Karena guru-guru sofis mengajarkan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai. Oleh sebab itu, tiap-tiap pendirian dapat “dibenarkan” dengan jalan retorika. Dengan daya kata dicoba memperoleh persetujuan orang banyak. Apabila orang banyak sudah setuju, itu dinggap sudah benar. Dengan cara begitu, pengetahuan menjadi dangkal.
Terhadap aliran yang mendangkalkan pengetahuan dan melemahkan rasa tanggung jawab itu, semangat Socrates memberontak. Dengan filosofi yang diamalkannya dan dengan cara hidupnya, ia mencoba memperbaiki masyarakat yang rusak. Orang diajak memperhitungkan tanggung jawabnya. Ia selalu berkata, “yang ia ketahui Cuma satu, yaitu bahwa ia tak tahu, sebab itu ia bertanya. Tanya jawab adalah jalan baginya untuk memperoleh pengetahuan.” Itulah permulaan dialektika.
Guru-guru sofis yang mengobralkan “ilmu” di tengah-tengah pasar ditantangnya dengan cara berguru. Ia yang tidak mengetahui itu ingin tahu dan bertanya. Tiap jawaban atas pertanyaannya disusul dengan pertanyaan baru. Demikianlah seterusnya. Pertanyaan itu beruntun sehingga kaum sofis terdesak dan menyerah. Akhirnya guru sofis tak sanggup lagi menjawab dan mengakui kekalahan perdebatannya dengan Socrates, atau mereka mengakui ketidaktahuannya. Lalu, Socrates mengunci tanya-jawab tersebut dengan berkata, “demikianlah adanya, kita sama-sama tidak tahu.”
Socrates mencari pengertian, yaitu bentuk yang tetap dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, ia selalu bertanya, “apa itu? Apa yang dikatakan berani, apa yang disebut indah, apa yang bernama adil?” pertanyaan tentang “apa itu” harus lebih dahulu daripada “apa sebab”. Ini biasa bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak kecil pun mulai bertanya dengan “apa itu”. Jawaban tentang “apa itu” harus dicari dengan tanya jawab yang semakin meningkat dan mendalam, maka Socrates diakui pula – sejak keterangan Aristoteles – sebagai pembangun dialektik pengetahuan. Tanya Jawab, yang dilakukan secara meningkat dan mendalam, melahirkan pikiran yang kritis. Mencari kebenaran yang hakiki, yaitu mencari pengetahuan yang sebenar-benarnya, terletak pada seluruh filosofinya.
Karena Socrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana dan sini, yang kemudian dibulatkan dengan pengertian. Jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dan definisi. keduanya bersangkut-paut. Induksi menjadi dasar definisi.
Bertens (1975: 85-92) menjelaskan ajaran Socrates sebagai berikut ini: ajaran itu ditujukan Untuk menentang ajaran relativisme sofis. Ia ingin menegakkan sains dan agama.
Kalau dipandang sepintas lalu, Socrates tidaklah banyak berbeda dengan kaum sofis. Sama dengan orang-orang sofis, Socrates memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Akan tetapi, ada perbedaan yang amat penting antara sofis dan Socrates. Socrates tidak menyetujuai relatifisme kaum sofis.
Orang sofis beranggapan bahwa semua pengetahuan adalah relatif kebenarannya, tidak ada pengetahuan yang bersifat umum. Dengan definisi, Socrates dapat membuktikan kepada kaum sofis bahwa pengetahuan yang umum ada, yaitu definisi tersebut. Jadi, orang sofis tidak seluruhnya benar: yang benar ialah sebagian pengetahuan bersifat umum dan sebagian bersifat khusus; yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya bersifat relatif.
Dengan mengajukan definisi itu Socrates telah dapat “menghentikan” laju dominasi relatifisme kaum sofis. Jadi, kita bukan hidup tanpa pegangan; kebenaran sains dan agama dapat dipegang bersama sebagiannya, diperselisihkan sebagiannya. Dan orang Athena mulai kembali memegang kaidah sains dan akidah agama mereka.
Plato memperkokoh tesis Socrates itu. Ia mengatakan kebenaran umum itu memang ada. Ia bukan dicari dengan induksi seperti pada Socrates, melainkan telah ada “di sana” di alam idea. Kubu Socrates semakin kuat. Orang sofis mulai kehabisan pengikut. Ajaran bahwa kebenaran itu relatif semakin ditinggalkan, semakin tidak laku. Orang sofis kalap, lalu menuduh Socrates merusak mental pemuda dan menolak tuhan-tuhan. Socrates diadili oleh hakim Athena. Disana ia mengadakan pembelaan panjang-lebar yang ditulis oleh muridnya, Plato, di bawah judul Apologia (pembelaan). Dalam pembelaan itu, ia menjelaskan ajaran-ajarannya, seolah-olah ia mengajari semua yang hadir di pengadilan itu dan dijatuhi hukuman mati.
Sekalipun ajaran Socrates mati, ajarannya tersebar justru sangat cepat karena kematiannya itu. Orang mulai mempercayai adanya kebenaran umum.
Pengaruh pemikiran filsafat
Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode elenchus, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, bahkan juga filsafat secara umum. Salah satu catatan Plato yang terkenal adalah Dialogue, yang isinya berupa percakapan antara dua orang pria tentang berbagai topik filsafat. Socrates percaya bahwa manusia ada untuk satu tujuan, dan bahwa salah dan benar memainkan peranan penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya.
Sebagai seorang pengajar, Socrates dikenang karena keahliannya dalam berbicara dan kepandaian pemikirannya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri, dan manusia pada dasarnya adalah jujur, dan kejahatan merupakan suatu upaya akibat salah pengarahan yang membebani kondisi seseorang. Pepatahnya yang terkenal: “kenalilah dirimu”. Socrates percaya bahwa pemerintahan yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak, yang dipersiapkan dengan baik, dan mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Ia juga dikenang karena menjelaskan gagasan sistematis bagi pembelajaran mengenai keseimbangan lingkungan, yang kemudian akan mengarah pada perkembangan metode ilmu pengetahuan.
Pemikiran politik Socrates
Pemikiran politiknya berawal di Yunani Kuno. Pikiran Yunani secara sistematis menyelidiki watak dan jalannya institusi politik. Dalam rekaman sejarah, tercatat muncul suatu pola konsepsi sosial politik yang mendasar dalam warisan kebudayaan dan intelektual barat. Ide demokratis pun telah muncul di sana. Di Yunani Kuno pula problem-problem manusia dan Negara pertama kali diangkat ke permukaan, termasuk di era Socrates.
Doktrin politik Socrates bahwa “kebijakan adalah pengetahuan” merupakan dasar bagi pemikiran politiknya mengenai Negara. Inilah salah satu pandangan politik Socrates yang amat penting dan belakangan berpengaruh pada pandangan politik muridnya, Plato. Meski Socrates tak menulis banyak hal berkaitan dengan pandangan-pandangan politiknya, informasi tersebut bias dilacak dari beberapa murid dan lawan diskusinya. Socrates mencurahkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh pada perkembangan metodologi atau model prosedural untuk mencapai kebenaran. Baginya, prinsip politik juga mendasarkan pada etika yang ia simpulkan “kebijakan adalah pengetahuan”.
Mengenai kontribusinya yang lain, Socrates mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang terdapat pada hukum-hukum dan tradisi-tradisi yang beragam di berbagai belahan dunia ini. Dia menegaskan bahwa norma-norma kebenaran itu bebas dari dan penting untuk individu. Socrates menjawab bahwa terdapat kerajaan yang supra-manusiawi yang peraturannya mengikat seluruh rakyatnya. Socrates mendasarkan pada hukum tersebut pada akal, konsepsi ini secara formal menjadi bagian dari pemikiran filosofis.
Konsep Ketuhanan
Kosepnya tentang roh, terkenal tidak tentu (indeterminate) dan berpandangan terbuka (openminded), jelas-jelas tidak agamis dan terlihat tidak mengandalkan doktrin-doktrin metafisik atau teologis. Juga tidak melibatkan komitmen-komitmen naturalistik atau fisik apapun, seperti pandangan tradisional bahwa roh adalah “nafs” yang menghidupkan. Sebenarnya juga tidak jelas bahwa ia sedang mencari kesepakatan bagi pendapatnya bahwa roh tidak dapat mati, dan didalam Apologi, ia hanya mengatakan betapa indahnya jika demikian adanya. Hidup (dan mati ) demi roh seseorang murni berkaitan dengan karakter dan integritas pribadi, bukan dengan harapan-harapan akan ganjarannya dimasa depan. Perhatian Socrates murni etis, tanpa suatu gambaran akan intrik kosmologi yang telah mempesona para pendahulunya.
Socrates diakhir-akhir hidupnya banyak memperkatakan tentang akhirat dan hidup yang abadi kelak dibelakang hari. Dia mempercayai adanya akhirat, dan hidup yang abadi dibelakang hari itu, begitu juga tentang kekalnya roh. Socrates berpendapat bahwa roh itu telah ada sebelum manusia, dalam keadaan yang tidak kita ketahui. Kendatipun roh itu telah bertali dengan tubuh manusia, tetapi diwaktu manusia itu mati, roh itu kembali kepada asalnya semula. Diwaktu orang berkata kepada Socrates, bahwa raja bermaksud akan membunuhnya. Dia menjawab: “Socrates adalah di dalam kendi, raja hanya bisa memecahkan kendi. Kendi pecah, tetapi air akan kembali ke dalam laut”. Maksudnya, yang hancur luluh hanyalah tubuh, sedang jiwa adalah kekal ( abadi ).
Sedangkan tentang mengenal diri Socrates menjadikan pedoman seperti pada pepatah yang berbunyi: “kenalilah dirimu dengan dirimu sendiri ” (gnothisauton). Pepatah ini dijadikan oleh Socrates jadi pokok filsafatnya. Socrates berkata: manusia hendaknya mengenal diri dengan dirinya sendiri, jangan membahas yang di luar diri, hanya kembalilah kepada diri. Manusia selama ini mencari pengetahuan diluar diri. Kadang-kadang dicarinya pengetahuan itu di dalam bumi, kadang-kadang diatas langit, kadang-kadang di dalam air, kadang-kadang di udara. Alangkah baiknya kalau kita mencari pengetahuan itu pada diri sendiri. Dia memang tidak mengetahui dirinya, maka seharusnya dirinya itulah yang lebih dahulu dipelajarinya, nanti kalau dia telah selesai dari mempelajari dirinya, barulah dia berkisar mempelajari yang lain. Dan dia tidak akan selesai selama-lamanya dari mempelajari dirinya. Karena pada dirinya itu akan didapatnya segala sesuatu, dalam dirinya itu tersimpul alam yang luas ini.
Socrates selalu mengakui bahwa dia adalah seorang yang bodoh. Sebab dia belum mengenal dirinya sendiri. Dia tidak akan dapat mengetahui sesuatu apapun kecuali kalau dia telah mengetahui dirinya sendiri. Sebab itu haruslah dia mengenal dirinya lebih dulu. Maka dijadikanlah diri manusia oleh Socrates jadi sasaran filsafat, dengan mempelajari substansi dan sifat-sifat diri itu. Dengan demikian menurut Socrates filsafat hendaklah berdasarkan kemanusiaan, atau dengan lain perkataan, hendaklah berdasarkan akhlak dan budi pekerti.
Menurut filsafat Socrates segala sesuatu kejadian yang terjadi di alam adalah karena adanya “akal yang mengatur” yang tidak lalai dan tidak tidur. Akal yang mengatur itu adalah Tuhan yang pemurah. Dia bukan benda, hanya wujud yang rohani semata-mata. Pendapat Socrates tentang Tuhan lebih dekat kepada akidah tauhid. Dia menasehatkan supaya orang menjaga perintah-perintah agama, jangan menyembah berhala dan mempersekutukan Tuhan.
PENUTUP
Boleh jadi karena pemikirannya diluar pemikiran khalayak umum yang berlaku. Socrates dituduh menolak dewa-dewa atau Tuhan-tuhan yang telah diakui oleh negara. Sebagai kelanjutan atas tuduhan terhadap dirinya, ia diadili oleh pengadilan Athena. Dalam proses pengadilan, ia mengatakan pembelaannya yang kemudian ditulis oleh Plato dalam naskahnya yang berjudul Apologi.
Plato mengisahkan adanya tuduhan itu. Socrates dituduh tidak hanya menentang agama yang diakui oleh negara, juga mengajarkan agama baru buatannya sendiri. Salah seorang yang mendakwanya, yaitu Melethus, mengatakan bahwa Socrates adalah seorang yang tak bertuhan, dan menambahkan bahwa matahari adalah batu dan bulan adalah tanah. Socrates menangkal tuduhan itu dan menanyakan kepadanya, siapakah orang yang memperbaiki pemuda? Melethus menjawab, mula-mula para Hakim, lalu semua orang, kecuali Socrates.
Sebagai seorang muslim, kita dibekali Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber pokok dari ajaran Islam. Sebagai sumber ilmu-sains, hukum. Sebagai sumber mengenal siapa kita, untuk apa kita hidup dan tujuan hidup manusia dan bagaimana menjalankan kehidupan itu. Mengenal alam semeseta dan penciptaannya, termasuk bagaimana proses penciptaan manusia dan apa tugasnya hidup di bumi. Bentuknya: meta, paradigma, referensi, petunjuk, pegangan, ajaran, ayat-ayat kauniyyah dan ayat-ayat quliyyah, dan seterusnya. “Tholabul ‘Ilmi Farīdhotun ‘Alā Kulli Muslimīn” – Mencari Ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Billahit Taufiq wal-Hidayah. □ AFM
Daftar Pustaka
Atollah Renanda Yafi (2019). Apologia Socrates. Yogyakarta : Penerbit Basabasi.