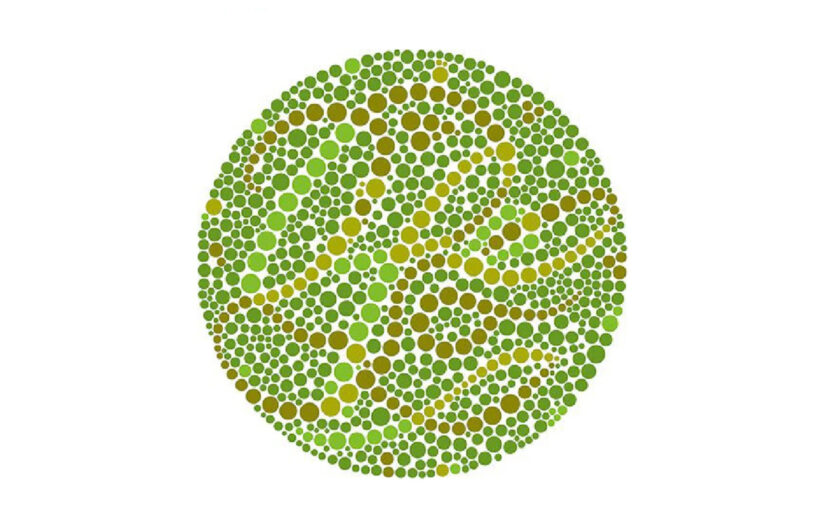Daftar isi
1. Teori Atom John Dalton
Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan mengemukakan pendapatnaya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa (hukum Lavoisier) dan hukum susunan tetap (hukum prouts). Lavosier mennyatakan bahwa “Massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi”. Sedangkan Prouts menyatakan bahwa “Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap”. Dari kedua hukum tersebut Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut:
- Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi
- Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda
- Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen
- Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada tolak peluru. Seperti gambar berikut ini:
model atom dalton
Kelemahan:
Teori dalton tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik.
2. Teori Atom J. J. Thomson
Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookers, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan diantara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom (partikel subatom) yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron.
Atom merupakan partikel yang bersifat netral, oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positifuntuk menetrallkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai Teori Atom Thomson. Yang menyatakan bahwa:
“Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan didalamya tersebar muatan negatif elektron”
Model atomini dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikelupas kulitnya. biji jambu menggambarkan elektron yang tersebar marata dalam bola daging jambu yang pejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai bola positif yang pejal. Model atom Thomson dapat digambarkan sebagai berikut:
atom thomson
Kelemahan:
Kelemahan model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut.
3. Teori Atom Rutherford
Rutherford bersama dua orang muridnya (Hans Geigerdan Erners Masreden) melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa (λ) terhadap lempeng tipis emas. Sebelumya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka, didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan (ada penyimpangan sudut kurang dari 1°), tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu diantara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90° bahkan lebih.
Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesipulan beberapa berikut:
- Atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan
- Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisanatom-atom emas, maka didalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif.
- Partikel tersebut merupakan partikelyang menyusun suatu inti atom, berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan.
Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan Model Atom Rutherford yang menyatakan bahwa Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa didalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak menolak.
Model atom Rutherford dapat digambarkan sebagai beriukut:
atom rutherford
Kelemahan:
Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom.
4. Teori Atom Bohr
ada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Neils Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah disekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck, diungkapkan dengan empat postulat, sebagai berikut:
1. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner (menetap) elektron dan merupakan lintasan melingkar disekeliling inti.
2. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap.
3. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat, besarnya sesuai dengan persamaan planck, ΔE = hv.
4. Lintasan stasioner yang dibolehkan memilki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari h/2∏ atau nh/2∏, dengan n adalah bilangan bulat dan h tetapan planck.
Menurut model atom bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam, semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya.
atom Bohr
Kelemahan:
Model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak.
5. Teori Atom Modern
Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrodinger (1926).Sebelum Erwin Schrodinger, seorang ahli dari Jerman Werner Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian yaitu “Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom”.
Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrodinger.Erwin Schrodinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam tiga dimensi.
atom modern
Persamaan Schrodinger
persamaan
x,y dan z
Y
m
ђ
E
V = Posisi dalam tiga dimensi
= Fungsi gelombang
= massa
= h/2p dimana h = konstanta plank dan p = 3,14
= Energi total
= Energi potensial
Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut ini.
Awan elektron disekitar inti menunjukan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk sub kulit. Beberapa sub kulit bergabung membentuk kulit.Dengan demikian kulit terdiri dari beberapa sub kulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama.
Ciri khas model atom mekanika gelombang
1.
Gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasannya (orbitnya) tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital (bentuk tiga dimensi darikebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom)
2.
Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. (Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut)
3.
Posisi elektron sejauh 0,529 Amstrong dari inti H menurut Bohr bukannya sesuatu yang pasti, tetapi bolehjadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron.