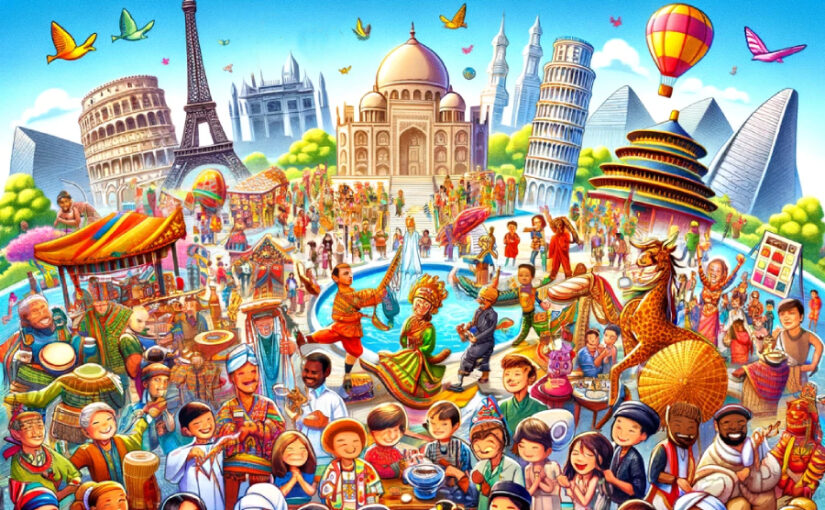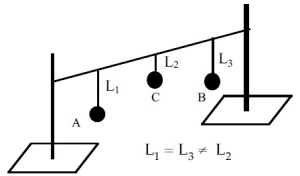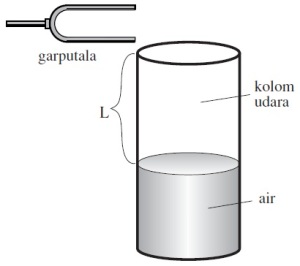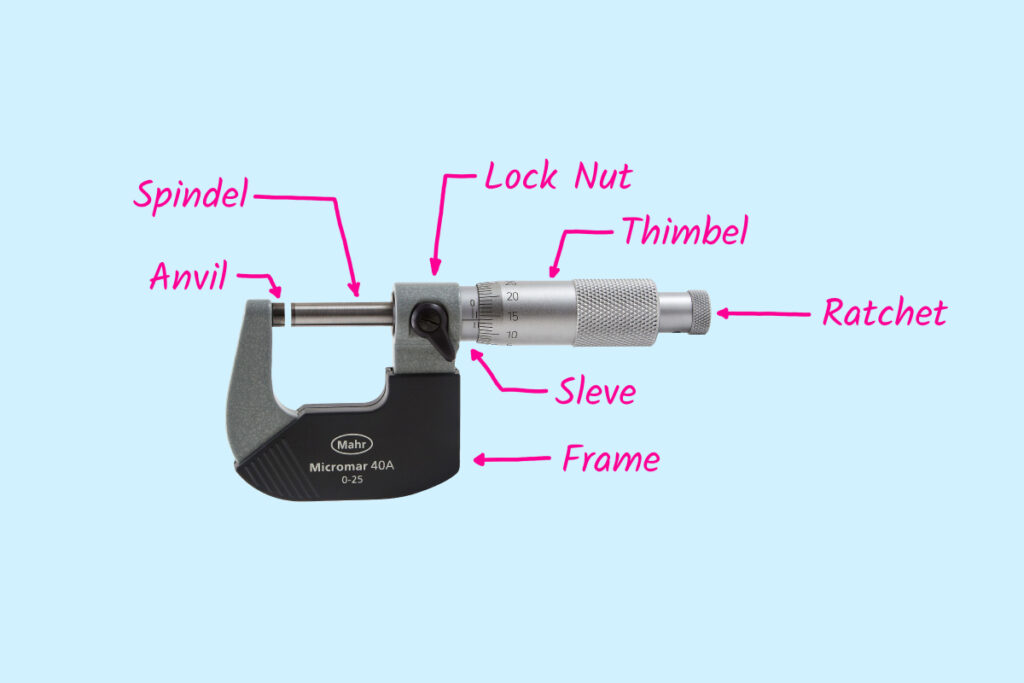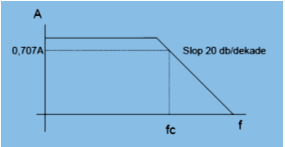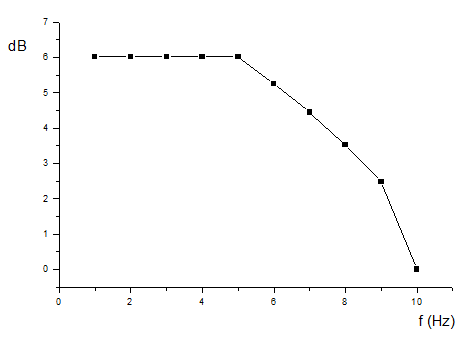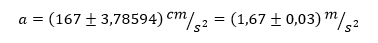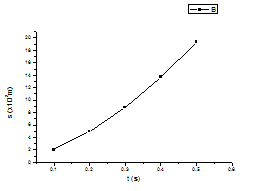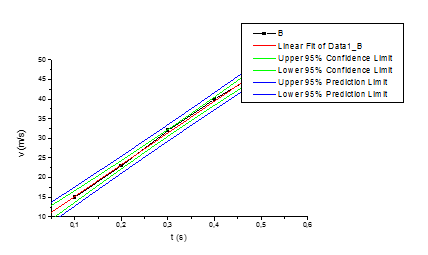Contoh makalah dengan topik masuknya Budaya asing ke Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk membahas proses masuk, dampak dan manfaat pertukauran budaya asing antar negara.
Daftar isi
Masuknya Budaya Asing ke Indonesia
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pada umumnya masuknya budaya asing ke Indonesia sangat cepat perkembangannya. Masuknya budaya luar bisa melalui banyak cara seperti, sarana multi media massa elektronik maupun cetak, serta media dunia maya (internet dan social media) sangat mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia. Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Jika kebudayaan asing yang bersifat negatif memasuki sendi-sendi kehidupan bangsa, terutama para generasi muda tanpa diimbangi upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dikhawatirkan Bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai bangsa.
Budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.
Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
Awal masuknya kebudayaan asing di Indonesia melalui penjajahan yang diakukan oleh orang asing, mereka tidak hanya mengambil rempah-rempah saja tetapi memasukan kebudayaan mereka di Indonesia sehingga kebudayaan rakyat Indonesia bercampur dengan kebudayaan asing.
Kebiasaan orang-orang barat yang biasa kita saksikan baik di media elektronik, cetak maupun secara langsung seperti cara berpakaian dan mode yang telah menjadi budaya masyarakat kita khususnya kalangan remaja. Pengaruh ini dapat merambat lebih cepat ke golongan bawah akibat artis-artis di jagad hiburan yang memiliki tingkat moderenisasi yang lebih tinggi. Dari perilaku dan gayanya itulah di lihat sebagai contoh dan layak di tiru karena di anggap lebih maju dan modern. Umumnya kalangan remaja Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang di anut dan adat kebiasaan yang mereka miliki. Para remaja juga merasa bahwa kebudayaan di negrinya sendiri terkesan jauh dari moderenisasi. Sehingga para remaja merasa gengsi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan budayanya. Sehingga pada akhirnya para remaja lebih menyukai kebudayaan barat, dibandingkan dengan kebudayaan kita sendiri. Dan kini nilai-nilai kebudayaan kita semakin terkikis karena di sebabkan oleh pengaruh budaya Asing yang masuk ke Negara kita.
Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau apa jadinya genersi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa, maka Pembangunan Nasional perlu bertitik-tolak dari upaya-upaya pengembangan kesenian yang mampu melahirkan “nilai-tambah kultural”. Seni-seni lokal dan nasional perlu tetap dilanggengkan, karena berakar dalam budaya masyarakat. Melalui sentuhan-sentuhan nilai-nilai dan nafas baru, akan mengundang apresiasi dan menumbuhkan sikap posesif terhadap pembaharuan dan pengayaan karya-karya seni. Di sinilah awal dari kesenian menjadi kekayaan budaya dan “modal social – kultural” masyarakat.
Bab II. Pembahasan
A. Perkembangan Budaya Asing di Era Globalisasi
Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut mengiringi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutahiran tekhnologi tidak dibarengi dengan budaya-budaya asing positif yang masuk. Budaya asing masuk ke negeri kita secara bebas tanpa ada filterisasi. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya terutatama pengaruh budaya Barat. Dengan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Membawa perubahan sampai ke tigkat dasar kehidupan manusia di Indonesia. Pengaruh interaksi dengan budaya Barat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia.
Pada umumnya masyarakat Indonesia terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, tetapi mereka belum bisa memilah mana yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan mana yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku di negara Republik Indonesia, sebagai contoh yaitu: cara berpakaian anak-anak remaja Indonesia yang sudah jauh melenceng dari aturan-aturan agama dan norma yang ada. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan sehingga ada bagian tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan malah diperlihatkan. Masuknya budaya asing diindonesia bisa melalui banyak cara salah satunya adalah melalui social media. Kaum remaja biasa melihat fashion orang asing. Mulai dari cara berpakaian hingga gaya rambut sehingga mereka dengan mudah terpengaruh dengan fashion orang barat, jujur saya sendiri juga mengikuti perkembangan fashion budaya barat. Dari yang ingin hanya melihat saja disosial media menjadi ingin mencoba fashion orang asing yang saat ini sedang tren. Padahal cara berpakaian mereka dengan cara berpakaian yang diajarkan oleh orang tua kita sangat jauh berbeda. Orang Indonesia cenderung ingin mencoba gaya yang mereka anggap baik dan bagus untung di pakai sehingga kaum remaja seperti kita ini dengan mudah terpengaruh. Kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cermin moderen. Hal ini jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang.
Hembusan pengaruh Barat, di anggap sebagai ciri khas kemajuan dalam ekspresi kebudayaan kekinian. Padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat sendiri. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan terjadi kebudayaan masyarakat nusantara. Dari sinilah juga nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya moderen dalam bentuk pergaulan masyarakat.
Dalam era globalisasi ini, jati diri bangsa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dan (bahkan) tidak cocok dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Batas antarnegara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah barang tentu, hal ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan siatuasi dan kondisi pemakaiannya. Dengan kata lain, pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakai bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Pada awalnya pintu masuk kebudayaan Asing di Indonesia adalah melalui kegiatan penjajahan para orang Asing di Indonesia. Tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah pada umunya, tetapi mereka juga menanamkan budaya mereka untuk mencampuri kebudayaan Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan, pada zaman sekarang pintu masuk kebudayaan Asing itu melalui kemajuan teknologi dan informasi. Dizaman dahulu salah satu contoh masuknya budaya asing, yaitu: gaya arsitektur keraton Yogyakarta yang mengarah ala-ala Japanese.
Para kaum remaja di Indonesia sudah jarang sekali mempelajari kebudayaan – kebudayaan lokal, tetapi anak anak lebih suka bermain play station dan bermain ke time zone. Sangat jarang saat ini saya melihat anak anak bermain kuda lumping, dakon, gobak sodor dll. Tetapi saat ini ada stasiun TV negeri secara konsisten menayangkan acara budaya – budaya Indonesia. Selain itu banyak Negara Negara tetangga yang mengklaim kebudayaan – kebudayaan kita, seperti contoh:
- Tari reog ponorogo dari jawa timur oleh pemerintah Malaysia.
- Alat music gamelan dari jawa oleh pemerintah Malaysia.
- Kain ulos dari Sumatra utara oleh Malaysia
- Alat music angklung oleh Malaysia dan masih banyak lagi.
Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga memiliki warisan budaya tersebut dan memberikan apresiasi dengan cara menjaga budaya kita agar tidak diklaim oleh Negara asing.
Faktor – Faktor Penyebab Budaya Asing Masuk ke Indonesia
1. Kurangnya Penjagaan yang ketat di wilayah gerbang Indonesia
Dalam gerbang wilayah Indonesia, sepertinya kurang adanya badan seleksi khusus yang bisa menyeleksi budaya-budaya asing negatif yang masuk ke Indonesia. Seperti masih banyaknya gambar serta video porno yang didatangkan dari luar.
2. Lifestyle yang berkiblat pada barat
Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang meniru gaya hidup atau lifestyle orang-orang bule atau lebih berkiblat kebarat-baratan, yakni melakukan sex bebas, berpakaian mini, gaya hidup bebas tanpa ikatan atau biasa sering kita sebut dengan kumpul kebo. Istilah ini digunakan kepada pasangan yang bukan muhrimnya tetapi tinggal seatap tidak dalam tali pernikahan.
Di Indonesia gaya hidup ini tidak dibenarkan karena menyalahi beberapa norma yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar juga cukup berat terutama pada lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang melakukan “kumpul kebo” atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan ini akan dipandang kurang pantas oleh warga sekitar. Sanksi yang diberikan masyarakat tidak berat tetapi cukup menyakitkan karena bisa-bisa akan mengucilkan orang yang melakukan kegiatan ini.
3. Menyalagunakan Tekhnologi
Seperti sempat kita bahas diatas bahwa pemanfaatan tekhnologi yang salah dapat mempermudah arus budaya asinya negatif yang masuk. Seperti Internet sekarang ini internet banyak disalahgunakan untuk hal-hal negatif, seperti ada situs porno, melakukan hal penipuan, dll. Orang-orang menyalahgunakan pemanfaatan tekhnologi ini denga cara yang tidak benar. Orang-orang bisa mengakses dengan mudah situs-situs porno yang mereka inginkan. Hal ini membawa dampak buruk bagi yang menikmatinya.
Mencegah
cara-cara untuk mengatasi memudarnya jati diri bangsa adalah sebagai berikut:
1. Jati diri harus berbasis kepada budaya dan kepribadian bangsa.
Jati diri yang telah tersusun harus berbasis kepada budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, antara lain:
- Religius
- Humanis
- Naturalis
- Terbuka
- Demokratis
- Integrasi dan Harmoni
- Nasionalisme dan Patriotisme
- Berkomitmen Terhadap Kebenaran
- Jujur dan Adil
- Profesional
- Ber-IPTEK
- Mandiri
- Etis dan Moralis
- Kepatuhan Kepada Hukum
- Berjiwa Kemasyarakatan
- Berjiwa Kultural
- Berjiwa Seni dan Estetika.
Hal yang sangat memprihatinkan rakyat Indonesia dewasa ini adalah munculnya kehidupan yang bersifat paradoks dan menjadi bagian dari krisis bangsa yang multidimensial. Kondisi yang paradoks itu antara lain berupa masuknya budaya sekuler kedalam kehidupan bangsa Indonesia yang religius dan spiritualis sehingga muncul gaya hidup modern yang materialistik, individualistik, liberalis, hedonis dan vulgar.
Sifat rakyat Indonesia yang sangat menghargai kejujuran, keikhlasan dan kemuliaan manusia, namun yang terjadi banyak orang yang memiliki karakter hipokrit atau munafik. Sifat ramah, terbuka, moderat dan bersahabat, namun yang terjadi sekarang adanya gerakan sosial radikal yang menggunakan kekerasan, sehingga Indonesia disebut negara sarang teroris. Untuk mengatasi kondisi sosial yang paradoks tersebut, maka rakyat Indonesia harus membudayakan dan mensosialisasikan jati diri bangsa seperti telah disebutkan sebelumnya.
1. Memiliki Loyalitas Terhadap NKRI.
Hubungan antar suku bangsa Indonesia belum harmonis karena masih ada suku bangsa yang mendominasi suku bangsa lain yang lebih kecil. Globalissi dan keterbukaan saat ini telah memperkuat paham etnosentrisme danprimordialisme sehingga beberapa suku bangsa di Indonesia ingin mendirikan negara merdeka baru. Tentu saja keinginan ini mengancam eksistensi NKRI, yang akhirnya akan memunculkan konflik sosial dengan kekerasan.
Hendaknya semua pihak meyakini bahwa pembangunan jati diri bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir, yaitu memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa. Jati diri inilah yang membangun dan mengembangkan bangsa agar memiliki identitas diri secara komprehensif sebagai pribadi yang percaya kepada diri sendiri, percaya akan potensi dengan kemampuan sendiri, mempertahankan harga diri, bersikap terbuka dan moderat.
2. Memiliki Komitmen Tinggi Untuk Pelestarian Unsur dan Nilai Sosial.
Kita harus menyadari bahwa setiap masyarakat akan menghadapi masalah perubahan sosial yang selalu terjadi sebagai dampak dari proses-proses sosial, seperti modernisasi dan industrialisasi
Menurut Anthony Giddens, dampak dari modernisasi ada yang positif dan ada yang negatif. Modernisasi itu membawa perubahan-perbuhan menuju kemajuan sekaligus juga membawa perubahan yang bersifat negatif seperti runtuhnya institusi sosial dan pudarnya budaya lokal. Tradisi dan budaya lokal dapat hilang secara perlahan-lahan karena ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.
Bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bangsa dan negara besar. Oleh karena itu harus memiliki identitas diri dan jati diri yang khas yang berbeda dengan bangsa dan negara lainnya. Sehingga bangsa Indonesia akan memberikan sumbangan besar bagi peradaban umat manusia dikemudian hari.
Demikian pembahasan yang saya buat, semoga apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan dari saya untuk seluruh lapisan masyarakat terutama anak muda untuk menyaring seluruh kebudayaan asing yang masuk ke budaya Indonesia, yang baik kita ambil sedangkan yang buruk kita tinggalkan. Dalam hal ini kita perlu bersifat bijak dan penyaringan budaya asing harus dilakukan dengan seksama dan cermat dan saya berpesan agar kita menanamkan rasa cinta kepada tanah air kita Bumi Indonesia, seperti: melestarikan budaya Indonesia dengan contoh seperti memakai baju batik, menghargai budaya suku lain serta turut mempelajari tari-tarian dan lagu lagu Indonesia.
Kata penutup
Demikianlah Kliping tentang masuknya budaya asing ke Indonesia Tak lupa kami mengucapkan terima kasih karena kesediaannya untuk membaca kliping yang kami buat untuk memenuhi tugas pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya masih banyak kekurangan karena berbagai keterbatasan kami baik itu berupa pengetahuan maupun bahan referensi, Oleh karena itu masukan berupa saran dan kritik sangat kami harapkan.